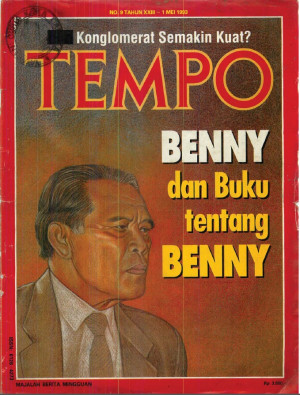LIMA puluh ribu orang mengelu-elukan Nawaz Sharif di Lahore, ibu kota Provinsi Punjab, Rabu pekan lalu. Sharif, yang dipecat dari kursi perdana menteri oleh Presiden Ghulam Ishaq Khan dua pekan lalu itu memang segera pulang ke kota kelahirannya, Lahore, dan mengajukan petisi ke pengadilan tinggi untuk menentang pemecatannya. Dari Lahore, agaknya Sharif ingin menggalang kekuatan untuk melawan Khan. ''Aku akan kembali memperoleh kekuasaan,'' katanya di hadapan para pendukungnya. Dan ia berencana menggerakan pendukungnya untuk memboikot pemilu Juli mendatang. Di Rawalpindi, yang berdampingan dengan ibu kota Islamabad, sejumlah besar pertokoan dan perkantoran tutup pada hari Selasa dan Rabu lalu untuk menunjukkan dukungan pada Sharif. Sementara itu di Karachi, kota perdagangan di pantai barat Pakistan, para pengusaha yang mendukung Sharif mengajak karyawannya tidak bekerja pada hari Kamis. Namun tak mudah bagi Sharif kembali ke kursi perdana menteri dan memperjuangkan pemerintahan parlementer yang ia cita- citakan. Sharif adalah korban ketiga dari Amandemen Kedelapan yang antara lain memberi kekuasaan pada presiden untuk memecat perdana menteri, membubarkan kabinet, dan melaksanakan pemilihan umum. Amandemen itulah sebenarnya yang oleh Sharif diusahakan untuk dicabut. Bagi Sharif, amandemen itu mencerminkan ketidakdemokratisan, karena perdana menteri dipilih lewat pemilu, bukan ditunjuk oleh presiden. Amandemen Kedelapan memang dilahirkan untuk memberi kekuasaan presiden mengambil sejumlah tindakan tanpa konsultasi ataupun persetujuan Majelis Nasional (parlemen). Itu adalah amandemen yang diciptakan oleh almarhum Jenderal Zia Ul-Haq pada pertengahan tahun 1985 lalu. Setelah berkuasa selama delapan tahun di bawah UU darurat, bekas Kepala Staf Angkatan Darat yang mengkudeta Zulfikar Ali Bhutto ini akhirnya melaksanakan pemilihan Majelis Nasional dan Dewan Daerah. Namun Zia Ul-Haq rupanya tetap tak mau kehilangan kendali atas pemerintahan di Pakistan. Maka ia perluas kekuasaan presiden dengan membuat Amandemen Kedelapan itu. Lewat amandemen itu presiden berhak menunjuk perdana menteri, menteri, gubernur, kepala staf dan panglima angkatan bersenjata, serta melaksanakan pemilihan umum. Padahal, menurut UUD 1973, perdana menteri ditunjuk oleh Majelis Nasional. Barulah kemudian para menteri, gubernur, kepala staf, dan panglima angkatan bersenjata ditunjuk oleh perdana menteri. Dengan kata lain, pemecatan seorang perdana menteri mestinya lewat Majelis Nasional, bukan langsung oleh presien. Pembagian kekuasaan seperti yang diatur oleh UUD 1973, menurut Zia, ''benar-benar tidak berarti.'' Perdana menteri memang seharusnya berkuasa ''tapi adalah tidak masuk akal jika seorang presiden sama sekali tidak berdaya.'' Setelah kekuasaannya dijamin oleh amandemen itu, barulah Zia mencabut keadaan darurat yang berlaku sejak tahun 1977. Zia Ul-Haq mungkin benar. Tapi sebuah negara yang ingin maju mestinya memiliki perangkat peraturan yang demokratis. Kontrol atas pemerintah yang berada di tangan satu presiden cenderung menjadi kekuasaan yang otoriter. Masalahnya bagi Pakistan, seberapa kuat sebenarnya parlemennya. Soalnya, tanpa ini, pemerintahan pun bakal cenderung otoriter. LPS
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini