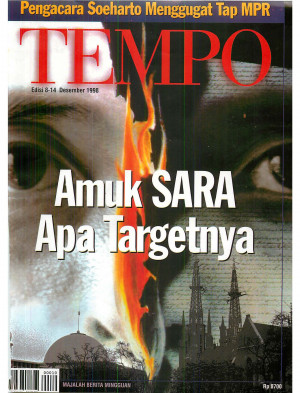Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Bagaimana harus saya katakan kenyataan yang pahit ini? Dalam sebuah rapat perguruan tinggi, seseorang dengan semangat tinggi bicara tentang sebuah keyakinan. Seperti berdoa, ia berkata, "Ibu-ibu, Bapak-bapak, uang kita sedikit, ruang kelas kita sudah teramat sempit. Tak mungkin kita menampung anak orang lain, ketika anak-anak kita sendiri membutuhkannya. Bagaimana bisa kita mendahulukan anak tetangga dan menelantarkan anak sendiri...?" Ruangan sunyi senyap, peserta rapat bungkam, bersitatap, lalu menebar pandang ke sekitar ruangan seperti melihat setan sedang bertengger di salah satu sudut.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo