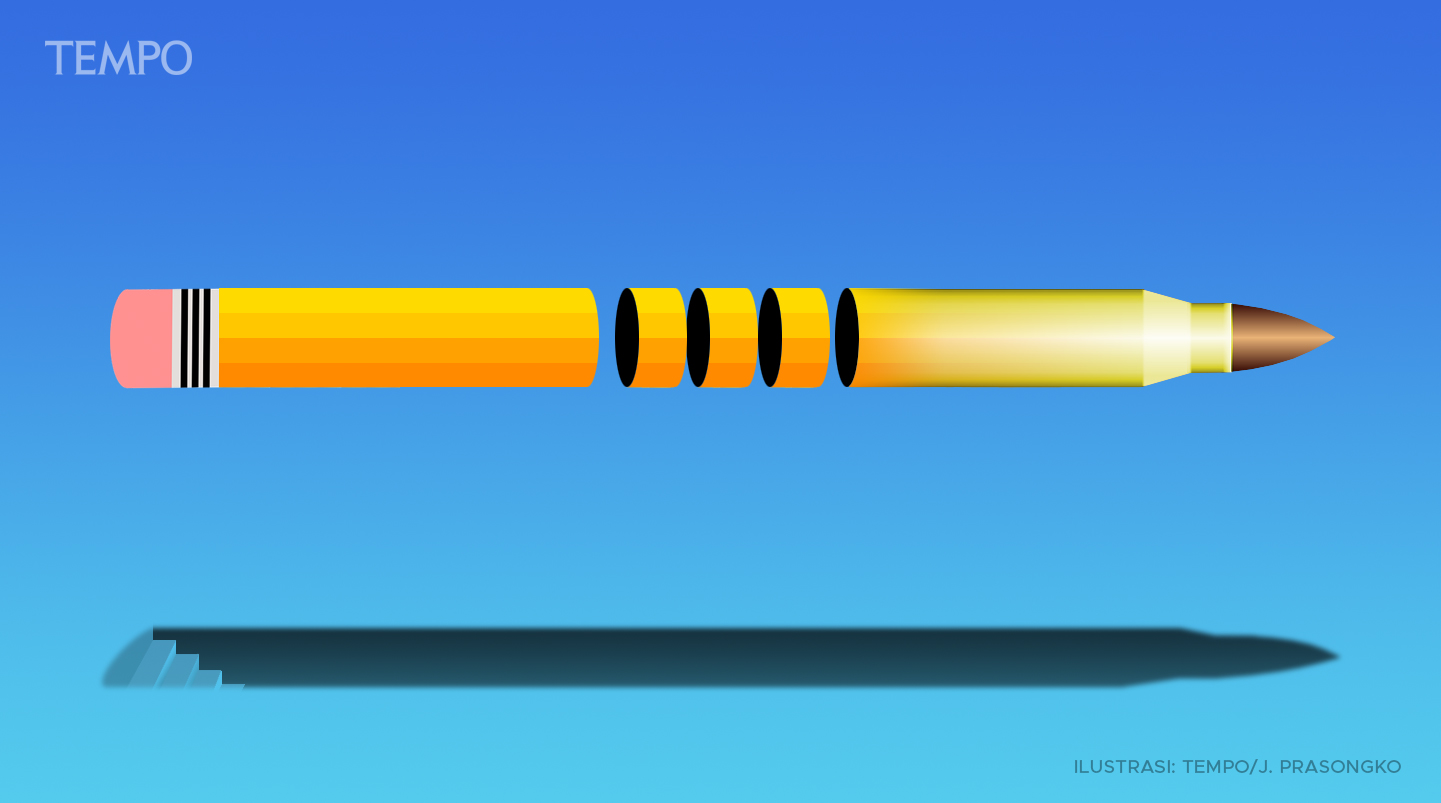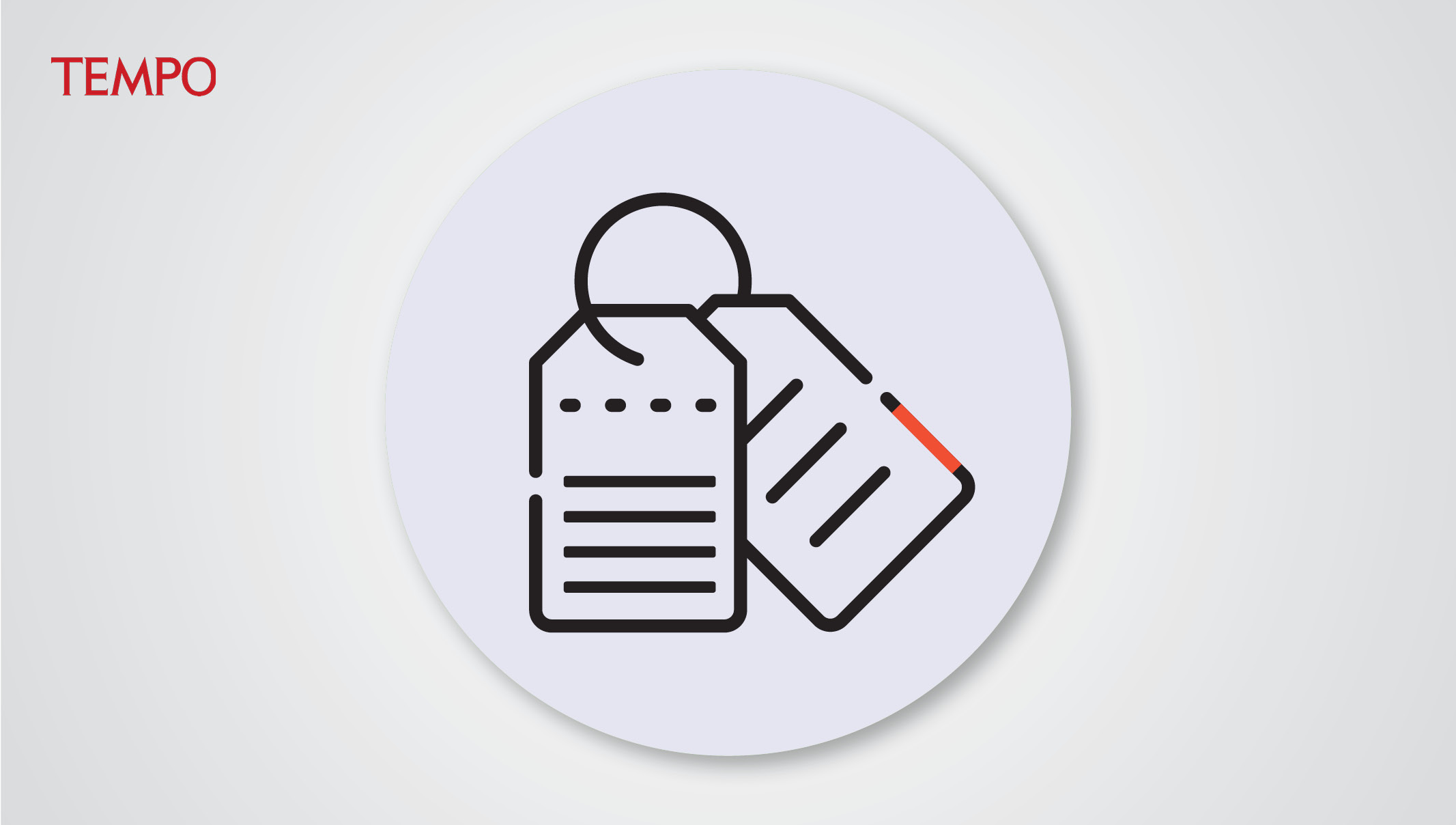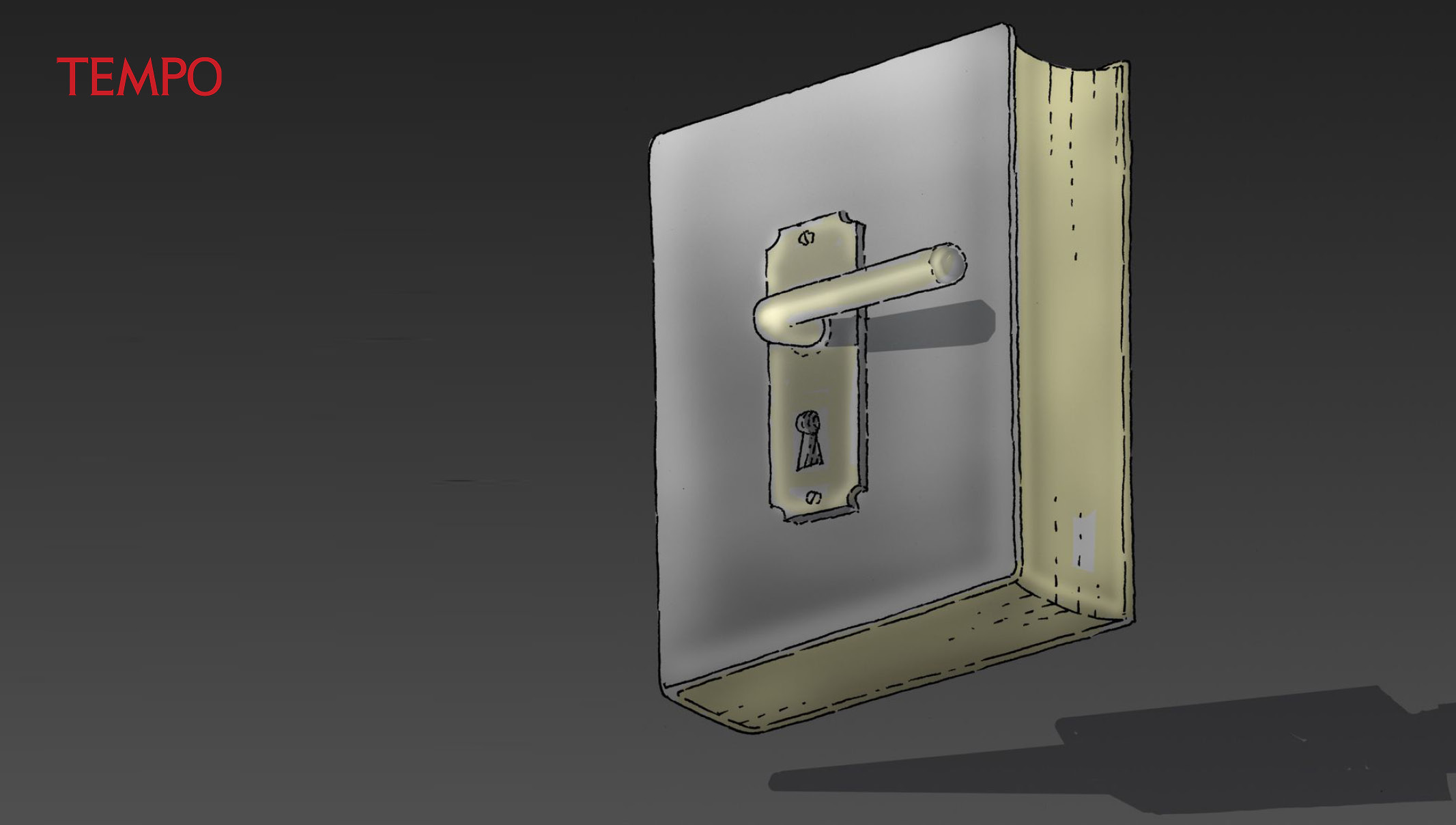Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Alek Karci Kurniawan
Analis Hukum dan Kebijakan pada Program Suku Adat Marginal Komunitas Konservasi Indonesia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Masyarakat adat yang masih eksis saat ini umumnya adalah suku-suku minoritas yang sudah ada sejak 100 tahun lalu. Mereka jarang diperhatikan dan lambat mengikuti modernitas. Kala Sumpah Pemuda menghadirkan pemuda-pemudi terdidik untuk memikirkan bangunan kemerdekaan, suku-suku besarlah yang tampil: Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dari Sumatera saja, apakah ada perwakilan suku Anak Laut, Bonai, Kuala, Rawa, Sakai, Talang Mamak, Ulu Muara Sipongi, Lubu, Siberut, Siladang, Mentawai, Belom, Gumbak Cadek, Orang Rimba, dan suku-suku lain? Jelas tidak.
Maka wajarlah bunyi "hak-hak tradisionalnya dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia" dalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih condong pada kepentingan mayoritas. Hal itu dapat dibuktikan dengan penempatan hak masyarakat adat dalam produk hukum turunan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang baru diterbitkan pada Oktober lalu.
Pasal 4 peraturan menteri itu menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya: (1) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau (2) yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat adat diperlakukan secara apriori. Mereka berada dalam konteks harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan NKRI, seakan-akan mereka bukan merupakan bagian dari bangsa ini. Bahkan Undang-Undang Pokok Agraria pun memakai kalimat yang lebih represif: masyarakat adat "harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara".
Apa yang dimaksud harus "sedemikian rupa" sehingga sesuai dengan kepentingan nasional itu? Apakah ketika ada kebijakan pemerintah membuat pelepasan kawasan hutan, masyarakat adat harus menyesuaikannya? Apakah ketika pemerintah sudah membuat program sertifikasi tanah yang dinilai cocok untuk "kepentingan nasional dan negara", masyarakat adat pun harus menyesuaikannya pula? Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kepentingan nasional itu? Apakah kepentingan masyarakat adat berada di luar atau di dalamnya?
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan umum, perlindungan subyek hukum Republik Indonesia, dan yurisdiksi nasional. Arti "kepentingan umum" itu sendiri, merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekarang, apa pula maksudnya "sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?"
Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara pengujian Undang-Undang yang dihadapkan kepadanya telah secara tegas memberi tolok ukur arti dari kalimat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adapun tolok ukur tersebut adalah (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tolok ukur di atas pula yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi, dalam perkara nomor 35/PUU-X/2012 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, melepaskan subordinasi hutan adat dari hutan negara.
Berkenaan dengan syarat "sepanjang kenyataannya masih ada" dan "diakui keberadaannya", MK menafsirkan, dalam kenyataannya status dan fungsi hutan dalam masyarakat hukum adat bergantung pada status keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Maka ada dua kemungkinan yang terjadi: kenyataannya masih ada tapi tidak diakui keberadaannya; dan kenyataannya tidak ada tapi diakui keberadaannya.
Jika kenyataannya masih ada tapi tidak diakui keberadaannya, dapat merugikan masyarakat bersangkutan. Misalnya, hutan adat mereka digunakan untuk kepentingan lain tanpa seizin mereka melalui penggusuran.
Maka dengan mengikuti alur penalaran di atas, Pasal 4 peraturan menteri tersebut, yang menempatkan hak atas tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat, jelas merupakan kemunduran hukum dan inkonstitusional.