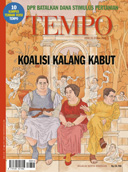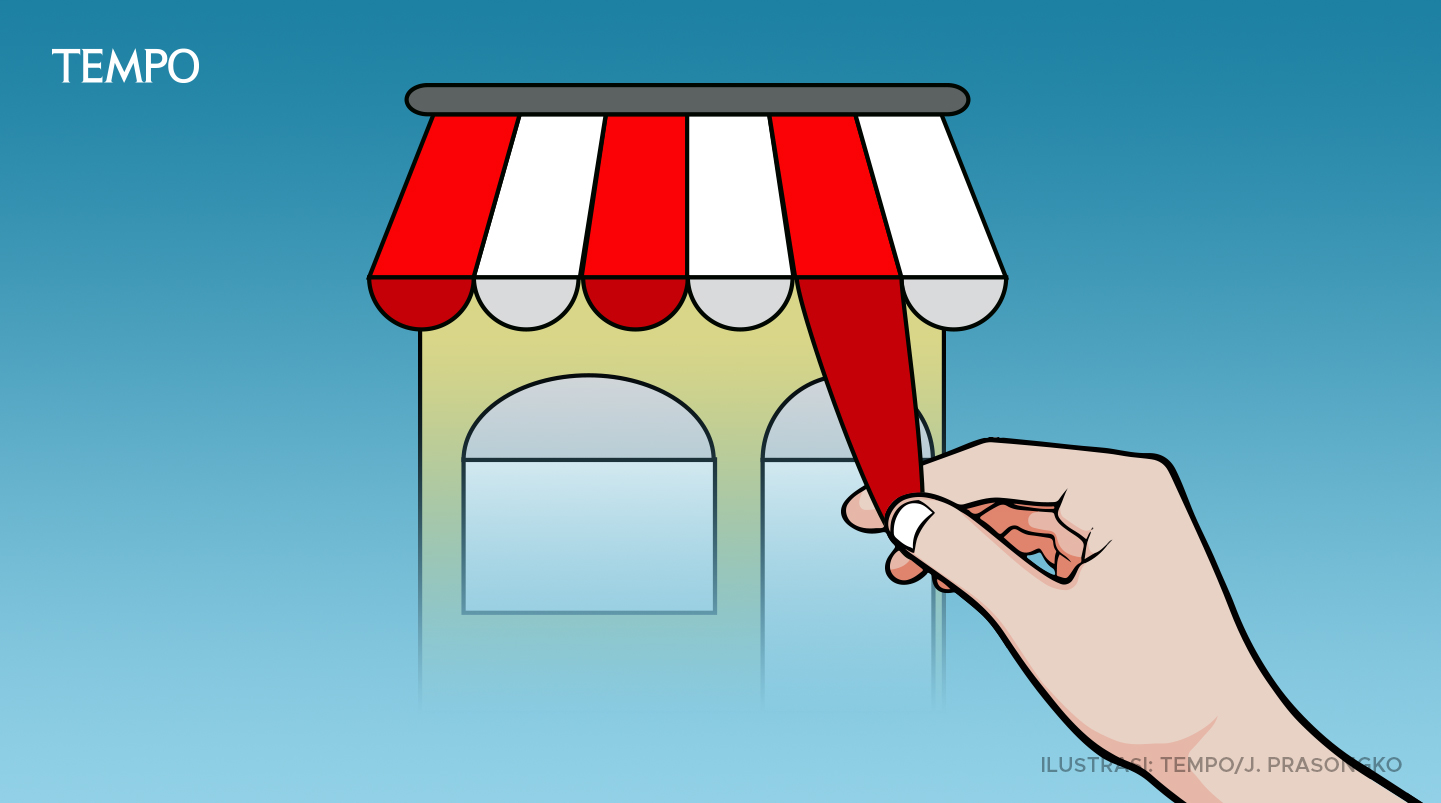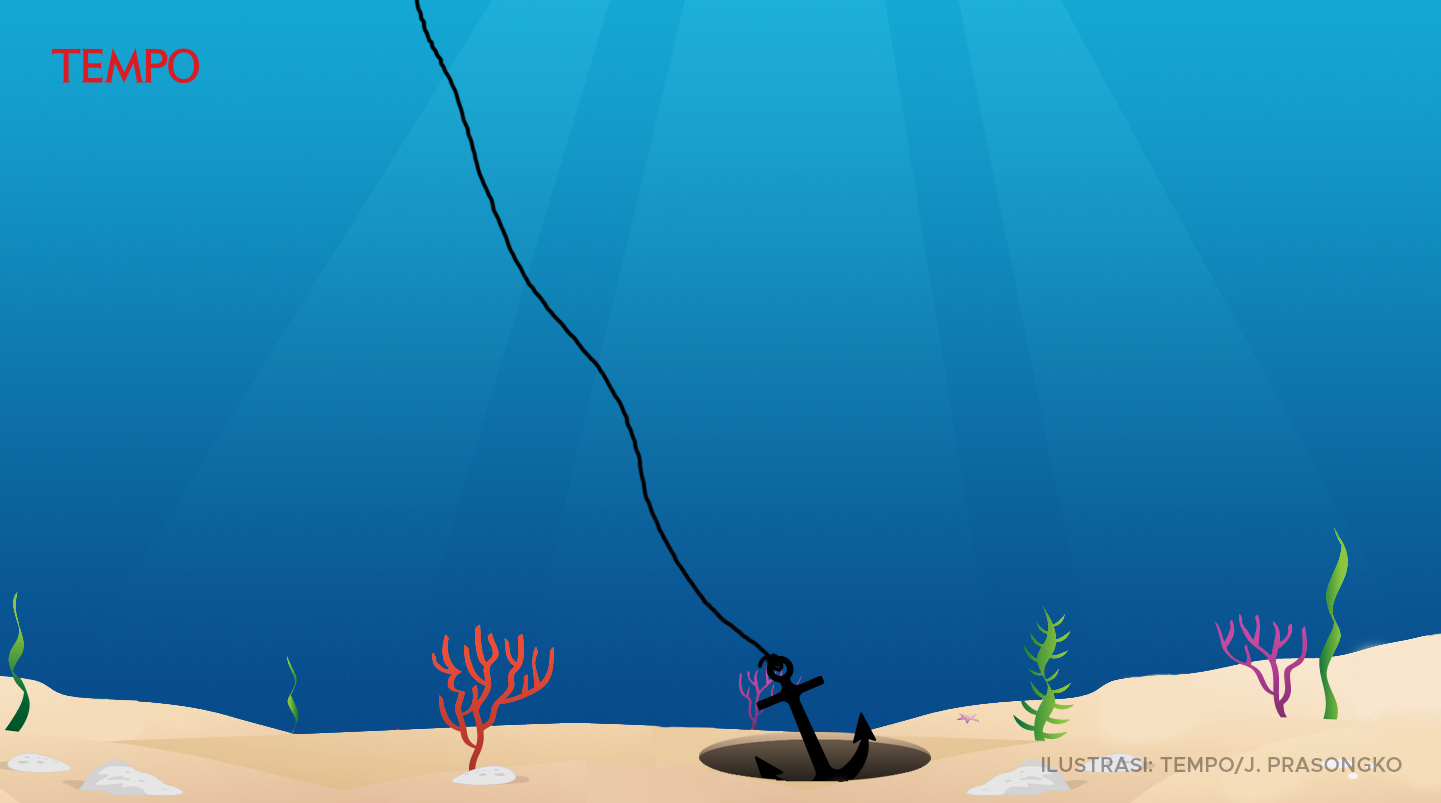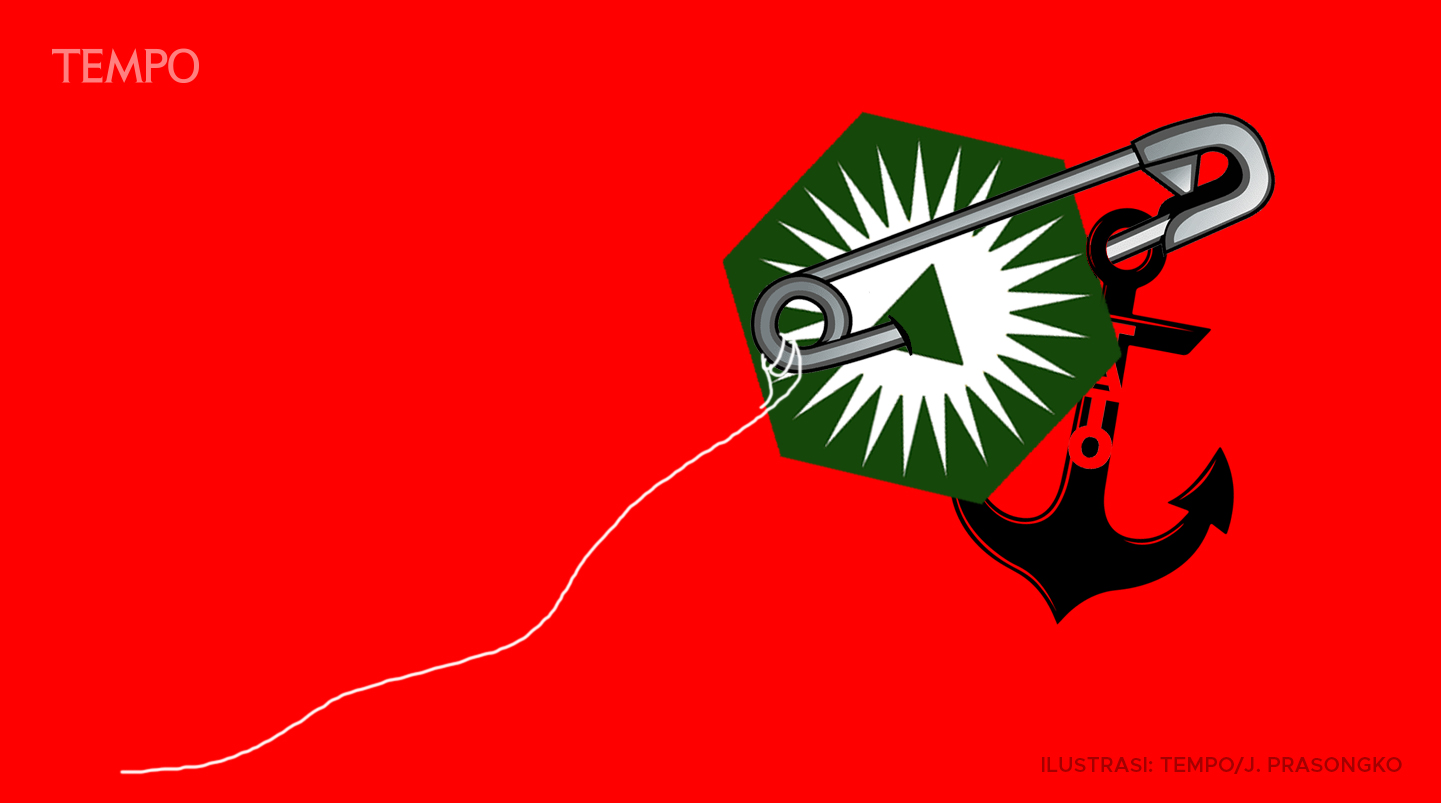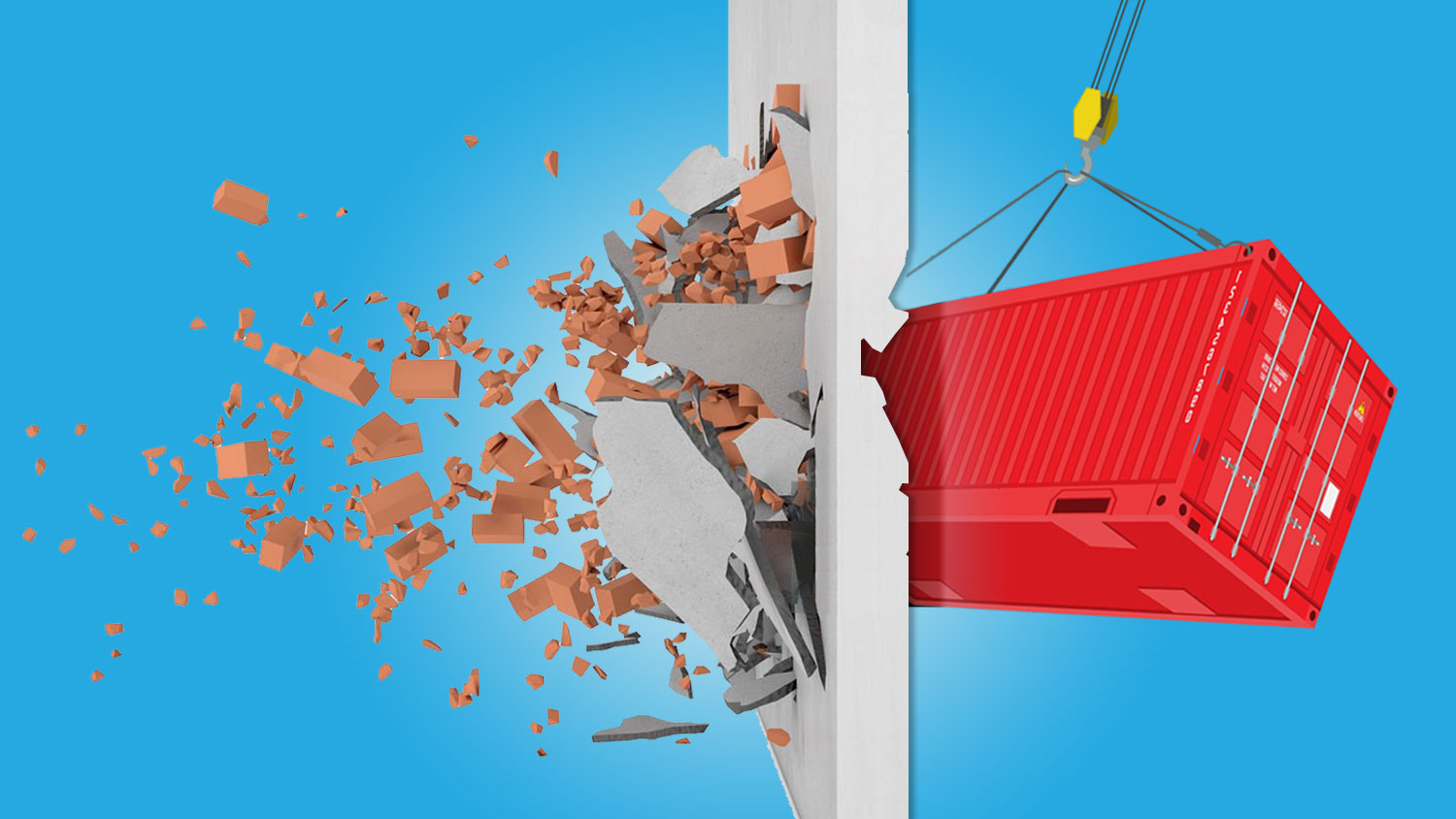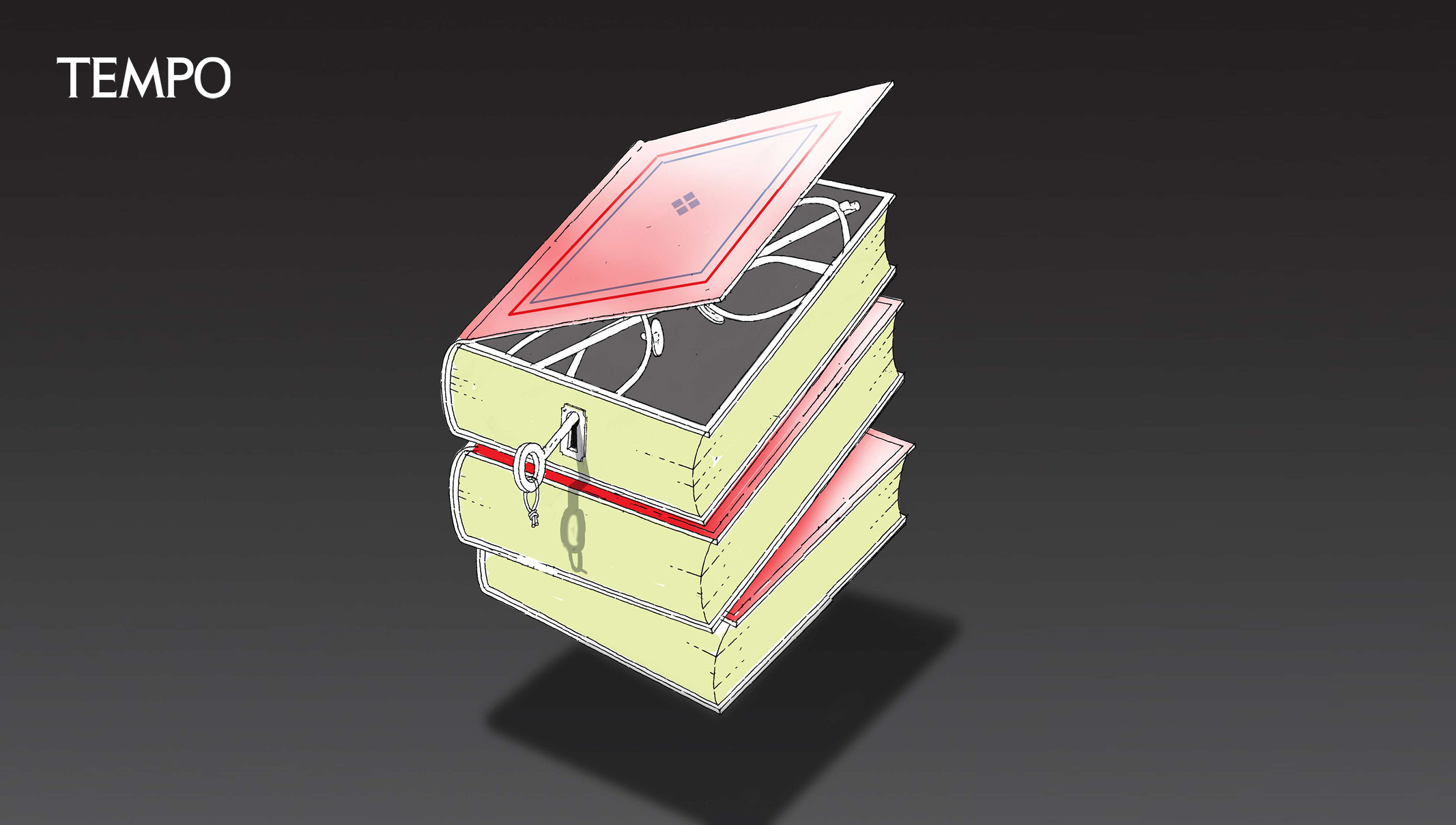Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Siti Khoiyaroh, bocah empat tahun itu, pasti tak paham kenapa dagangan ibunya harus ditertibkan. Ibunya, Sumariyah, hanya berjualan bakso, bukan barang terlarang seperti narkoba. Tapi Sumariyah tentu maklum. Polisi pamong praja datang mengobrak-abrik pedagang karena diperintahkan menciptakan ketertiban. Perintah itu datang dari atasannya, ya, sebut saja Wali Kota. Dan sang Wali Kota bertindak atas nama peraturan, karena Jalan Raya Boulevard, di depan World Trade Center Surabaya yang megah itu, harus menjadi kawasan yang tertib. Artinya, tidak boleh ada yang berjualan di jalanan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo