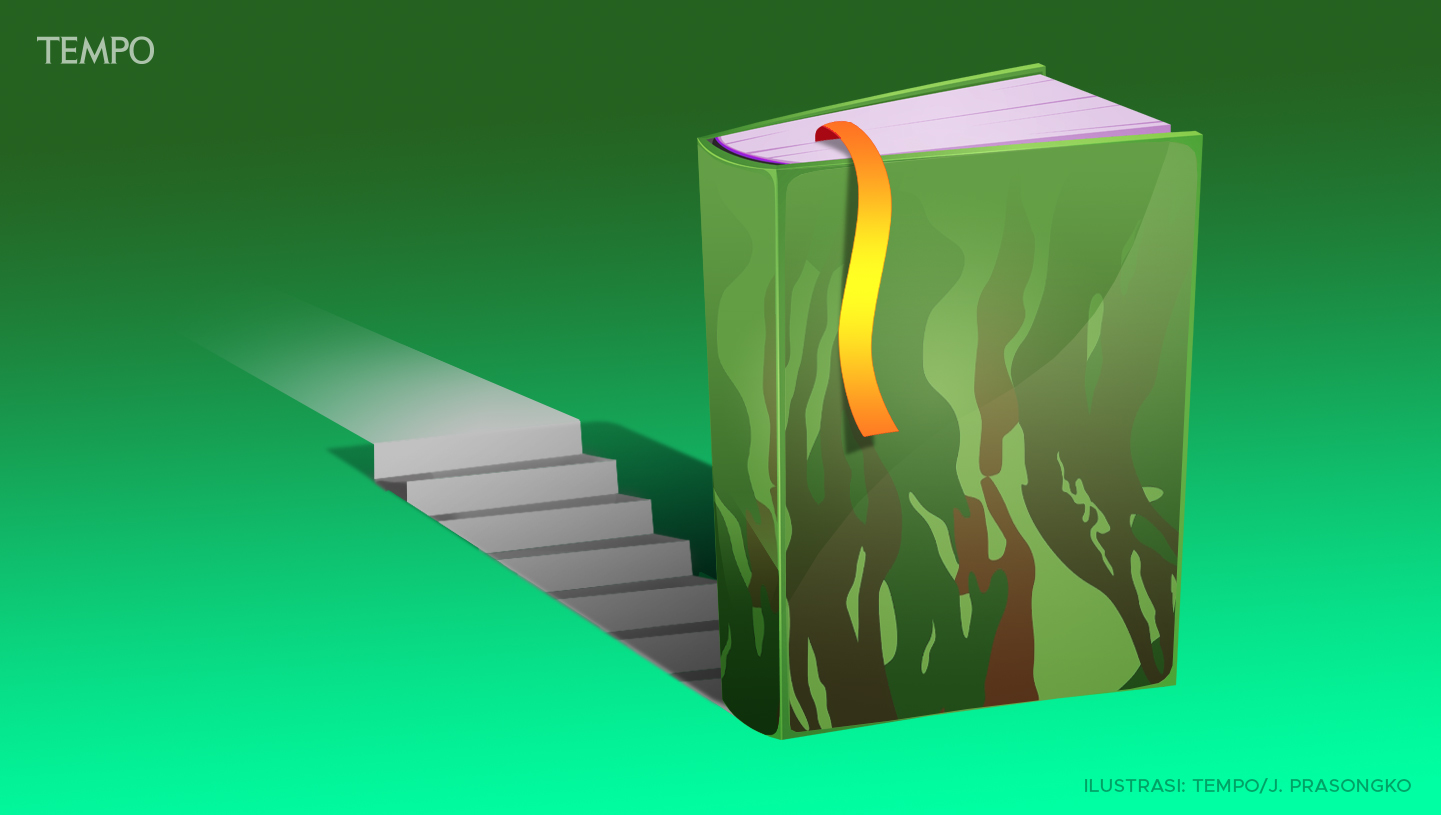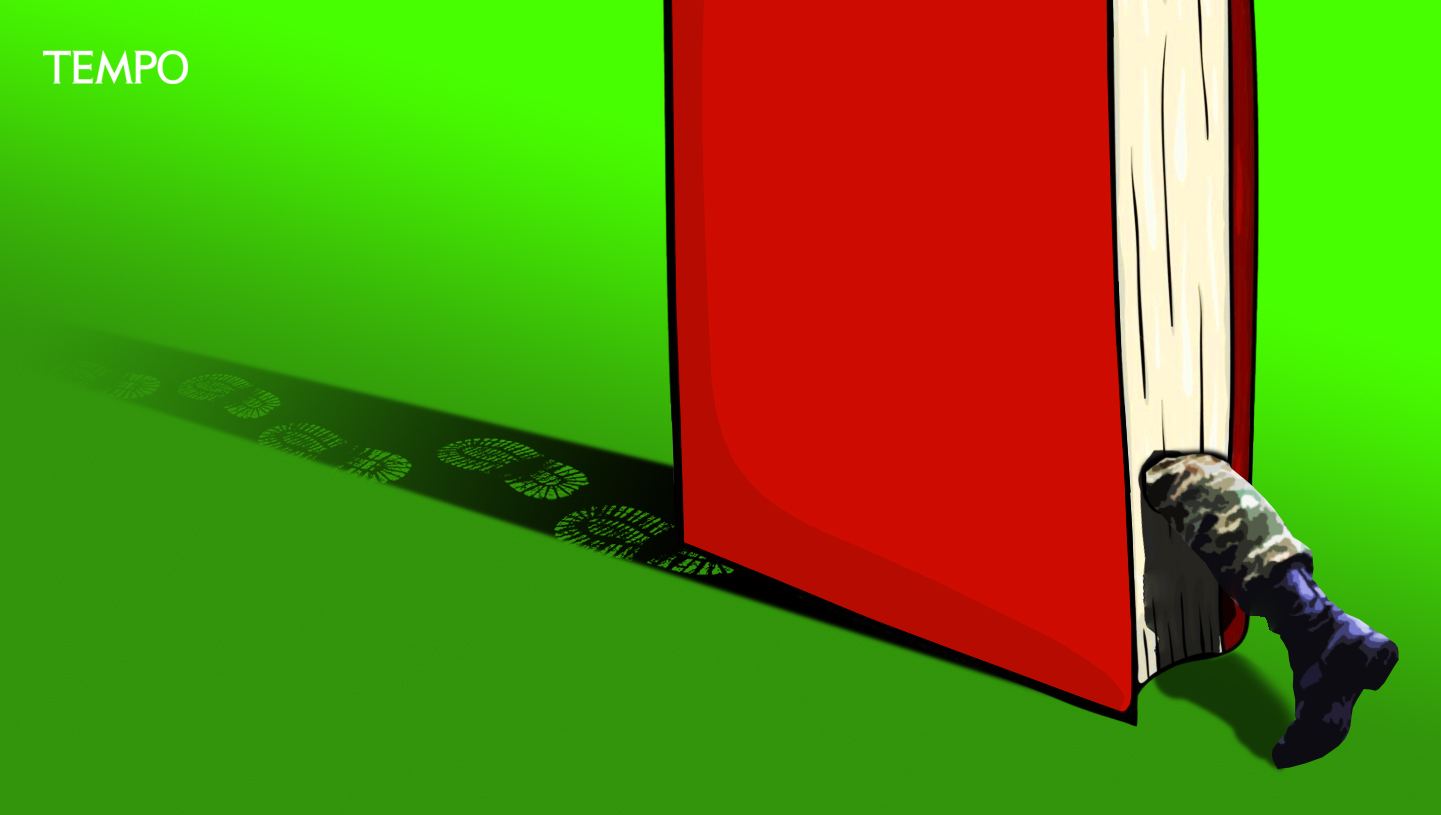Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TAK ada catatan tentang apa yang terjadi hari itu, 1.000 tahun yang lalu di Kediri. Hanya diketahui bahwa di tahun 1045 itu Airlangga turun takhta. Baginda yang baru berusia 43 tahun itu meninggalkan istana. Ia pergi ke hutan. Ia memutuskan untuk jadi pertapa.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Airlangga"