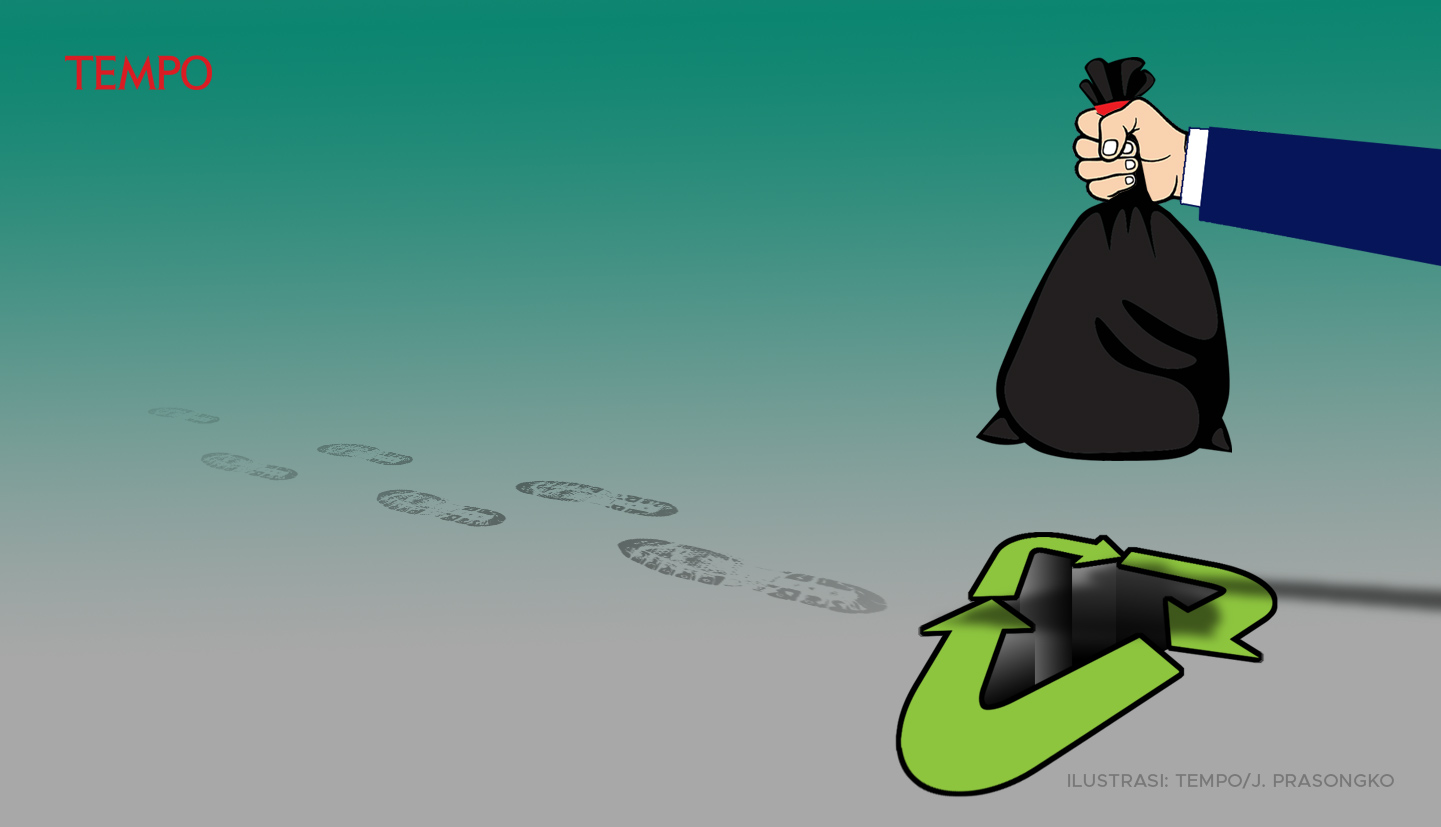Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

APAKAH Indonesia hari ini bagi orang yang lahir seratus tahun silam? Apakah negeri ini sekarang bagi Sitor Situmorang atau A.A. Navis, yang lahir pada tahun 1924?
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Seratus Tahun"