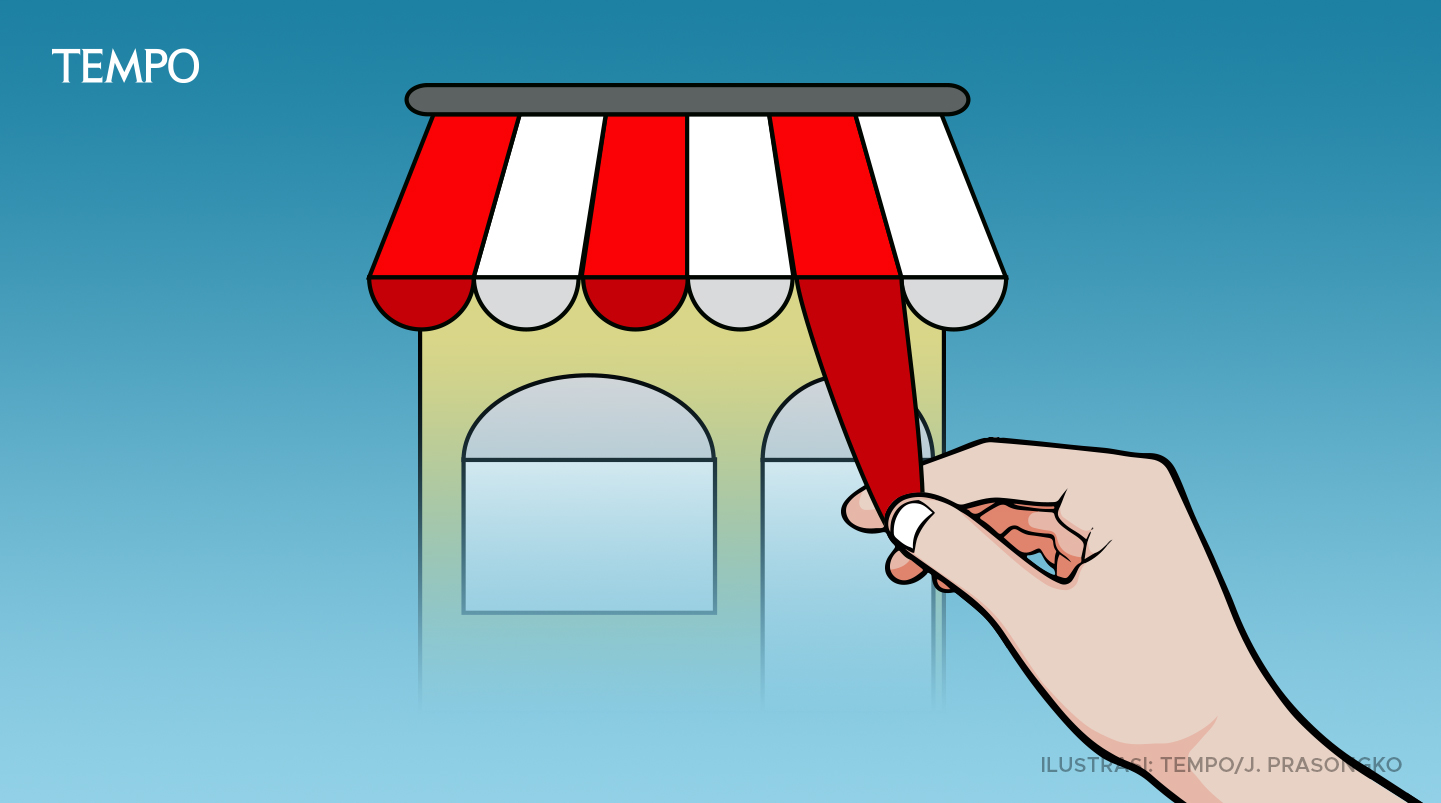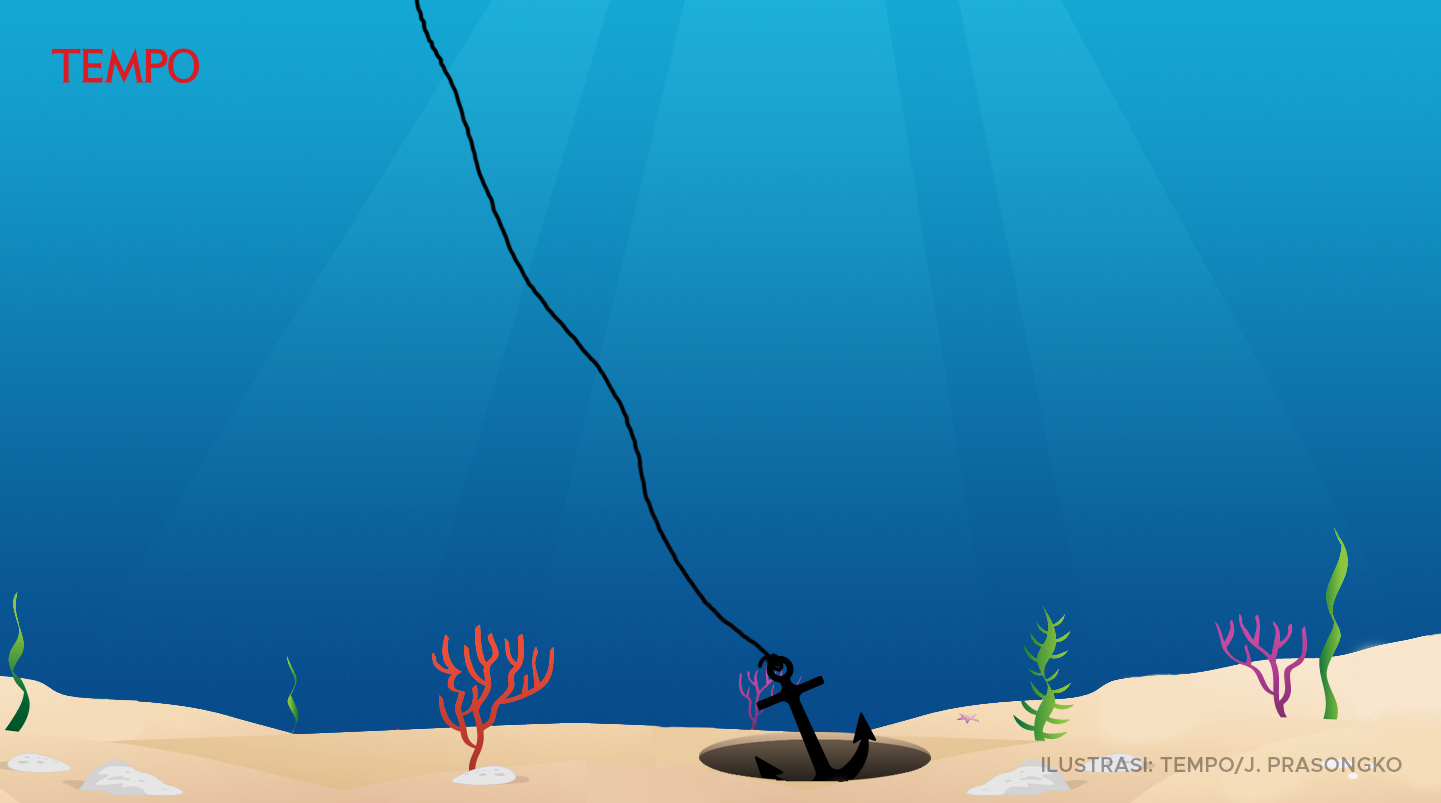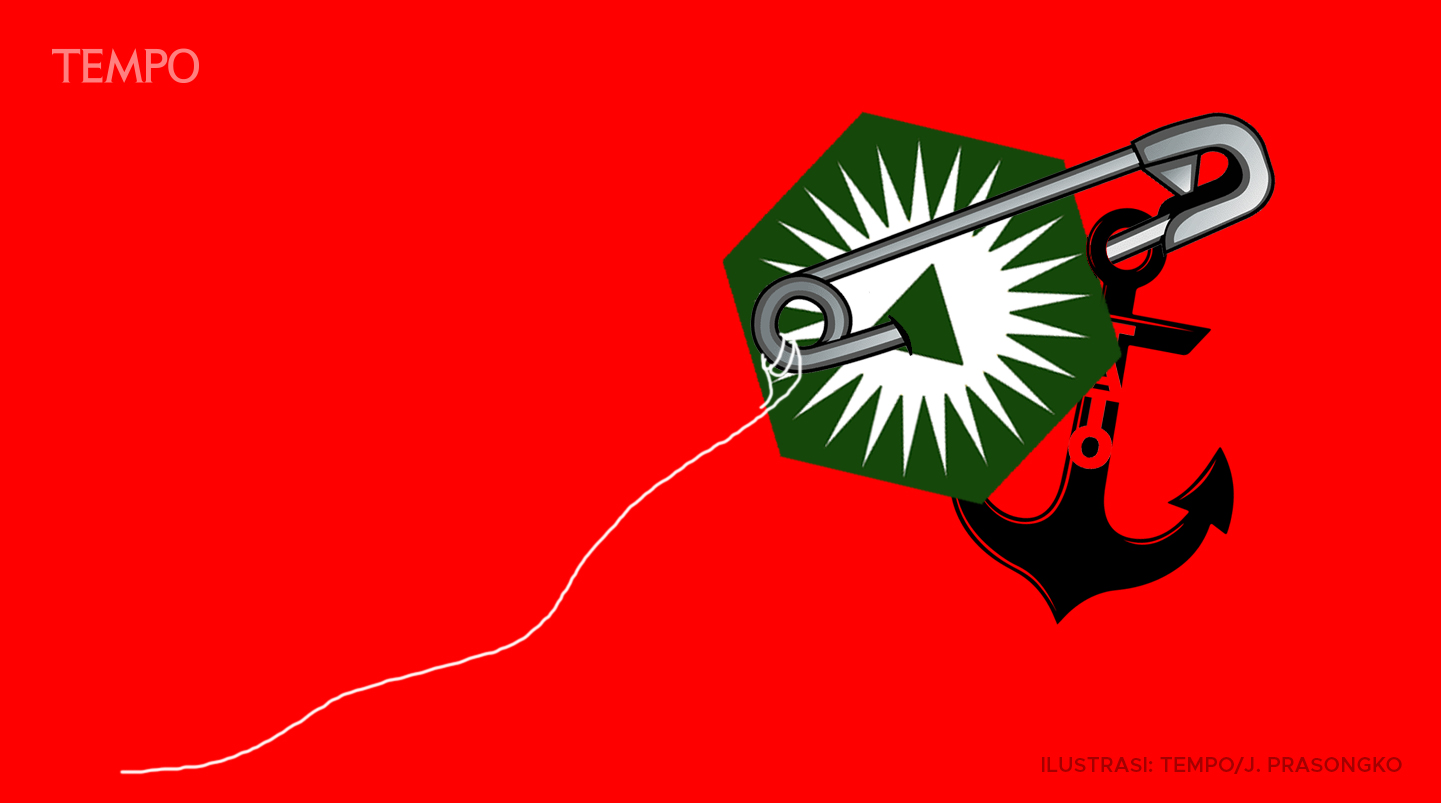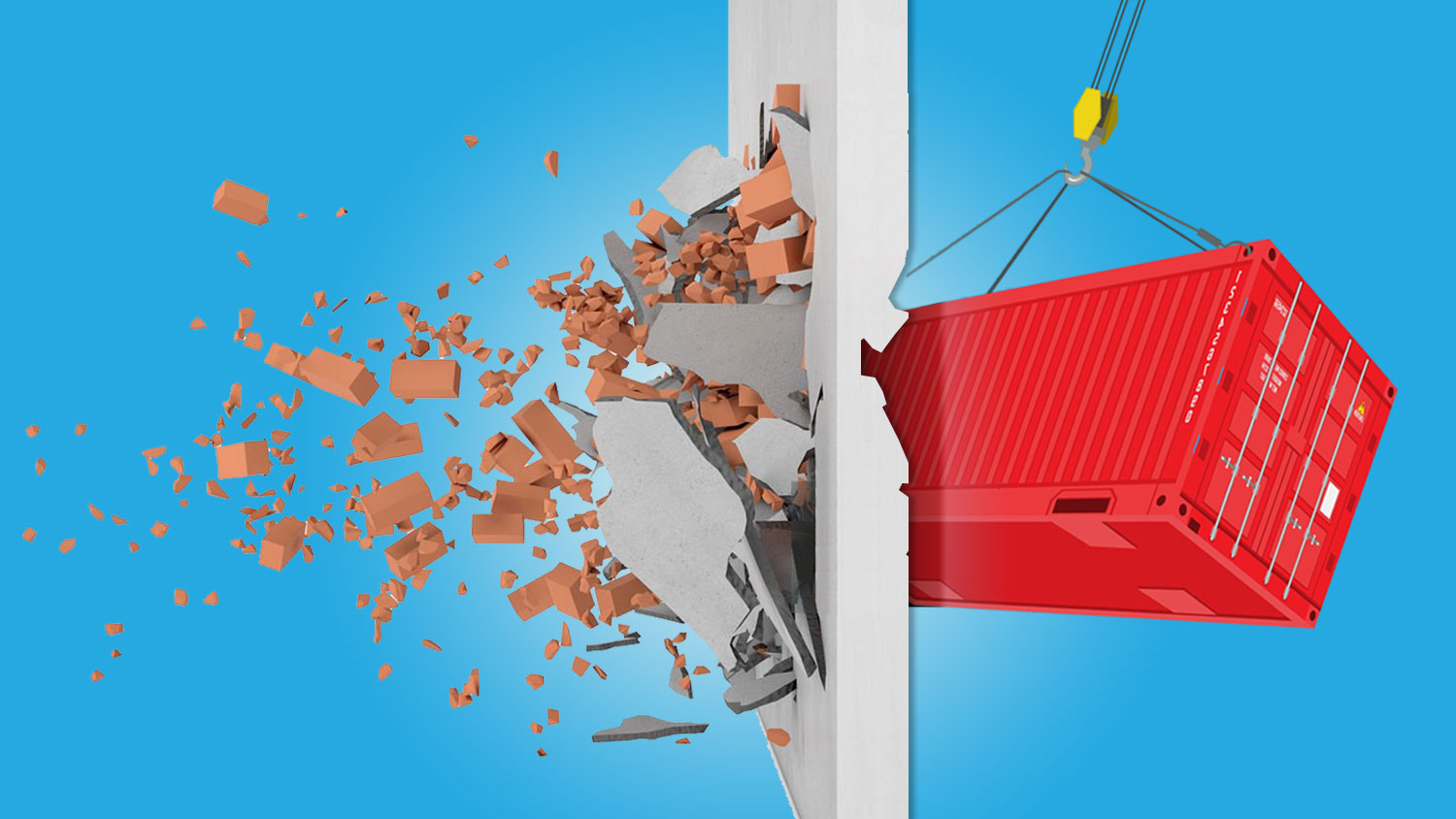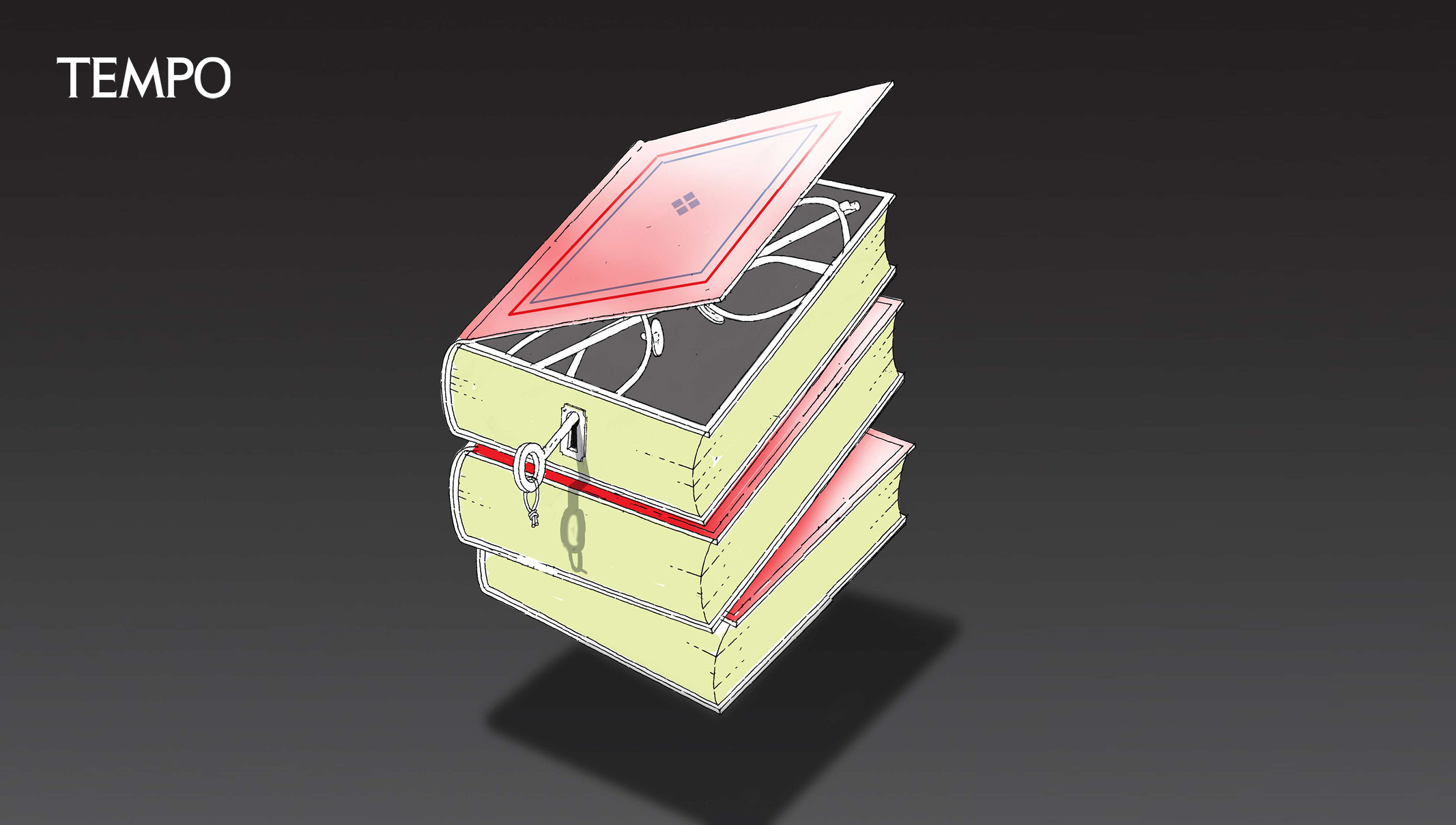Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Konser di Graha Sabha Permana Kompleks Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu, 19 April, adalah proyek kedelapan dari perhelatan jazz yang kini berlabel Smooth Jazz. Itulah pertunjukan musik yang konteksnya repertoar yang mudah kita temui di kafe lobi hotel, bahkan nomor-nomor televisi yang sama sekali tak menyebut jazz.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo