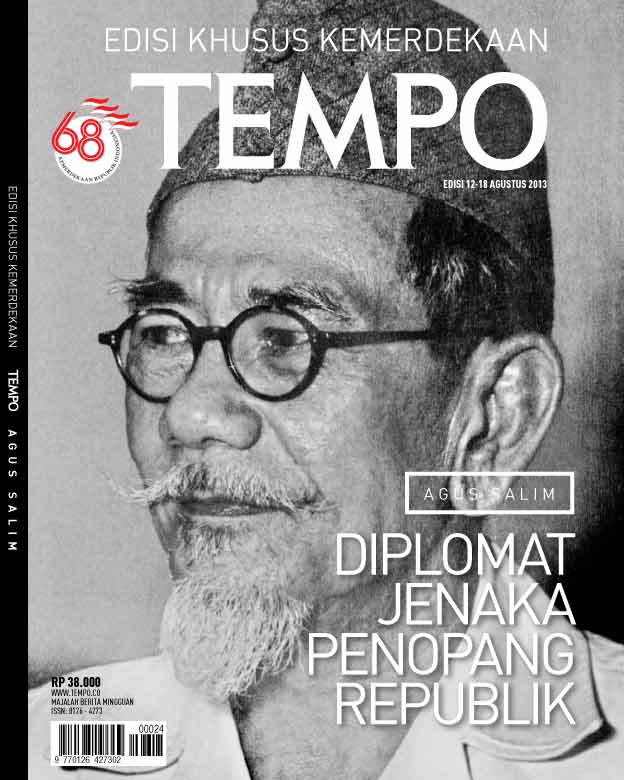Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pengumuman di papan dengan cat putih itu dipasang di pohon meranti. Isinya menjelaskan bahwa lahan itu milik masyarakat adat Muara-tae. Mereka mengklaim melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada bagian bawah tertulis kalimat "Sempekat Pesuli Lati Tana Adat Taqaak" atau "Kembalikan Hutan dan Tanah Adat Kami".
Setelah menancapkan plang, tokoh adat berfoto bersama. Ada tiga plang ditancapkan di beberapa lokasi di hutan adat di Kutai Barat, Kalimantan Timur, itu. Sejak belasan tahun lalu, sebagian lahan di hutan ini menjadi perkebunan kelapa sawit milik PT Borneo Surya Mining Jaya dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa. "Dua pekan kemudian kami tak melihat plang itu lagi," kata Petrus Asuy, tokoh warga Muara-tae, yang dihubungi lewat telepon oleh Tempo pada Jumat pekan lalu.
Tak mau kalah, mereka pasang plang kembali. Namun akhir bulan lalu woro-woro tersebut dicabut orang. Petrus akhirnya memfotokopi selebaran berisi putusan MK dan membagikannya kepada semua warga Kampung Muara-tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Warga, kata dia, bangkit lagi semangatnya setelah membaca selebaran yang dibuat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) itu.
Pada 16 Mei 2013, MK memang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan AMAN dan dua komunitas masyarakat adat, yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu. Dalam putusan Mahkamah, hutan adat yang sebelumnya menjadi bagian dari hutan negara dalam undang-undang itu harus dimaknai sebagai hutan hak. Putusan ini memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak berupa hutan.
Putusan ini membuat beberapa masyarakat adat bergerak menentang izin konsesi jangka panjang yang telah dikeluarkan pemerintah kepada perusahaan dalam pengelolaan hutan adat. Masyarakat adat Panduman-Sipituhuta di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, misalnya, memasang lima papan di wilayah hutan Kemenyan, daerah Dolok Ginjang.
Pengumuman tersebut ditulis dengan cat merah, yang menjelaskan bahwa hutan adat Panduman-Sipituhuta bukan lagi hutan negara, sesuai dengan putusan MK. "Kami pasang plang di tapal batas hutan kami yang pernah diukur bersama-sama dengan pemerintah daerah dan PT Toba Pulp Lestari," kata Ketua Dewan Daerah AMAN Tano Batak James Sinambela kepada Tempo, Jumat pekan lalu.
Sejak 2008, perusahaan yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama itu menguasai 500 hektare dari 4.100 hektare hutan Kemenyan yang ditanami eukaliptus. Secara keseluruhan di Humbang Hasundutan dan kabupaten lain, perusahaan bubur kayu milik Sukanto Tanoto ini menguasai lahan 269 ribu hektare, dengan izin untuk hutan tanaman industri. Konflik sering terjadi antara perusahaan dan masyarakat adat. Unjuk rasa juga dilakukan perwakilan masyarakat ke kantor Kementerian Kehutanan. Pada Februari lalu, polisi menangkap 16 warga sehubungan dengan konflik tersebut.
Beruntung tak ada yang mencabut papan itu. Bulan lalu Bupati mengundang pimpinan masyarakat adat untuk bersama-sama membuat tapal batas. Namun mereka menolak karena sudah beberapa kali pengukuran itu dilakukan. "Kenapa tidak pakai hasil yang lama saja?" ujar James. Dia kini menyiapkan peta tanah adat dalam format tiga dimensi untuk dipaparkan dalam pertemuan di luar negeri. "Kami," kata dia, "tetap menuntut hutan Kemenyan yang dicuri perusahaan dikembalikan ke warga adat."
Aksi yang sama dilakukan masyarakat adat Sawai Gemaf dan Sawai Kobe di Halmahera, Maluku Utara. Begitu pula dengan masyarakat adat Matteko dan Karunsi'e Dongi, Tana Luwu, Sulawesi Selatan; masyarakat adat Tumbang Bahanei, Kalimantan Tengah; warga adat Naga Hulambu, Tano Batak, Sumatera Utara; serta masyarakat adat di Papua dan Nusa Tenggara.
Putusan MK tersebut memang ibarat membuka kotak pandora. Bagi masyarakat adat, "Undang-Undang Kehutanan Tahun 1999 menampilkan wajah penjajah," kata Deputi I Sekretaris Jenderal AMAN Arifin Saleh Monang tatkala berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Wajah itu ditampilkan melalui izin kepada perusahaan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, serta intimidasi oleh aparat keamanan. Kini mereka mulai mempercayai negara. Namun, kata Monang, negara harus cepat melakukan renegosiasi antara perusahaan dan masyarakat adat, tanpa menunggu izin konsesi selesai.
Aneka tuntutan itu tak urung meningkatkan tensi ketegangan di lapangan. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sandra Moniaga, mewanti-wanti pemerintah segera turun tangan dengan mengeluarkan kebijakan transisional seperti peraturan presiden. Jika tidak, kata dia, ada potensi chaos di lapangan. "Belum lagi penunggang gelap yang mengaku-aku sebagai masyarakat adat, padahal mereka pembalak liar," ujarnya.
Sandra Moniaga tak yakin peraturan daerah yang diusulkan Kementerian Kehutanan akan menyelesaikan masalah. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menjelaskan, pihaknya telah mensosialisasi ke dinas kehutanan dan unit pelaksana teknis agar mempercepat aturan daerah.
Enam bulan lalu Kementerian meminta pemerintah provinsi mengirimkan peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat di wilayahnya. Ada 11 provinsi yang menyampaikan aturan itu. "Namun mereka tidak melampirkan peta batas wilayah, termasuk koordinatnya," kata Hudoyo, Direktur Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan.
Hadi Daryanto tak setuju dilakukan renegosiasi karena lahan yang dimiliki masyarakat adat relatif kecil. "Tinggal dienklave, dikeluarkan saja dari area konsesi," ucapnya. Cara ini sudah dilakukan dalam kasus tanah di Mesuji, Lampung. Atau penyerahan lahan untuk hutan desa di Sungai Utik dan sejumlah daerah.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Purwadi Soeprihanto tak sependapat dengan model penyelesaian lewat enklave. Menurut dia, kondisi di lapangan berbeda dengan pengamatan di atas meja. Masyarakat adat di Papua dan Papua Barat, misalnya, mengklaim semua hutan di provinsi itu miliknya. Artinya, tak ada lagi lahan yang dimiliki perusahaan telah mendapat izin konsesi dari pemerintah.
Klaim tersebut juga akan berbuntut pada permintaan fee untuk tanah ulayat kepada perusahaan pemegang izin konsesi. Aturannya, fee minimum adalah Rp 60 ribu per meter kubik. Di lapangan, kata Purwadi, tarifnya mencapai Rp 200 ribu per meter kubik. Padahal harga kayu meranti hanya Rp 800 ribu per meter kubik. Untuk biaya operasional, perusahaan harus mengeluarkan cost sekitar Rp 500 ribu sehingga banyak perusahaan kini gulung tikar. Perusahaan yang tetap bertahan, kata Purwadi, hanya mengambil kayu merbau yang harganya tinggi.
Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan berharap Kementerian Kehutanan proaktif membuat peta wilayah dan memfasilitasi pemerintah daerah membuat aturan tentang masyarakat adat. Menurut Abdon, ada banyak komunitas masyarakat adat sehingga dibutuhkan banyak peraturan daerah. Dia tak yakin anggaran pembangunan daerah mampu membiayainya. Belum lagi pengaruh dari perusahaan atau pihak tertentu kepada DPRD ketika membuat aturan.
Abdon memprediksi ada sekitar 40 juta hektare wilayah hutan adat di Tanah Air. AMAN telah memetakan 3,4 juta hektare hutan adat milik masyarakat adat. "Tak mungkin kami sendirian membuat peta. Ada kewajiban negara membuat peta itu," katanya. Abdon telah menyerahkan peta itu kepada Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Menteri Lingkungan Hidup, dan Badan Informasi Geospasial.
Deputi Pemantauan Program dan Institusi Penegakan Hukum UKP4 Mas Achmad Santosa berharap Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi mediator antara masyarakat adat dan perusahaan yang mendapat izin. Dua kementerian ini, kata Achmad, tidak mengeluarkan izin dan tak punya konflik kepentingan.
Dia sepakat perlunya kebijakan transisional karena Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat serta RUU Pertanahan baru akan dibahas DPR. Menurut dia, keterlibatan UKP4 bertujuan mencegah terjadinya konflik agraria yang semakin luas. Putusan MK, kata dia, jadi pintu masuk untuk menyelesaikan konflik itu.
Petrus Asuy sendiri tak ingin konfliknya dengan perusahaan berkepanjangan. Dia ingin kehidupan masa kecilnya pada 1970-an dapat dinikmati cucunya. Ketika itu hutan menyediakan apa yang ia perlukan. Dia sering diajak ayahnya, seorang pemburu, keluar-masuk hutan. Namun, sejak akhir 1970-an, perusahaan mulai menebang pohon dan membuka hutan tanaman industri. "Menghilangkan hutan sama artinya dengan menghilangkan budaya kami," katanya.
Untung Widyanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo