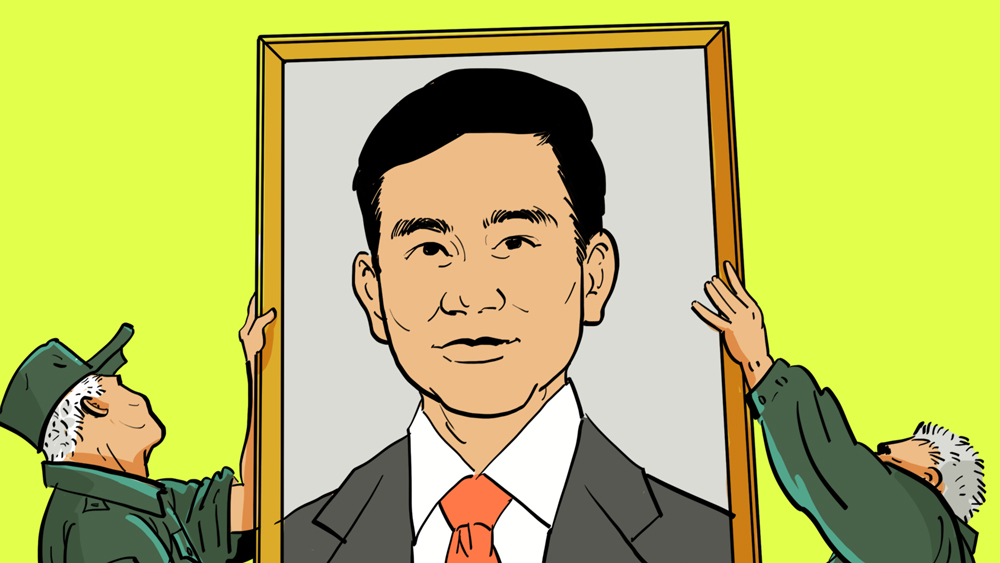Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

BIDUK itu merayap perlahan dalam senyap, menghampiri pantai di dekat Port Klang, Malaysia, akhir Februari silam. Malam mulai menyentuh pesisir, dan kabut yang bersahabat dengan gerimis seakan memberikan rasa aman bagi Hamdun—bukan nama sebenarnya. Lelaki berkulit legam itu beringsut dari buritan, lalu melompat ke bagian bawah geladak. Di lambung perahu kayu itu—mereka menyebutnya pong-pong—dia membangunkan sekitar 20 lelaki, yang selama hampir dua malam menyuruk di sana.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo