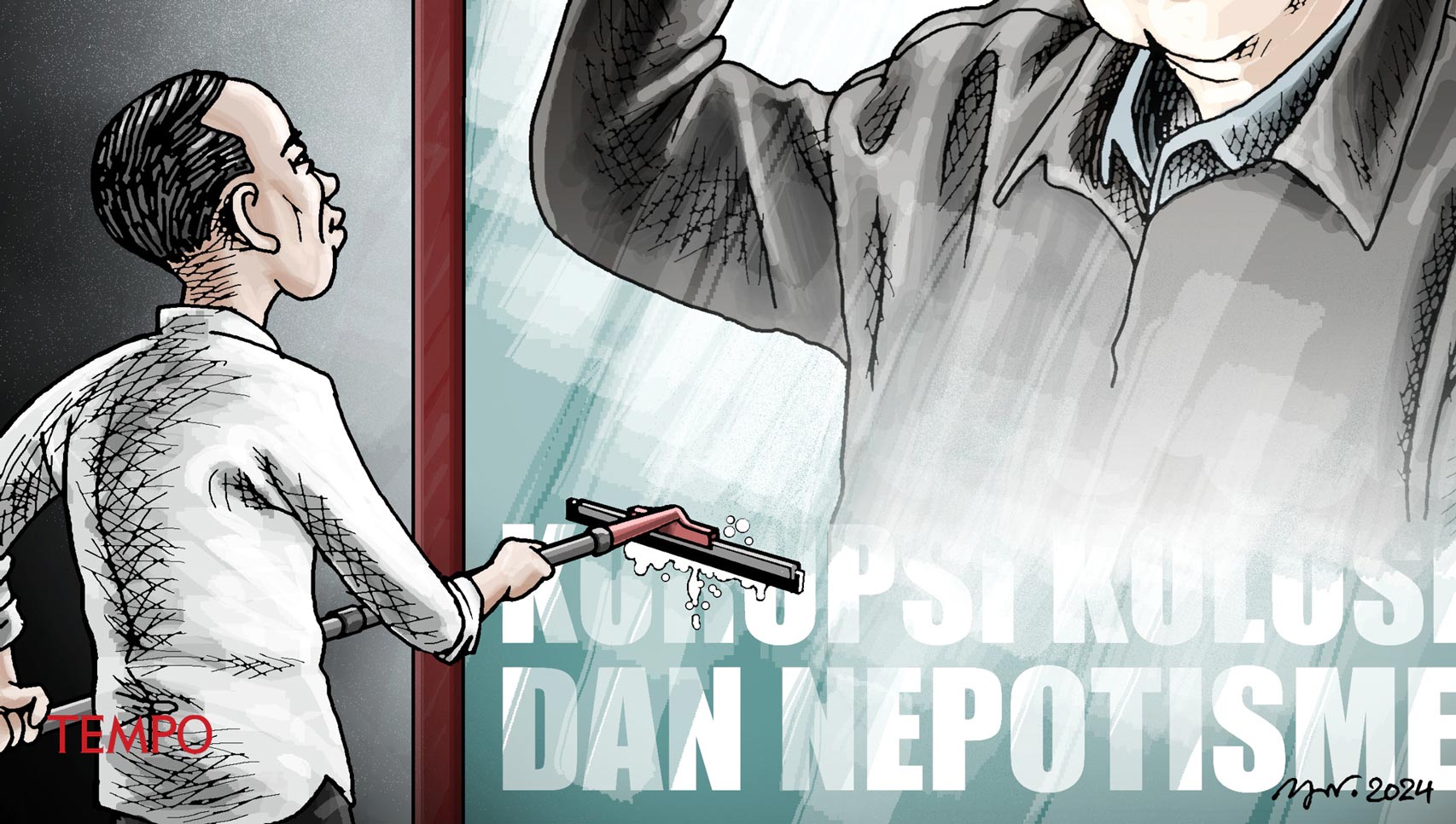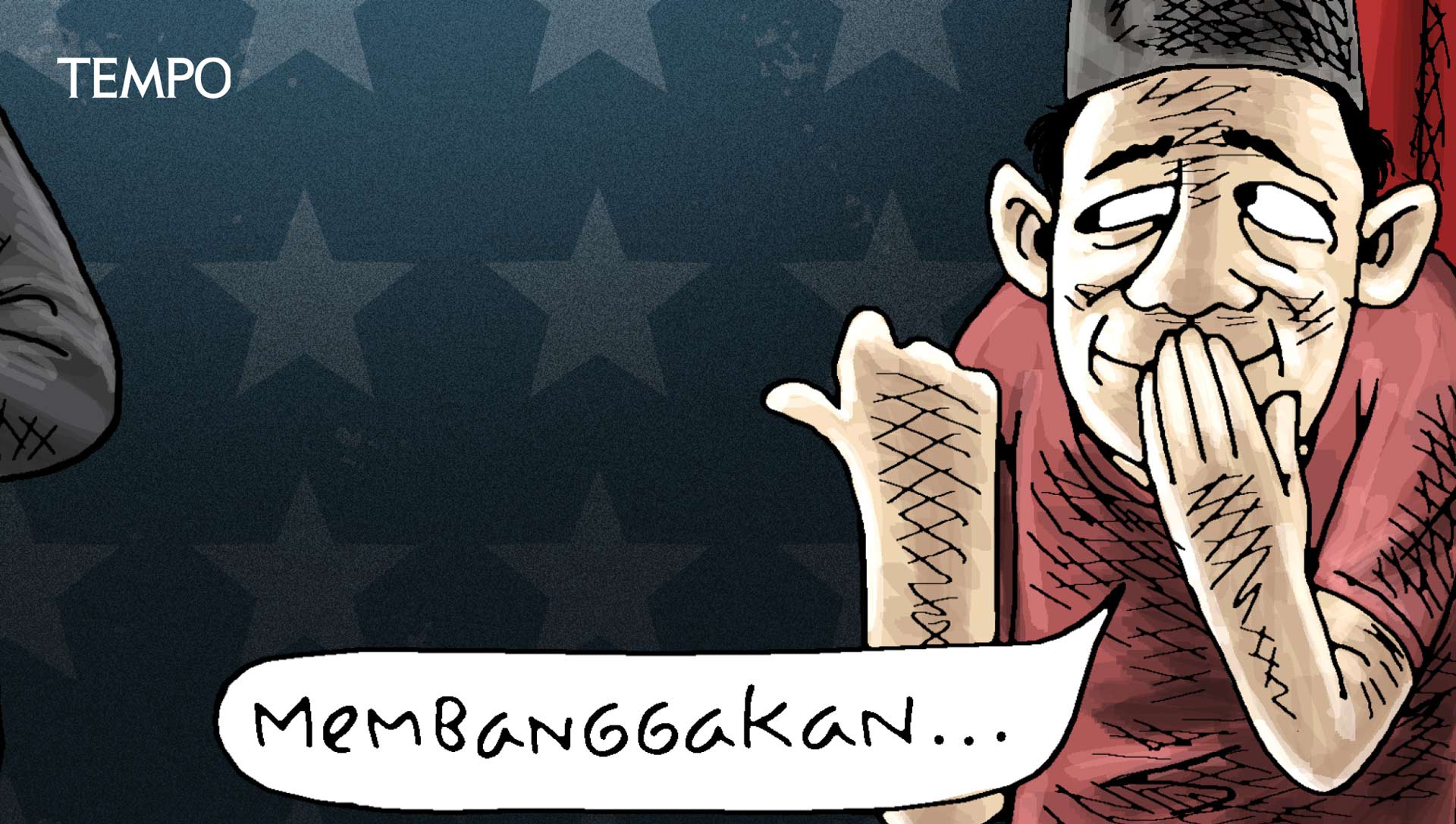Jurnalisme adalah sebuah dunia yang lasak. Ia seakan-akan ketagihan kepada "yang baru". Ada orang tewas tertembak, ada bus dibakar, dan pengungsi berhamburan, semua itu cerita yang dramatis dan menyedihkan. Tetapi, begitu mereka jadi rutin, mereka akan cenderung diabaikan oleh para pengasuh surat kabar. Dalam bahasa Inggris, berita disebut news dan dalam kata itu selalu ada unsur new (baru).
Dengan kata lain, jurnalisme adalah sebuah dunia yang peka akan terjadinya perubahan. Sebuah surat kabar mau tak mau terdorong untuk tidak melihat apa yang telah lalu. Terutama ketika tingkat perubahan kian lama kian cepat, sehingga yang kemarin kita anggap sebagai sesuatu yang kelak baru akan tiba ternyata pagi ini sudah muncul mendadak di depan pintu: future shock. Untuk menghadapi shock itu dan mengantisipasi "guncangan masa depan" itu, ketangkasan jadi soal yang menentukan.
Ketangkasan itu tentu saja menuntut organisasi yang baik. Dengan itulah sebuah surat kabar senantiasa siap mengasimilasikan apa yang baru -- juga berkenaan dengan tubuhnya sendiri, Sebab itulah, secara teratur, TEMPO mengadakan perencanaan lima tahun. Seperti kata orang, kita tidak bisa melawan masa depan. Kita harus menyesuaikan diri dengannya.
***
Perubahan yang sejak pekan lalu terjadi adalah perubahan pemimpin redaksi. Goenawan Mohamad, yang menjadi pemimpin redaksi majalah ini sejak 1971, (dan sebenarnya sudah berhenti setahun sebelum TEMPO dibredel pada 1994), tahun ini secara resmi digantikan oleh Bambang Harymurti. Dilihat dari sudut organisasi, perubahan ini bukan sesuatu yang dramatis.
Goenawan, yang menjadi pemimpin redaksi TEMPO ketika berumur 27 tahun, sejak 18 tahun lalu bersepakat dengan tim manajemen TEMPO bahwa pergantian kepemimpinan sudah harus disiapkan. Maka, ketika rekrutmen untuk memperoleh tenaga wartawan baru dilakukan, salah satu syarat yang ditentukan ialah umur. Diperhitungkan bahwa para wartawan baru itu bisa menjadi pemimpin redaksi sebelum mereka berumur 45 tahun. Dengan seorang pemimpin redaksi seusia itu, majalah ini akan dikemudikan oleh seorang jurnalis dalam usia produktif dan matang.
Bambang Harymurti kini berusia 42 tahun. Sejak 1984, sejak bulan-bulan pertama ia menjadi wartawan TEMPO, ia sudah dicatat sebagai salah seorang kandidat utama untuk, suatu hari, menjadi pemimpin redaksi. Yusril Djalinus, kini salah seorang direktur penerbitan ini, sejak 1981—ketika ia menjadi koordinator reportase—sudah menyeleksi dan mempersiapkan tenaga-tenaga kepemimpinan untuk masa depan. Ia memberi tugas kepada para wartawan muda bukan saja untuk mengumpulkan berita dan menulis, tetapi juga untuk menilai cara mereka memimpin sebuah tim. Dari hasil catatan dan observasinya itu, Yusril kemudian membicarakannya dengan Goenawan, Fikri Jufri, Zulkifly Lubis, serta anggota pimpinan TEMPO yang lain. Di antara sejumlah nama, Bambang Harymurti selalu ada dalam daftar utama.
Bambang pernah menjadi kepala biro Jawa Barat (1987), Jakarta (1987-1989), dan Washington, D.C. (1991-1994). Prestasinya selalu mengesankan, baik sebagai jurnalis maupun sebagai pemimpin tim. Energinya hampir tak pernah surut. Ia secara wajar mampu berkomunikasi dengan beragam orang. Sikapnya berimbang. Ia mudah mendapatkan sumber berita. Rasa humornya ramai—dan humor adalah salah satu syarat penting dalam pergaulan TEMPO—dan pada saat yang sama ia mampu mengilhami sebuah tim untuk mencapai hasil yang optimal. Ia hampir tak pernah marah. Ia tenang bahkan dalam suasana paling kritis. Ketika TEMPO dibredel oleh pemerintahan Soeharto, Bambang memimpin orang-orang TEMPO yang menolak bekerja di bawah kontrol rezim dan mendirikan "markas TEMPO dalam pengasingan": sebuah kantor berita untuk mencari nafkah bagi rekan-rekannya, seraya mempertahankan spirit TEMPO di sana.
Bagi TEMPO di masa depan, Bambang punya kelebihan daripada Goenawan Mohamad: ia akrab dengan teknologi. Bambang, lulusan Institut Teknologi Bandung dan Harvard University, kini juga memimpin Tim Teknologi TEMPO dalam rencana lima tahun mendatang, ketika informatika menjadi vital bagi dunia pers.
Bambang didampingi oleh Toriq Hadad, sebagai redaktur eksekutif—sebuah jabatan yang tak kalah rumit dan memerlukan kepemimpinan dengan saraf yang lebih kuat ketimbang siapa pun juga di TEMPO. Ia harus siap berdiskusi soal ide berita dan setiap hari ia harus membuat tim bergerak dalam mencari data dan menuliskannya. Toriqlah yang dari jam ke jam mengelola 40-an berita setiap pekan, yang mencakup 80 halaman dengan 55 orang wartawan yang bekerja untuk itu. Tidak mengherankan bila di tempat ramai orang jarang melihat Toriq: ia harus lebih banyak di dalam ketimbang di luar.
Toriq, lulusan Institut Pertanian Bogor, juga seorang yang sudah disiapkan sejak awal. Ia bukan saja wartawan yang tangguh, tapi juga manajer dan pemimpin tim yang efektif ketika ia menjadi kepala biro di Jawa Timur (1987-1989) dan Jakarta (1993-1994). Ketika TEMPO dibredel oleh pemerintah Soeharto, Toriq ikut "bergerilya" bersama Goenawan Mohamad, di samping mengurus TEMPO Interaktif yang dipimpin Yusril Djalinus—sebagai isyarat bahwa TEMPO tetap hidup, meskipun dimatikan.
***
Pergantian pemimpin redaksi memang bukan hal yang dramatis seperti pergantian presiden Indonesia. Tapi memang kurang lazim dalam sejarah pers di sini. Sebagian hal ini karena aturan SIUPP di masa Menteri Harmoko, yang menyebabkan pergantian seperti ini memerlukan "perkenan" Menteri secara susah payah -- satu hal yang syukur telah ditiadakan oleh Menteri Mohamad Yunus
Juga umumnya sosok sebuah surat kabar diidentikkan dengan pemimpin redaksinya: Indonesia Raya dengan Mochtar Lubis, misalnya. Sering TEMPO juga diidentikkan dengan Goenawan Mohamad.
Tetapi, sebuah surat kabar adalah sebuah institusi, juga sebuah kehidupan bersama. Ia tak pernah ditentukan oleh satu orang, bahkan ia juga ditentukan oleh para pembacanya. TEMPO sebetulnya bertahun-tahun berjalan sebagai inspirasi orang banyak. Bahwa nama Goenawan Mohamad "berbunyi", itu terutama karena kebetulan ia juga memakai "topi" lain, sebagai penyair, sebelum TEMPO lahir sampai sekarang.
Digantinya Goenawan Mohamad —dilakukan setelah majalah ini terbit kembali dari pembredelan, dan menghadapi milenium baru—menunjukkan bahwa institusi itulah yang hidup kuat, dan lebih penting ketimbang sang pemimpin. Apalagi seorang pemimpin redaksi.
Apa tugas Goenawan Mohamad kemudian? Ia akan menjadi salah seorang redaktur senior (bersama Isma Sawitri, Putu Setia, dan S. Prinka)—sebuah lapisan di bawah pemimpin redaksi. Sesuai dengan permintaan kami, ia akan tetap menulis Catatan Pinggir. Dengan itu, katanya, ia ingin membuktikan bahwa menjadi pemimpin redaksi sebenarnya "hanya sebuah pekerjaan sampingan seorang wartawan."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini