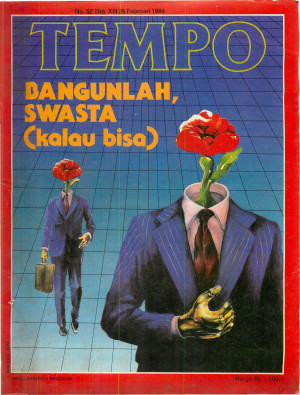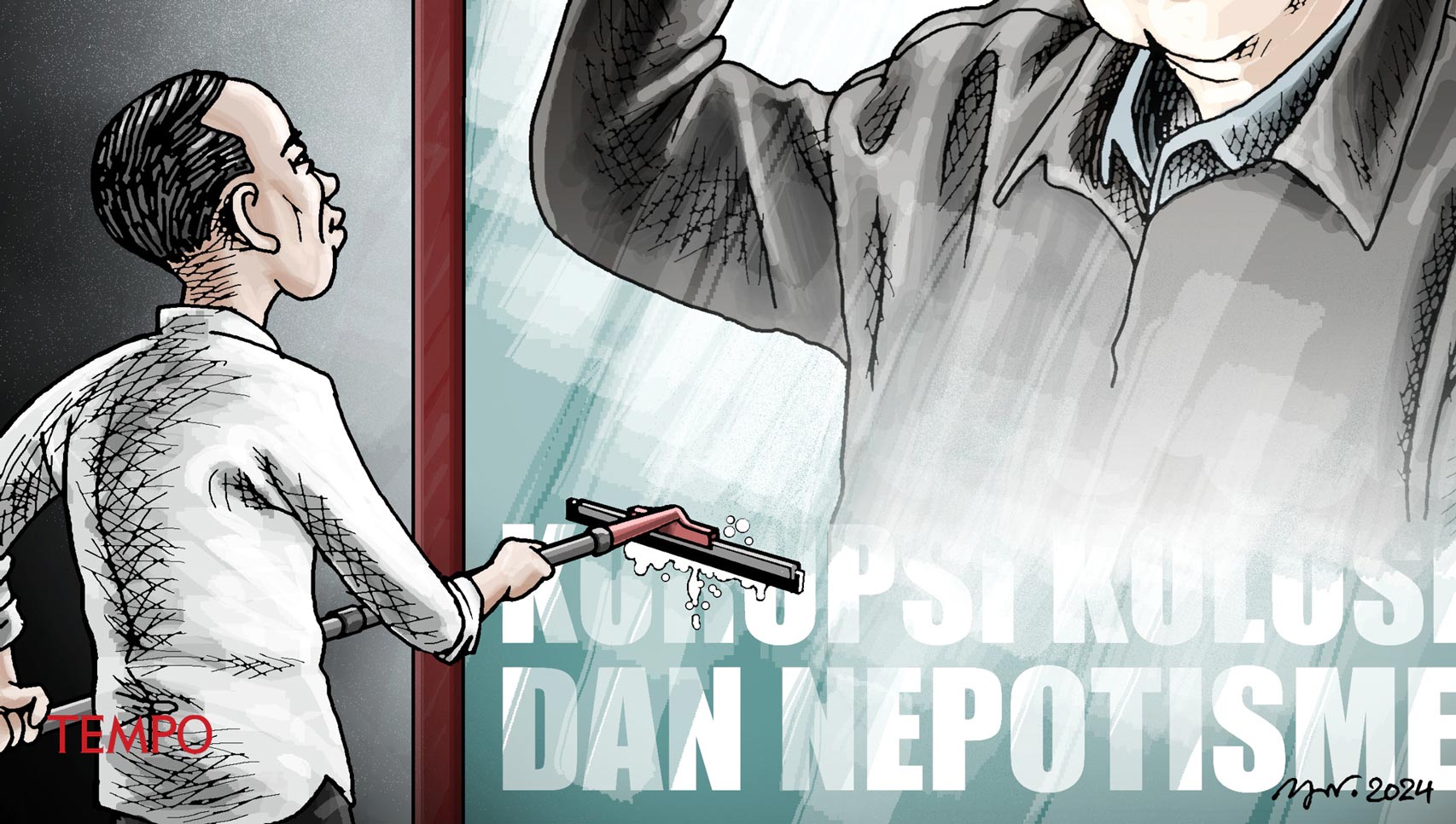SEKITAR 200 pengusaha swasta berdiskusi di Jakarta pekan lalu, dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan harian Suara Karya. Temanya jadi topik laporan utama kita pekan ini: soal-soal apa yang dihadapi dunia swasta jika harus tumbuh. Bagi orang pers, soal-soal itu bukan cuma untuk diliput dan dilaporkan ke pembaca. Soal-soal itu telah jadi soal-soal yang mereka hadapi sendiri. Maklumlah dalam 10 tahun ini dunia pers praktis telah tumbuh jadi sejenis bisnis yang penting. Dalam TEMPO nomor lalu misalnya, kita melaporkan perkembangan harian Suara Merdeka di Semarang yang baru berulang tahun. Dari koran daerah yang tak penting, kini dalam usia 34, ia beropah 150.000 sehari, memiliki sejumlah penerbitan lahir dan juga. . . pabrik pembalut wanita dengan investasi Rp 2,9 milyar. Hal yang sama bisa diceritakan tentang Surabaya Post. Koran Surabaya ini beroplah sekitar 80.000 sehari. Di salah satu lantai gedungnya yang megah dan apik, terdapat peralatan komputer yang paling maju untuk urusan penjualan. Di Jakarta, tentu kita harus menyebut Kompas yang beroplah 400.000 sehari (salah satu yang terbesar di Asia Tenggara) dan Sinar Harapan, yang berkisar 200.000 sehari. Pertumbuhan itu menghadapkan dunia pers kepada nasalah investasi, permodalan, izin, birokrasi, ketenagaan, dan manajemen. TEMPO sendiri, dalam skala yang lebih kecil tiap waktu bergulat dengan soal-soal itu. Memang, akhirnya kami tak cuma repot dengan soal bagaimana mencari dan menulis berita. Namun, ada untungnya. Paling sedikit bagi Eddy Herwanto, yang menuliskan laporan utama ini dari sejumlah hasil laporan para wartawan lain. Bergabung dengan TEMPO sejak 1974, Eddy mengenal banyak segi bisnis sebuah perusahaan karena - seperti banyak wartawan TEMPO lain - ia ikut aktif dalam proses penyusunan perencanaan perusahaan PT Grafiti pers, baik pada waktu lalu maupun untuk lima tahun mendatang. Ia juga, sebelum penuh memegang rubrik Ekonomi & Bisnis, pernah dikirim ke pendidikan manajemen - termasuk manajemen keuangan. Problem memang mengharuskan proses belajar. Dan pers sebagai usaha bisnis terpaksa belajar lebih: sesuai dengan tradisi pers Indonesia, ia punya komitmen lain. Ia merasa harus menjaga kontinyuitas usaha pencerdasan bangsa, dengan merangsang kemerdekaan berpikir dan menyatakan pendapat. Agak "kecap" kedengarannya, tapi benar. Ruangan dalam koran dan majalah kita, misalnya, tak hanya diisi oleh berita pidato atau iklan. Di sana juga ada artikel para cendekiawan dan keluhan pembaca. Beberapa penerbitan bahkan mensponsori kegiatan ilmu dan budaya (Kompas, Sinar Harapan, Pikiran Rakyat), seminar atau diskusi (seperti pernah diselenggarakan Sarinah, dan terakhir, dengan sukses, oleh Suara Karya). Ada juga yang membantu penerbitan majalah sastra Horison, dan memberikan beasiswa kepada anak pintar yang tak mampu (misalnya Femina). Di samping, tentu saja, ada bantuan sosial, seperti yang diberikan Kartini. Lalu bagaimana dengan pers yang berani dan berapi-api? Mungkin di situ juga tecermin posisi pers sebagai usaha swasta: cukup kuat untuk bisa mandiri, tapi usaha ini akhirnya terbatas bukan suatu kekuatan politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini