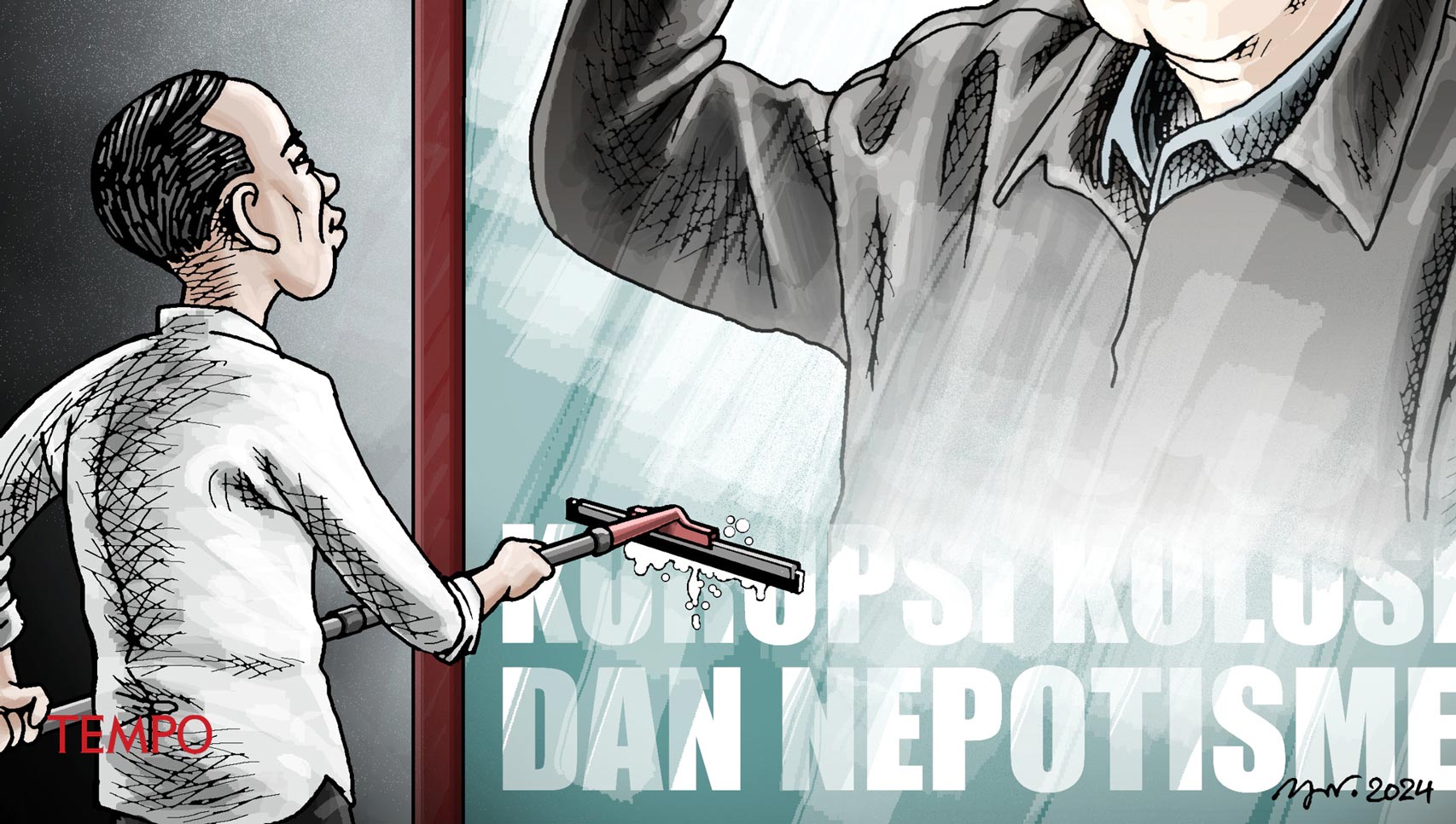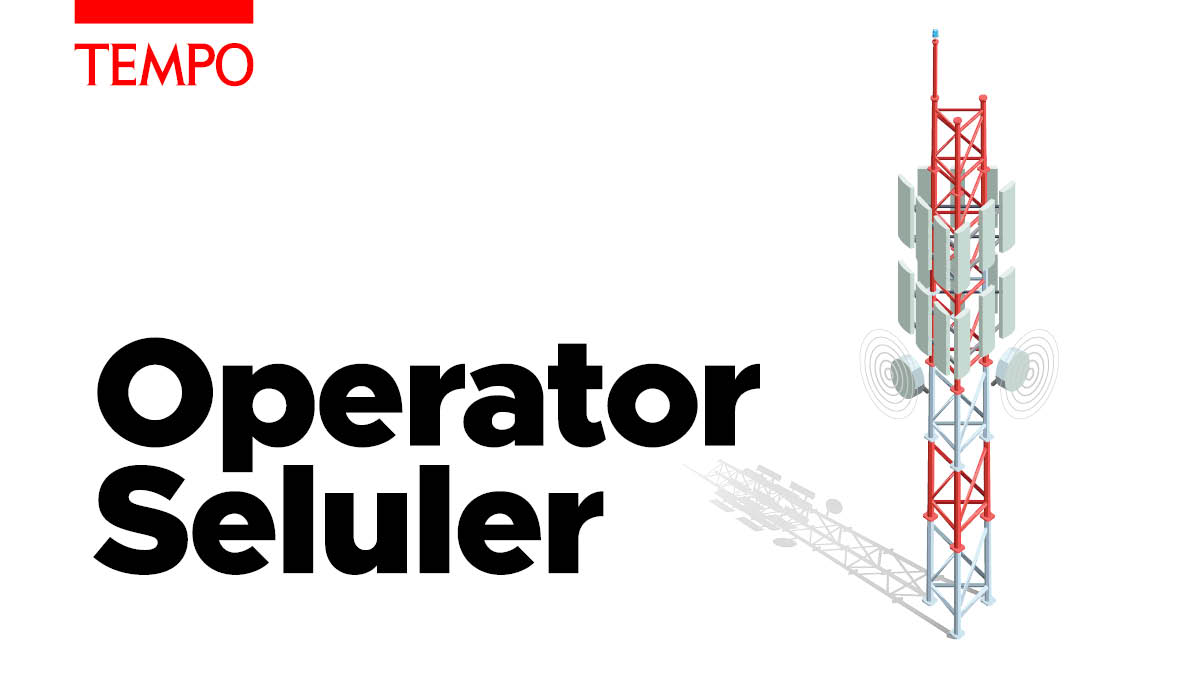Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Artikel Tempo berjudul “Islam Naik, Pelahan-Lahan” mengungkap geliat kalangan menengah-atas yang sedang mengalami ekstase spiritualitas. Wajah mereka banyak mewarnai kegiatan keagamaan di komunitas masing-masing, baik di masjid maupun di tempat pengajian. Aktivitas itu kontras dengan kehidupan mereka sebelumnya yang jauh dari nilai-nilai agama.
Satu perubahan sedang terjadi. Orang seperti berduyun-duyun kembali ke agama. Di Jakarta, Bandung, dan berbagai kota besar lain, orang seperti menginsafi kekosongan mereka pada hari-hari lalu dan mendapat “hikmah baru” tentang dunia. Ribuan masjid dipenuhi kehadiran jemaah, yang luber sampai ke halaman atau trotoar. Yang menarik, banyak pengunjung masjid ataupun anggota pengajian yang dikenal tidak berasal dari lingkungan “khas santri”.
Titik Hartono, koordinator pengajian ibu-ibu di bilangan Menteng, Jakarta, boleh jadi memberikan sebuah kisah yang merupakan contoh lain “perpindahan kultur” itu. Pengajian itu penting karena mewakili gambaran “masuknya Islam” ke kalangan “atas” dan “menengah-atas”. Dari 50 pengajian ibu-ibu yang tergabung dalam koordinasi Titik Hartono, 20 terletak di daerah yang dianggap elite seperti Kebayoran dan Menteng (sudah termasuk, misalnya, pengajian yang memakai alamat Nelly Adam Malik).
Tapi apa benar yang mendorong mereka itu? Haji Kosim Nurzeha, tenaga Dinas Rohani Angkatan Darat, menyebutkan faktor kelonggaran ekonomi sebagai salah satu sebab penting. “Setelah menjadi lebih makmur, mereka lalu merasa kurang.” Dan kekurangan itu bukan materi. Tapi mengapa merasa kurang? Karena ada sesuatu dari luar yang menyadarkan mereka tentunya, bahwa ada yang kurang. Ini adalah zaman, seperti sering dikatakan, ketika orang kecewa kepada harapannya sendiri terhadap modernisasi dan buahnya.
Islam memang sedang “naik harga”. Nama-nama orang pintar, yang muncul di televisi atau di mimbar masjid, seakan-akan menjadi “jaminan mutu”. Profesor Tubagus Bachtiar Rifa’i, Ahmad Baiquni, Profesor Doddy Tisnaamidjaja, Mukti Ali, Profesor Sadali, Profesor Garnadi, H.B. Jassin, juga Rendra atau yang lain yang terdengar namanya ke mana-mana. Kenyataan bahwa Kyai Hamam di Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah, didatangi 600 remaja yang ingin berdiskusi memang menunjukkan kebutuhan akan suatu pegangan.
Dan masjid, dalam keadaan lebih terorganisasi, lebih kuat lagi sebagai pemberi kepastian dan pertahanan jiwa yang muda terhadap ketidaktentuan masa depan atau ketidakmampuan materiel. Bahkan, andaikata khotbah yang mereka dengar sebenarnya membosankan lantaran itu-itu juga, faktor kebersamaan itu sendiri—bahkan untuk bisa mematuhi kebersamaan sementara, mereka melakukan gerak sembahyang di trotoar—rupanya cukup menyenangkan.
Di kalangan puncak sendiri, pengajian sebenarnya sudah lama umurnya. Agaknya Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Mayor Jenderal R.H. Sugandhi-lah yang membentuk pengajian di kalangan tokoh seperti Jenderal Nasution, Martadinata, dan Omar Dhani. Pengajian lalu menyebar ke daerah-daerah, merangkul para panglima, gubernur, dan bupati. Dengan kata lain, para jenderal, gubernur, atau pejabat lain yang sekarang sibuk berhaji atau salat tarawih bukanlah hal baru.
Dan yang terjadi sekarang, seperti dikatakan Abdurrahman Wahid, adalah bertemunya arus dari atas—yang secara tradisional menjadi lambang—dengan yang dari bawah. Tentu saja ada penopang di tengah-tengah. Ia mengingatkan jasa para eks kader mahasiswa Islam yang pada 1966-1969 sangat aktif. Ini agaknya lapisan yang pernah dikatakan Nurcholish Madjid sebagai “anak-anak orang Islam yang pertama masuk bangku sekolah sesudah kemerdekaan”.
Bila demikian, bukankah perkembangan yang terlihat itu sekadar sesuatu yang biasa: bahwa anak-anak pada akhirnya akan menempati tempat yang memang miliknya, yang sudah disediakan dulu sejak mereka kecil? Atau, boleh juga, masalah yang disebut Abdurrahman Wahid sebagai “kesadaran semu” dalam beragama. Dan ini tidak harus, misalnya, di kalangan bintang film atau penyanyi yang banyak berhaji akhir-akhir ini.
Artikel lengkap terdapat dalam Tempo edisi 9 Desember 1978. Dapatkan arsip digitalnya di:
https://majalah.tempo.co/edisi/2012/1978-12-09zz
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo