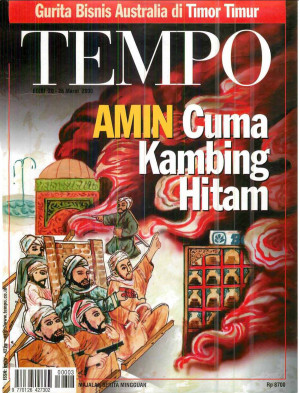Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
ARTIKEL TEMPO Edisi 13-19 Maret 2000 berjudul Ular Lamban dan Nasib Freeport menyajikan berita yang berlebihan. Beberapa fenomena lingkungan Freeport ditulis TEMPO dengan gaya membesar-besarkan sehingga bisa saja menimbulkan pemahaman yang keliru di benak pembaca—terutama mereka yang belum pernah ke Timika.
Misalnya, ”Sejauh mata memandang, dari dataran tinggi Timika... hingga jauh ke selatan di lautan Arafura, hanya hamparan lumpur yang terlihat.” Saya pernah tinggal tiga tahun dan melakukan penelitian di Tembagapura dan Timika. Tapi, ketika memandang dari dataran tinggi yang dominan, saya melihat hamparan hijau hutan tropis. Bahkan, Kota Timika dan daerah transmigrasi di sekitarnya saja sulit tampak dari ketinggian dimaksud.
Hal lain adalah membandingkan tanggul pengaman aliran tailing Freeport dengan Tembok Cina. Setahu saya, panjang Tembok Raksasa Cina itu sekitar 6.000 kilometer, sementara panjang tanggul Freeport, menurut laporan TEMPO, hanya 30 kilometer. Kalaupun Freeport nanti beroperasi ratusan tahun, mau ”ditarik” ke mana tanggul itu menyeberangi laut Arafura sehingga bisa lebih panjang dari Tembok Cina?
Yang cukup membingungkan pula, menurut TEMPO, tahi Freeport (tailing) menghancurkan adat suku Kamoro. Suku Kamoro adalah suku yang cukup besar yang mendiami daerah pantai dari Otakwa sampai Potowaiburu di dekat Teluk Etna. Karena itu, masih banyak lahan suku Kamoro yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan operasi PT Freeport Indonesia, apalagi terkena dampak. Yang sebenarnya terkena dampak tailing ini adalah kelompok-kelompok Nawaripi-Koperapoka dan Tipuka, yang memiliki lahan ulayat di sekitar Sungai Aijkwa yang digunakan Freeport untuk mengangkut tailing, dan sebagian orang Sempan di sebelah timur.
Hal lain, menurut laporan TEMPO, terdapat kawasan seluas 230 ribu hektare yang digunakan Freeport untuk menampung tailing-nya. Kalau benar angka ini, artinya, dengan metode pengelolaan tailing-nya, Freeport telah memberikan dampak terhadap lebih dari setengah persen dari luas seluruh daratan Papua. Yang benar, luas kawasan penampungan tailing itu 23 ribu hektare. Kalau Freeport mewujudkan komitmennya sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), mestinya seluruh kawasan ini bisa direklamasi menjadi lahan produktif dengan berbagai tanaman, sesudah tambang ini selesai beroperasi. Hal yang kurang-lebih sama terjadi pada Danau Wanagong, yang digunakan Freeport untuk menampung batuan penutup, yang menurut TEMPO biotanya tersiksa. Beberapa teman di Freeport yang tahu benar keadaan Danau Wanagong memberitahukan bahwa danau ini bukan terbentuk karena aliran masuk dan keluar dalam bentuk sungai, sehingga tidak ada biotanya seperti yang dimaksud TEMPO.
Tanpa perlu berlebihan, semua pihak yang berpikir obyektif tentu menyadari bahwa operasi raksasa seperti ini pasti memiliki dampak yang relatif lebih besar terhadap lingkungan diban- dingkan dengan kegiatan sebagian industri yang lain. Tapi mungkin ini harga yang harus kita bayar sepanjang tulang punggung perekonomian kita masih tetap bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Mestinya majalah sekaliber TEMPO melaporkan apakah yang dilakukan oleh Freeport untuk mengelola dampak lingkungannya sudah tepat, misalnya dengan membandingkannya dengan pertambangan-pertambangan lain di dunia, termasuk di negara maju. Selain itu, TEMPO perlu pula melaporkan apakah peraturan-peraturan yang kita miliki dan pihak-pihak yang bertugas menegakkannya sudah efektif dalam mengatur dan mengawasi operasi Freeport sehingga tidak terjadi dampak-dampak yang seharusnya bisa dihindari.
AGUS SUMULE
Universitas Cenderawasih
[email protected]
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo