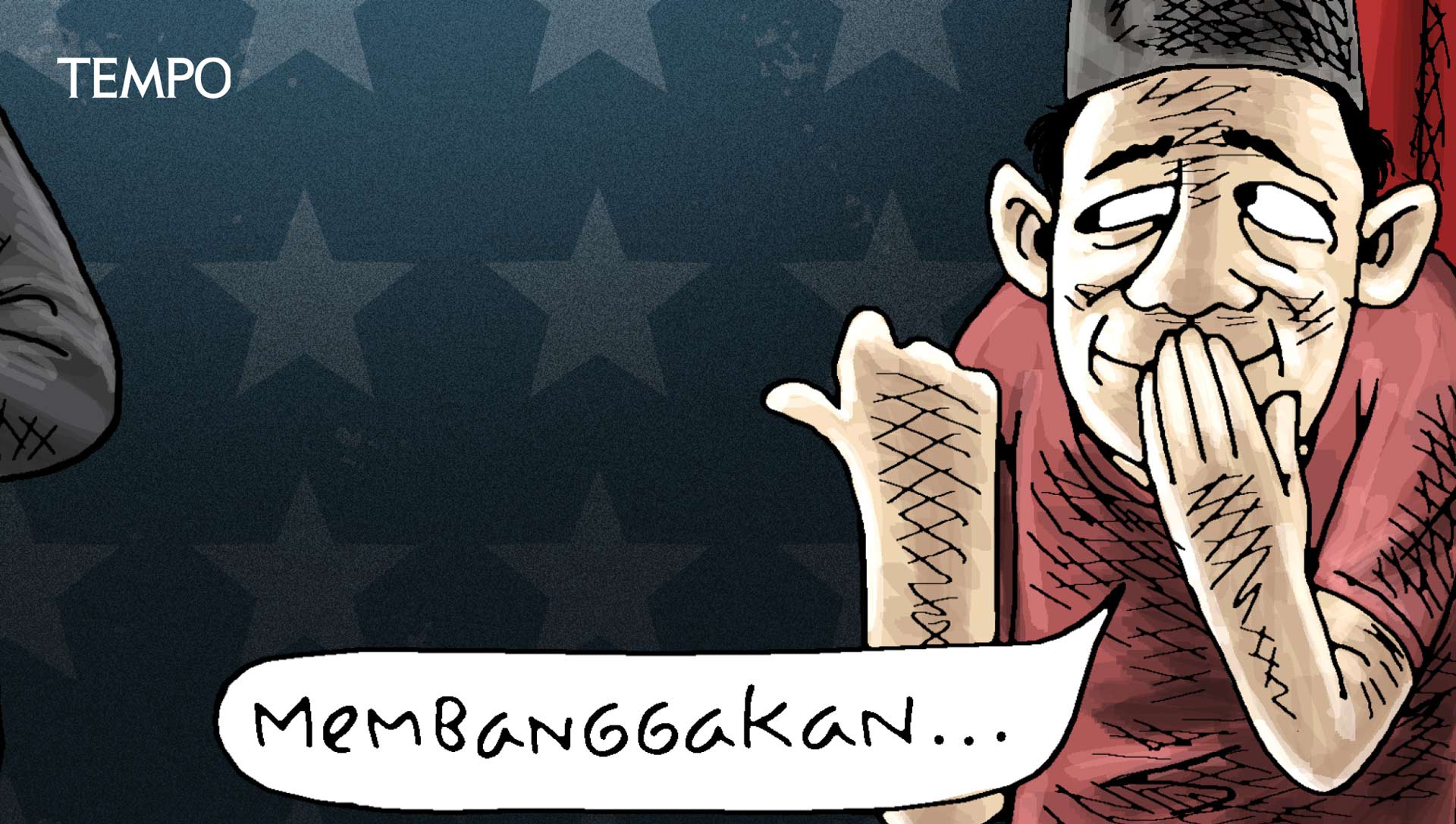Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Departemen Keuangan mengklasifikasi barang mewah ke dalam beberapa kategori tertentu, dengan tarif PPn BM mulai dari 10 hingga 75 persen. Penetapan ini terkesan tidak terencana, dilihat dari berbagai kejanggalan dalam klasifikasi barang dan nomor harmonized system yang tidak lengkap. Kebijakan ini sepertinya diambil sebagai bentuk penyesuaian ekonomi untuk mengimbangi beban akibat utang luar negeri terhadap anggaran pemerintah dan neraca pembayaran. Setelah sebelumnya melakukan pengetatan anggaran dalam bentuk kontraksi ekonomi dan pengurangan subsidi. Untuk tahun anggaran berjalan ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak hampir Rp 179,9 triliun.
Entah atas dasar apa pemerintah melakukan klasifikasi barang mewah kena pajak ini yang sebagian besar adalah barang-barang elektronik dan perlengkapan rumah tangga. Kalaupun dikatakan barang mewah, barang kena pajak tersebut merupakan perlengkapan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Perubahan tarif yang memberatkan ini akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang sudah rendah. Keadaan ini akan melesukan dunia usaha dengan mengurangi target penjualan. Bukan hal yang tidak mungkin akan menimbulkan pengurangan tenaga kerja. Lagi-lagi, kecenderungan asimetris dari kebijakan pemerintah ini mesti ditanggung bebannya oleh masyarakat luas.
Dalam sistem ekonomi Islam, pajak (dharibah) bukanlah sumber pendapatan tetap dan utama dari baitul mal (kas negara). Sumber tetap dan utamanya berasal dari fa’i, ghanimah, anfal, kharaz, jizyah, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, serta zakat. Zakat disimpan dalam pos khusus dan hanya didistribusikan kepada delapan kelompok yang tertera dalam Alquran.
Apabila sumber pemasukan tetap baitul mal di atas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat, baru negara memungut pajak dari kaum muslimin. Pajak dikenakan dari sisa nafkah (kebutuhan hidup) muslim yang kaya, yaitu harta yang merupakan sisa dari pemenuhan kebutuhan primer dan sekundernya yang ma’ruf. Besarnya pajak yang diambil harus memperhatikan asas keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan (taraf hidup) tiap individu yang kena pajak.
Pendapatan pajak temporer ini semata-mata hanya untuk memenuhi pengeluaran wajib baitul mal seperti kebutuhan fakir miskin, ibnu sabil, dan jihad. Pengeluaran untuk membayar kompensasi (gaji) dan nonkompensasi yang penting. Kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi rakyat akan mengalami penderitaan. Juga kebutuhan akibat keterpaksaan seperti menanggulangi bencana alam dan melunasi utang negara.
Tidak akan pernah ditemukan pajak atas pertambahan nilai atau penjualan barang mewah. Pajak benar-benar dikenakan atas residual income orang muslim yang kaya sesuai dengan taraf kemampuan individual. Itu pun hanya dipungut apabila sumber tetap (utama) baitul mal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan wajib masyarakat.
Jelas sekali, perpajakan dalam sistem ekonomi kapitalis berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Sebab, asas yang membangun sistem ekonominya pun berbeda. Ekonomi Islam dibangun untuk menjamin kebutuhan primer setiap individu masyarakat dan membantu kemungkinan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya setiap anggota masyarakat. Sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan mekanisme distribusi kekayaan di tengah-tengah umat melalui cara yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.
AULIYA ASH SHIDDIQ
Bandung
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo