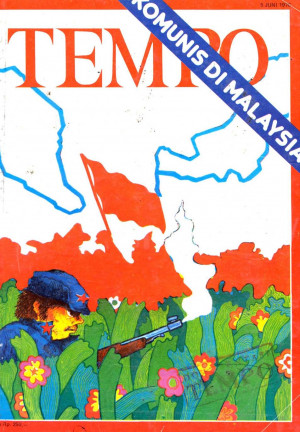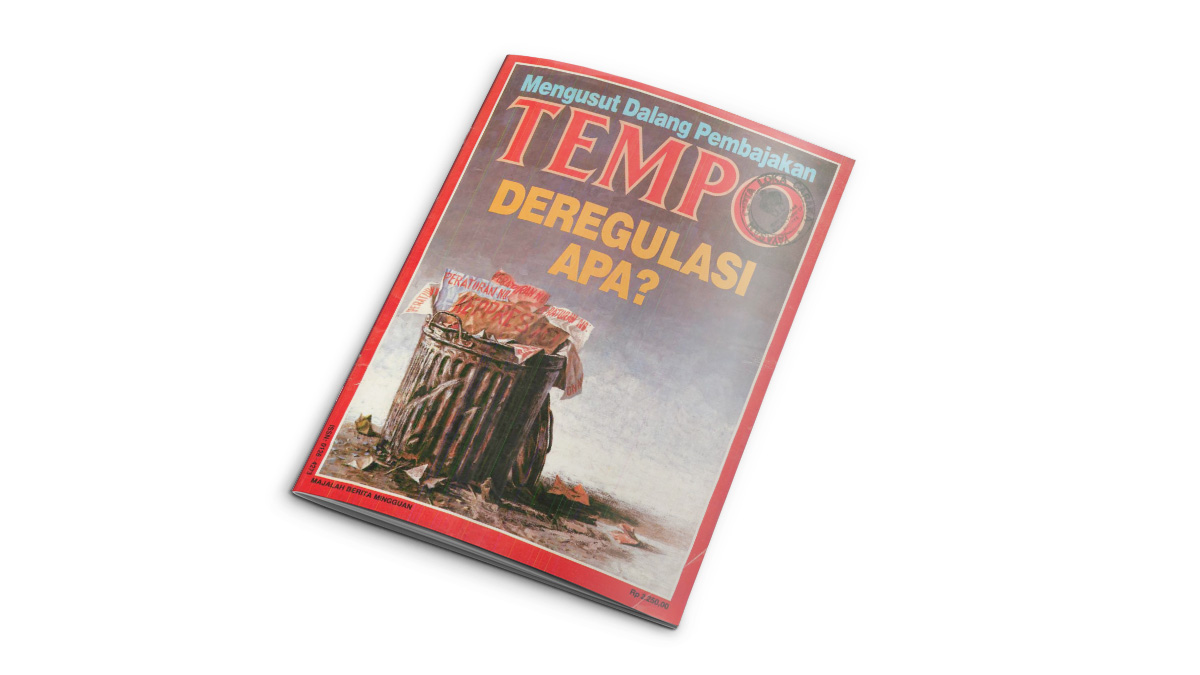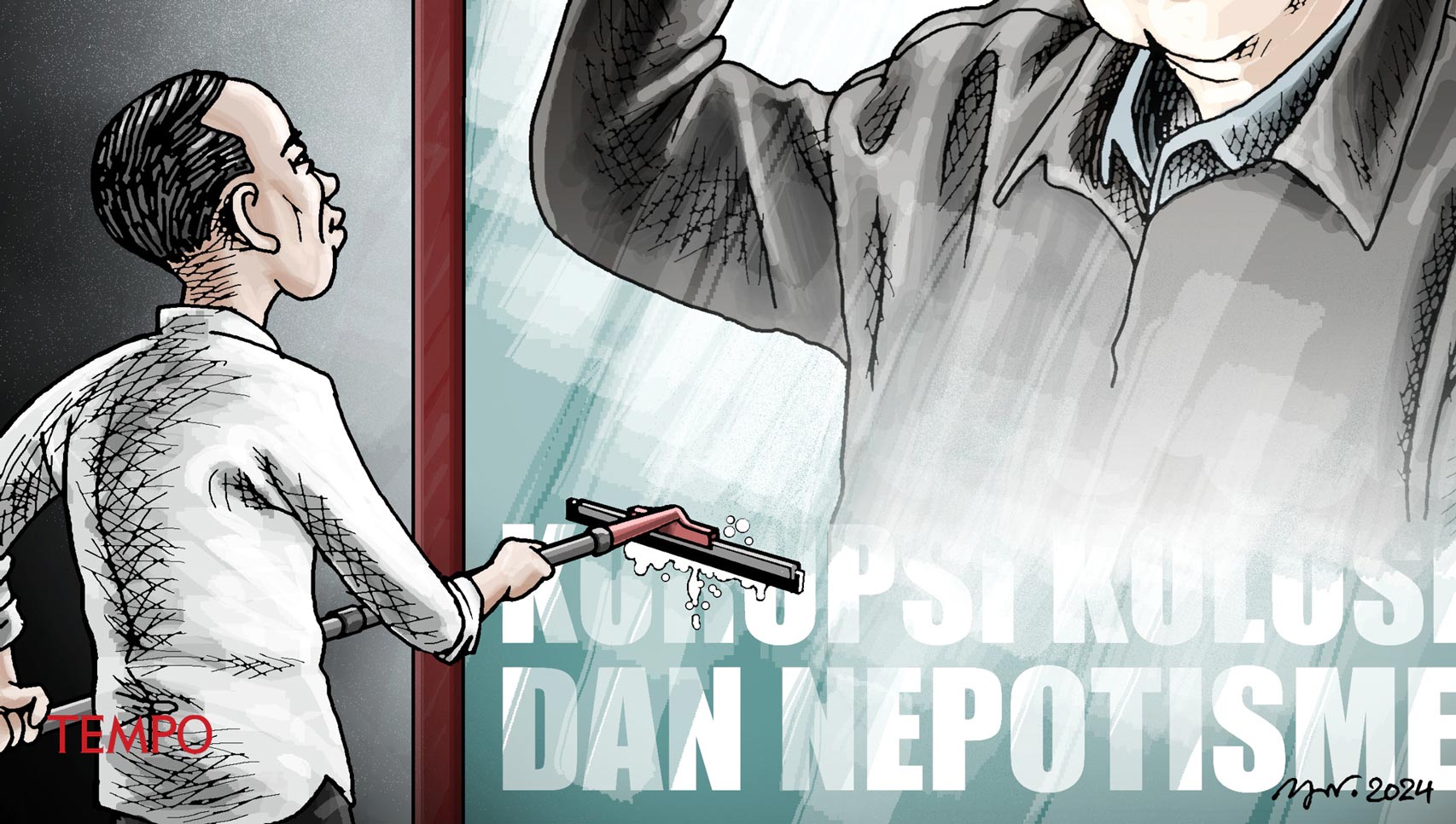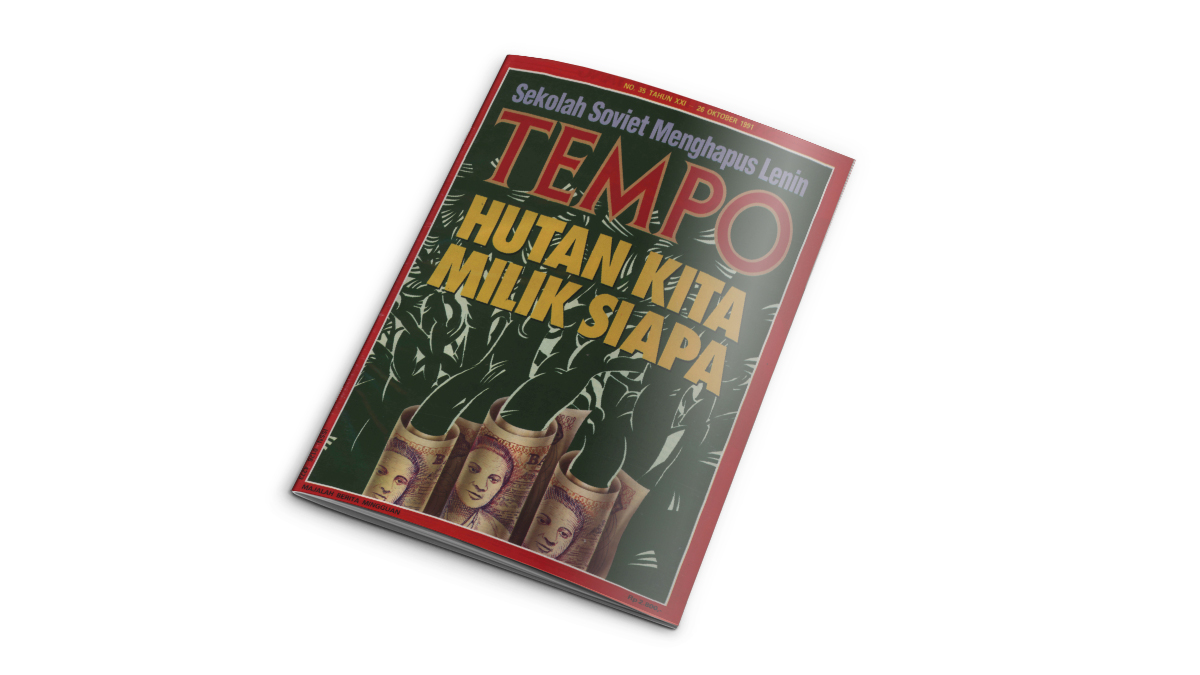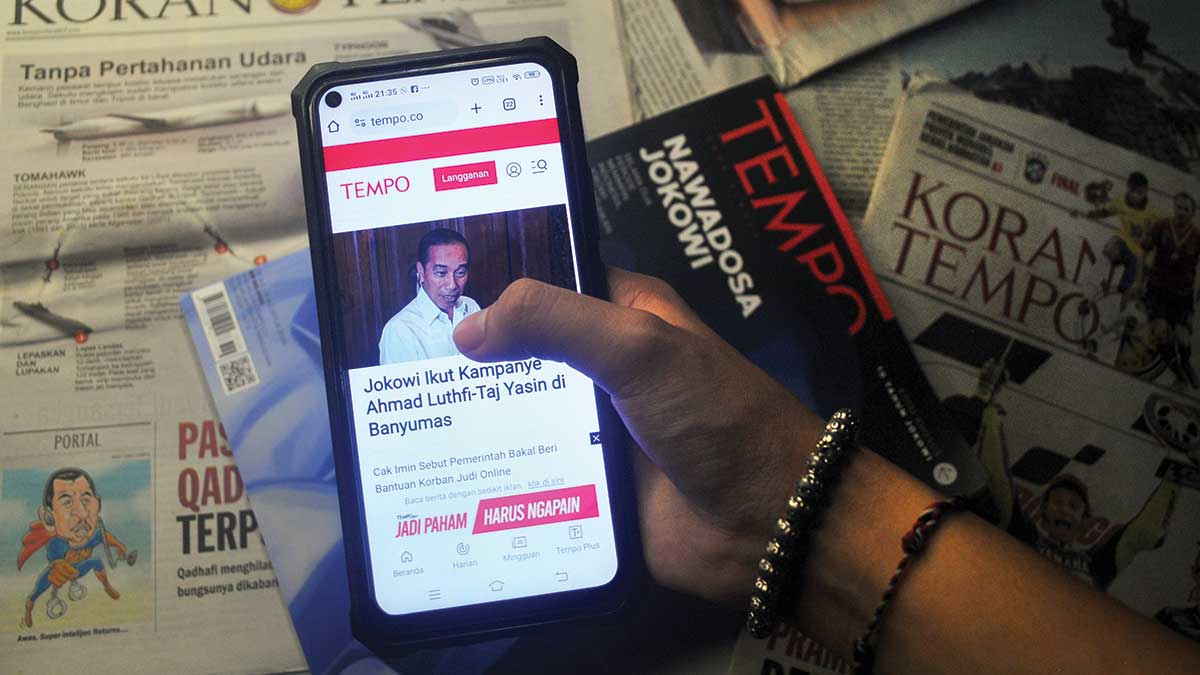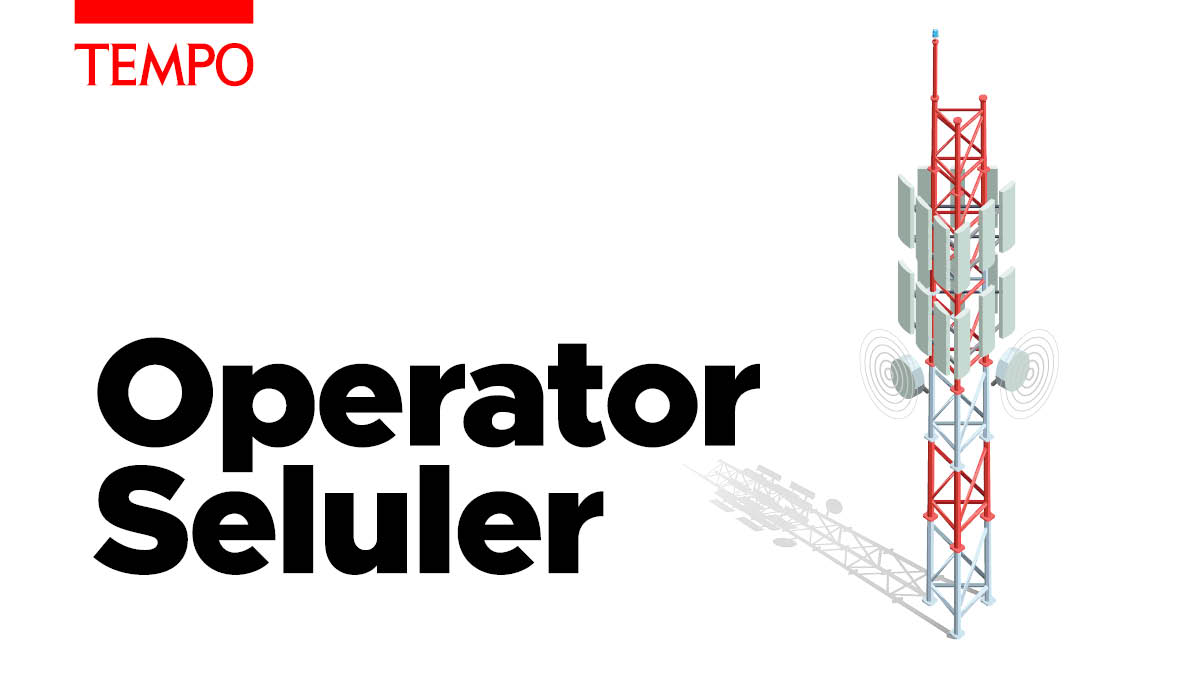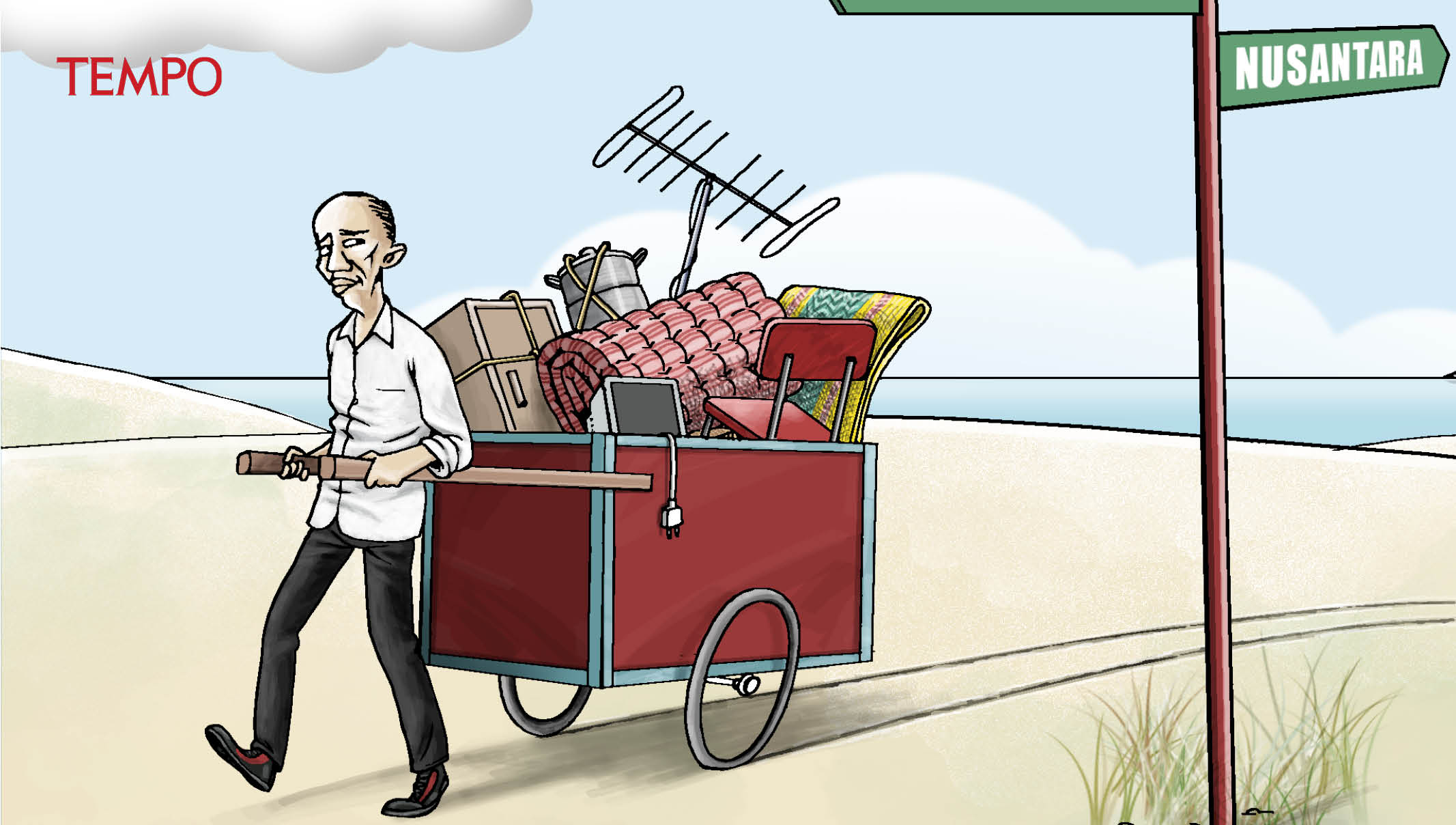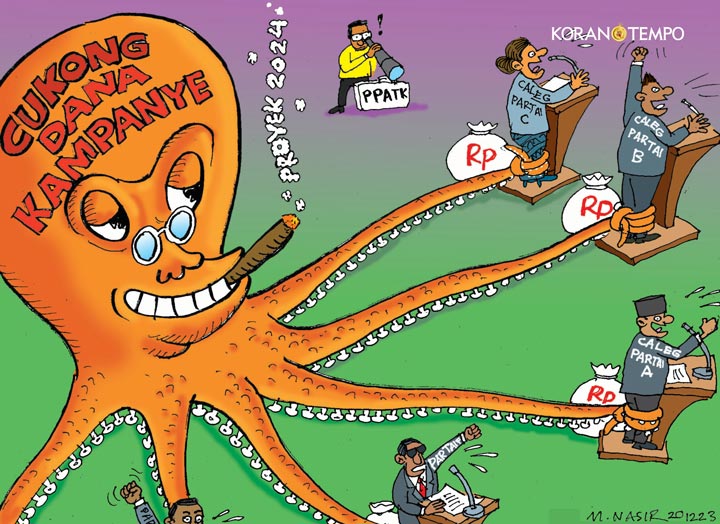MENYEBUT kata subak tentu dengan cepatnya membayangkan wajah
pulau Bali. Organisasi pengairan yang tak ada duanya di dunia
itu begitu terkenalnya, sempat memjadi bahan penelitian yang tak
habis-habisnya dari berbagai kalangan. Dari buku agenda
penerimaan tamu di Pemda Kabupaten Badung misalnya jelas
terlihat dalam setiap bulan sekitar 3 rombongan dari luar Bali
yang ingin minta penjelasan tentang subak ini. Dan konon, di
luar Bali terutama daerah Jawa Tengah sistim pengairan yang
mencontoh subak dan mereka namakan Dharmu Tirta, sedang
dikembangkan. Tentu secara tidak langsung subak telah menjadi
bahan promosi yang sejak dulu ampuh buat Bali, dan subak telah
ikut memberi tamu buat kamar-kamar hotel kecil dan menengah di
kota Denpasar. Artinya subak sejak lama berpartisipasi di bidang
pariwisata.
Bagaimana halnya kalau subak itu dilihat dari dalam? Kepala
Dinas Pertanian Daerah Tk.I Bali, ir. Sukaca, memang tak
mengatakan secara tegas, bahwa mutiara Bali itu sedang "sakit".
Tetapi ketika masalah subak ini diseret ke dalam gelanggang loka
karya pertengahan Maret lalu, ir. Sukaca ada berucap: "gejala
melemahnya partisipasi Krama (anggota) Subak saat ini nampak
sekali, terutama pada subak-subak sekitar kota". Diberikan
contoh seperti merajalelanya sistim tulak sumur, yaitu sistim
penanaman padi yang tidak seragam dan tidak teratur. Contoh lain
adanya bangunan subak terutama saluran ke sawah-sawah yang
terlantar karena di sana-sini dibangun perumahan. Lalu, berbagai
macam sengketa yang cukup merumitkan.
Tentang tulak sumur jelas akibat lemahnya kesadaran krama subak
dan tentu saja lemahnya awig-awig subak (hukum dalam subak).
Jelas dalam peran Iran subak-- tertulis atau
tidak--sistim penanaman padi harus mengikuti kcrta masa, artinya
saat menanam padi ditentukan batas waktunya. Biasanya dalam cat
hal lamanya batas waktu tak lebih dari seminggu -- disebut awuku
-- sebelum dan sesudah batas waktu itu dikenakan denda dan
sanksi yang cukup berat. Tetapi didobraknya ketentuan ini tak
sepenuhnya kesalahan petani. Di pinggiran kota, atau pada jalur
pariwisata di mana pekerjaan lain menanti, sawah menjadi
"pekerjaan sambilan". Sedang petani ini mengejar tugas lain
seperti berburuh, berdagang, jadi kusir dokar dan lain-lain. Dan
karena pekerjaan di luar bertani ini tak ada ketentuan waktu,
pekerjaan di sawah pun menjadi tidak tentu, tergantung sepinya
pasaran kerja di kota. Akibatnya jelas sekali, sistim tulak
sumur sukar untuk diberantas.
Di pinggir barat Kota Denpasar terjadi pula kasus tentang
saluran subak yang lama terkatung-katung dan tak terpecahkan.Ini
menyangkut pula perkembangan kota Denpasar yang kesohor
semerautnya. Sebidang tanah sawah dijual. Seorang pengusaha --
kebetulan saja WNI Cina--membelinya dan membangun pabrik di
situ. Celakanya, di tengah sawah ada saluran air yang mengairi
Subak Semila. Bagaimana mengatasinya? Subak Semila memang telah
cukup payah untuk memperjuangkan saluran airnya yang tersumbat
di tengah-tengah, melalui Pekaseh (Ketua Subak), melalui Kepala
Desa, Camat sampai ke Bupati. Tetapi toh sang pengusaha bertahan
diri sambil memperlihatkan sertifikat hak milik, sementara yang
punya lahan sawah itu dulu tidak ikut pusing-pusing, karena ia
bukan anggota subak semila. Masalah yang terkatung-katung sampai
saat ini, sempat pula singgah di forum loka karya tempo hari.
Loka Karya merumuskan dalam sebuah saran, bunyi lengkapnya
"dalam mutasi tanah sawah, haruslah ditekankan bahwa jual beli
tidak termasuk prasarana yang ada, baik sebagai saluran pembawa
maupun saluran pembuangan". Saran ini memang logis dan
terkandung niat menyelamatkan subak. Kalau saluran pembawanya
tersumbat -- seperti Subak Semila -- bagaimana krama Subak di
hilir memperoleh air? Atau kalau saluran pembuangan ditutup, air
akan tergenang dan bisa-bisa menyebabkan banjir. Tetapi rumusan
loka karya subak itu baru saran.
18 Mulut
Sistim pengairan subak sudah dikenal mulai abad pertama tahun
Caka. Sejarah perkembangannya tertulis dalam prasasti-prasasti
di zaman kerajaan. Ia tak bisa dipisahkan dengan kehidupan yang
penuh dengan upacara-upacara keagamaan. Menurut ir. Putu Djapa
Winaya M.Sc. dari fakultas Pertanian UNUD subak tak lain adalah
"organisasi para petani sawah yang memperoleh air dari satu
sumber".
Data tahun 1971 menunjukkan luas Bali seluruhnya 5.620 km2 atau
562.000 ha. Dari luas ini 21,8 prosen adalah sawah, artinya
sebanyak 122.316 hektar. Kalaupun dari tahun itu sampai sekarang
ada ladang yang disulap jadi sawah, namun angka jumlah sawah itu
naiknya praktis tak seberapa, karena ada pula--dan bahkan
banyak--sawah dijadikan pabrik, art shop, lapangan tennis,
perumahan dan lainnya. Sedang penduduk Bali sekarang katakanlah
2,15 juta jiwa. Maka setiap satu hektar tanah sawah hidup 18
orang . Kalau kita ambil target minimum kebutuhan beras tiap
kepala per tahun 120 kg, maka setiap hektar sawah paling sedikit
harus berproduksi sebesar 2.160 kg tiap tahun agar bisa mengisi
mulut yang 18 itu. Kalau dihitung secara populer saat ini dengan
perhitungan gabah maka didapat angka 4.320 kg. "Jelas dari data
itu kalau saia para petani masih bercocok tanam secara
tradisionil target produksi itu mustahil akan dapat dicapai,
ujar ir. Putu Djapa Winaya. Ientusaja data di atas dimaksudkan
beras yang masuk mulut, belum lagi yang dipakai untuk upacara
keaamanan yang setiap saat perlu beras mengisi sesajen.
Seperti diketahui Subak boleh dihilang "kebudayaan tradisionil"
seperli pula rekannya kesenian Bali lainya. Kalau kesenian Bali
sudah diseret ke gelanggang loka karya, seminar, lalu terakhir
perlombaan, maka subak akan mengikuti jalur itu. Subak sudah
diseminarkan, maka nayris tak ada jalan lain kecuali dilombakan
saja. "Kami tidak menganjurkan perlombaan subak. karena kami
maklum suatu perlombaan yang diadakan pada subak yang
pembinaannya belum mantap mungkin sekedar merupakan kejutan
sementara yang tidak banyak dapat diambil manfaatnya untuk
jangka panjang". Ini kata-kata Jelantik Sushila dari Dinas PU
Propinsi Bali. Barangkali ini betul. Membuat sesuatu lebih baik,
tak mesti dengan jalan berlomba. Yang diperlukan adalah
meningkatkan pembinaan dengan lebih berencana dan mantap.
Tetapi masalahnya-- untuk di Bali-- terlanjur percaya, bahwa
jalan pembinaan terbaik justru perlombaan. Sementara Jelantik
Sushila yang tidak menganjurkan bukan pula berarti tidak setuju
perlombaan. Maka begitulah, subak pun diperlombakan dengan
berbagai batasan dan katagori yang berbeda penilaiannya di
tiap-tiap kabupaten agar tidak begitu over acting. Maklum
kekayaan subak di tiap kabupaten tidaklah sama.
Ir. Sukaca mengusulkan agar lomba subak dititik beratkan pada
pembangunan pertanian, pemberantasan sistim tulak sumur serta
penanggulangan hama. Kriteria yang dinilai misalnya
intensifikasi Bimas dan Inmas, paket pupuk, effisiensi
penggunaan tanah, kelengkapan subak seperti adanya awig-awig
yang tertulis, kas, lumbung bibit, regu pemberantas hama,
kelompok pemuda-pemudi tani, penggunaan bibit jenis unggul dan
tak lupa sistim pemberantasan hama. Ir. Putu Djapa Winaya
sarannya tentu saja sama, dengan tambahan produksi tertinggi per
hektar, keberhasilan pembagian air, dan besar kecilnya jumlah
sengketa.
Jengkal Tangan
Organisasi subak tidak ada hubungannya dengan desa, baik desa
adat maupun desa dinas . Ia berdiri sendiri dengan anggota para
petani yang sawahnya mempunyai air dari satu sumber. Karena itu
I Gst Ketut Kaler, seorang tokoh agama Hindu mengingatkan agar
otonomi subak dilindungi. Bukan iu saja, kalau memang perlu baik
juga dibentuk Badan Pembina Subak, diambilkan dari tokoh-tokoh
petani membantu pekerjaan Pekaseh. Semacam LSD untuk desa. Namun
yang paling penting menurut Ketut Kaler adalah perhatian
pemerintah terhadap subak, merawat dan membangun dam, bendungan,
saluran induk tak mungkin dipikul krama subak tanpa bantuan dana
pemerintah. Tentang timbulnya sengketa, Kepala Binmas Hindu dan
dan Budha Departemen Agama Propinsi Bali ini menganjurkan agar
bangunan-bangunan pembagian air mulai dipermoderen sesuai dengan
perkembangan. Sampai saat ini dipakai dasar tek-tek (memakai
jengkal tangan, untuk mengetahui berapa jumlah air yang
diberikan kepada sawah setelah dihitung luasnya). Pada saluran
pembagi -- terbuat dari kayu atau bambu -- sering tidak dapat
selalu dikontrol oleh Pekaseh. Petani yang nakal, di bawah kayu
pembagian air menuju, sawahnya dilubangi, agar air nyerocos
lebih banyak. Di musim kering inilah sumber sengketa. Sampai
terjadi pembunuhan. Pencatatan dan pengaturan air ini jika
dilakukan secara "ilmu sekarang" sedikitnya masalah sengketa
sesama anggota subak menjadi berkurang.
Lalu masalah Pekaseh yang kerjanya tidak ringan sementara tak
dapat imbalan sudah dianjurkan oleh loka karya subak pertengahan
Maret itu untuk diperhatikan nasibnya. Entah sampai di mana
subak mentaati loka karya.
Subak, seperti halnya nasib kesenian Bali lainnya, tidak bisa
diramalkan secara pasti, apakah tetap ada atau berkembang atau
sirna? Sekarang memang ada suara-suara yang menganjurkan agar di
Bali didirikan "Museum Subak" di mana ada sebidang sawah dengan
perlengkapan subaknya yang komplit, seperti zaman kerajaan tempo
dulu. Subah"yang komplit" memang saat ini tidak ada lagi,
seperti lumbung bibit dan "lumbung kekayaan bersama" menghilang.
Bibit bisa dibeli di BUUD, kekayaan bisa diganti dengan iuran
dan uangnya ditaruh di bank. Namun agaknya "Museum Subak" bukan
pertanda akan tergusurnya mutiara Bali yang kesohor ini, tetapi
cuma konsumsi pariwisata.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini