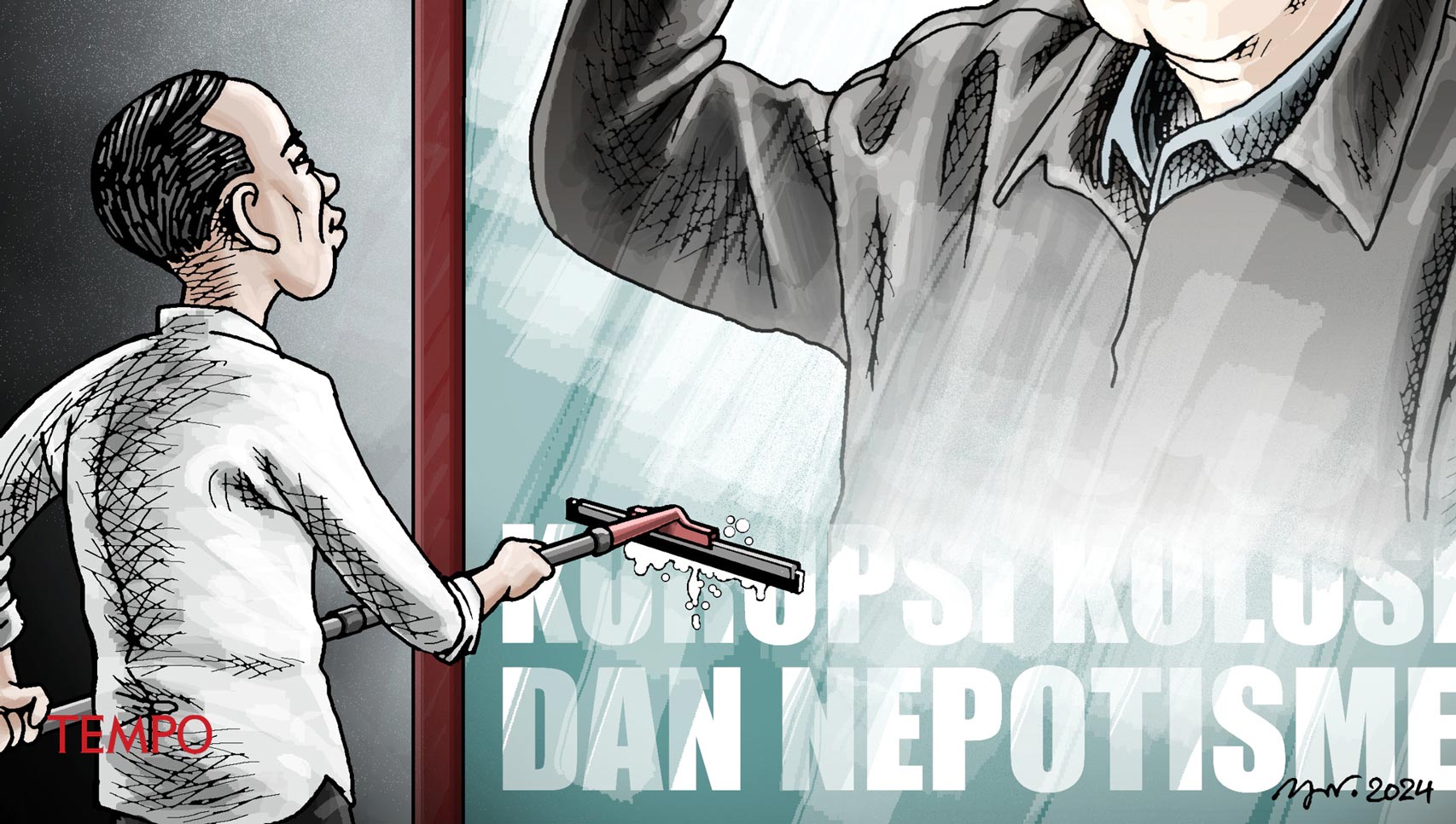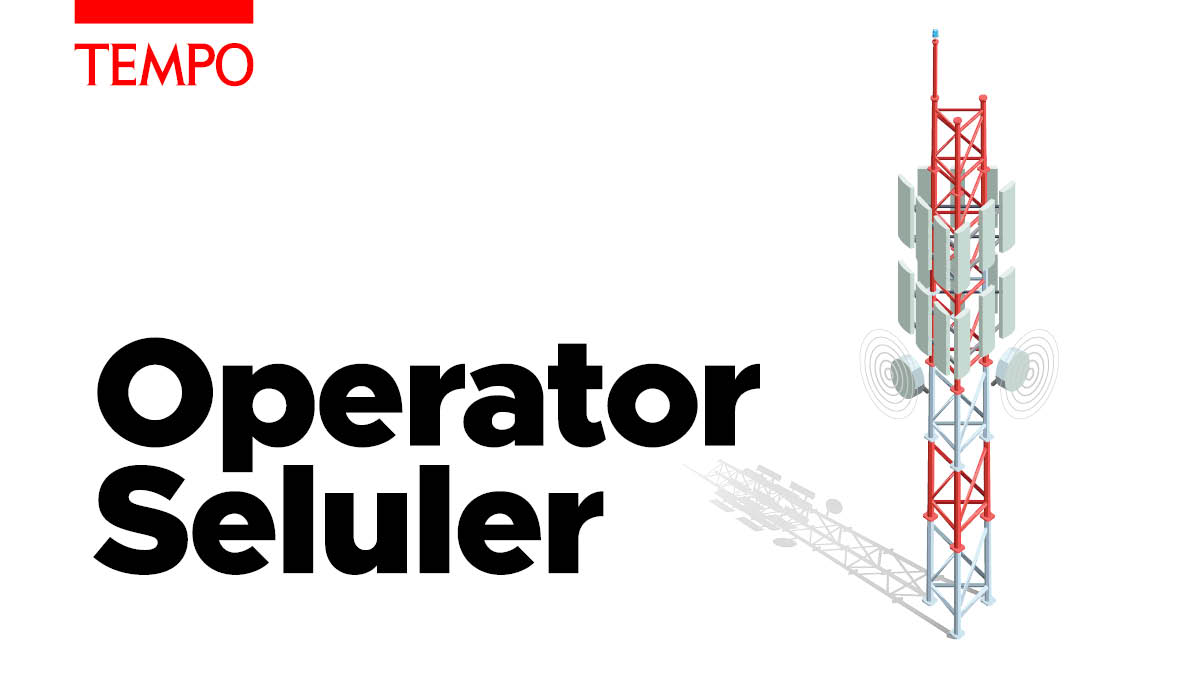Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
LEPASNYA Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat menghilangkan semua prasangka buruk dari dunia internasional yang selama ini terus menghantui kita. Namun, dengan hilangnya prasangka-prasangka buruk tersebut, bukan berarti tidak ada efek lain lagi bagi Indonesia. Kewaspadaan harus tetap dijaga dan mungkin harus lebih ditingkatkan, mengingat Timor Timur yang akan menjadi negara baru tersebut masih terkungkung di antara wilayah hukum laut/udara Indonesia.
Mungkin timbul suatu pertanyaan: apa alasannya Indonesia harus lebih waspada terhadap negara baru yang hanya berupa pulau kecil tersebut? Soalnya, bukan suatu hal yang mustahil bila pasukan multinasional Interfet yang kemudian digantikan oleh pasukan perdamaian di bawah naungan pemerintahan sementara PBB, United Nations Temporary Authority of East Timor (UNTAET), yang bercokol di Timor Timur, akan menjadi benih (embrio) bagi pembangunan pangkalan militer asing, walaupun pembangunannya mungkin dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun. Suatu hal yang tidak mustahil pula, bila pangkalan tersebut sudah permanen dan layak operasi, akan banyak kapal perang atau pesawat militer asing melakukan persinggahan dan berlalu-lalang dengan bebas melewati perairan—termasuk semua selat yang lebar ataupun sempit—dan kawasan udara Indonesia.
Kita dapat melihat dengan jelas bahwa yang mempunyai sikap agresif terhadap pembentukan dan pengiriman pasukan Interfet/UNTAET tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah negara-negara industri maju dan sebagian besar dari mereka memiliki program dan sistem pertahanan dan keamanan bertenaga nuklir. Maka, secara otomatis perairan Indonesia melalui pangkalan militer Interfet/UNTAET di Timor Timur bisa dijadikan jalur nuklir yang paling nyaman bagi mereka. Sejalan dengan hal tersebut, sudah selayaknya Indonesia bersama anggota ASEAN lainnya mulai meninjau kembali kebijakan politik luar negeri, khususnya yang menyangkut konsep regional Asia Tenggara sebagai ”Kawasan Damai dan Bebas dari Senjata Nuklir” atau ”Zone of Peace and Free of Nuclear Arms (Zopfan)”—karena beberapa negara ASEAN ikut pula berpartisipasi dalam Interfet.
Peninjauan kembali kebijakan politik tersebut mungkin harus dilakukan. Sebab, bila kita tetap berpegang teguh pada sistem lama Zopfan, tidak mustahil Indonesia akan semakin tergilas dan terlecehkan oleh masyarakat internasional.
Sangat ironis, kita menolak senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara, tapi pada kenyataannya tetap membiarkan kapal-kapal perang asing bertenaga nuklir dan pesawat-pesawat pengangkut fasilitas nuklir (umumnya akan lebih didominasi oleh negara Barat yang juga secara langsung atau tidak langsung menjadi donatur untuk bantuan pembangunan nasional Indonesia) berlayar/terbang atau melakukan manuver-manuver latihan dengan leluasa tanpa hambatan di perairan kawasan tersebut, yang sebagian besar juga termasuk sebagai daerah hukum laut/udara Indonesia.
Sehubungan dengan kemungkinan semakin ramainya kapal perang bertenaga nuklir atau pesawat pengangkut fasilitas nuklir menggunakan jalur laut/udara di kawasan Asia Tenggara, kestabilan lingkungan biota (environment conservation) di kawasan tersebut harus tetap diawasi dan terjaga karena, sekalipun pemilik kapal perang atau pesawat tersebut adalah negara-negara maju yang memiliki teknologi mutakhir, bukan suatu hal yang mustahil sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang kemudian akan berdampak pada pencemaran nuklir—atau mereka secara diam-diam membuang limbah nuklir ke laut sebagai hasil sisa perawatan/pemeliharaan peralatannya.
Alasan-alasan tersebut diharapkan bisa menjadi pekerjaan rumah bagi para wakil rakyat atau elite politik Indonesia dan anggota ASEAN lainnya untuk mampu mengantisipasi berbagai gejolak dan dinamika politik internasional di masa mendatang. Mungkin saja konsep Zopfan bisa berubah atau berkembang menjadi ”Kawasan Damai dengan Efek Nuklir yang Terkendali” atau ”Zone of Peace and Under Controlled Nuclear Consequences (Zopcon)”. Mungkin segala peraturan dan perundang-undangan nasional, khususnya yang menyangkut ketenaganukliran, perlu direvisi sehingga mampu menjadi salah satu penyokong konsep tersebut.
Konsep tersebut diharapkan bisa memberikan konsekuensi yang lebih berat kepada negara-negara maju jika mereka menebar dan menggunakan teknologi nuklir di kawasan Asia Tenggara. Sebab, memang sangat sulit menolak kapal perang bertenaga nuklir Amerika Serikat—kapal induk/selam—yang sedang berpatroli di kawasan Asia Pasifik atau kapal-kapal Prancis yang mengangkut berbagai macam fasilitas percobaan nuklirnya (sebetulnya, secara implisit, negara tersebut masih tetap agresif dengan program-program nuklirnya) ke Kepulauan Karang Mururoa, Samudra Pasifik, untuk singgah atau berlabuh di pangkalan militer hasil rekayasa Interfet/UNTAET di Timor Timur. Tidak tertutup pula kemungkinan negara industri maju lain seperti layaknya negara-negara Eropa—sebagian dari mereka adalah anggota NATO—ikut menyiagakan berbagai macam fasilitas keamanan di pangkalan militer tersebut untuk melindungi investasi/instalasi bisnisnya menyongsong dimulainya perdagangan bebas pada tahun 2020 nanti.
Mungkin pada akhirnya dapat dikatakan bahwa lepasnya Timor Timur dari Republik Indonesia proporsional dengan pepatah: ”Karena setitik nila, akan rusaklah susu sebelanga.” Karena perubahan situasi di Timor Timur, seluruh dinamika sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik secara cepat atau lambat akan berubah.
ALVANO YULIAN
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Pusat Pengembangan Perangkat Nuklir
[email protected]
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo