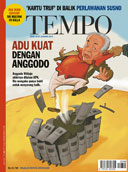Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TIGA perempuan peneliti mengerumuni sebuah meja bertudung kaca. Tangan mereka cekatan mengisi tabung-tabung kecil dengan cairan yang diteteskan dari pipet. Di tabung itu, bersemayam sampel tumbuhan dari Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat. Para peneliti itu sedang mengekstrak untuk mengambil asam deoksiribonukleat (DNA) sampel tersebut.
Begitulah secuplik kegiatan di Laboratorium Biosistematik, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cibinong, Bogor, pada Selasa pekan lalu. Aktivitas itu untuk menentukan struktur DNA suatu contoh tumbuhan. ”Setelah diidentifikasi DNA-nya, sampel itu disimpan di herbarium,” kata Teguh Triono, Kepala Kelompok Taksonomi dan Penelitian Sistematis di Herbarium Bogoriense di lembaga tersebut.
Herbarium Bogoriense kini menyimpan 2,5 juta jenis tumbuhan, dihimpun sejak 1817 oleh Caspar Georg Karl Reinwardt, pendiri Kebun Raya Bogor. Namun baru 14 ribu jenis yang sudah didigitalkan dan ditampilkan di situsnya, http://ibis.biologi.lipi.go.id. ”Karena tenaganya sedikit, proses entrinya lambat. Kalau lancar, satu orang sehari bisa memasukkan 30 entri data,” kata Teguh.
Teguh saat ini bekerja bersama Campbell O. Webb, peneliti senior di Arnold Arboretum, Universitas Harvard, dalam sebuah proyek rintisan untuk menghimpun dan membuat barcode DNA semua flora di Gunung Palung. Mereka dibantu Rani Asmarayani, peneliti LIPI yang menangani ekstraksi dan pemetaan DNA, dan, salah satunya, Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia.
Inventarisasi itu penting karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati nomor satu di dunia. Teguh memperkirakan ada 31 ribu jenis tumbuhan tinggi di Indonesia, belum termasuk jamur dan lumut.
Semua temuan di Gunung Palung dan koleksi Herbarium Bogoriense lalu diubah dalam bentuk digital dan dipublikasikan lewat Internet. ”Dengan disajikan di web, para ilmuwan di belahan dunia lain dapat mempelajarinya juga,” ujar Teguh.
Salah satu kesulitan dalam inventarisasi tumbuhan di Indonesia, kata Teguh, adalah banyaknya jenis yang belum dikoleksi dan diidentifikasi serta luasnya wilayah. Dengan berbagi informasi melalui situs web ini, diharapkan setiap hasil temuan taksonom atau ahli di setiap wilayah dapat saling melengkapi.
Webb dan Teguh bahkan mengusulkan perlunya situs jejaring sosial semacam Wiki khusus keanekaragaman hayati. Di situs itu komunitas daring dapat saling menyumbang koleksi tumbuhan temuannya, termasuk memperbarui data. Para ”ilmuwan warga” ini dapat membantu mengamati dan menghimpun tumbuhan di sekitarnya, seperti yang telah dilakukan para pengamat burung amatir yang telah menyumbangkan data sangat banyak untuk sebaran burung di Amerika Serikat dan Eropa. Afrika Selatan juga pernah menggelar proyek penelitian semut, yang melibatkan 3.000 pelajar dari 13 SMA, tahun lalu.
Sebagai rintisan proyek besar itulah mereka memulainya dari koleksi tumbuhan Gunung Palung. Dan Januari ini merupakan bulan yang paling dinanti-nanti. ”Saat ini musim panen raya yang langka bagi dipterokarpa, karena terjadi hanya lima tahun sekali di hutan Kalimantan. Lamanya empat bulan. Inilah saatnya kami bisa melihat tumbuhan lengkap dengan bunga dan buahnya,” kata Webb, yang bekerja di sana sejak November 2008.
Suku meranti-merantian atau dipterokarpa (Dipterocarpaceae) merupakan kelompok tumbuhan tropis yang anggotanya banyak dimanfaatkan dalam bidang perkayuan, seperti meranti, kruing, mersawa, kapur, dan tengkawang. Semua suku ini berupa pohon yang biasanya sangat besar dengan ketinggian hingga 70-85 meter. Karena banyak dieksploitasi, beberapa jenis pohon dari suku ini telah masuk ”daftar merah” Perserikatan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) sebagai spesies terancam punah, seperti kruing, kapur, meranti kuning, meranti merah, dan meranti batu.
Area Gunung Palung sekitar 90 ribu hektare. Jenis hutannya beragam, dari rawa-rawa dan hutan rendah hingga hutan pegunungan di puncak Gunung Palung (sekitar 1.116 meter dari permukaan laut). Taman ini menjadi tempat bermukim orang utan dan beragam jenis burung enggang. Sejak dilindungi pada 1937, sebagian besar kawasan taman itu tak diganggu manusia, kecuali oleh pencari kayu bakar dan gaharu. Namun sejak 1995 taman itu diancam oleh para pembalak liar yang mencari dipterokarpa di sepanjang sungai-sungai besar yang menuju ke taman.
Webb dan Teguh berbagi kerja. Webb, dibantu parataksonom (teknisi terlatih), jagawana Taman Nasional, dan masyarakat lokal, mencari dan mengumpulkan spesimen tumbuhan, memotretnya, dan mengirim spesimen tersebut ke Bogor. Kekhususan dari proyek ini adalah jenis tumbuhan yang diambil sampelnya harus lengkap dari daun, bunga, hingga buahnya.
”Spesimen ini seperti kartu tanda penduduk,” kata Teguh. Di situ ada nama, foto, dan keterangan lain. ”Kalau satu spesimen ada buah, bunga, dan daun, kita bisa mengidentifikasi sampai dengan jenis, karena tujuannya membuat acuan awal untuk barcode DNA.”
LIPI ingin Indonesia menjadi proyek semacam ini. Tapi Teguh mengakui, untuk efisiensi biaya, beberapa sampel dikirim ke Macrogen di Korea Selatan ”Kami punya alatnya, tapi kecepatannya terbatas, hanya bisa 4 sampel per 2 jam. Padahal kami perlu lebih banyak,” katanya.
Hingga kini lebih dari 500 sampel telah diambil dari Gunung Palung. Dari semua koleksi itu, baru 228 jenis tumbuhan yang sudah dipetakan DNA-nya. Penggabungan taksonomi dengan pemetaan DNA ini merupakan langkah baru dalam dunia taksonomi.
Barcode DNA taksonomi pertama kali digagas pada 2003 oleh Paul D.N. Hebert, profesor di Universitas Guelph di Ontario, Kanada. Dia mengusulkan pembentukan suatu perpustakaan umum barcode DNA yang tertaut dengan spesimen. Perpustakaan ini diharapkan menjadi kunci utama dalam mengidentifikasi spesies. Belakangan para ilmuwan mendirikan Barcode of Life Initiative, yang mendorong para ilmuwan menggunakan barcode DNA sebagai standar dalam penelitian rutin mereka. Sejauh ini konsorsium untuk prakarsa ini telah beranggota 170 lembaga lebih dari 50 negara lebih, yang meliputi kampus, herbaria, kebun binatang, taman botani, lembaga pemerintahan, dan organisasi konservasi lainnya.
Barcode ini memuat 640 pasangan basa DNA (diwakili huruf A, C, G, dan T). Ini cuma bagian kecil dari miliaran pasangan basa yang membentuk seluruh genom dari organisme. Namun potongan kecil ini dianggap mampu menunjukkan identitas suatu tanaman atau hewan. Barcode DNA hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesimen, bukan untuk tujuan medis seperti yang dikembangkan di dunia farmasi. Sejauh ini bank data di Barcode of Life Data Systems mencatat 65.578 spesies secara resmi ditetapkan barcode-nya dari total 768.707.
Manfaat basis data tumbuhan, kata Teguh, sangat banyak, misalnya untuk menentukan jenis kayu hasil pembalakan. ”Kalau kita ingin tahu jenis kayunya, kita bisa mengekstrak kayu tersebut untuk menentukan DNA-nya. Lalu sekuen DNA itu dicocokkan dengan basis data kita. Prosesnya cukup dua minggu, termasuk masa pengiriman dari lokasi ke lab kami,” kata Teguh.
Selama ini identifikasi tanaman dilakukan secara fisik dengan mengambil fragmennya untuk dilihat strukturnya. ”Kalau dengan cara ini kadang kita cuma bisa sampai penentuan genus, bahkan hanya famili/suku. Lebih spesifik dari itu sulit,” katanya.
Webb dan timnya juga mengambil 10-20 foto setiap tumbuhan yang mereka jadikan spesimen sedetail mungkin. Foto-foto tumbuhan dalam keadaan segar itu menguntungkan para taksonom karena warna aslinya jelas terlihat dan bagian-bagian tertentu, misalkan bulu pada batang atau ciri lain, masih dapat dikenali. Warna terutama akan hilang bila dikeringkan untuk dimasukkan ke herbarium.
Seluruh informasi tumbuhan itu, termasuk foto dan barcode DNA-nya, kemudian diunggah di situs Xmalesia (http://phylodiversity.net/flora-tngp/). Malesia adalah kawasan flora yang melingkupi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Papua Nugini. Situs dipakai untuk menganalisis struktur komunitas filogenetis, yakni hubungan di antara kelompok-kelompok organisme yang dikaitkan dengan proses evolusi yang dianggap mendasarinya.
Keuntungan dari berbagi informasi data dan foto di Internet adalah kemudahan penentuan jenis tumbuhan baru. Ketika dipasang di web, beberapa ahli yang melihatnya memberi tahu mereka bahwa tiga spesimen belum dikenal. Salah satunya jenis pandan dan satunya lagi hoya, tanaman merambat dengan bunga sebesar ibu jari yang tak sengaja mereka temukan di sungai dekat tempat mereka mandi. ”Kita tahu itu hoya, tapi tak tahu jenisnya, jadi kita pasang di situs. Lalu ada seorang ahli hoya dari Italia yang mengatakan bahwa ini hoya jenis baru,” kata Teguh.
Menurut Teguh, basis data ini penting untuk mengetahui seberapa banyak keanekaragaman hayati Indonesia yang punah. ”Rumput laut di Jawa, misalnya, sudah hilang dua jenis. Saya menelitinya bersama lembaga Oseanografi Indonesia. Di herbarium kami ada catatan bahwa dua jenis tumbuhan itu dulu diambil di pantai utara Jawa Barat dan Jawa Timur. Kini sudah tak ada,” katanya.
Kurniawan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo