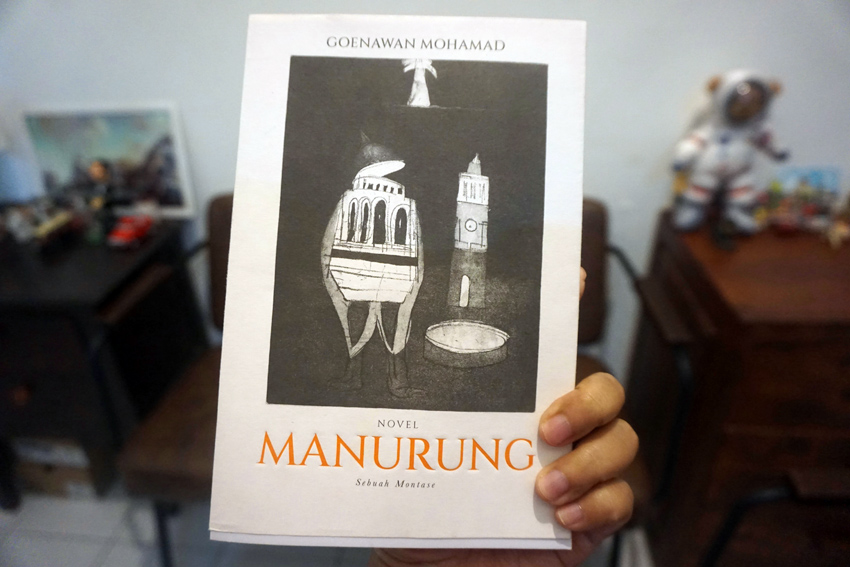Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
EMPAT pemuda berkopiah hitam dan bersarung itu berdiri tegap di sebuah tebing miring. Di samping mereka, mesin alat berat backhoe menderu menggaruk-garuk sisi lain tebing. Ketika trompet saronen (instrumen tiup Madura) ditiup tanda pertunjukan dimulai, empat pemuda "santri" bertelanjang dada dan tak beralas kaki itu kemudian duduk bersila. Tangan mereka memutar-mutar gilis (alat tradisional Madura yang terbuat dari batu untuk menghaluskan jagung). Jagung diganti batu kapur.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo