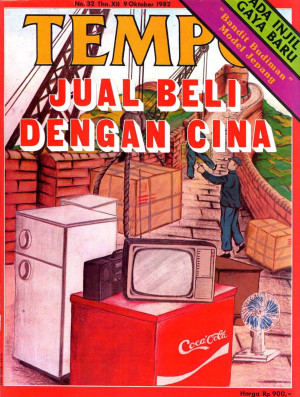BOM WAKTU
Naskah & Sutradara: N. Riantiarno
Produksi: Teater Koma
SEKELOMPOK gelandangan muncul lagi di Teater Tertutup Taman
Ismail Marzuki 24 - 30 September 1982. Lengkap dengan rumah
gurem, berlapis karton, koran bekas, seng bekas dan plastik. Ada
pula Pos Hansip. Juga WC seng di bawah jembatan. Sampah pun
berserakan. Tak ada lalat, memang. Yang ada sinar-sinar lampu
merah, biru violet, hijau dan kuning tua. Dan nun jauh di latar
belakang, tampak gedun gedung bertingkat tinggi menjulang.
Di kompleks itulah ada Jumini, perempuan yang menunggu. Ia
selalu menunggu suami dan anaknya yang bertransmigrasi ke
Lampung--yang sesungguhnya telah mati tenggelam ketika kapal
yang mereka tumpangi karam. Di situ pula hidup Roima, laki-laki
tulen yang berpacaran dengan Djulini (ditulis dengan ejaan lama)
wadam yang kenes. Lantas sejumlah pelacur murahan .
Dalam naskah, sesungguhnya mereka itu satu per satu tidak
mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Tapi mereka ada di
satu kompleks gubuk-gubuk apak di balik kota yang megah.
Masing-masing mempunyai cerita sendiri-sendiri, yang tidak harus
dihubungkan satu sama lain. Tak ada tokoh utama.
Maka terasa klop antara naskah dan konsep pemanggungan kali ini.
Sutradara dengan sengaja tidak selalu menghadirkan panggung
dengan utuh. Lampu seringkali hanya menyorot seputar adegan
berlangsung. Entah di kanan atau kiri panggung, atau sama sekali
di luar panggung--di tengah penonton misalnya. Sementara sisi
yang lain gelap.
Maka yang tersuguhkan adalah pertunjukan suasana demi suasana.
Inilah teater yang mencampurkan dialog, peran, musik, tata
panggung, permainan lampu tapi tanpa "ceriu". Hanya sebuah
sketsa.
Ada dialog berdua saja anura Tarsih (Titi Qadarsih) dan Kasijah
(Nunuk Chaerul Umam) tentang nasib mereka sebagai pelacur. Dan
bila suasana menjadi muram kemerahan, ketika lampion di belakang
panggung bagaikan bulan purnama, terdengar Jumini (Ratna
Riantiarno) berdesah sendiri, kadang ditemani Turkana (Topan)
tetangganya. Apalagi yang dikatakannya selain tentang suami
dan anaknya yang menanam cengkih di Lampung, yang segera akan
menjemputnya. Atau bila panggung berdentang ramai, tentulah itu
percekcokan antara Djulini (Salim Bungsu) si wadam dan Roima
(Idries) pacarnya.
Yang tersuguhkan memang kemungkinan-kemungkinan yang bisa
terjadi di gubuk-gubuk liar di bawah jembatam Hansip yang
memeras. Gadis desa yang terpaksa mengorbankan kehormatannya
agar tetap diizinkan tinggal di situ. Dan sekali-sekali muncul
Abung (Syaeful Anwar) si gila dengan kostum bak pembajak atau
perampok bank, disertai temannya yang selalu menggesek biola
dengan lagu yang tak jelas. Abung ini bisa muncul di mana-mana:
di balkon di atas penonton, di samping panggung, dan di tengah
penonton. Si gila ini selalu meneriakan kalimat-kalimat yang
tidak jelas maksudnya, tapi asosiatif. "Banyak orang hidup tanpa
persiapan. Jiwa mereka menjerit, benjol-benjol. Berderet orang
antre mencari kebahagiaan Tapi antrean mandek. Ada banyak setan
kredit.
Drama ini berakhir ketika Abung tewas ditembak Hansiru Karena
yang pertama itu ingin memanjat ke bagian aas panggung, tempat
lima orang yang dari awal sampai akhir cuma makan dan minum --
mereka agaknya mewakili golongan "atas" yang diam-diam
menyaksikan apa pun yang terjadi di "bawah".
Dua setengah jam penonton yang hanpir penuh, memang cukup
terpaku oleh adegan per adegan yang memang ditata bagus.
Lelucon-lelucon segar, terutama dari Komandan Hansip si Kumis
(Dudung) dan pengawalnya si Bleki (Manta). Atau omongan kacau
Abung si gila. Kata-kata sembarangan dari Djulini yang erotis.
Dan tentu saja, lenggang-lenggok Tarsih dan Kasijah yang membuat
Pak Camat jebol pertahanannya. Tak ada lagi tepuk-tangan
penonton karena dari arah panggung tidak terdengar protes sosial
yang galak. Tapi sungguh terasa ini sebuah drama puisi-kalau
boleh disebut begitu - yang menyuarakan protes.
Keberhasilan Riantiarno kali ini, saya kira, karena ia tidak
terjatuh menjadi klise. Sukaduka masyarakat gelandangan
ditampilkan dengan simpatik tapi tidak berlebihan, dan tidak
mencoba membuat mereka menjadi corong protes, atau pengkhotbah
dengan kata-kata mutiara dan kalimat panjang.
Bambang Bujono.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini