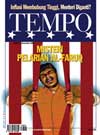Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang hakim agung diduga keras terlibat korupsi saat menyusun nasihat kepada presiden. Seorang terpidana yang terlibat dalam kasus penyelundupan telah mengajukan amnesti, dan sang hakim mengubah rekomendasinya tiga kali. Pertama, agar pidana diringankan. Kedua, lebih besar lagi. Dan ketiga, membebaskan terpidana.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo