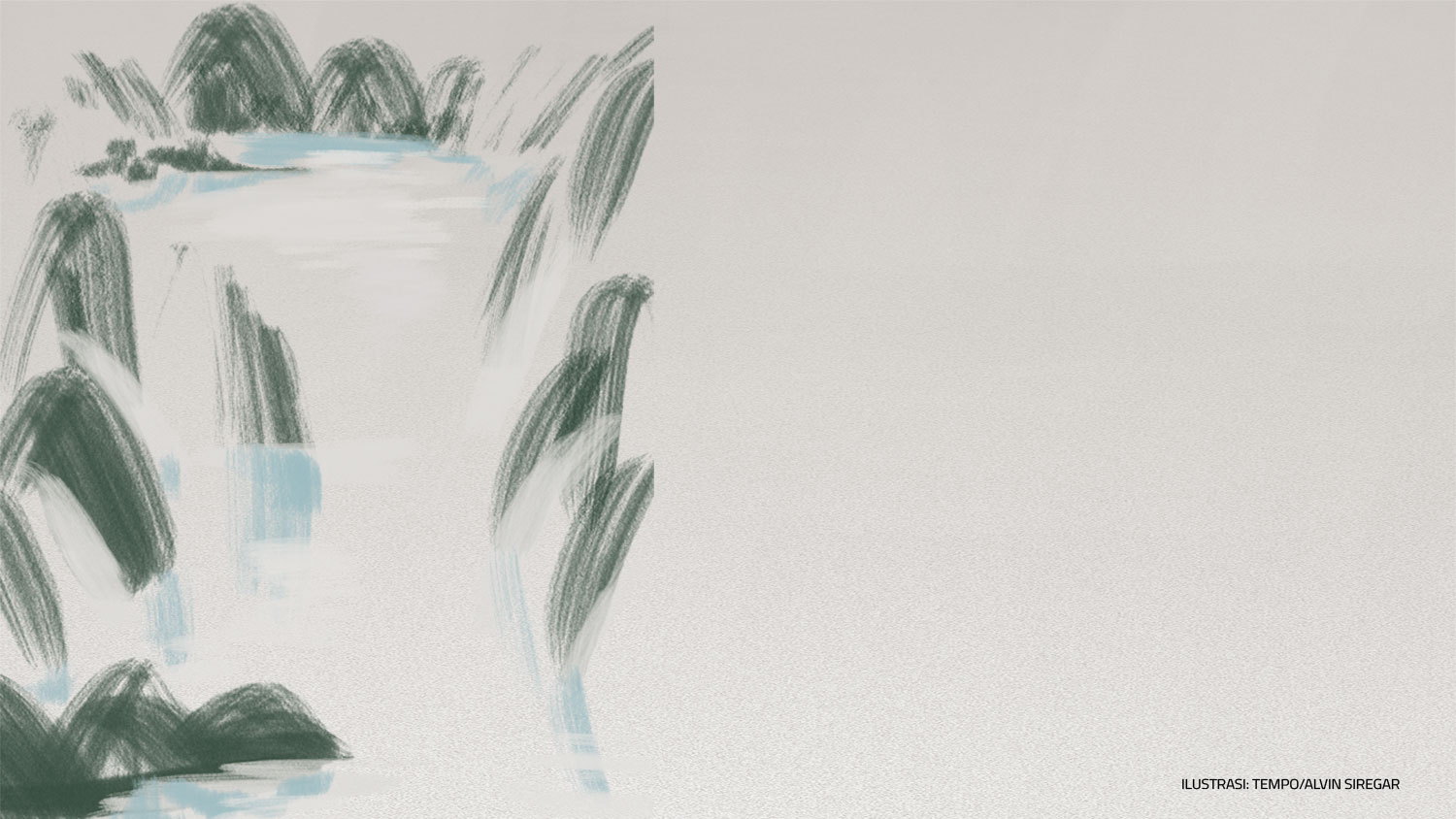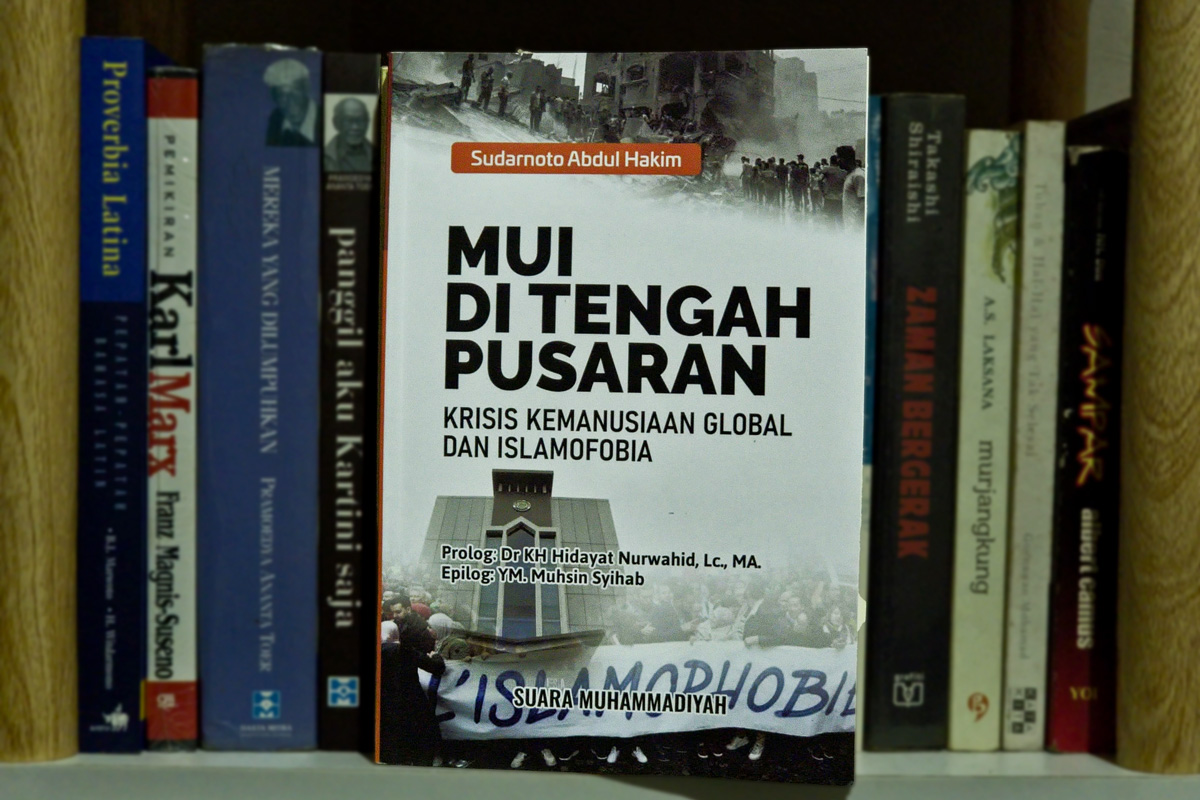Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“AKU ingin mati di Sumba!” katanya berulang kali semasa hidup. Ia lahir di Malang, Jawa Timur; sempat tinggal di Bali; lama hidup di Jakarta; setelah pensiun kembali ke Surabaya; dan di akhir petualangan ia ingin dikubur di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Keinginan aneh itu berasal dari Hadipurnomo, perintis kajian antropologi visual dan etnofotografi di Indonesia. Senin, 8 Juni 2020, di tengah sunyi subuh, pada umur 89 tahun, keinginan itu lunas sudah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perkenalan Hadipurnomo dengan sinema dimulai pada 1974. Saat itu, sutradara Teguh Karya memintanya bergabung sebagai penata artistik dalam pembuatan film Cinta Pertama. Tawaran itu diterima dengan bersemangat. Namun, selama pembuatan film berlangsung, Hadipurnomo justru merasa gelisah. Menurut dia, bahasa film fiksi konvensional membosankan karena menempatkan sutradara dan juru kamera sebagai dewa pencipta ilusi. Semua serba tertata dan artifisial. Kegelisahan itu kemudian mendorong Hadipurnomo menjelajahi kemungkinan bahasa film yang berbeda, yang lebih luwes untuk menggambarkan realitas sosial.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Masih pada tahun yang sama, Hadipurnomo mendekati Affandi. Ia mengutarakan keinginannya membuat dokumenter yang merekam proses Affandi melukis. Awalnya Affandi menolak ide tersebut. Affandi tidak ingin prosesnya melukis diganggu oleh kepentingan sutradara. Hadipurnomo lantas menyanggupi permintaan tersebut. Ia berjanji selama mengambil footage tidak akan mengintervensi proses melukis Affandi. Kolaborasi tersebut menghasilkan tiga buah dokumenter pendek yang merekam perjalanan Affandi melukis di Cirebon, Tangkuban Parahu, dan Lembah Baliem. Tampak dalam sebuah bagian, lensa kamera diarahkan Hadipurnomo untuk merekam jemari kaki yang bergerak liar. Seolah-olah ingin menggambarkan getaran energi Affandi ketika menghadapi kanvas.
Untuk membuat dokumenter tersebut, Hadipurnomo tinggal bersama keluarga Affandi selama sekitar satu setengah tahun. Ia dekat dengan Kartika. Ia juga dekat dengan Pak Djon, sopir pribadi yang memahami Affandi luar-dalam. Proses panjang ini kemudian membuahkan konsep yang disebut Hadipurnomo sebagai “film zonder sutradara”. Subyek dibiarkan beraksi di depan kamera. Tanpa arahan, tanpa skenario. Pembuat film hanya memiliki kuasa menentukan sudut pandang dan memencet tuas rekam.
Sejak saat itu, Hadipurnomo berkeliling Indonesia untuk mendokumentasikan berbagai ritual budaya menggunakan pendekatan serupa. Pada 1976, ia membuat dokumenter pemakaman bangsawan Toraja, Nek Atta, yang empat tahun kemudian—atas undangan Jean Rouch—diputar di Musée de l'Homme, Paris. Dalam kesempatan lain, ia mendapatkan izin membuat dokumenter Saur Matua mengenai tradisi kematian masyarakat Batak Toba dalam keluarga besar sastrawan Sitor Situmorang.
Berbekal pengalaman tersebut, Hadipurnomo mendapatkan beasiswa Fulbright sebanyak dua kali untuk mendalami studi mengenai etnografi dan sinema di UCLA (1979), New York University (1980), dan University of Southern California (1988). Selama studi, ia belajar dari antropolog visual kawakan, antara lain Robert Gardner serta Timothy dan Patsy Asch, yang di kemudian hari cukup mempengaruhi gaya dan pemikiran Hadipurnomo. Sepulang dari Amerika Serikat, ia diminta Profesor Dr Koentjaraningrat membantu mengajar dan membimbing mahasiswa di Departemen Antropologi Universitas Indonesia.
Boleh dibilang Hadipurnomo adalah antropolog yang komplet. Ia paham teori dan kenyang pengalaman lapangan. Kawan dan murid mengenalnya sebagai manusia bebas yang bergerak leluasa. Mudah beradaptasi dan bergaul dengan siapa saja. Ia bisa dekat dengan para jenderal, tapi juga bergaul dengan preman dan kaum pinggiran. Sesekali menjadi akademikus atau pemain teater, tapi juga sering nongkrong bersama seniman bohemian di bongkaran rel Tanah Abang. “Aku ini seperti bunglon,” tutur Hadipurnomo.
Pergaulannya yang luas dengan para seniman dan budayawan kemudian membawa Hadipurnomo menjelajahi wilayah artistik lain di bidang teater. Panggung dan sorot lampu sebetulnya bukan hal asing baginya, karena di masa muda ia pernah menjadi balerino. Dia, misalnya, bersahabat dengan Julie Taymor membentuk Teater Loh di Bali pada 1970-an. Taymor sekarang adalah salah satu sutradara Broadway yang diperhitungkan. Karyanya di Broadway, Lion King, adalah salah satu pertunjukan paling laris. Taymor juga dikenal banyak membuat film. Salah satunya tentang Frida Kahlo.
Hampir semua dokumenter yang ia garap direkam menggunakan kamera super 8 milimeter, yang saat itu dianggap sebagai “kamera rumahan”.
Tak banyak yang tahu pada masa mudanya Taymor pernah berguru kepada Rendra di Bengkel Teater. Kemudian dia di Bali mendirikan kelompok teater bernama Teater Loh bersama Hadipurnomo. Pemainnya beragam. Sebagian berasal dari Bali, Jawa, Sunda, Jerman, dan Amerika. Mereka menyewa dua bungalo di daerah Petitenget, yang pada 1976 masih terpencil dan jauh dari keramaian. Selama delapan bulan, semua anggota berlatih secara intens menyiapkan lakon bertajuk Tirai yang dipentaskan keliling, antara lain di Denpasar, Surabaya, Padang, Pekanbaru, dan Jakarta.
Putu Wijaya dalam resensinya di majalah Tempo pada 1978 menggambarkan panggung Tirai dilatari tiga buah layar, sebagaimana pentas wayang kulit, tapi diberi sentuhan unsur teater tradisional Jepang. Pertunjukannya dibuka “dengan keindahan yang getir dan magis” dan kostum yang dikenakan para aktor tampak sugestif. Bisa jadi karakter penyutradaraan Julie Taymor, yang gemar menggubah bentuk dan tampilan visual aduhai, berkembang dari sini.
Pada 1974-2007, Hadipurnomo memproduksi sekitar 30 film. Hampir semua dokumenter yang ia garap direkam menggunakan kamera super 8 milimeter, yang saat itu dianggap sebagai “kamera rumahan”. Berbeda dengan pembuat film profesional yang menggunakan sistem 16 mm atau 35 mm. Karena dianggap remeh dan tidak penting itulah Hadipurnomo justru menemukan kekuatannya. Dengan menggunakan kamera rumahan, ia bebas bergerak tanpa perlu takut belitan birokrasi dan ketatnya sistem sensor pada masa Orde Baru.
Selain merekam ritual budaya, Hadipurnomo kerap membuat film mengenai isu sosial. Bahkan sering kali isu yang diangkat melawan arus narasi rezim saat itu. Pada 1982, berbekal surat jalan dari Pusat Kajian Kriminologi UI, Hadipurnomo blusukan untuk merekam kondisi narapidana politik (napol) dan tahanan politik (tapol) di tujuh lembaga pemasyarakatan. Dari Cipinang sampai Wirogunan, dari Gunung Kelotok hingga Kalisosok. Dokumentasi yang dihasilkan menjadi bahan kajian penting untuk menunjukkan budaya kekerasan, pola hubungan, dan struktur sosial yang terbentuk dalam lingkungan penjara di Indonesia. Selain itu, film dan fotonya menjadi bukti visual keberadaan para napol dan tapol di era Orde Baru yang dibui tanpa pernah diadili.
Posisinya yang berseberangan dengan rezim Orde Baru juga ditunjukkan melalui film Suara dari Borobudur (1983), yang merekam perlawanan warga Desa Ngaran, Krajan, dan Kenayan mempertahankan tanah mereka. Penduduk ketiga desa tersebut dipaksa pindah demi pembangunan kawasan wisata Candi Borobudur. Sampai sekarang film ini nyaris dianggap sebagai mitos, karena selalu dibicarakan tanpa pernah ditayangkan secara luas. Ia hanya dikonsumsi terbatas sebagai bahan kajian sengketa tanah di beberapa universitas, baik dalam maupun luar negeri. Setelah film tersebut dibuat, Hadipurnomo lebih banyak membatasi diri dan cenderung menghindari sorotan publik.
Dari berbagai karya yang pernah dibuat, barangkali arsip film dan studinya mengenai budaya Sumba adalah warisan terpenting. Hadipurnomo begitu mencintai Sumba. Ia datang pertama kali ke Sumba pada 1978 untuk merekam proses pemakaman Raja Lewa Kambera di Prailiu. Lima tahun berselang, ia kembali untuk merekam upacara penguburan Raja Umbu Nggama Haumara di Melolo. Peristiwa terakhir ini menghasilkan dokumenter berjudul Tanggalo: The Last Stone Dragging (1983).
Film yang dibuat dengan pendekatan ciné-trance ini menggambarkan orkestrasi akbar manusia Sumba dalam mempersiapkan ritual kematian yang diwariskan sejak masa megalitikum. Selama empat bulan proses pengambilan gambar, Hadipurnomo juga mencoba mengaplikasikan konsep shared anthropology dengan menayangkan dokumenter pemakaman Raja Lewa Kambera keliling dari kampung ke kampung. Film diproyeksikan ke atas kain putih yang dibentangkan di tanah lapang. Ini menjadi momentum bagi masyarakat Sumba Timur untuk melihat kebudayaan mereka sendiri melalui sinema sekaligus mengkritiknya.
Di luar kedua film tersebut, Hadipurnomo membuat studi lain. Terutama dokumentasi visual tenun dan kriya di Sumba Timur, yang beberapa di antaranya kini sudah tidak dapat ditemui. Selama hidup, Hadipurnomo terobsesi untuk terus menguji ulang definisi dari “film Indonesia”. Adakah yang disebut dengan film Indonesia? Benarkah kita sudah mampu mengembangkan bahasa visual sendiri?
Dalam kritiknya terhadap Karl Heider, Hadipurnomo menolak adanya penyebutan film Indonesia, karena baginya hampir semua film yang diproduksi saat itu masih menggunakan bahasa visual Barat. Maka ia selalu berangan-angan: “orang-orang lokal harus belajar membuat film” dan mencatat kebudayaan mereka sendiri melalui sinema. Dengan cara ini, ia berharap setiap corak kebudayaan di Indonesia dapat menemukan bahasa film yang khas sekaligus memperkaya bahasa film dunia.
AYOS PURWOAJI, PENGAJAR UNIVERSITAS CIPUTRA, SURABAYA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo