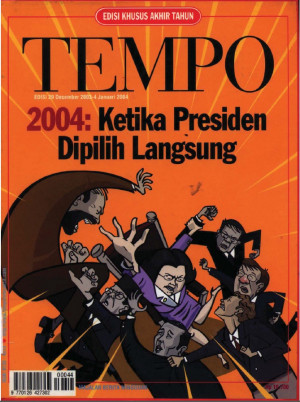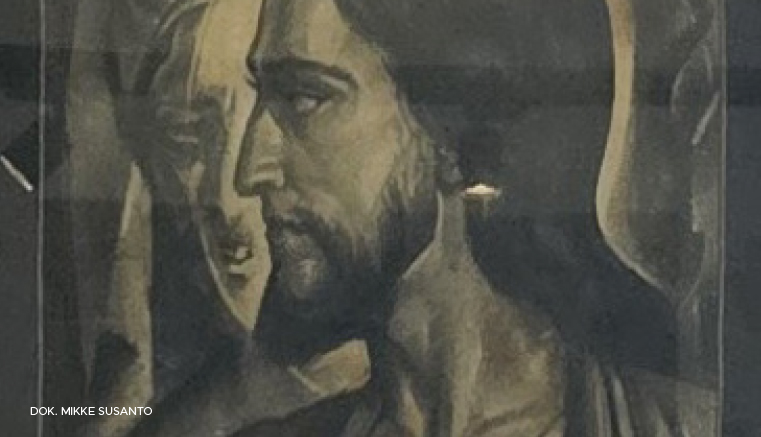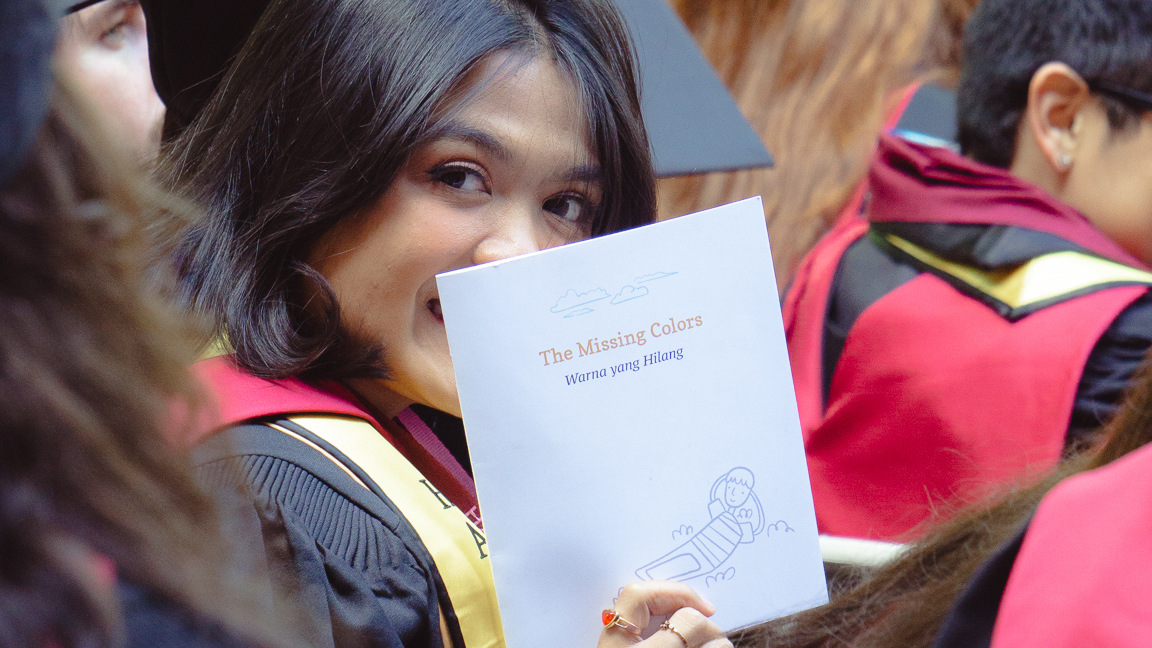Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Poros Jakarta-Peking adalah istilah politik sekaligus sebuah kenang-kenangan. Kita mengingatnya, di samping Poros Jakarta-Pyongyang, Jakarta-Hanoi, bagian dari cita-cita besar Sukarno menyatukan negara-negara Selatan sebagai the new emerging forces.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo