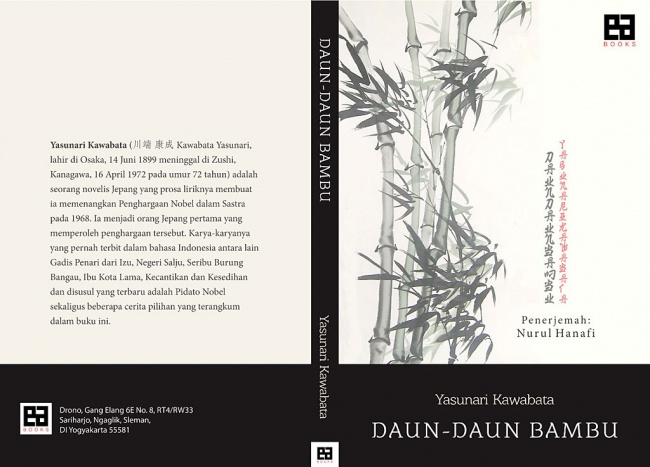Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Judul : Daun-daun Bambu
Penulis : Yasunari Kawabata
Penerbit: EA Books, Yogyakarta
Tebal: 154 halaman
Cetakan : I/Desember 2015
ISBN : 9786021318195
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo