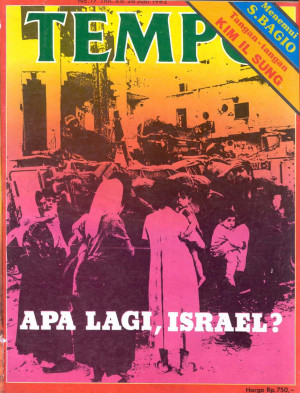SARTONO KARTODIRDJO (ed.),
Elite Dalam Perspektif Sejarah,
Jakarta: LP3ES/Buku Obor, 1981, 233, index.
MUNGKIN juga Shils benar, ketika mengatakan bahwa oligarki
militer umumnya kurang bersifat ideologis. Tetapi waktu ia
memberi contoh, perasaan tertegun tak bisa dielakkan. Ia
mengatakan bahwa di beberapa negara, antara lain Indonesia, kaum
militer mempunyai aspirasi yang moderat saja. Maksudnya: hanya
berkeinginan menjaga suatu masyarakat politik yang sederhana
dengan peralatan pemerintahan secukupnya pula. Bahkan, katanya
lagi, mereka cenderung menjalankan kebijaksanaan (bukan
kebijakan, seperti yang ditulis dalam buku terjemahan ini) tanpa
politik, dan membiarkan politisi "mengatur negara seperti suatu
perkemahan tentara yang besar".
Biarkanlah dugaan Shils -- teoretikus sosiologi terkemuka --
tentang negara lain tak perlu digubris. Tetapi mengenakan hal
yang umum itu kepada situasi khusus Indonesia memang agak
merepotkan. Bukan apa-apa -- hanya saja, terlepas dari segala
corak praduga politik, kita tentu bisa mempersaksikan betapa
jauhnya keterlibatan tentara (ABRI) dalam berbagai proses
pematangan ideologi negara ini.
Meski contoh di atas hanya secuil dari berbagai hal yang bisa
ditanggapi dari eseinya, ini memperlihatkan betapa cukup
terbatasnya uraian sosiologi politik dalam menangkap dinamik
historis yang sedang berjalan. Maklumlah Shils tidak sekedar
mencari patokan umum tentang negara-negara berkembang, yang
memang sangat beragam dan beraneka. Ia menulis eseinya di saat
optimisme di kalangan para ahli sosial Barat di tahun 1950-an
tentang masa depan demokrasi dari negara-negara berkembang mulai
dihantui oleh kemungkinan munculnya "oligarki militer".
Optimisme yang mendua itu jelas pula kelihatan pada Benda --
yang seperti halnya Shils, mengambil negara-negara berkembang
sebagai sasaran studi. Jika dibanding dunia Barat, kata Benda,
tampak bahwa kaum cendekiawan atau inteligensia di dunia Timur
bukan saja bergumul dengan dunia pikiran dan nilai-nilai, tetapi
juga terlibat secara langsung dalam kekuasaan. Bahkan, katanya
lagi para inteligensia itulah penguasa.
Tentu saja mereka yang terlalu sadar dengan realitas politik
hari ini akan tersenyum membaca hal itu. Tetapi Benda tak
seluruhnya salah. Bukankah di akhir 1950-an masih cukup terang
bintang Nkrumah, Nehru, Sukarno, Castro dan lain-lain? Dan
bukankah mereka sesungguhnya bermula sebagai inteligensia?
Tetapi, jika Shils secara cukup realistis mengatakan bahwa para
inteligensia punya kecenderungan untuk tidak mempunyai rasa
kepastian yang tinggi, maka Benda, yang terlalu melihat
inteligensia sebagai hasil produk Barat yang 'murni", mengatakan
bahwa mereka pada dasarnya terpisah dari rakyat. Mereka dan
rakyat berada dalam dua dunia yang berbeda. Karena itulah
Isereka melakukan usaha identifikasi dengan rakyat. (Tentu kita
tahu juga identifikasi adalah suatu proses, sedang identik suatu
keadaan). Jadi, katanya lagi, dibanding negara Barat, "proses
politik di masyarakat Timur itu lebih merupakan suatu bangunan
bertingkat tanpa landasan yang kokoh". Mungkin juga.
Tetapi dua tahun setelah menulis esei tentang kaum inteligensia
ini Benda malah mengatakan, untuk mengerti Demokrasi Terpimpin
dan Sukarno perlulah disadari bahwa gejala itu sebenarnya proses
kembalinya Indonesia ke dinamik sejarahnya yang telah
diintervensi oleh kolonialisme. Kalau begitu, secara logis tentu
bisa diperkirakan bahwa perkembangan selanjutnya akan
menunjukkan berakhirnya fungsi inteligensia sebagai penguasa.
Bukankah mereka tak berakar?
MUNGKIN Shils benar juga jadinya. Dalam situasi keterlepasan
dari idealisme (yang Barat), kemampuan teknis, sifat praktis,
serta kesadaran yang kuat akan pentingnya arti stabilitas dan
sekedar ideologi akan lebih banyak berbicara. Hanya saja kedua
esei yang ditulis di awal 1960-an di atas hanya bisa menyebut
pentingnya kemampuan teknokratis. Belum berbicara tentang suatu
golongan elite, yang kini bersama militer adalah kaum yang
"binnen" secara politik, yaitu teknokrat.
Esei Shils tentang militer dan Benda tentang inteligensia di
dunia ketiga, yang disinggung di atas, adalah dua dari delapan
esei atau studi yang dimuat Prof. Sartono Kartodirdjo dalam
kumpulan tulisan tentang 'elite' ini. "Diskusi" pendek di atas
hanyalah pula salah satu kemungkinan yang bisa dipakai dalam
mencoba membuat suatu pendekatan integratif dari buku yang
bervariasi ini.
Tetapi, sebelum melantur lebih jauh, apakah 'elite' itu
sesungguhnya? Kamus tentu bisa dipakai, dan nama-nama besar
mulai dari Pareto, Mosca, Mills sampai Mannheim tentu bisa
menghiasi uraian. Bahkan, meski tidak mengenal kata 'elite'
sebagai konsep, Marx adalah tokoh yang sangat memperhatikan
gejala sosial ini. Hanya saja ia memakai konsep tentang bisa
dibaginya masyarakat atas kelas-kelas. Tetapi jika
disederhanakan semua itu, maka yang dimaksud dengan elite adalah
golongan fungsional yang mempunyai status tinggi (apa pun
dasarnya) dalam masyarakat. Setidaknya begitulah secara populer
diartikan oleh Bottomore.
Kalau begitu tentu berbagai jenis elite bisa dibedakan. Maka ada
yang mengatakan bisa dibagi dua, yaitu 'yang berkuasa' dan 'yang
tidak berkuasa'. Tetapi kalau ini yang diikuti agak payah juga
kita mengadakan identifikasi "yang manakah yang mana".
Paling-paling kita akan bisa membeda-bedakan kelompok-kelompok
tertentu dalam berbagai golongan elite itu. Sebab itu,
barangkali pilihan Prof. Sartono tepat juga. Ia tampaknya
mengikuti cara Suzanne Langer, yang lebih menekankan klasifikasi
elitenya berdasar kriteria strategis atau tidaknya suatu
golongan dalam masyarakat.
Dengan begitu bisalah dibedakan golongan-golongan elite atas
kaum bangsawan, pengusaha, cendekiawan, ulama (elite agama),
militer dan sebagainya. Begitulah artikel atau esei yang dimuat
dalam kumpulan tulisan berdasarkan klasifikasi tersebut. Yang
unik ialah, kesemuanya tidak dilihat dalam suasana kesezamanan,
tetapi historis. Jadi penyusunan artikel juga diatur berdasar
suatu interpretasi sejarah tentang evolusi dari
golongan-golongan elite.
Demikianlah artikel yang dipilih itu membicarakan kaum bangsawan
(Eropa dan Tiongkok) dan ulama (India) dari Abad Tengah, para
burjuis (Eropa) dari periode Peralihan ke Abad Modern, dan
akhirnya cendekiawan dan militer (Dunia Ketiga) dari abad
modern. Di samping itu, sebagai sasaran dari para elite yang
terpilih itu (mungkin istilah paling tepat dalam bahasa
Indonesia ialah ungkapan Melayu lama, 'orang patut') dimuat juga
satu karangan tentang masyarakat petani (Asia Tenggara).
Setiap artikel atau esei yang dimuat bermutu tinggi. Bahkan
tulisan Marc Bloch, tentang feodalisme, telah masuk kelas
'elite' dari historiografi modern. Hanya saja sebagai
keseluruhan timbul suatu masalah, yang tak terlalu mudah
diselesaikan, seandainya kita hanya berpegangan pada buku ini:
Pendekatan historis pada dasarnya bersifat partikularistik.
Sedang tulisan-tulisan yang dimuat ini, meski runtut secara
kronologis, berada dalam dunia yang berbeda-beda. Jadi
kontinuitas tak terjamin. Di samping itu tingkat generalisasi
masing-masing artikel juga sangat berbeda-beda. Jika Benda dan
Shils sibuk dengan dunia ketiga, maka Saletore, yang menulis
tentang ulama, hanya bicara tentang India. Sedang perhatian Marc
Bloch terbatas pada Eropa -- dengan fokus utama Prancis.
Tetapi memang bukan suatu studi integratif yang ingin dicapai
buku ini. Ini adalah perkenalan terhadap masalah yang dari dulu
merupakan salah satu tema pokok dari studi berbagai cabang,
ilmu sosial. Dari sudut ini tampaknya sasaran telah tercapai.
Buku ini adalah suatu "panorama" yang kaya, diserta pula oleh
ilustrasi sejarah dan pemikiran yang cukup merangsang. Juga
dengan begini buku ini "buku wajib" bagi para mahasiswa dan
sarjana ilmu-ilmu sosial serta mereka yang berminat.
Akhirnya ada tiga hal kecil yang perlu diingatkan. Pertama,
istilah-istilah masih harus dibenahi, baik ejaan (hierarki atau
hirakhi, charisma atau kharisma), maupun pengertian-pengertian
pokok (apakah sama arti susunan dengan struktur?). Kedua,
bibliografi yang tercantum di halaman 23 barangkali mestinya
dimuat di belakang kata pengantar Prof Sartono, di halaman XVI,
Dan ketiga, di bawah artikel Marc Bloch, dikatakan bahwa
terjemahan dilakukan atas izin penulis dan pengarang. Bisa jadi.
Hanya saja Bloch telah meninggal dunia ketika Prancis diduduki
tentara Hitler. Jadi repot juga baginya untuk memberi izin
langsung.
Taufik Abdullah
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini