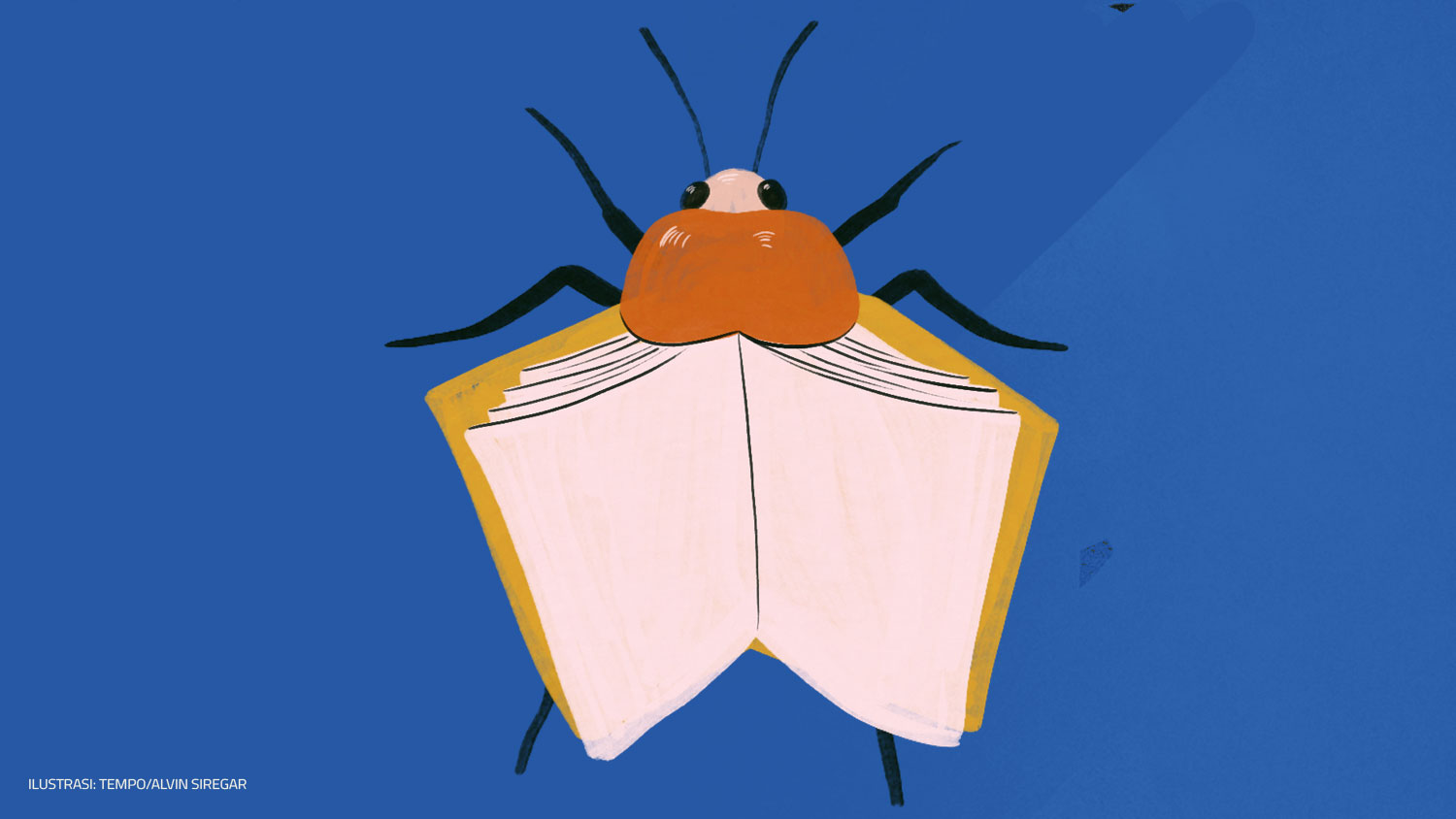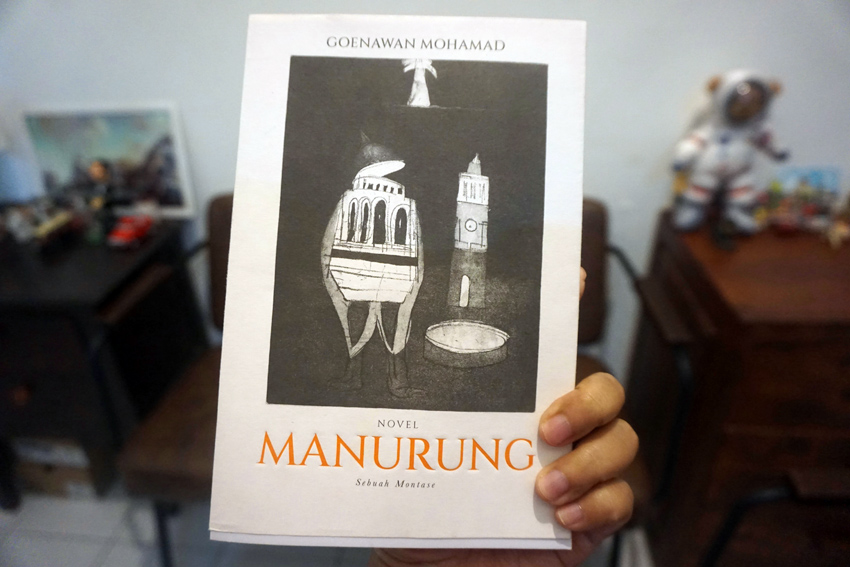Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
A. Khotibul Umam
Hampir tujuh tahun, setiap hari menjelang terbenamnya matahari, seekor anjing selalu datang sendirian ke sebuah dermaga di tepi laut Kota Kawabata. Anjing itu duduk meringkuk dengan kedua kaki depan menyangga dagu, menatap matahari senja, mendengarkan irama riak gelombang yang saling berkejaran.
Anjing itu bernama Kirani. Ia termasuk anjing dari ras Akita Inu. Tubuhnya tak terlalu besar, ekornya panjang, bulunya halus berwarna abu-abu dan cokelat kehitaman. Dari moncong sampai matanya terdapat sepasang garis putih tipis yang membuatnya terlihat lebih manis.
Bentuk dermaga itu hampir mirip dengan jembatan: berlantai papan dengan pagar pembatas terbuat dari batang-batang kayu berukuran kecil. Ujung dermaga yang menghadap ke arah terbenamnya matahari, berjarak sekitar dua ratus meter dari bibir pantai. Di ujung dermaga itulah si anjing duduk, menunggu dan berharap seseorang akan kembali, seorang gadis berusia sekitar delapan belas tahun yang begitu ia rindukan, gadis berambut hitam lurus yang wajahnya selalu dihiasi senyum ceria, gadis bermata sipit yang senang mengenakan sweter berwarna merah jambu, gadis yang tak lain adalah majikannya sendiri.
Ia ingin sekali menjilat-jilat pipi ranum kemerahan majikannya sambil menyalak-nyalak manja dan mengibas-ngibaskan ekornya pelan seperti tujuh tahun lalu ketika ia masih seekor anjing kecil yang lucu dan menggemaskan. Namun sekarang sudah tidak bisa lagi, majikannya telah pergi, entah kapan kembali.
Anjing itu menatap matahari yang mulai turun perlahan. Di benaknya terbayang betapa si gadis sangat baik, sangat menyayanginya. Ia ingat ketika setiap pagi, si gadis selalu mengantarkan makanan kesukaannya ke kandangnya. Ia ingat ketika sebelum berangkat sekolah, si gadis selalu menciumnya, mengelus-elus kepalanya dan melambaikan tangan untuknya. Dan yang paling tak bisa ia lupakan adalah saat majikannya itu rela duduk berlama-lama di salon hewan, hanya untuk menunggunya dimandikan dan dirias secantik mungkin.
Dan setiap sore, menjelang matahari terbenam, si gadis selalu mengajaknya ke dermaga itu. Sebelum berangkat dengan berjalan kaki dari rumahnya yang berjarak beberapa ratus meter dari pantai, si gadis mengikatkan tali penuntun berwarna hitam ke leher anjing itu. Begitu sampai, mereka duduk di ujung dermaga menunggu detik-detik lenyapnya matahari di ufuk barat.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo