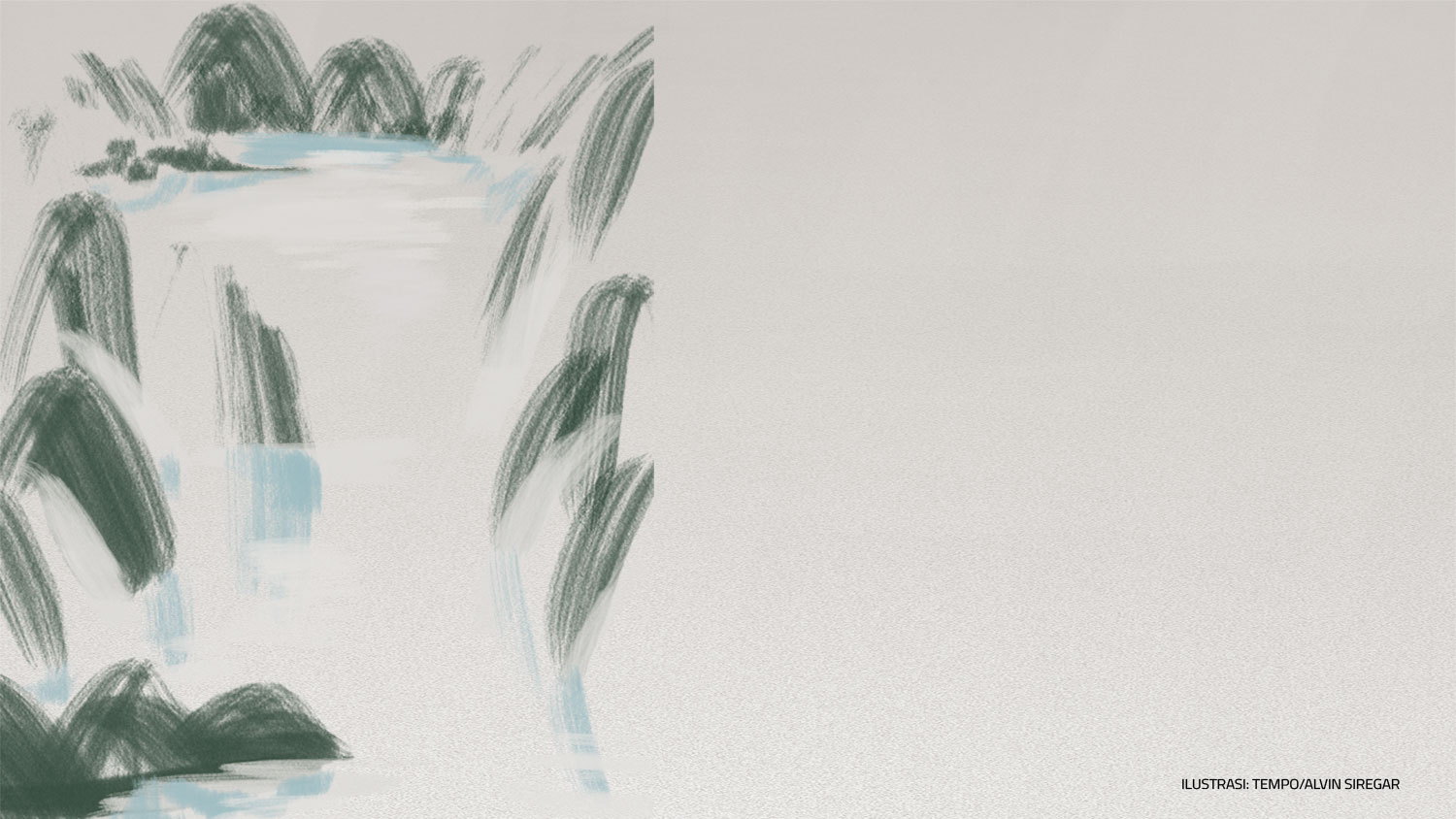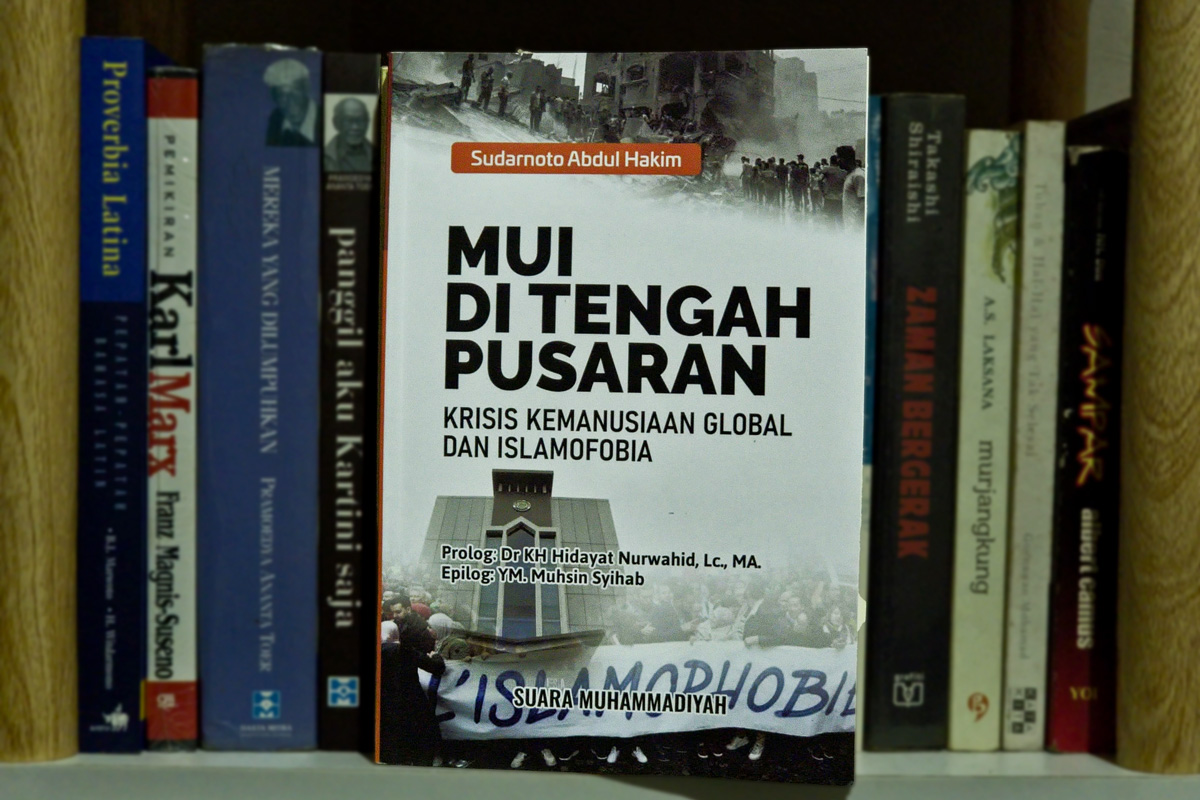PERTAMA kalinya di Indonesia: sebuah grup teater berhasil
merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Usia seperempat abad, apa
boleh buat, rupanya cukup tua-untuk kelompok seniman panggung
jenis 'modern' di Indonesia yang masih tetap berkarya. Bengkel
Teater Rendra, Teater Populer Teguh Karya, Teater Kecil Arifin
C. Noer, Teater Mandiri Putu Wijaya, Teater Koma Nano
Riantiarno, Teater Saja Ikranagara, yang sebagiannya sudah tak
terdengar kabarnya, semuanya berada di bawah kelompok ini dalam
hal usia.
Dilihat dari situ, pantas bila Studiklub Teater Bandung (STB)
merayakan ulang tahunnya yang ke-25 dengan agak besar-besaran.
Arifin, Teguh, Putu, Nano, Ikra, antara lain, datang ke Bandung
- selain yang dari Bandung sendiri. Sebagian dari mereka
menyumbang pementasan pula, 29 Oktober malam di Gedung Rumentang
Siang - dan kursi yang berjumlah 400 itu terisi penuh dengan
harga karcis Rp 1.000. Lalu diskusi teater diadakan esoknya,
di aula Pikiran Rakyat.
Ada pula pameran di gedung PWI Jawa Barat: foto-foto, poster,
dan bendabenda lain dari kegiatan teater di Bandung dan Jakarta,
berlangsung sampai 5 November. Terakhir, sampai dengan 13
Novemher selama empat hari STB sendiri mementaskan saduran Romeo
dan Yuliet Shakespeare di Rumentang Siang. Biaya seluruhnya
sekitar Rp 6 juta.
Padahal, grup ini, resminya, tak punya kekayaan. Tak punya
tempat latihan permanen atau sanggar. Bahkan tak punya anggota
tetap. Selama seperempat abad, di STB orang datang dan pergi -
hanya dipersatukan oleh "ikatan batin", ujar Suyatna Anirun,
sutradara utama dan sesepuh STB sejak 1969. Yakni sejak pemimpin
lama, Jim Lim, meninggalkan Bandung dan pindah ke Paris.
Suyatna memang pembantu Jim Lim, pemain yang pernah hampir
legendaris di kalangan para tokoh teater Indonesia - sebelum
Rendra, Arifin, dan Teguh, misalnya, menggantikan tempatnya.
Jim sendiri, salah seorang pendiri STB, yang didirikan pada 30
Oktober 1958 - dengan sebagian besar pendukung, mula-mula para
mahasiswa Seni Rupa ITB - adalah salah satu pembawa arus
terpenting teater 'modern' sesudah Kemerdekaan: Yakni masa
ketika orang menganggap 'drama' sebagai sekumpulan ilmu yang
rumit, didukung dengan teori akting terjemahan dari buku
berbahasa Inggris, juga dengan naskah terjemahan asing, atau
naskah Indonesia dengan dramaturgi Barat - yang menyebabkan
orang Indonesia sendiri banyak merasa asing. Seperti kata
Suyatna kepada TEMPO, "Kondisinya menyebabkan kami banyak
menggelarkan karya Barat." Toh, dituturkannya naskah asing itu
mulai berkurang sejak 1970, ketika mereka mulai mengadaptasi.
Dan adaptasi, usaha menembus keasingan - selain praktis
mengurangi kesulitan para pemain - memang salah satu ciri STB.
Juga bila itu hanya berarti penggantian lokasi permainan,
nama-nama peran, serta pakaian mereka, dan bukan jiwa - seperti
bisa diingat dari pementasan Lingkaran Kapur Putih Brecht
(1978), Jambangan Pecah von Kleist (1979), atau Kuda Perang
Goethe (1982). Ataupun pementasan HUT kemarin ini, Romeo dan
Yuliet. Romeo-nya bernama Urawa, Yuliet-nya Arini. Semua peran
berpakaian Jawa, setting-nya Jawa, logat bicaranya Indo-Eropa
mbakyu-mbakyu yang berkain dan ber-kemben itu mondar-mandir (dan
bukan duduk takzim) dengan monolog Shakespeare.
MEMANG ada adaptasi yang pas, misalnya Tabib Tetiron (1976),
karya STB - di bawah pimpinan Suyatna yang barangkali paling
bagus. Lebih lagi, tingginya nilai pementasan karya Moliere itu
juga karena ia terbebas dari ciri lain yang juga khas STB:
kelambanan. Bahkan untuk komedi yang sedianya kocak dan sukses
seperti Karto Lak, adaptasi dari Ben Jonson (1973). Para
pemain, yang begitu dipolakan dan tak pernah kelihatan bebas,
jarang sekali menunjukkan diri mereka punya force, alias greget.
Di STB, tempo dan ritme seperti tidak masuk pelajaran.
Toh jasa grup ini jelas: selama seperempat abad berhasil
mengadakan pementasan 1 kali setiap tahun. Dan itu penting
sekali meski jumlah pengunjungnya sangat jauh di bawah penonton,
misalnya, Remy Sylado yang di Bandung tak pernah mendapat
pemberitaan pers, dan yang kemudian hijrah itu. STB juga
menyelenggarakan kursus akting, tentunya demi kontinuitas.
Dalam pada itu, kedudukan para pimpinan atau seniornya sendiri
menguntungkan teater. Sebagian dari mereka di Pikiran Rakyat -
termasuk Suyatna, redaktur kebudayaan. Ada yang jadi staf
pimpinan gedung pertunjukan Rumentang Siang. Ada yang mengajar
di ITB, dan di Institut Kesenian Indonesia di Bandung. Ada pula,
sebagai tambahan, yang di DPRD. Untuk setiap pementasan, koran
besar seperti Pikiran Rakyat bisa tiga sampai lima kali memuat
bentanya, awal dan akhir.
Dan berlangsunglah kegiatan kebudayaan yang rutin. Tapi justru
faktor itulah, agaknya, yang memelihara kelangsungan kelompok
ini - selain ketekunan pengasuh yang sangat tenang dan berjiwa
guru seperti Suyatna. Kerutinan, dan bukan ekspresi, memang bisa
abadi: tak ada orang yang bisa berekspresi seperempat abad
terus-menerus. Kecuali bila ada tenaga cadangan atau pengganti.
Dan itulah yang tak ada.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini