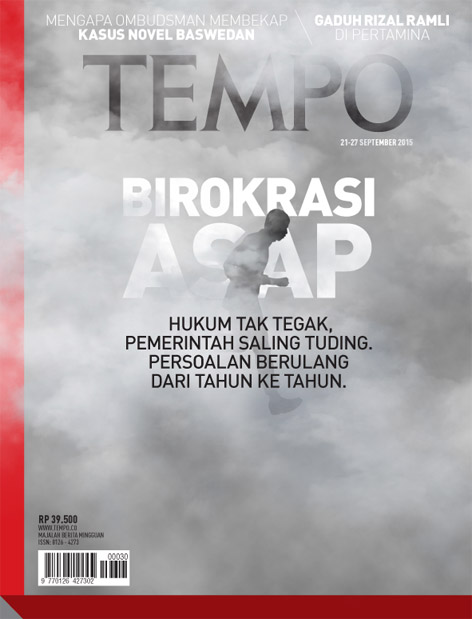Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nama lengkap saya Amrus, ya, hanya Amrus. Ayah saya suka membolak-balik nama untuk memberi nama anaknya. Contohnya, nama adik saya Altan, itu memakai rumus bolak-balik ala ayah saya dari kata Natal. Sedangkan nama Amrus didapat setelah Ayah membolak-balik namanya sendiri: Rustam kemudian jadilah Amrus. Saya tidak paham rumus yang dipakai Ayah itu bagaimana.
Natalsya adalah nama tambahan yang saya buat sendiri di Yogyakarta. Natal diambil dari kota kelahiran, Mandailing Natal, sementara Sya diambil dari nama kakek saya, Syah Alam, seorang jaksa yang pandai bermain biola. Jadi Natalsya artinya anak yang lahir di Natal dan merupakan keturunan Syah Alam.
Sejak duduk di sekolah dasar di Kota Natal, saya sudah gemar menggambar. Gambar pertama saya adalah peta dengan simbol gunung dan jalanan Kota Medan saat pelajaran ilmu bumi. Waktu itu saya belajar di sekolah Jepang. Saya ingat tiap pagi diwajibkan menghadap ke timur laut dengan sikap hormat ke arah bendera Jepang dan menyanyikan lagu Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang.
Gambar saya dinilai bagus oleh guru. Rata-rata nilainya 8-10. Tidak tahu juga gambarnya yang bagus atau gurunya kurang mengerti. Selain menggambar, saya suka sejarah, tapi benci pelajaran berhitung.
Beranjak remaja, saya suka menggambar kapal. Saya kagum terhadap kapal layar milik paman saya, Safi'un, yang memiliki kapal dagang bermuatan 50 ton. Saya beberapa kali ikut Paman mengarungi laut dari Pelabuhan Natal ke Sibolga, yang terletak di pantai barat Sumatera Utara. Biasanya waktu tempuhnya selama tiga hari dua malam untuk mengantar bahan kebutuhan pokok dan barang.
Di Medan, saya sempat mengenyam pendidikan di sekolah Muhammadiyah (tingkat SMP). Jujur, saya amat anti-PKI (Partai Komunis Indonesia) kala itu. Waktu ditanya oleh guru soal pemberontakan PKI di Madiun, saya dengan tegas menyatakan bahwa PKI bukan partai yang baik, apalagi yang saya pahami ketika itu mereka juga tak beragama.
Tapi, ketika saya bersekolah di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), Yogyakarta, pemahaman saya justru berbalik. Partai yang saya benci itu saya anggap membela rakyat. Persepsi saya berubah. Ya, tak kenal maka tak sayang.
Adapun orang tua tidak bisa berharap banyak kepada saya sebagai anak pertama. Saya lebih sering di luar rumah ketimbang memperhatikan adik-adik. Saya senang dengan keramaian kota, seperti di sekitar Jalan Antara dan Jalan Jeparis, kawasan padat penduduk di Medan.
Saya memang nakal. Namanya remaja. Saya dengan beberapa teman kerap duduk-duduk di sekat pembatas lalu lintas di kawasan niaga, yang tidak jauh dari pecinan. Kerjaan saya bertarung atau berkelahi dengan geng-geng yang ada di tempat itu. Salah satu pemicunya adalah berebut menjadi calo karcis bioskop. Aktor Hollywood, Marlon Brando dan Paul Newman, adalah sosok dalam film yang paling ditunggu di bioskop Medan.
Saya membeli tiket Rp 1.000, lalu dijual Rp 1.500. Ketika itu, jika ada geng calo karcis membeli lebih banyak atau mengambil lapak saya, dipastikan perkelahian akan terjadi. Hanya, tidak berani pakai senjata tajam, pertarungan masih sebatas saling pukul. Semua saya lakukan buat penghasilan tambahan.
Semasa berstatus pelajar, Amrus telah mencoba mandiri dengan penghasilan yang ia dapat dari hasil usahanya sendiri, tanpa tergantung bantuan orangtua. Dengan sebuah foto tustel (kamera) yang dipinjamkan pamannya, ia mencari nafkah di sela-sela waktu sehabis sekolah. (buku Amrus Natalsya dan Bumi Tarung karya Misbach Tamrin, 2008)
Dari perkawanan di pecinan itu, saya mendapatkan teman-teman baik, seperti Kiat Sek dan Benny Chung, yang saya buatkan puisinya—tentang tragedi Mei 1998. Saya juga satu geng dengan Saiful Sulun, yang ketika besar berhasil menjadi Pangdam V Brawijaya dan salah satu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
Namun tatkala saya ditahan pada 1968, setelah tragedi kemanusiaan pada 1965, saya tidak pernah minta dibebaskan Saiful. Saya mengerti betul masing-masing posisi kami, meski saat remaja bertarung demi geng yang sama, he-he-he.... Saya amat paham posisinya.
Setamat SMA, tekad saya bulat berangkat ke Jawa melanjutkan sekolah di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) Yogyakarta. Saya tahu ASRI dari berbagai sumber. Saya mendengar akademi ini tempat yang bagus untuk menimba ilmu kesenirupaan, yang merupakan kesukaan saya. Sebelum memilih ASRI, saya melirik Seni Rupa ITB, Bandung.
Amrus berangkat meninggalkan Medan menuju Yogyakarta tanpa menunggu pertimbangan orangtua. Keluarga ingin Amrus jadi pegawai negeri, pejabat perusahaan negara atau swasta, yang sudah jelas jamiman ekonominya. Tanpa ongkos cukup dan sepengetahuan keluarga, ia berangkat diam-diam naik kapal laut meninggalkan Medan menuju Jakarta. (buku Amrus Natalsya dan Bumi Tarung karya Misbach Tamrin, 2008)
Pada 1954, saya diterima di ASRI Jurusan Dekorasi dan Reklame, yang pelajarannya berlangsung reguler (pagi). Rupanya, saya merasa kurang cocok, lantas pindah ke Jurusan Lukis dan Patung, yang juga reguler. Itu pun saya tetap tidak betah dan memutuskan mengambil ASRI sore, yang jauh lebih bebas daripada ASRI reguler. Di ASRI sore, saya bertemu dengan Soenarto Pr., Arby Samah, Arwan Isa, Sulistyo, Gani Lubis, juga Michael Wowor.
Perkenalan saya dengan Michael Wowor (yang dikenal sebagai pematung) menumbuhkan semangat. Dari situ saya mulai menekuni seni patung. Patung pertama buatan saya berjudul Orang Buta yang Terlupakan, dipamerkan di lustrum pertama ASRI pada 1955 di ruang depan utama gedung Sono Budoyo, Yogyakarta. Tak disangka, Presiden Sukarno yang hadir kepincut oleh patung saya dan langsung membelinya. Itu amat membanggakan.
Sejak itu pergaulan saya cepat merambat ke luar lingkungan akademi. Saya suka berdebat dan berpendapat, sehingga hampir semua sanggar pada waktu itu kenal saya. Terutama Sanggar Pelukis Rakyat pimpinan Hendra Gunawan.
Di Sanggar Pelukis Rakyat, Amrus banyak berdiskusi tentang Marxisme. Di sanggar itu juga ia berkenalan dengan para pimpinan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), seperti Njoto, A.S. Dharta, Pramoedia Ananta Toer, Jubaar Ajoeb dan Basuki Resobowo. (buku Amrus Natalsya dan Bumi Tarung karya Misbach Tamrin, 2008)
Pada 1961, saya dan teman-teman ASRI, antara lain Isa Hasanda, Misbach Tamrin, dan Djoko Pekik, mendirikan Sanggar Bumi Tarung, yang berada di bawah Lekra di Yogyakarta. Pada masa tersebut, Lekra termasuk lembaga kebudayaan yang aktif melakukan pendidikan politik di kalangan seniman.
Saya memandang rakyat kala itu sedang bertarung, yaitu antara neokolonialisme dan kekuatan sosialis. Rakyat Indonesia waktu itu sebagian besar merupakan buruh dan tani. Inilah yang menjadi dasar garapan saya dan teman di Sanggar Bumi Tarung (SBT), yaitu menggambarkan perjuangan peranan buruh dan tani.
Penamaan Bumi Tarung merupakan ide saya. Bumi diartikan dalam arti fisik dan dalam arti pikiran. Bumi itu tempat bertarung, yaitu pertarungan antara baik dan buruk. Hingga sekarang pertarungan itu terus berlangsung. Tinggal tunggu siapa yang menang.
Menurut saya, Sanggar Indonesia Muda, Sanggar Pelukis Rakyat, Sanggar Bambu, dan lain-lain itu tidak jelas. Kalau Bumi Tarung jelas, yaitu berpihak. Bertarung itu berpihak, tidak mungkin tidak. Kepada siapa? Kepada rakyat.
Anggota SBT saya wajibkan untuk tahu Marxisme, sehingga tahu tentang perkembangan sejarah. Saya sendiri ikut kursus politik yang diselenggarakan PKI. Biasanya dilakukan sore dalam bentuk diskusi, dengan waktu yang tidak terjadwal.
Sebagai seniman, saya bukan menekankan pada aktivitas politiknya saja, melainkan juga pandangan politik yang harus keluar dalam lukisan. SBT tidak mengikuti realisme sosialis, tapi realisme revolusioner. Karena waktu itu (1961) Indonesia dalam tahap revolusi, seperti ganyang Malaysia dan perebutan Irian Barat, SBT bertumpu ke situ. Sanggar lain tidak ada yang seperti itu.
Menjelang Pemilu 1995, saya ikut kampanye dan membawa PKI ke peringkat keempat. Selanjutnya, pada awal meletusnya peristiwa 1965, banyak kawan saya ditangkap dan ditahan. Tapi saya masih bisa berada di pelarian selama tiga tahun, hingga akhirnya tertangkap dalam Operasi Kalong pada 1968 di rumah kontrakan saya di Grogol, Jakarta.
Lima tahun menjalani masa tahanan, pada 1973 saya bebas. Saya kemudian sibuk mengerjakan order patung kayu di Proyek Bina Karya, Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kemudian pada 1978 saya mengambil salah satu kios di Pasar Seni Ancol. Setelah dua tahun di Ancol, saya menemukan media lukis yang sebelumnya tidak pernah ada.
Saya mengandaikan penemuan media lukis itu seperti ketika Newton menemukan teori gravitasi bumi saat pulang kampung berlibur dan jalan-jalan di perkebunan apel milik ayahnya. Dia beristirahat dan duduk di bawah pohon apel. Ketika itu jatuh sebuah apel yang kebetulan diamati olehnya.
Begitupun saya. Saya secara tak sengaja mendapat ilham membuat lukisan dari kayu ketika sedang mengumpulkan potongan limbah kayu untuk digunakan membuat dingklik atau bangku kecil. Saya terdorong berimprovisasi ketika pahatan pertama itu terbentuk menjadi pohon, kemudian saya tambahkan bentuk rumah biar bagus, lalu saya buat juga pahatan pasar.
Saya melihat, kok tampak bagus dan unik. Nah, dari situlah saya menemukan sebuah media seni rupa yang tadinya belum ada. Kemudian, dengan berbagai cara, saya mendapatkan modal untuk membeli bahan papan kayu. Dalam beberapa bulan, kios saya semakin banyak terisi lukisan kayu.
Saya memilih tema kerakyatan untuk lukisan kayu. Pada 1981, saya berpameran di Balai Budaya Jakarta untuk pertama kalinya sejak peristiwa 1965. Ternyata publik menyambut positif. Lukisan kayu banyak terjual, bahkan saya mendapat order dari Wali Kota Jeddah pada 1970-1980-an, Mohammed Said Farsi, yang meminta saya membuatkan lima buah kaligrafi kayu berlafazkan Allahu Akbar.
Heru Triyono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo