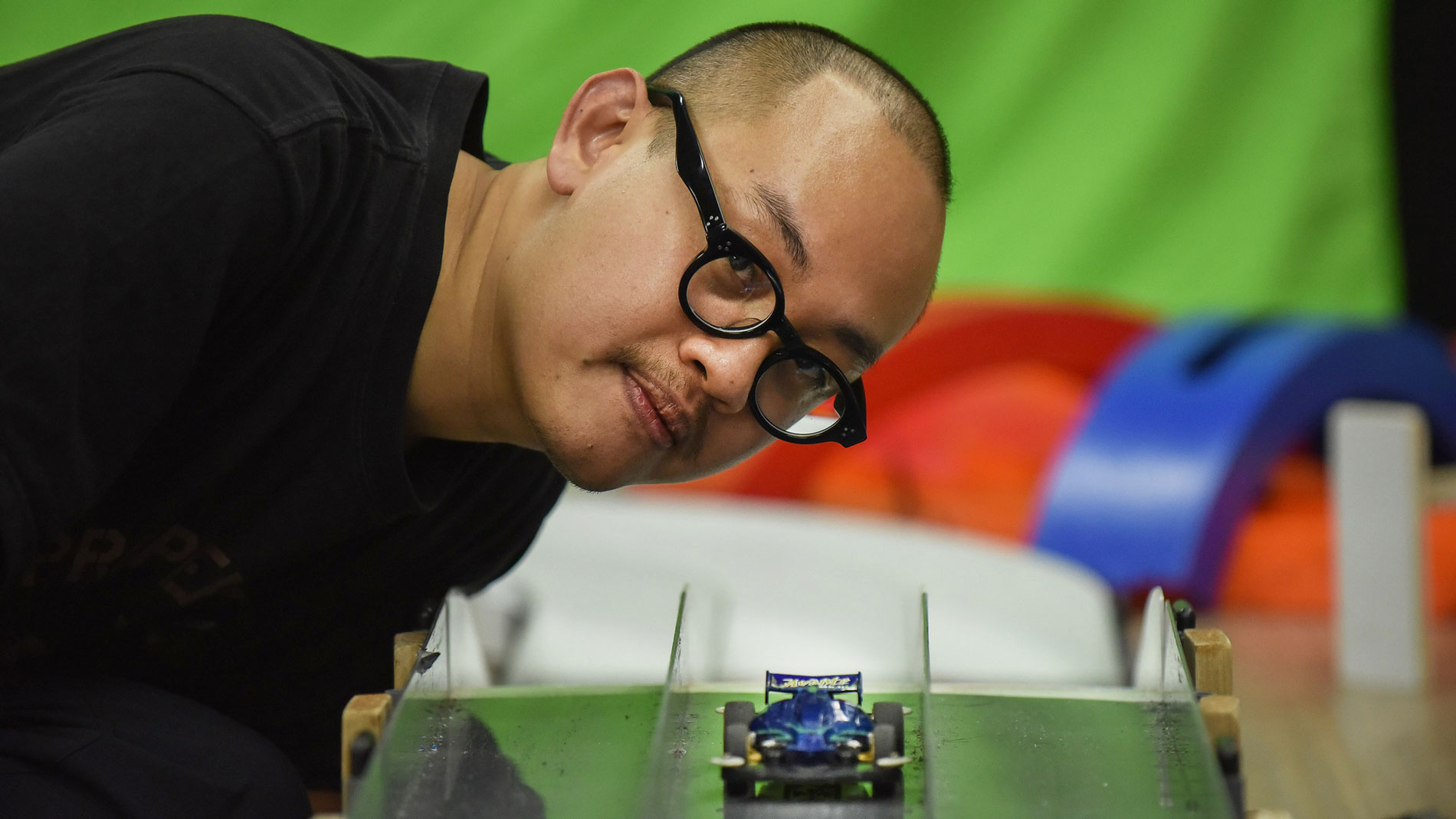Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI usia senjanya, Kartolo belum surut dari panggung kesenian ludruk, meski tak sesibuk dulu ketika berada di puncak kejayaannya pada 1980-an. Ia masih kerap diminta menghibur dalam acara resmi pemerintah dan hajatan.
Hingga pertengahan tahun lalu, sepekan sekali, ia masih aktif mengisi acara hiburan berdurasi satu jam berjudul Goro-goro Kartolo di stasiun televisi lokal Surabaya, JTV. Meski rekaman sudah disetop, acara itu masih ditayangkan ulang di JTV setiap Sabtu malam.
Kartolo mengatakan tarifnya sekali manggung Rp 8-10 juta untuk tiga orang. "Saya ini jualan suara, tidak terpengaruh BBM. Tolong kisah saya ini jangan dimasukkan rubrik kriminal," katanya berseloroh saat ditemui Tempo di rumahnya yang luas di Jalan Kupang Jaya, Surabaya, awal Juni lalu.
Siang itu, mengenakan kaus hitam, celana abu-abu, dan songkok, Kartolo bercerita dengan lancar tentang perjalanan hidupnya, yang masih terekam dengan baik di ingatannya. Wajahnya seperti tak berubah dari dulu, tetap awet muda dengan brengos (kumis) yang juga masih tebal.
Humor segar seakan-akan tak pernah kering sepanjang wawancara. Namun, menurut putri sulungnya, Gristianingsih, bila sedang di rumah, Kartolo lebih banyak serius ketimbang santai. "Bapakku kalau di rumah serius banget, hanya sesekali bercanda kalau lagi bersama cucu-cucunya," ujarnya.
Rumahnya ramai oleh celoteh kelima cucunya, yang masih berusia di bawah tujuh tahun, yang bermain bersama teman-temannya di teras. Terkadang diselingi teriakan keras dan tangis. Meski mereka masih bocah, Kartolo sudah memikirkan masa depan para cucunya. "Saya ingin membelikan mereka rumah satu per satu walau hanya perumahan. Kalau perlu rumah ini saya jual buat mereka," kata Kartolo.
Di panggung, Kartolo menggunakan bahasa Jawa Suroboyoan-Malang yang kasar. Penggemarnya sudah terbiasa dengan ungkapan-ungkapan Kartolo seperti kleleken timbo (tertelan timba) dan cangkeme legrek (mulutnya rusak).
Pada 30 Mei lalu, Kartolo menerima penghargaan Sapta Wikrama dari Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) Nahdlatul Ulama Surabaya. Menurut Lesbumi, Kartolo dinilai berhasil merevitalisasi ludruk gaya Suroboyoan yang sarat pesan moral untuk membangun peradaban yang mulia. Penghargaan serupa tahun ini diberikan kepada penyanyi dangdut Ida Laila.
SAYA dilahirkan di Desa Watuagung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tapi saya tidak tahu persis tanggal dan tahunnya. Di kartu tanda penduduk, memang tertera tanggal lahir saya 2 Februari 1947, tapi itu dimudakan dua tahun.
Emak, Payanah, tinggal di Kampung Manyar Sambongan, Surabaya, ketika saya masih di dalam kandungan. Adapun Bapak, Aliman, bekerja di pabrik karung di Jalan Juwingan, tak jauh dari Manyar Sambongan. Saat usia kandungan Emak semakin tua, Jepang mengebom gudang beras di Barata Jaya. Situasi Surabaya mencekam.
Khawatir akan keselamatan Emak, Bapak pun memutuskan pulang ke rumah kakek di Watuagung untuk mempersiapkan persalinan. Saya lahir di desa itu. Tapi orang tua saya tidak mencatat tanggalnya. Bila ditanya kapan saya lahir, jawaban Emak selalu sama, "Pokoke sakmarine pabrik beras Barata Jaya dibom Jepang (Pokoknya setelah gudang beras di Barata Jaya dibom Jepang)."
Orang tua memberi nama saya Tolo. Saya tidak pernah bertanya mengapa diberi nama begitu. Namun ada yang bilang bahwa tolo adalah sarang lebah yang dipelihara masyarakat di desa untuk diambil madunya. Saya mengubah nama saya menjadi Kartolo ketika aktif bermain ludruk pada awal 1960-an.
Saya tumbuh dan besar di Watuagung. Di desa itu pula saya menempuh pendidikan sekolah rakyat hingga lulus pada 1958. Sejak kecil, saya bercita-cita menjadi pegawai negeri. Waktu itu di Watuagung ada beberapa kelompok seni karawitan. Saya bergabung dengan salah satu kelompok untuk belajar gending dan menabuh gamelan. Kelompok karawitan saya sering mengiringi pentas ludruk, wayang kulit, dan tayub hingga ke luar daerah. Dari situ, saya mulai menggemari dunia seni.
Karena itu, ketika ada tawaran untuk menjadi guru bantu, saya menolaknya. Saya lebih tertarik pada tawaran bergabung dengan kelompok Ludruk Margo Santoso, Prigen, Pasuruan. Ludruk ini populer di Watuagung dan sekitarnya. Saat itu usia saya menginjak 18 tahun.
Awalnya tugas saya hanya menari remo untuk membuka pertunjukan. Sang sutradara tidak melibatkan saya ke dalam cerita. Saya belajar ngremo otodidaktik, hanya meniru gerakan penari remo di grup-grup ludruk yang pernah diiringi kelompok karawitan saya.
Setelah beberapa bulan, tugas saya tak hanya ngremo, tapi juga ngidung dan melawak. Pemimpin Ludruk Margo Santoso bilang saya punya bakat melawak karena celetukan-celetukan saya sering mengundang tawa.
Ketika Ludruk Margo Santoso sedang naik daun, tiba-tiba pecah peristiwa 30 September 1965 di Jakarta. Imbasnya, kesenian tradisional, termasuk ludruk, dilarang berpentas. Tak sedikit seniman yang dicurigai terlibat Partai Komunis Indonesia. Saya pun diwajibkan mengurus surat bersih diri ke komando rayon militer setempat. Oleh koramil, saya dinyatakan bersih.
Selama dua tahun seni ludruk vakum akibat larangan pentas. Akhirnya pada 1967, ketika ludruk boleh dipentaskan lagi, saya bergabung dengan Ludruk Dwikora, yang saat itu sedang nggedhong (main di tobong untuk beberapa lama) di Lawang, Kabupaten Malang.
Setahun kemudian, setelah Ludruk Dwikora bubar, saya pindah ke Ludruk Gajah Mada milik Korps Komando Angkatan Laut (sekarang Korps Marinir) di Malang. Dari Ludruk Gajah Mada, saya pergi ke Surabaya untuk bergabung dengan Ludruk Bintang Surabaya. Setelah itu, saya menyeberang ke Ludruk Tansah Trisno dan Jombang Selatan sebelum memutuskan tidak terikat dengan grup ludruk mana pun.
Banyak suka-duka saya alami ketika ikut nggedhong. Sukanya, kalau penontonnya banyak, otomatis honor yang saya terima juga lumayan. Dukanya, kalau sedang hujan, penontonnya sepi. Kalau sudah begitu, makan pun harus ngutang dulu di warung. Karena masih bujangan, saya tidak terlalu berpikir soal honor. Diberi kesempatan main saja rasanya sudah senang. Saya ikut keliling bersama grup hingga ke semua wilayah Jawa Timur.
Kala itu ludruk tobong masih digemari. Saat kami main, penontonnya lumayan banyak. Maklum, hiburan masih langka. Biasanya kami nggedhong maksimal 15 hari. Setelah itu baru pindah ke tempat lain. Tobongnya pun sederhana, hanya beratap daun tebu yang diberi sekat bambu. Kadang-kadang kami main di gedung yang tak terpakai. Di ludruk tobong tak ada pemain perempuan. Tokoh perempuan diperankan oleh waria atau yang dikenal dengan sebutan tandhak.
Pada 1971, saya bertemu dengan Bakron, sutradara Ludruk Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya. Dia mengajak saya bergabung. Bakron mengatakan dia sudah lama memantau saya. Dia menilai gaya saya cocok untuk mengisi siaran RRI. Bagi saya, ini kesempatan emas. Bergabung dengan Ludruk RRI kala itu bisa dikatakan impian semua seniman, karena ada kemungkinan diangkat menjadi pegawai negeri. Bila tidak ada yang mengajak, sulit bisa masuk ke Ludruk RRI.
Banyak selentingan dari kalangan seniman ketika saya bergabung dengan Ludruk RRI. Tidak sedikit yang mempertanyakan perekrutan saya. Intinya, kok bisa saya yang hanya berangkat dari ludruk daerah masuk RRI. Padahal seniman yang ditarik masuk Ludruk RRI umumnya sudah punya nama dan diakui kehebatannya. Saat itu Ludruk RRI memang gudangnya seniman top. Trio lawaknya, Kancil Sutikno, Markuat, dan Sidik Wibisono, sudah tenar.
Ludruk RRI hanya khusus rekaman on air untuk mengisi program siaran tiap Senin malam. Namun, di luar siaran, Ludruk RRI juga melayani tanggapan tampil di hajatan atau di acara instansi pemerintah dan swasta. Di Ludruk RRI, saya diberi peran serius, meski basic saya pelawak. Sebab, tidak mungkin menggeser trio Kancil, Markuat, dan Sidik, yang sudah identik dengan Ludruk RRI.
Saya kembali jadi pelawak saat Ludruk RRI sedang pentas off air di Malang dalam lakon Kancil Sekolah. Menjelang main, tiba-tiba Sidik pamit pulang ke Surabaya. Oleh sutradara, saya diminta menggantikan peran Sidik sebagai pelawak bersama Kancil dan Markuat. Sejak saat itu, saya sering diminta jadi pelawak. Apalagi, tak lama kemudian, Sidik keluar dan membentuk grup Ludruk Sidik Cs.
Di RRI, saya ketemu jodoh. Salah satu seniman perempuannya, Kastini, saya persunting pada 1974. Dari pernikahan ini, saya punya tiga anak, yakni Agus Slamet (almarhum), Gristianingsih, dan Dewi Triyanti. Setelah menikahi Kastini, tahun itu juga saya memutuskan keluar dari Ludruk RRI karena peluang untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri tipis. Sebab, ketika itu memang sedang tidak ada pengangkatan pegawai radio pemerintah, sementara gaji saya sebagai pegawai honorer RRI kecil sekali.
Keluar dari Ludruk RRI, saya bergabung dengan Ludruk Persada, Malang. Ibarat kembali ke habitat lama, saya nggedhong lagi bersama Persada. Saya kembali menjalani kehidupan sebagai seniman tobong. Untung istri saya juga seniman sehingga, meski penghasilan dari panggung minim, dia tak pernah mengeluh. Sampai akhirnya pada 1980 saya bertemu dengan Nelwan Subuhadi, pemimpin karawitan Ludruk RRI. Dia mengajak saya mencoba masuk dapur rekaman Nirwana Record, Surabaya, dengan format grup lawak.
Nelwan yang menentukan personelnya, yakni Sapari, Munawar, Yakin, dan Amin Tohari. Saya mengajak istri saya. Nama grupnya Sawunggaling, Kartolo Cs. Saya pun memutuskan keluar dari Persada. Tidak saya sangka, kaset saya laku. Radio di daerah banyak yang memutar kaset saya. Rekaman berjalan terus hingga 1995 dan menghasilkan 112 album. Saya tidak memungkiri, sejak terjun ke dunia rekaman, nama saya kian terkenal.
KETIKA sedang berada di puncak kejayaan, Kartolo mulai memikirkan hari tuanya. Pada 1984, dari honornya manggung, ia membeli sebidang tanah seluas 420 meter persegi di Jalan Kupang Jaya, Kelurahan Sonokwijenan, Surabaya. Menurut dia, saat itu harga tanahnya Rp 30 ribu per meter persegi.
Di atas lahan itu, ia membangun rumah secara bertahap. Kini berdiri rumah besar berlantai dua di atas lahan itu. Kartolo menyekat rumah tersebut menjadi tiga bagian, dua di antaranya ditempati dua anak perempuannya yang sudah berkeluarga.
Adapun Kartolo menempati rumah bagian tengah. Di lantai dua rumahnya tersedia musala. Kartolo mengaku sengaja membangun rumah besar untuk menjadi tempat singgah bagi para seniman dari daerah yang sedang ke Surabaya. "Bisa untuk istirahat mereka," ujarnya.
Dinding luar bagian depan rumahnya berlapis porselen hitam dengan kombinasi hijau. "Kalau dilihat dari jauh, rumah saya seperti pagupon (kandang merpati)," katanya berseloroh.
Tak ada perabotan berharga di ruang tamunya yang lapang. Ruangan itu hanya berisi seperangkat meja-kursi dan bufet. Dindingnya dihiasi foto-foto Kartolo ketika masih muda. Sedangkan di dalam bufet berjejer penghargaan yang pernah diterimanya, baik berupa piala maupun piagam. Tulisan "Selamat Datang" dari Styrofoam yang dipasang saat Kartolo pulang haji beberapa tahun lalu belum dicopot dari dinding. KUKUH S. WIBOWO
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo