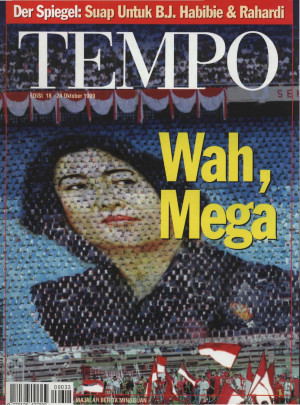Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SIDANG Umum MPR 1988 diwarnai sebuah peristiwa menarik. Seorang pria kurus, berkacamata, Wakil Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meminta voting atas tujuh masalah pokok dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Permintaan voting yang disampaikan Hartono Mardjono, pria berperawakan kurus itu, tak ubahnya terobosan bagi sidang-sidang MPR selanjutnya.
Sebelum ’’gebrakan” Hartono, voting ibarat ’’barang haram” di Senayan. Almarhum Mayjen Soebiyakto, juru bicara Fraksi ABRI di MPR, misalnya, pernah mengatakan: ’’Voting mencerminkan warna liberal, bukan Pancasila” (TEMPO 12/3/88).
Awal Oktober 1999 yang baru lalu, Hartono Mardjono kembali meneriakkan permintaan voting melalui interupsi. Suaranya lantang mendesak, forumnya sama: Sidang Umum MPR. Namun, kali ini Hartono mewakili Partai Bulan Bintang (PBB). Usianya sudah 11 tahun lebih tua. Toh, sikapnya mantap tak tergoyahkan. Dalam pemilihan Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR RI, ia sanggup ’’memaksa” seluruh anggota majelis untuk melakukan voting. Padahal jarum jam menunjukkan sudah lewat tengah malam dan para wakil fraksi telah diberi kesempatan berembuk selama dua jam. Namun Hartono Mardjono bersikukuh untuk voting dengan alasan kalau ada satu suara saja tidak setuju, keputusan yang diambil tidak bisa dianggap sebagai hasil mufakat. ’’Voting mencerminkan pemilihan dengan napas demokrasi. Itu yang terpenting,” ujarnya,
Kepiawaian Hartono dalam adu argumentasi bukanlah hasil latihan sesaat dalam ruang sidang. Sudah lebih dari 35 tahun pria ini bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan sebagai advokat—sebuah karir yang memaksanya untuk tangkas berpikir dan berargumentasi. Dan politik adalah panggung yang sangat dikenal Hartono Mardjono.
Ia lahir di Tegal, 17 Juli 1937, dari sebuah keluarga muslim yang taat. Ayahnya, Mardjono, adalah aktivis Hizbullah—laskar rakyat Masyumi. Ibunya, Suparti, sekretaris Masyumi cabang Tegal. Ketika ayahnya bekerja sebagai pegawai DPR di Jakarta pada 1950-an, Hartono—usai sekolah—kerap mampir ke kantor ayahnya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Di sana, selama berjam-jam ia betah ’’menonton” perdebatan antara Mohamad Natsir, Prawoto, Zainal Abidin Ahmad, Mr. Mohamad Roem, dan Mr. Kasman Singodimejo. Atau melihat Aidit adu argumentasi dengan lawan-lawan politiknya.
Pendiri Pelajar Islam Indonesia (PII) ini akrab dengan tokoh-tokoh Masyumi sejak remaja. Ia aktif di KAPU (Komite Aksi Pemilihan Umum) Masyumi—menjelang Pemilu 1955. Pada masa mahasiswa, ayah lima putri ini aktif di Pemuda Muhammadiyah. Pada 1963, ia ikut mendirikan Persami (Persatuan Sarjana Muslim Indonesia). Setelah Masyumi dibubarkan, pendiri dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini kemudian aktif di Parmusi (Partai Muslim Indonesia) sejak 1967. Ia menjadi Ketua Parmusi Wilayah DKI hingga partai ini berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973. Jabatan sebagai Ketua PPP DKI dipegangnya selama enam tahun lebih.
Pada 1982, saat usianya 45 tahun, Hartono, yang lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjadi anggota DPR/MPR. Dalam Sidang Umum MPR 1988, ia tampil sebagai Wakil Ketua Fraksi PPP. Sebelas tahun kemudian, Hartono kembali hadir di Senayan mewakili Fraksi Bulan Bintang. ’’PBB bukan penjelmaan Masyumi, walau grand ideas-nya berasal dari sana,” ujar Wakil Ketua DPP PBB ini seraya mengepul-ngepulkan asap rokok. Dalam usia 62 tahun, ia mampu menghabiskan sebungkus rokok sehari dan tetap merasa sehat-sehat saja.
Kini, bersama keluarganya, Hartono mendiami rumah asri di tengah sebuah kampung padat di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Pekan lalu, di sela-sela kesibukannya, anggota MPR ini menerima wartawan TEMPO Darmawan Sepriyossa dan Hermien Y. Kleden di kediamannya, yang banyak dihiasi lukisan kaligrafi.
Petikannya:
Voting yang Anda minta dalam Sidang Umum MPR lalu mengingatkan orang pada peristiwa serupa dalam SU MPR 1988. Rupanya Anda ini ’’pelanggan” voting?
Voting pada SU MPR 1988 itu menyangkut tujuh masalah pokok. Agama, asas tunggal, sebangsa itulah. Yang lainnya saya kurang ingat. Saat itu, saya juga duduk di Panitia Ad Hoc (PAH) II non-GBHN. Ketika itulah, untuk pertama kalinya suatu fraksi di luar pemerintah (Golkar) berani mengajukan rancangan ketetapan (rantap) MPR. Saya membuat delapan rantap, antara lain mengenai pengulangan sebuah ketetapan yang diperbarui setiap lima tahun. Tap ini menyangkut pelimpahan kekuasaan kepada presiden dalam keadaan darurat—yang sama saja dengan memberikan blangko cek kosong kepada presiden.
Apa saja rantap yang dibuat oleh Anda dan rekan-rekan dari Fraksi PPP untuk mencegah presiden bebas ’’menulis di atas blangko cek kosong”?
Kami membuat satu tap MPR yang memerintahkan presiden dan DPR untuk menyusun undang-undang yang mengatur keadaan bahaya, seperti UU PKB (Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya) sekarang. Usul itu kami ajukan agar kebebasan orang berdemokrasi tidak dilanggar. Dalam rantap kedua, saya minta supaya wewenang pelimpahan kekuasaan di atas dicabut karena wewenang ini membuat kapan saja Pak Harto mau, keadaan bisa jadi darurat. Ini legalisasi bagi lahirnya Kopkamtib, Laksus, Opsus. Kami juga menolak Tap Referendum dan Rantap Pemilu. Meskipun kalah, kami, toh, sudah mencoba dan beberapa keputusan itu diambil dengan cara voting.
Bukankah pada tahun yang sama (1988) Anda memprakarsai penarikan Naro dari bursa calon wakil presiden?
Benar. Sebab, saya melihat pencalonan Naro saat itu adalah manifestasi dari perang dingin yang kian memuncak antara Cilangkap (markas besar TNI) dan Cendana (istana kediaman Presiden Soeharto). Cilangkap menentang penunjukan Pak Harto pada Sudharmono. Tapi, untuk kontroversi secara terbuka, dengan menunjuk calon dari ABRI, mereka tidak berani. Maka, Naro-lah yang diajukan.
Secara resmi, PPP memang tidak pernah mencalonkan Naro. Tapi, apakah pernah ada niat untuk melakukannya?
PPP tidak pernah punya inisiatif untuk itu. Justru pihak luar (ABRI) yang mencalonkannya. Mereka masuk, memengaruhi, dan Naro pun tiba-tiba begitu berhasrat. Yang menarik bagi saya, ide pencalonan ini makin hari makin kuat. Malam hari, sebelum Naro resmi dicalonkan, Ibrahim Saleh dari Fraksi ABRI bicara, persis di belakang tempat duduk saya: ’’Pak Naro jangan mundur. Kalau mundur, saya tembak.” (Ibrahim Saleh membantah ketika hal ini dikonfirmasi TEMPO. ’’Itu OKB, omong kosong belaka,” ujarnya.) Saya kaget juga dan mulai berpikir.
Apa yang Anda pikirkan?
Saya berpikir bahwa Cilangkap akan melawan Cendana dengan menggunakan kekuatan lain di luar mereka. Saya merenung-renung di Hotel Sahid—tempat kami menginap ketika itu. Mengapa mereka mencalonkan Naro? Sebab, Naro itu anggota Opsus (Operasi Khusus, lembaga ekstrakonstitusional yang dipimpin langsung oleh Ali Moertopo). Pukul 01.00 pagi, saya datangi Naro di kamarnya. Saya tanya kepada Naro, PPP itu tidak punya kekuatan, jadi siapa yang akan mendukung pencalonannya?
Lalu, apa saja yang Anda perbincangkan?
Saat itu sudah lewat tengah malam. Kami berdebat keras dan bertengkar. Pak Naro bilang: ’’ABRI mendukung kita, begitu pula sebagian Golkar.” Jawab saya: ’’Pak, kalau Anda betul-betul maju karena keinginan umat, karena PPP, saya dukung sepenuhnya. Tetapi kalau kita hanya jadi alat dan kalau kita babak belur, saya tidak bisa terima kalau umat hanya dijadikan bemper.” Hari itu Kamis, 9 Maret 1988.
Bukankah Naro tetap bersikeras untuk maju? Bagaimana cerita di balik mundurnya?
Oh, ya. Beliau marah dan tetap ingin maju. Saya bilang: ’’Oke. Kalau Anda tetap ingin maju, besok saya akan menghadap presiden terpilih.” Saya tidak mau umat dibenturkan pada kekuasaan dan kita akan babak belur tanpa ada gunanya. Perdebatan malam itu berlanjut dengan sebuah rapat di rumah Pak Naro, pada pukul 07.00, keesokan harinya. Yang hadir adalah anggota fraksi dan DPP PPP. Beliau membuka rapat dengan mengatakan saya tidak setuju pencalonannya, padahal semua yang hadir sudah dibaiat (disumpah secara agama) di Hotel Sahid untuk mendukungnya.
Anda ikut dibaiat?
Saya dan beberapa teman keluar diam-diam dari Hotel Sahid waktu acara itu berlangsung. Pak Naro kemudian bertanya kepada kita, satu per satu. Naro menyerah setelah mayoritas suara ternyata mendukung saya. Ia lalu menentukan delegasi yang menghadap Pak Harto dan meminta saya menjadi juru bicara. Saya dan Pak Harto saling berbicara dalam bahasa Indonesia dan Jawa halus. Ketika pengumuman resmi tentang mundurnya Naro keluar, semua orang terkejut, termasuk orang PPP sendiri. Sebab, di luar tim yang rapat di rumah Naro, tak seorang pun mendapat bocoran soal ini.
Dengan konstelasi politik pada masa itu, sikap Anda meminta Naro mundur itu terkesan oportunis, sekaligus melempangkan jalan bagi calonnya Presiden Soeharto, yakni Sudharmono.
Saya tidak peduli. Saya lihat pencalonan Naro hanya menyakibatkan partai jadi bemper bagi orang lain untuk menghadapi orang lain lagi. Saya mengatakan ini karena saya mengikuti seluruh prosesnya, sampai Naro diancam Ibrahim Saleh segala macam….
Mengapa Anda harus ’’ngotot” seperti itu? Apa ada manfaatnya mengingat kehidupan politik yang sangat represif pada masa itu?
Sebagai muslim, saya tidak mengenal istilah putus asa. Betapapun kecilnya celah, harus diperjuangkan. Suatu ketika, Mas Dahlan Ranuwiharjo bertanya kepada saya, apakah saya tidak capai ’’menceboki” Naro. Saya bilang, kalau diibaratkan, saya ini petugas yang menjaga benteng strategis, tapi penuh limbah. Jadi, bukan soal nyeboki Naro, tapi menjalankan sebuah amanat yang diberikan umat.
Nama Anda masuk bursa calon ketua PPP menjelang Muktamar 1989. Mengapa gagal?
Banyak orang mencalonkan saya menjadi ketua ketika itu—termasuk Buya Ismail Hasan, yang kemudian terpilih sebagai ketua. Tapi, waktu muktamar mau mulai, pemerintah mencegah pencalonan saya. Pelakunya Rudini, yang ketika itu Menteri Dalam Negeri. Jadi, di Departemen Dalam Negeri saja saya sudah akan payah. (Rudini membenarkan hal ini ketika dikonfirmasi TEMPO: "Wakti itu pemerintah memang banyak campur tangan dalam urusan partai dan ada usaha menggolkan Buya Ismail menjadi Ketua PPP.") Akhirnya, Buya Ismail jadi ketua. Sedangkan saya, untuk masuk DPP saja dicegah. Begitu pula Husni Thamrin. Dia dicoret dari daftar.
Sebelum di PPP, Anda aktif di Permusi hingga partai-partai Islam berfusi ke dalam PPP pada 1973. Apakah fusi, menurut Anda, menjadi awal mula pengerdilan partai Islam?
Pengerdilan belum mulai pada saat itu karena aturan main Soeharto belum tertata dengan baik. Lepas dari soal itu, fusi ada hikmahnya. Yakni, bersatunya partai-partai Islam—sesuatu yang susahnya setengah mati. Terbukti, dalam pemilu pertama setelah fusi (1977), PPP mengalahkan Golkar di DKI . Kematian partai-partai Islam mulai setelah 1985-an, saat jaya-jayanya Orde Baru.
Anda termasuk tokoh yang menyaksikan runtuhnya partai-partai Islam dari Orde Lama ke Orde Baru. Benarkah ada semangat anti-Sukarno di lingkungan Masyumi selepas pembubaran partai ini pada 1960?
Sikap anti ini muncul terhadap sikap Sukarno, yang menganggap marhaenisme sebagai marxisme yang diterapkan di Indonesia, bukan terhadap Sukarno pribadi. Ketika Bung Karno sakit, tokoh-tokoh Masyumi menengoknya. Lalu, saat beliau meninggal, Mr. Kasman Singodimejo turut memanggul kerandanya. Saat Sukarno belum dekat ke kalangan kiri, hubungan Sukarno-Masyumi baik sekali. Ia pernah menunjuk dr. Soekiman Wirjosandjojo dan Mr. Roem untuk membentuk kabinet.
Sebagian masa muda Anda lewatkan bersama Masyumi. Bagaimana Anda melihat sikap Masyumi sebagai partai Islam yang menganut garis keras?
Sikap anak muda sekarang sesungguhnya lebih keras dibandingkan dengan Masyumi. Dulu, Masyumi selalu bisa bekerja sama dengan Partai Kristen dan Partai Katolik—selama sikap jujur dan supremasi hukum ditegakkan. Ketika Orde Baru membabat seluruh aktivitas sosial-politik, yang marak adalah organisasi tertutup, usroh, halaqah. Agak sukar bagi anak-anak muda untuk hidup seperti ini. Tak ada gerai untuk melihat pikiran secara transparan. Timbul organisasi eksklusif, tertutup, yang membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi kelompok eksklusif. Partai Keadilan, misalnya, lahir dari situasi eksklusif seperti ini.
Setelah reformasi, partai-partai Islam, yang terpinggirkan selama hampir 40 tahun, berkembang lagi. Menurut Anda, perlukah ide Masyumi untuk mengembalikan Pancasila kepada Piagam Jakarta—yang mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya—dihidupkan kembali?
Untuk apa kita meributkan lambang? Apa yang disebutkan Piagam Jakarta itu kan cerita lambang, hanya simbol. Saat Masyumi memerintah, tidak ada Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Perkawinan, yang menjadikan agama sebagai dasar perkawinan yang sah. Kini, ada Undang-Undang Zakat bagi umat Islam karena masyarakat memerlukannya. Itu kan tidak eksklusif. Biarkan semuanya berjalan secara natural.
Dengan tokoh Masyumi siapa Anda merasa dekat?
Sejak remaja, saya sudah banyak bergaul dengan para pemimpin Masyumi. Hubungan saya dengan Mohamad Roem, Natsir, Hamka, Mr. Kasman, sangat baik. Dengan Mr. Kasman, saya sering keluar-masuk desa, mandi di kali. Pak Roem, misalnya, sangat familiar tapi formal. Bila saya ke rumahnya dan beliau masih pakai kaos oblong, Pak Roem akan bilang: ’’Sebentar, Nak. Saya pakai baju dulu.” Beliau selalu pakai baju koko. Hidupnya sangat sederhana. Saya tak akan pernah melupakan pengalaman dengan Pak Roem pada 1981.
Peristiwa apa itu?
Teman-teman dari UMJ meminta saya menghubungi Pak Roem untuk menjadi rektor di sana, setelah mereka berkali-kali gagal membujuknya. Akhirnya beliau setuju dan mengatakan, ’’Nak Hartono, dengan uang pensiun saya yang sekarang, ternyata rumah tangga saya masih kekurangan Rp 300 ribu sebulan. Supaya saya bisa konsentrasi memimpin, bisakah pihak universitas menggaji saya sebesar Rp 300 ribu? Langsung saya sambar, ’’Lo, UMJ bisa menggaji Bapak Rp 2 juta sebulan.” Tapi beliau bilang, ’’Cukup Rp 300 ribu saja, Nak. Saya tidak butuh banyak-banyak.” Beliau kemudian urung menjadi rektor karena ’’dipaksa” Mr. Kasman—koleganya—untuk memiliki kartu anggota Muhammadiyah.
Anda termasuk generasi terakhir Masyumi yang masih aktif berpolitik. Apakah kelahiran PBB bisa dipandang sebagai kebangkitan Masyumi?
Kesamaan barangkali hanya ada pada grand ideas-nya. Tetapi ini dua partai yang berbeda. Kita sadar akan zaman yang berubah dan bahwa kita menghadapi situasi yang berbeda.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo