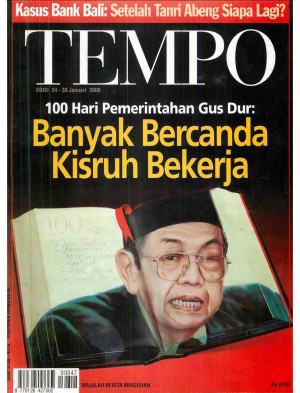TAHUN Naga ini adalah tahun kegemilangan. Saat kemujuran bakal meruap. Begitu kata kalender Cina kuno. Dan kini warga Tionghoa di Indonesia membuktikan ramalan itu. Dua pekan lalu, melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
Dengan itu, setelah tiga dasawarsa diberangus rezim Orde Baru, pada 5 Februari ini perayaan tahun baru Imlek 2551 bakal lebih meriah dirayakan. Pertunjukan barongsai—sejenis singa-singaan—boleh kembali meramaikan jalan-jalan. Kain merah bertuliskan aksara emas Gong Xi Fa Coi—ucapan selamat tahun baru—bebas dipajang di mana saja. Lampion, hio, dan lilin-lilin raksasa di kelenteng-kelenteng bakal menyala lebih terang dari tahun sebelumnya.
Namun, bukan cuma itu soalnya. Lebih dari sekadar urusan pengerangkengan barongsai, Instruksi 14 adalah sebuah monumen kebijakan Orde Baru dalam menyikapi keberadaan warga Tionghoanya. Beleid itu dibuat berdasarkan sebuah kecurigaan bahwa kaum ini akan selalu saja main mata dengan Tiongkok. Apalagi, Peking—dialek lain untuk Beijing—ditengarai berada di balik upaya kup Partai Komunis Indonesia 1965. Karena itulah, tali ikatan kultur mereka dengan tanah leluhur mesti dipotong habis. Segala yang berbau budaya Cina, mulai dari aksara, sekolah, kesenian, mesti dipagari—untuk tak menyebut diharamkan.
Stigma paling gawat yang diterakan ke kalangan ini adalah soal pelarian modal. Investasi tiga kelompok usaha kakap seperti Salim, Sinar Mas, dan Lippo di Fujian dan Guangdong di wilayah selatan Cina tak henti-hentinya dikecam atas nama nasionalisme.
Dan salah kaprah itu, meski untuk beberapa hal ada benarnya, dicoba diluruskan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Cina bahkan menjadi negara yang secara resmi pertama-tama dikunjunginya pada awal Desember lalu. Di sana, selain mengumumkan dirinya sebagai keturunan Cina—entah guyon entah serius—Abdurrahman juga gencar mengampanyekan hubungan dagang di antara kedua negara. Pekan ini sebuah pertemuan regional yang dihadiri Menteri Alwi Shihab bahkan menyarankan dibentuknya kerja sama Indonesia-Cina-India untuk menangkal kekuatan internasional lainnya.
Sejak Deng Xiaoping melancarkan politik pintu terbuka dan tak lagi mengharamkan kapitalisme pada 1978, Cina mengalami sebuah "lompatan ke depan" sesungguhnya. Pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu itu melesat di angka 9 persen setahun. Dan sempat digembar-gemborkan "roket" itu dilesatkan oleh besarnya arus dana dari Cina perantauan Asia Tenggara, juga Indonesia.
Namun, menurut Profesor Liang Yingming, Deputi Direktur Center for Overseas Chinese Studies di Universitas Beijing, anggapan itu terlalu dibesar-besarkan. Selama ini, kata lelaki asal Solo yang memilih pulang ke Cina pada 1955 itu, publikasi soal itu selalu dipukul rata dengan juga memasukkan Hong Kong, Makao, dan Taiwan. Padahal, dari total investasi asing US$ 27 miliar, kucuran modal dari Asia Tenggara cuma 5 persen. Itu pun kebanyakan dari Singapura dan Thailand. "Investasi dari Indonesia sangat kecil," katanya.
Data Kamar Dagang dan Industri Jakarta pun menunjukkan minimnya hubungan dagang Indonesia dengan Cina. Perdagangan di antara kedua negara pada tahun kemarin (Januari-Juni) cuma 1,32 persen dari total perdagangan Cina dengan dunia senilai US$ 156 juta. Nilai ekspor Indonesia juga berada jauh di bawah negara ASEAN lainnya. Di sektor kertas, misalnya, Thailand mampu menyedot US$ 66,22 juta dari total impor Cina. Sementara itu, Indonesia masih terseok-seok di angka US$ 14,56 juta.
Memang, data itu tak mampu menelusuri pergerakan modal yang selalu dengan lincah berpindah-pindah. Sebagaimana diketahui, para taipan Indonesia masuk melalui berbagai perusahaan multinasional mereka di Singapura atau Hong Kong. Arus modal kelas menengah lebih sulit lagi dideteksi. Pergerakan pengusaha level ini justru lebih tak kasat mata. Perusahaan didirikan atas nama mitra lokal yang digaetnya. Mereka bergerak secara tak mencolok, nonformal, melalui jaringan kekerabatan.
Tengoklah profil Panuju. Awal Desember lalu, Cina muslim asal Riau ini ditemui tengah menggigil di Masjid Niu Jie di Distrik Xiangwu, Beijing. Ia tak mengenakan overcoat. Jas kumal tipis yang dikenakannya tak mampu menahan dinginnya hujan salju. Tak ada yang menyangka bahwa dia adalah presiden direktur perusahaan dengan cabang di sejumlah negara. Padahal, kantor PT Wira Citra Lestari miliknya (produsen radiator untuk perusahaan listrik) tersebar di Amerika Serikat, Jerman, Vietnam, Kamboja, dan tentu saja Cina. Lima tahun lalu, Panuju melebarkan usahanya ke Cina Daratan. Tahun ini ia merencanakan membuka perwakilan di Shanghai. Sementara itu, kantor pusatnya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, cuma sebuah ruko gelap berlantai empat di dalam gang. Sayang, ia cuma melengos ketika ditanya berapa nilai investasinya di sini.
Fenomena itu diiyakan Tan Wei Wen, Direktur The China International Center for Economic and Technical Exchanges—sebuah badan di bawah kementerian perdagangan RRC. Meski begitu, katanya lagi, volume perdagangan dan investasi dari Indonesia tetap saja masih kecil. "Saya kira kurang dari 1 persen," kata mantan atase perdagangan Kedutaan RRC di Jakarta (1993_97) itu.
Keterlibatan pengusaha Tionghoa Indonesia dalam jaringan Cina perantauan juga diragukan Profesor Liang. Menurut dia, secara umum, akibat pemberangusan Orde Baru, jalur itu sudah nyaris terpotong habis. Yang banyak berperan di jaringan ini adalah pengusaha asal Hong Kong dan Singapura.
Tan, misalnya, kerap menerima keluhan banyak pengusaha Tionghoa Indonesia yang bisnisnya tersungkur di Cina. Penyebabnya, ya itu tadi, rata-rata tak cukup punya koneksi bisnis dan buta situasi pasar. Cerita serupa datang dari Guo Yuan Xian, pengusaha kayu di Beijing asal Jawa Tengah yang banyak melakukan kontak dengan pengusaha Tionghoa Indonesia. "Biasanya, mereka dibohongi kongsinya di sini. Dijanjikan yang muluk-muluk, eh, malah jeblok," katanya.
Benar bahwa pemerintah Cina secara sadar memanfaatkan kaum Cina perantauan untuk memacu pertumbuhan ekonominya. "Terus terang saja, kami memang memanfaatkannya," kata Tan Wei Wen. Dan dalam hal ini, yang paling agresif adalah pemerintah daerah, khususnya Guandong dan Fujian, dua provinsi asal Cina perantauan Asia Tenggara. Pemerintah daerah memang diberi kewenangan meneken kontrak maksimal US$ 300 juta.
Untuk keperluan itu, salah satu langkah pemerintah RRC adalah memaksimalkan peran Jiao Pan (kantor urusan Cina perantauan). Lembaga ini dipimpin pejabat setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung ke perdana menteri.
Toh, pemikiran seperti ini mulai mendapat tentangan. Profesor Liang adalah salah satu yang paling vokal menyuarakannya. "Saya tidak menyukai lembaga semacam itu," katanya. Liang dan kawan-kawannya yang berasal dari Asia Tenggara berulang kali menyuarakan bahwa lembaga semacam Jiao Pan tak lagi diperlukan. Soalnya, 95 persen Cina perantauan di Asia Tenggara telah menjadi warga negara setempat. "Mereka adalah orang Indonesia, Malaysia, Thailand," katanya.
Kini, kewenangan Jiao Pan telah dibatasi hanya untuk melindungi kepentingan huaqiao (warga negara RRC yang berada di luar negeri) dan tidak dibenarkan cawe-cawe terhadap urusan yang menyangkut huaren (etnis Tionghoa yang telah menjadi warga negara lain). Titik beratnya pun semata-mata untuk mempromosikan investasi di kalangan pengusaha Cina perantauan.
Sering disebut-sebut, salah satu manifestasi dari kekukuhan jaringan itu adalah adanya Konferensi Pengusaha Cina Perantauan se-Dunia. Forum ini diprakarsai mantan perdana menteri Singapura, Lee Kuan Yew, dan telah diselenggarakan empat kali. Di Singapura (1991), Hong Kong, Australia, dan terakhir di Kanada.
Lagi-lagi, berbagai pihak meragukan efektivitasnya. Menurut analis SocGen Securities, Lin Che Wei, yang pernah menghadirinya, pertemuan itu sebenarnya sangat informal dan tidak terorganisasi secara baik. "Cuma omong-omong," katanya. Atau, "Lebih mirip arisan ketimbang wahana investasi," kata Direktur Pusat Data Bisnis Indonesia, Christianto Wibisono.
Profesor Liang juga skeptis terhadap forum semacam itu, yang dinilainya cuma nostalgia dan justru semakin membuat pengusaha Tionghoa terkungkung dalam tempurung eksklusifnya. "Untuk RRC sendiri, juga tidak banyak gunanya," katanya.
Ia menyodorkan contoh menarik. Di sebuah simposium di Singapura, seorang pejabat Provinsi Guangdong RRC hadir sebagai pembicara. Di mimbar, berbunga-bunga ia merayu warga Cina perantauan di Asia Tenggara agar membenamkan modal di provinsinya. Tiba-tiba, seorang Tionghoa Malaysia berdiri dan angkat suara, "Maaf, saya adalah orang Tionghoa Malaysia bukan overseas Chinese." Kalimat tajam itu diungkapkannya dalam bahasa Mandarin yang sempurna.
Karaniya D(Beijing), Agus Hidayat, Purwani D. Prabandari (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini