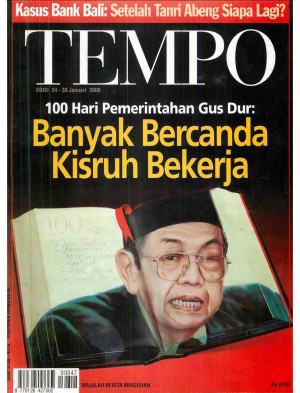SEPINTAS tak ada yang istimewa dengan jalan kecil berbatu itu. Terletak di salah satu sudut Distrik Hai Dian, ia tersembunyi dari gemerlap kapitalisme Beijing. Sunyi, gelap dan beku di titik minus tiga derajat Celcius bulan Desember. Di tepinya, cuma ada sederet toko yang sepi pengunjung. Para pedagang kaki lima yang termangu-mangu. Gudang tua batu bara— tungku pemanas—yang tak terawat. Dan sebuah rumah makan kecil berlampion merah kusam dengan pelayan wanita yang selalu terlihat cekikikan.
Keramaian tiba-tiba muncul di ujung belokan. Dari Nan Men (Gerbang Selatan) Beijing Language and Culture University (BLCU) terdengar dering bel sepeda dan canda ramai belasan mahasiswa. Kebanyakan wanita. Wajah mereka mirip. Tipikal raut wanita Cina: mata sipit, kulit putih mulus dengan pipi bersemu merah. Tapi, dengarlah baik-baik. Di antara bunyi-bunyian Mandarin yang mencerocos, terselip kata-kata semacam gue-elu.
Dua di antaranya, Atin (Li Yun Qing, 22 tahun) dan adiknya, Yuni (Li Yun Ni, 20 tahun) memang berasal dari Jakarta. Mereka datang awal Februari tahun lalu dan mengambil kursus singkat bahasa Mandarin selama setahun. Dan, ternyata, belajar bahasa bukan tujuan utama mereka. Kedua gadis cantik yang masih berstatus sebagai mahasiswa Universitas Tarumanegara Jakarta itu rupanya diungsikan kedua orang tuanya, yang jerih dengan peristiwa Mei 1998 yang berbau rasial itu.
Kisah senada dengan mudah bisa ditemukan dari banyak mahasiswa Indonesia lainnya. Ada kisah Jenny—eks-mahasiswi BLCU yang memilih menetap sementara di Beijing—yang langsung terbang setelah pucat pasi menyaksikan aksi penjarahan dan pembakaran persis di muka rumahnya di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Dan banyak lagi kisah lain semacam itu (lihat boks). Namun, tentu saja ada juga yang datang khusus untuk belajar Mandarin semata.
Petaka Mei memang menorehkan mimpi buruk buat warga keturunan Cina. Saat itu Jakarta—juga Solo—luluh-lantak dibakar dan dijarah massa. Di Jabotabek saja, 1.000 rumah, 2.000 kendaraan bermotor, dan 3.000 pertokoan, yang kebanyakan milik keturunan Cina, jadi puing. Hingga 7 Juni 1998, menurut data Tim Relawan yang dimotori Romo Sandyawan Sumardi, S.J., ada 1.100 mayat (sebagian besar malah "pribumi") tewas terbakar. Sejumlah perempuan Tionghoa, yang jumlah persisnya tak pernah jelas, dikabarkan diperkosa secara brutal. Dan buntutnya, menurut catatan Badan Komunikasi Penghayat Kesatuan Bangsa, 30 ribu warga Tionghoa eksodus ke luar negeri.
Gelombang pengungsian ke "tanah leluhur", RRC, diawali Agustus 1998, tiga bulan setelah kerusuhan Mei meledak. Arus ini terus berlanjut sampai menjelang pemilu Juni lalu. Saat itu spekulasi seram berseliweran. Pemilu yang diikuti puluhan partai politik itu bakal berdarah-darah. Dan, jangan-jangan, amuk massa episode kedua meledak. "Situasinya, kan, waktu itu tegang. Belum tahu siapa yang menang," kata Daniel Dharmawan, 30 tahun. Li Tian Rong—begitu nama asli Daniel—adalah pendukung fanatik Megawati Sukarnoputri, tapi menyoblos Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), partai warga Tionghoa. Pada pemilu lalu di Beijing, PBI menduduki posisi runner-up, dengan seratusan suara di bawah PDI Perjuangan, yang mengantongi suara seribu lebih.
Data Kedutaan Besar RRC menggambarkannya. Pada 1997 jumlah WNI di Beijing cuma sekitar 300 orang. Tahun berikutnya, angka itu melonjak hampir 500 persen (1.400 orang) dan menjadi 3.000 orang pada 1999 (lihat grafik). Dari jumlah itu, kata Duta Besar RRC Kuntara, sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa.
Hitung-hitungan Jenny juga demikian. Saat ia masuk BLCU pada 1998, ada 530 pelajar asal Indonesia. Padahal, saat normal paling banter berkisar 100 orang. Februari 1999, jumlah itu membengkak jadi sekitar 1.000, 700 di antaranya kuliah di BLCU dan 548 di antaranya mengambil kursus singkat, setengah sampai satu tahun. Dan sebagian besar adalah wanita. Proporsinya, dibandingkan dengan siswa pria, sepuluh banding satu. Di jurusannya saja saat itu terdaftar 30 siswa baru. Dan, kecuali satu laki-laki, semuanya perempuan. Maklum, isu pemerkosaan amat mencekam para orang tua yang punya anak gadis.
Cina menjadi pilihan karena di sini rata-rata mereka punya kerabat. Mengurus visa pelajar ke RRC—disebut visa X—juga amat mudah. Apalagi, setelah kerusuhan Mei, pemerintah dan berbagai universitas di Cina menerapkan kebijakan khusus. Khusus kepada mahasiswa asal Indonesia, diberikan potongan biaya kuliah US$ 100 dan keringanan mencicil pembayarannya. Bahkan, di daerah seperti Xiamen dan Guangzhou, mereka boleh menginap gratis di asrama universitas setempat. Bagi yang tak punya sanak saudara, Jiao Lien—organisasi Cina perantauan di tiap provinsi dan kota—pun selalu mengulurkan tangan, mulai dari pendaftaran sekolah, mencari tempat tinggal, sampai lowongan pekerjaan.
Kursus Mandarin adalah metode umum pengungsian para pelajar asal Indonesia itu. Lumayan, mengungsi sementara sambil belajar Mandarin langsung di negeri asalnya. Begitu rata-rata pemikiran mereka. Di Beijing, memang bertebaran universitas dan akademi yang menawarkan paket singkat enam bulan sampai setahun. Buat pelajar asal Indonesia, BLCU jadi favorit. Universitas ini cukup tua, meski tak semegah Universitas Beijing. Universitas yang didirikan pada 1962 di atas lahan seluas 380 ribu meter persegi ini tiap tahun menerima 7.000 mahasiswa, 5.000 di antaranya pelajar asing dari puluhan negara. Seleksinya pun tak seketat Universitas Beijing.
Yang terpenting, biaya sekolah di Cina relatif lebih murah ketimbang negara semacam Singapura atau Australia. "Hampir sama dengan Jakarta," kata Pan Jia Hui, 18 tahun, yang menghabiskan SMA-nya di Singapura. Di sana, Widia—demikian ia dipanggil—paling tidak menghabiskan S$ 3.000 (Rp 15 juta dengan kurs Rp 5.000) per bulan. Itu pun setelah diirit-irit. Padahal, di Beijing uang saku anak seorang pengusaha asal Malang ini "cuma" RMB (ren mim bi—mata uang Cina) 3.000 atau Rp 2,4 juta dengan kurs Rp 800. Ini sudah termasuk belanja sana-sini dan bolak-balik makan di kafe sekelas Thank God It's Friday, yang jadi favorit kalangan pelajar Indonesia di sana.
Toh, buat ukuran kantong rata-rata, biaya "pengungsian" itu lumayan mahal. Paling tidak, dalam setahun orang tua mereka mesti merogoh US$ 7.000 (Rp 80 juta). Itu sudah termasuk biaya kursus US$ 1.300 untuk kelas reguler atau US$ 2.500 untuk kelas intensif. Untuk asrama, boleh dipilih, mulai dari jenis sederhana seharga US$ 2,5 per hari sampai kelas ala hotel melati bertarif US$ 11. Jenis terakhir ini lengkap dengan pendingin ruangan, televisi 14 inci, telepon, kamar mandi, plus wall paper dan karpet. Uang saku bulanan mereka yang rata-rata RMB 2.000 (Rp 1,6 juta) juga cukup membelalakkan mata para siswa lokal yang luar biasa irit dengan RMB 600.
Namun, tetap saja buat mereka Indonesia terasa lebih nyaman. Jarang ada yang betah berlama-lama. Apalagi, situasi Tanah Air mulai "normal". Abdurrahman Wahid dan Mega—dua tokoh yang mereka anggap tak diskriminatif terhadap warga Tionghoa—pun telah bertakhta di Istana. "Kayaknya, udah aman, ya? Pingin segera balik," kata Atin. Tambahan lagi, di "negeri leluhur" ini mereka malah makin bingung dengan identitasnya. Sebagai keturunan Cina, kata Jenny, ia memang merasa keberadaannya sebagai warga negara tak diakui di Indonesia. Tapi, eh, di Cina ini mereka pun ternyata tak dianggap sesama orang Tionghoa. Di mata warga Cina pribumi, keluhnya, tetap saja mereka dilihat sebagai orang asing.
Karaniya Dharmasaputra (Beijing), Dwi Wiyana (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini