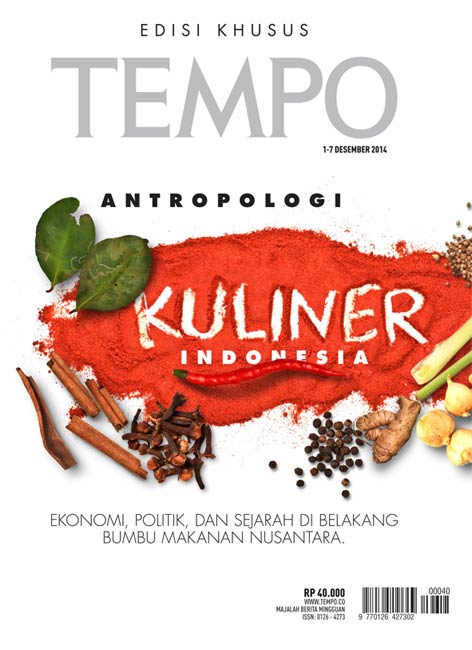Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ratusan batu nisan di Gampong Pande itu menjadi saksi bisu masa lalu Aceh yang gemah ripah. Ada yang dipagari, seperti Makam Tuan Di Kandang dan Putroe Ijo, tapi lebih banyak yang terserak di sela pohon bakau yang ditanam pasca-tsunami 2004. "Di sini awalnya pusat Kesultanan Aceh Darussalam," kata Rusdi Sufi, sejarawan Universitas Syiah Kuala, Aceh, kepada Tempo, awal bulan lalu.
Aceh Darussalam merupakan kerajaan yang didirikan pada 1507 oleh Sultan Ali Mughayat Syah, hasil penyatuan Kerajaan Lamuri, Perlak, Pasai, Pidie, dan Lingga. Sistem hubungan internasional mengubah wajah Aceh. Setelah Portugis menguasai Malaka pada 1511, para pedagang, terutama Islam, mencari pelabuhan baru untuk berdagang rempah-rempah. Dan di Acehlah mereka menemukan pelabuhan baru itu.
Aceh Darussalam membuka bandar alternatif pada 1514 di muara Krueng (Sungai) Aceh. Letaknya di ujung utara Pulau Sumatera, pintu masuk Selat Malaka. Fungsi pelabuhan itu mirip seperti Singapura saat ini: menjadi hub, menghubungkan pedagang dari berbagai penjuru dunia.
Dalam Nathaniel's Nutmeg, Giles Milton mencatat kejayaan pelabuhan Aceh yang oleh pelaut Eropa disebut Achin. Mengutip catatan pelaut Inggris, Sir James Lancaster, Milton menyebutkan Bandar Aceh Darussalam merupakan kota kosmopolitan saat dia mendarat pada 5 Juni 1602. "Di pelabuhan, bersandar 16 kapal, di antaranya dari Gujarat, Bengal, dan Semenanjung Malaya," kata Lancaster. "Ini merupakan pusat perdagangan yang penting, meski bukan sumber langsung rempah-rempah."
Kesultanan berpanji pedang dan bulan-bintang itu membeli rempah-rempah dari India dan Arab di barat dan dari pulau-pulau lain di Nusantara di timur. Dari Tidore, mereka mendapatkan cengkeh. Dari Kepulauan Banda, mereka mengimpor pala. Rusdi yang berumur 72 tahun itu mengatakan rempah-rempah dipusatkan di ibu kota, Bandar Aceh Darussalam, yang dekat dengan pelabuhan di Gampong Pande—berarti kampung tempat pandai besi.
"Posisi pelabuhan itu sekarang sudah jadi laut karena abrasi," ujar Adian Yahya, 62 tahun, warga Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh. Permukimannya habis disapu tsunami 2004, berganti jadi rumah bantuan bertipe 36. "Letak pelabuhan lama sekitar satu kilometer dari garis pantai sekarang." Pria yang mengaku sebagai keturunan ke-52 Sultan Alauddin Johan Syah—sultan ke-24, yang berkuasa pada 1735-1764—ini mengatakan pelabuhan itu digunakan sampai sekitar abad ke-19.
Dari pelabuhan, rempah-rempah dibawa masuk ke ibu kota dengan kapal melewati Krueng Aceh. Lebar sungai itu kini sekitar 80 meter. "Dulu lebih lebar," kata Rusdi. Sungai itu bersih. Sepanjang mata memandang, sulit mendapati sampah. Saban tahun, Pemerintah Kota Banda Aceh menyelenggarakan festival di sana. Satu acara favorit masyarakat adalah lomba menangkap bebek, seperti yang berlangsung pada 9 November lalu.
Sekitar satu kilometer di selatan Gampong Pande, di sisi timur Krueng Aceh, terdapat kawasan yang dikenal sebagai Peunayong. "Diperkirakan berasal dari kata 'payung' atau wilayah yang dipayungi sultan," ujar Rusdi. Di sinilah para pedagang antarbangsa berkumpul sebelum bertemu dengan sultan di istana. Tempat tinggal sultan itu dihancurkan Belanda pada 1874. Letaknya kurang-lebih 500 meter di selatan Masjid Raya Baiturrahman.
Waktu tunggu bisa berbulan-bulan, sehingga mereka membutuhkan hiburan. "Di sana ada Kampung Bideun, yang berasal dari tempat tinggal para biduan," kata Rusdi. Sekarang, Kampung Bideun merupakan wilayah permukiman yang masuk Kelurahan Lampulo, Kecamatan Kuta Alam. Sebuah kapal nelayan sepanjang 25 meter mendarat di atas rumah warga ketika terjadi tsunami, sepuluh tahun lalu, dan dijadikan obyek wisata. Masyarakat menyebutnya Kapal Apung Lampulo.
Perpaduan budaya itu semakin kuat lewat perkawinan pelaut dengan penduduk lokal. Tidak aneh, secara bergurau, orang Aceh merasa nenek moyang mereka terwakili oleh huruf-huruf dalam kata Aceh: Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Di Bandar Aceh Darussalam, bermunculan permukiman pendatang yang namanya masih digunakan sampai detik ini, seperti Kampung Jawa, Kampung Kedah (Malaysia), Kampung Bitai (Turki), dan Kampung Keling (Tamil dan Gujarat, India). "Asalnya dari tempat tinggal orang-orang itu," ujar Rusdi.
Di tempat-tempat seperti Peunayong—pasar tertua di kota yang dibangun pada 1205—itulah terjadi peleburan budaya, yang turun ke masakan. Pakar kuliner William Wongso mengatakan lamanya waktu berlabuh membuat para pelaut asing merindukan masakan rumah mereka. "Maka mereka membawa cara masak mereka ke sana," tuturnya.
Maka turunan masakan asing, mulai nasi beriani dari Asia Selatan sampai hidangan mi ala Tiongkok, bisa kita temukan di Aceh. Misalnya di Peunayong, yang menjadi kawasan wisata kuliner di Banda Aceh. "Yang paling terasa pengaruhnya di makanan adalah India," ujar Rusdi.
Posisi Aceh sebagai negara merdeka—baru ditaklukkan Belanda pada 1903 setelah Sultan Muhammad Daud Syah Johan menyerah—membuat masyarakat bebas mengakses rempah-rempah. Tidak seperti di daerah lain—tempat Belanda memonopoli perdagangan dan memboyong komoditas itu ke Eropa—di Aceh, rempah dari berbagai wilayah Nusantara bisa dibeli di pasar, seperti di Peunayong. "Makanan Aceh banyak menggunakan rempah-rempah, seperti cengkeh, bunga lawang, kayu manis, kapulaga, dan jintan," kata Rusdi.
Orang Aceh memang royal soal bumbu. Pagi itu, kami menemani Rosmawati, 59 tahun, yang menghabiskan sekitar Rp 200 ribu untuk berbelanja bumbu kari kambing di Peunayong. Ibu rumah tangga asal Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar, itu membeli ketumbar, lada, bunga lawang, cengkeh, bawang, cabai, daun salam, dan tidak ketinggalan kas-kas. "Total ada 27 bumbu," ujarnya. Hanya di Aceh, satu masakan membutuhkan rempah sebanyak itu.
Matahari baru merangkak naik saat kami tiba di rumah Rosmawati—sekitar 17 kilometer dari pusat Banda Aceh. Namun seisi rumah Rosmawati sudah sibuk. Mereka hendak memasak kari kambing untuk menyambut kedatangan kerabat dari luar kota.
Bagi Rosmawati, semua bahan harus segar. Di halaman belakang rumahnya di kaki Bukit Barisan itu, tiga pria mengelilingi seekor kambing cokelat berusia dua tahun. Kambing jantan dengan berat sekitar 15 kilogram itu direbahkan menghadap kiblat. Sesaat kemudian, setelah empat takbir berkumandang, hidupnya berakhir di ujung pisau Teungku Syekh Ibrahim, imam meunasah (musala) kampung itu. "Di sini, pemotongan hewan harus dilakukan oleh imam," kata Rosmawati.
Imam 67 tahun tersebut dibantu dua pria paruh baya warga Lampisang menguliti dan mencacah daging kambing itu menjadi kubus seukuran sekitar lima sentimeter. Di dapur, Rosmawati bersama anak dan tetangga perempuannya menyiapkan bumbu. Masyarakat Aceh mempertahankan tradisi gotong-royong dalam memasak untuk kenduri. "Yang mengaduk di kuali harus laki-laki," ujar Azhar Ma, 52 tahun, warga Lampisang. Pembagian tugasnya selalu seperti itu.
Bumbu seperti lada, cengkeh, kapulaga, pala, kas-kas, jintan, dan ketapang digiling, kemudian dicampur. Ketumbar disangrai, ditumbuk pakai lesung kayu. Di sudut lain dapur, seorang ibu paruh baya sibuk menumis irisan bawang merah dan bawang putih.
Berikutnya, giliran serai, kayu manis, bunga lawang, dan cabai giling yang masuk wajan. Lalu campuran bumbu kecil, kepala sangrai, bawang merah, bawang putih, dan kemiri giling. Rosmawati menggunakan dua bentuk bawang dengan alasan bawang iris menambah sedap daging saat tergigit, sedangkan bawang halus meresap lebih cepat ke daging. Terakhir, masuk kemiri giling yang tadi disangrai, air, kunyit, dan sekantong garam 250 gram.
"Makan bumbunya saja pun aku mau, tinggal campur nasi," kata Azhar sembari menyalakan api pada serbuk kayu di tungku drum. Asap mulai mengepul di kolong rumah panggung kayu itu. Penghuni awal belanga satu meter itu adalah daging dan adonan bumbu. Karena kuali belum panas, mantan juru masak di Rumah Makan Spesifik Aceh ini membaurnya pakai tangan. Diawali dari bawah ke atas, lalu sebaliknya. Dia mengulangi gerakan itu sampai lima kali sebelum memasukkan air.
Perlahan, wangi rempah mulai memenuhi udara, sementara Azhar mengaduknya dengan kayu satu meter, yang lebih mirip dayung ketimbang centong. Dia lalu membubuhkan daun temurui (Murraya koenigii). Daun yang lebih dikenal dengan salam koja atau daun kari ini merupakan penyedap yang hadir di hampir semua masakan Aceh. Bersama belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi)—buahnya dikeringkan menjadi asam sunti—pohon kari merupakan tanaman yang hampir selalu ada di pekarangan rumah warga Aceh. "Daging sudah mulai empuk," ujarnya setelah 50 menit mengaduk.
Air di belanga mulai surut. Rosmawati memasukkan santan encer hasil perasan kedua. Santan perasan pertama diguyurkan belakangan, supaya kari tidak terlalu berminyak. "Semakin lama santan dimasak, semakin berminyak," katanya. Dia juga memasukkan potongan kentang, yang bisa diganti dengan nangka. Setelah kentang matang, dia mengguyurkan santan kental. Dan sekitar 15 menit kemudian, kari kambing itu siap disajikan.
Kami makan bersama di pekarangan rumah kayu tersebut. Tidak banyak cerita mengalir saat piring yang dipenuhi kari kambing dan nasi mendarat di depan mata. Selusin manusia itu berkonsentrasi pada hidangan mereka. Saya, yang sejak kecil merupakan penggemar masakan berbahan kambing, mengakui kari ini sebagai satu masakan terenak.
"Kari seperti ini sebenarnya bukan masakan Aceh Besar," ujar Rosmawati, memecah kesunyian. Di Aceh Besar, juga Banda Aceh, hidangan kambing tidak menggunakan banyak rempah dan santan. Bumbunya kurang dari 12. Pala, kayu manis, bunga lawang, cengkeh, kapulaga, dan sebagainya tidak ikut dalam masakan yang disebut kuah beulangong atau sie kameng itu.
Adapun kari kambing, menurut Rosmawati, berasal dari masyarakat pesisir, seperti Pidie. "Tapi kari lebih terkenal di luar Aceh, termasuk di Jakarta, karena pedagang masakan Aceh perantauan biasanya dari Pidie," katanya.
Rosmawati, yang makan belakangan dengan alasan menghormati tamu, lalu menyajikan es timun serut. Minuman dingin tersebut biasa hadir sebagai pendamping hidangan kambing. "Biar yang darah tinggi tidak sakit," ujar ibu enam anak itu seraya tersenyum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo