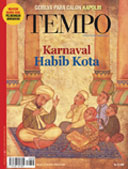Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Reruntuhan bangunan setinggi satu meter itu terlihat jelas begitu tanah di area persawahan digali. Terbuat dari batu bata, dengan struktur rapat tanpa spasi. Satu batu bata memiliki ukuran tiga kali lebih besar dari batu bata yang dipakai orang sekarang.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo