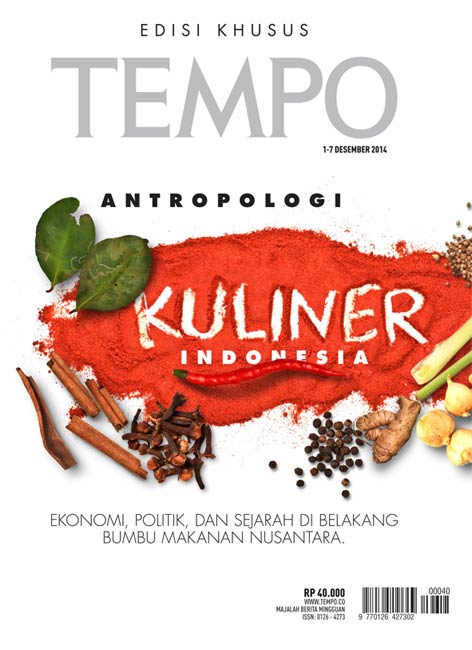Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SELEPAS pukul dua belas malam, puluhan anggota keluarga Pura Mangkunegaran, Solo, bersila dengan khidmat di Dalem Ageng, ruang utama istana itu. Dalam keheningan, tiga pusaka didatangkan. Tombak-tombak jangkung setinggi 2,5 meter yang terbungkus kain kuning itu diletakkan dengan penuh takzim di tengah ruangan. Lampu diredupkan, kemenyan dinyalakan, dan keheningan ditetapkan.
Ini adalah puncak dari perayaan 1 Sura tahun Jawa 1948, bertepatan dengan 24 Oktober 2014. Beberapa jam sebelumnya, tak lama setelah bulan muda muncul di cakrawala barat, perayaan yang lebih meriah berlangsung di pendapa seluas 3.500 meter persegi. Empat pusaka dikeluarkan dan dicuci. Airnya diperebutkan oleh ribuan orang yang sudah menunggu sejak sore. Pusaka-pusaka itu lalu diarak oleh anggota keluarga istana, yang memakai kebaya dan beskap hitam, berkeliling tembok keraton.
Keriuhan itu sirna pada saat semadi tengah malam berlangsung. Tak ada suara dari perangkat gamelan di pendapa, tak ada rapalan mantra dan doa. Semua lampu dimatikan. Gelap-gulita. Kita tak bisa melihat tangan sendiri.
Satu jam setelah semadi dalam kegelapan, lampu-lampu kembali dinyalakan, kemenyan dimatikan, dan ketiga pusaka kembali disimpan. Suasana menjadi cair ketika Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna, anak tertua Mangkunegara IX, membagikan makanan sesaji yang tadi ditaruh di depan pusaka. "Setiap orang punya makanan sesaji favorit. Pemilihannya bukan didasarkan pada selera lidah, melainkan lebih pada ketertarikan sukma," kata pria 35 tahun itu.
Ada pisang kepok yang direbus, apem, opor ayam, telur pindang, dan sejumlah makanan lain. "Untuk sesaji, masing-masing jumlahnya harus ganjil," ujar Sri Sutarni, 52 tahun, ahli masak istana yang membuat makanan itu.
KAMI-fotografer Aditia Noviansyah dan saya-menemui Sutarni sehari sebelumnya tepat pukul 07.30 di dekat pendapa. Dengan berjalan kaki, kami menemaninya menuju Pasar Legi, yang berada di sebelah utara istana. "Di sini lebih murah dibanding Pasar Gede," katanya. Selain berbelanja untuk keperluan makanan sesaji saat semadi, dia berbelanja buat membikin jenang suran.
Jenang bukan berarti dodol, melainkan bubur. "Jenang adalah makanan istimewa bagi masyarakat Surakarta," ucap pendiri Yayasan Jenang Indonesia, Slamet Raharjo. Pada masa lampau, jenang selalu hadir dalam ritual, dari selamatan jabang bayi hingga acara untuk orang meninggal.
Menurut hasil riset Yayasan Jenang Indonesia, dulu terdapat sekitar 20 varian jenang. "Yang dikenal oleh masyarakat pada saat ini hanya separuhnya," ujarnya. Bahkan kebanyakan masyarakat juga sudah tidak lagi tahu makna filosofis di balik jenang yang mereka santap di pasar tradisional.
Adapun kata suran berarti Sura atau Muharam, bulan pertama dalam kalender Islam dan Jawa. Kata Sura diambil dari Asyura atau 10 Muharam, salah satu tanggal terhormat dalam Islam. "Jenang suran biasanya dibuat pada tanggal 10," tutur Sutarni. Kami meminta dia membuat bubur itu pada tanggal 1 agar dapat merasakannya sebelum pulang ke Jakarta.
Hanya perlu lima menit untuk sampai di pasar yang didirikan oleh Mangkunegara VII pada 1930 ini. Saat dia baru berkuasa pada 1916, Praja Mangkunegaran membentuk Markt-wezen, yang khusus mengelola pasar. Mereka menetapkan sistem baru, yaitu para pedagang harus membayar karcis. Pada 1933, sudah terdapat 87 pasar yang dikelola Markt-wezen, termasuk Pasar Legi.
Di sini Sutarni membeli pisang kepok, krecek dan ayam untuk opor, bumbu tumbuk, tape ketan, serta sejumlah bahan makanan lain. Dia meminta bantuan Wagiyem, seorang kuli panggul perempuan, untuk mengangkat belanjaan sebanyak dua becak. "Saya tak tahu lahir tahun berapa, tapi kata orang umur saya 65," ujar Wagiyem, yang juga tak menghitung berapa tahun dia bekerja di pasar ini.
Sekembali dari pasar, sambil membuat apem di dapur utama istana, Sutarni bercerita bahwa ia mulai memasak di sini pada 1973 karena diajak bibinya, Bu Simi. Tak ada buku resep yang menjadi panutan mereka. Setelah bu lik-nya meninggal pada 1991, ia dan tiga juru masak lain akan saling mengingatkan jika ada resep terlupa.
Selain resep, mereka harus ingat weton atau hari pasar setiap anggota keluarga kerajaan. Pada hari weton itu akan disajikan makanan kesukaan anggota keluarga yang telah tiada. Lewat makanan, mereka mengingat orang-orang yang telah berpulang.
Apem yang sedang dibuat Sutarni adalah untuk memperingati wetonan permaisuri Mangkunegara VIII. Dia mencampur tepung beras, tape, dan gula merah dalam baskom, lalu mengaduknya dengan tangan. "Harus sabar menguleninya agar bisa mengembang, tidak bantat," katanya sambil mengeluarkan serat-serat tebal tape singkong dari adonan. Sutarni lalu menjemurnya selama tiga jam agar lebih mengembang.
Sambil menunggu apem mengembang, Sutarni membuat jenang suran. Seorang asistennya membuat bubur di atas kuali berbahan bakar kayu. Sutarni mempersiapkan bumbu untuk enam jenis lauk: sambal goreng krecek, opor ayam, telur pindang, sayur bumbu tumbuk, teri, dan perkedel. Ketika disajikan, akan ada tambahan kerupuk.
Dari kesemuanya, hanya sayur bumbu tumbuk yang memakai rempah-rempah agak kuat. "Baunya seperti jamu," ujar Sutarni tentang bumbu yang dipakainya: bunga lawang, cengkih, kapulaga, dan kayu manis. Sebenarnya bumbu yang dipakai ini tak terlalu berbeda dengan bumbu pada makanan Sumatera, yang terpengaruh India. Bahkan pemakaiannya di Solo jauh lebih irit.
Rempah kering tidak terlalu banyak dipakai di kawasan selatan Jawa-Yogyakarta, Solo, dan daerah Mataraman lain. "Itu berbeda dengan daerah di pesisir utara, seperti Pekalongan, yang pengaruh Arabnya terasa," kata pakar kuliner William Wongso. Hal ini ada kemungkinan karena jalur perdagangan rempah dari Maluku ke Sumatera hanya mampir di pesisir utara.
Upacara adat dan ritual seperti peringatan 1 Sura, wetonan, dan jumenengan (peringatan kenaikan takhta) memiliki pengaruh besar dalam kuliner Jawa. Pada acara-acara seperti inilah makanan istimewa dikeluarkan. Makanan itu sebagian dibagikan kepada lingkungan keraton ataupun ke masyarakat luas. Ini adalah salah satu kanal perluasan selera makanan istana.
Hal yang sama terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta. Pengamat kebudayaan dari keraton itu, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo, mengatakan, pada masa lalu, setiap Kamis malam Keraton menyajikan jenang lemu dan sega liwet. "Selanjutnya masakan tersebut dibagikan kepada masyarakat yang lewat di depan Kori Kamandungan (pintu gerbang keraton)," ujarnya.
Lambat-laun, masyarakat membuat sendiri masakan tersebut. Waktu memasaknya juga tidak melulu Kamis malam. "Saat ini banyak warung yang menyajikan kedua hidangan tersebut, sehingga menjadi makanan khas dari Kota Solo," kata Dipokusumo.
Tradisi membagikan makanan ini terjadi sejak sebelum kerajaan Islam Mataram muncul. Hedi Hinzler, pakar Jawa kuno dari Universitas Leiden, mengatakan prasasti-prasasti Jawa abad ke-9 mencatat pembagian makanan dalam pesta dan upacara yang dihadiri pejabat atau pemuka agama. "Dalam kesempatan itu, sang raja bisa mengizinkan hadirin memakan hidangannya-yang disebut rajamangsa," ucap Hinzler kepada Tempo. Bedanya, pada masa Jawa kuno itu, rakyat jelata hanya boleh menonton.
TENTU makanan tidak hanya datang di acara keagamaan. "Setiap ada wayangan, pasti dihidangkan nasi lodoh pindang untuk penonton," katanya. Nasi ditaruh di daun (takir). Di atasnya diberi telur dadar yang dipotong panjang-panjang, daging pindang, acar bening dari wortel dan mentimun, serta sosis jawa. Sosis jawa sebenarnya adalah daging yang digulung dalam telur dadar lalu dikukus. Sebelum disajikan, nasi disiram kuah lodoh atau lodeh. "Tapi makanan ini sudah jarang dibuat," ujar Sutarni. "Sekarang, ya, pakai nasi kotak biasa."
Lodoh pindang mungkin sudah jarang dibuat, tapi sosis jawa yang ada di dalamnya bisa kita temukan di warung timlo yang banyak ada di Solo. Sosis jawa, bistik, dan selat Solo adalah makanan-makanan yang jelas dipengaruhi oleh Eropa-dalam hal ini Belanda. "Saya melihat fenomena unik," kata William Wongso. "Belanda ada di mana-mana di Indonesia, tapi pengaruh kuliner Belanda yang paling menonjol adalah Solo. Ada kemungkinan ini muncul karena kerajaan yang sering menjamu tamu Belanda."
Hal ini dibenarkan oleh Gusti Raden Ayu Retno Astrini, putri bungsu Mangkunegara VIII. "Makanan-makanan Belanda itu masuk lewat istana, karena itu semua adalah hidangan saat ada tamu Belanda," ujarnya. Khusus untuk Pura Mangkunegaran, makanan-makanan tersebut mulai banyak dikenal saat Mangkunegara IV berkuasa pada 1853-1881.
Pada masa Mangkunegara IV-ketika Pura Mangkunegaran masuk masa kemakmuran-makanan yang lebih mewah daripada sebelumnya dikenalkan. "Beliau sangat suka nasi tim burung dara. Burung daranya harus yang masih muda, belum ada bulunya, lalu dimasak bersama sarang burung walet. Beliau juga suka dendeng agi," kata Sutarni, yang mengetahui semua itu karena kerap memasak untuk memperingati hari lahir mereka.
Pada saat itulah makanan-makanan Eropa masuk. Kemakmuran membuat mereka menggandrungi hal-hal yang berbau Eropa. "Kuatnya pengaruh Eropa itu bisa kita lihat dari arsitektur istana ini," ujar Astrini. Pendapa, misalnya. Balairung ini lantainya berlapis marmer Italia, dihiasi lampu gantung dari Belanda, ada patung singa duduk berwarna keemasan, dan tiang-tiang kurus didatangkan dari Prancis. Sejumlah patung dewa Yunani dan prajurit Eropa bisa ditemui di sejumlah sudut Pura Mangkunegaran.
Bahkan tempat masak utama istana disebut keuken-bahasa Belanda untuk dapur. Ini untuk membedakan dapur-dapur lain di Mangkunegaran yang mungkin tak sesering keuken dalam memasak makanan Belanda. Di keuken itulah Sutarni memasak.
KEGEMARAN akan makanan Belanda sebenarnya juga bisa ditemui di Keraton Yogyakarta. Menurut Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat, cucu Hamengku Buwono VIII, banyak resep masakan lahir pada masa Hamengku Buwono VIII berkuasa (1921-1939). Salah satu makanan kegemarannya adalah lidah asap atau asin lidah untuk makan siang. Bahan utamanya adalah lidah sapi yang direbus, dipotong agak besar, dan dijepit dengan bambu. Lidah itu lalu dilumuri mentega dan dibakar.
Ada pula pastei atau pastel krukup dan semur krukup, yang berbahan utama kentang yang dihaluskan, serta sayur semur. Cara membuatnya: sayur semur soun atau semur ayam diletakkan di atas pinggan, dibungkus dengan kentang rebus yang sudah dihaluskan. Baru kemudian dikukus dengan langseng hingga masak.
Kegemaran HB VIII akan makanan menurun pada Hamengku Buwono IX. "Setelah naik takhta, HB IX mengangkat Endro Bujono sebagai koki untuk melayani keraton," kata Jatiningrat saat ditemui di kantornya, Tepas Dwarapuro di kompleks Keraton Yogyakarta, awal November lalu. Endro adalah koki asal Surakarta yang bekerja di kamar bola, tempat bermain biliar orang-orang Belanda. Gedung yang sekarang tidak ada itu dulu berada di ujung tenggara Istana Negara Gedung Agung.
TENTU saja makanan Belanda yang disajikan di keraton-keraton itu sudah dimodifikasi. Di Solo, selain sosis jawa, ada selat solo yang berasal dari bistik. Sama-sama dilengkapi sayur-mayur, seperti wortel, buncis, dan kentang, serta telur rebus. Bedanya terletak pada daging dan sausnya. Steak dan saus jamur diganti daging semur. "Selat solo itu mungkin asalnya adalah biefstuk (steak sapi). Tapi, karena mahal, dagingnya dibikin seperti semur," ujar William Wongso.
Di Solo juga ada kue songgobuwono, yang namanya sangat keraton. "Tapi sebenarnya, ya, kue sus. Bentuknya saja yang diubah," kata William.
Modifikasi terbesar adalah pada rasa. Makanan-makanan Belanda itu kemudian berubah menjadi lebih manis. Astrini mencontohkan dengan huzarensla versi Mangkunegaran yang memakai dressing lebih manis dan encer. "Manis itu kan Jawa, lebih enak untuk lidah kita," ujar Astrini.
Lalu kenapa orang Jawa menyukai masakan yang manis? Menurut Hedi Hinzler, di Jawa kuno, manis memang dikenal sebagai salah satu rasa yang wajib ada dalam makanan, tapi itu tidak dominan. "Dalam teks-teks Jawa kuno sering disebut ajaran Hindu tentang enam rasa atau sad rasa, yaitu manis, asin, asam, pedas, pahit, dan sepat. Hidangan baru akan nikmat kalau mengandung enam rasa itu dengan perimbangan yang harmonis," katanya.
Janoe Arijanto dari bagian Research and Culinary Culture di komunitas Aku Cinta Masakan Indonesia punya jawabannya. "Rasa manis dalam masakan Jawa mungkin bisa dikaitkan dengan banyaknya suplai gula di Jawa akibat didirikannya banyak pabrik gula," ucapnya. Hal ini dikuatkan oleh buku Semerbak Bunga di Bandung Raya karangan Haryoto Kunto yang terbit pada 1986.
Pada 1830, Gubernur Jenderal Van den Bosch memberlakukan Cultuurstelsel (Tanam Paksa) untuk mengisi kas Belanda yang kosong karena terkuras oleh perang melawan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (De Java Orloog), yang berlangsung pada 1825-1830.
Dalam tanam paksa ini, petani diwajibkan menanam tanaman untuk komoditas ekspor, seperti tebu dan kopi. Petani di Jawa Barat harus menanam teh, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur harus menanam tebu. Selama Cultuurstelsel berlangsung, di Jawa Tengah dan Jawa Timur didirikan seratus pabrik gula.
Untuk menggerakkan itu, ada sejuta petani tebu dan 60 ribu buruh pabrik. Sekitar 70 persen sawah harus diganti menjadi ladang tebu. Akibatnya, stok beras menipis dan rakyat kesulitan mendapatkan pasokan karbohidrat. Sebagai gantinya, mereka memakai air perasan tebu untuk memasak.
Ketika tanam paksa dihapus pada 1870, bisnis gula beralih ke swasta Belanda, orang Tionghoa, dan raja-raja Jawa. Dari pabrik gula inilah keraton-keraton memperoleh kemakmuran. "Mangkunegaran, sultan Yogyakarta, dan susuhunan Solo menghapuskan sistem pembayaran para priayi dan abdi dalem dengan tanah dan menjadikan tanah itu sebagai perkebunan gula dan pabrik-pabriknya. Dari penghasilan gula ini, para abdi dalem dapat digaji," tulis budayawan yang ahli makanan, Onghokham, pada artikelnya, "Gula dalam Sejarah Indonesia".
Setelah menyaksikan Sutarni dan timnya memasak jenang suran, kami memutuskan pergi ke Tasikmadu, salah satu pabrik gula yang pernah dimiliki oleh Mangkunegaran. Pabrik ini terletak di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, sekitar 12 kilometer arah timur Kota Solo. Pabrik yang didirikan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara IV pada 1871 ini berdiri di atas tanah seluas 28.364 hektare.
Meski pengelolaan pabrik itu kini dilakukan PT Perkebunan Nusantara IX, kita masih bisa merasakan kehadiran sang pangeran adipati di sana. Foto-foto Mangkunegara IV masih terpasang di setiap ruangan. Di halaman pabrik itu ada gerbong buatan 1875 yang ia pakai saat mendatangi Tasikmadu. Juga masih ada gerbong bikinan Chevalier Construction Prancis berwarna hijau yang dulu ia gunakan menemui rakyat. Delman yang ia pakai untuk inspeksi pabrik tebu pun masih bisa dilihat.
Sayang, ketika kami datang, penggilingan tebu memakai mesin buatan tahun 1926 dengan roda gerigi berdiameter lima meter itu baru selesai. Penggilingan dilakukan pada Mei-Oktober. "Saat ini kami cuti dua hari setelah penggilingan selesai," kata Rahmat, karyawan bagian sumber daya manusia pabrik tersebut.
Meski bisnis gula meredup diterpa krisis ekonomi pada 1930, pabrik gula telah mengubah para priayi dan bangsawan di Yogyakarta dan Solo. "Kemakmuran yang tercipta dari berdirinya banyak pabrik gula berpengaruh pada gaya hidup mereka," ujar peneliti sejarah Kota Solo, Heri Priyatmoko. Hal itu diiyakan oleh sosiolog Universitas Sebelas Maret, A. Romdhon. "Masyarakat saat itu bisa menyalurkan banyak hobi, termasuk menikmati kuliner," katanya.
Perubahan gaya hidup dan pola makan-terutama yang manis-manis-ini berpengaruh pada kesehatan keluarga kerajaan di Yogya dan Solo. "Sultan Hamengku Buwono VIII sangat gemar makan enak. Makanya beliau sakit gula," ucap Jatiningrat.
KETIKA kami kembali dari pabrik gula Tasikmadu, jenang suran sudah tersedia di ruang makan keputren yang bernuansa Bali. "Interiornya dipersembahkan oleh Raja Karangasem, Bali, yang berkawan dengan Mangkunegara VII," kata Raden Mas Ario Bayu Putro, salah seorang cucu Mangkunegara VII. Di ruang makan itu, ada sepasang lukisan pedesaan Bali setinggi dua meter, patung Garuda Wishnu Kencana dari kayu, gading yang diukir selama 20 tahun oleh seorang perajin, dan kaca patri yang menggambarkan masyarakat Pulau Dewata.
Makanan itu sudah terhidang rapi di atas meja. Jenang atau buburnya putih biasa. Yang membedakan dengan bubur-bubur lain adalah lauk-pauknya. Kami dan sejumlah anggota keluarga istana mencicipi jenang suran dan kudapan untuk wetonan. Lalu saya teringat beberapa baris dari Serat Wedhatama yang ditulis oleh Mangkunegara IV-penguasa yang mendatangkan kemakmuran sekaligus mengajarkan kesederhanaan dan penggemar kelezatan yang menasihatkan pembatasan makan.
Sanityasa pinrihatin,
Puguh panggah cegah dhahar lawan nendra
(Senantiasa menjaga hati untuk prihatin, dengan tekad kuat, membatasi makan dan tidur).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo