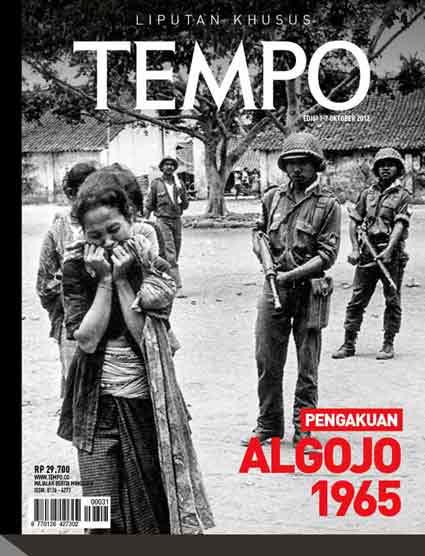Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kebun singkong memenuhi sebagian area di perbatasan Kabupaten Gowa dan Maros, Sulawesi Selatan. Beberapa pengembang mulai membangun perumahan di kawasan penyangga pengembangan Kota Makassar ini.
Mungkin tidak sampai lima tahun lagi daerah ini menjadi bagian Kota Daeng. Sejarah kelam kampung di Desa Paccellekang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa, itu makin terlupakan. Tapi tidak bagi Soemiran.
Laki-laki 69 tahun ini salah satu dari seribuan bekas penghuni Instalasi Rehabilitasi Moncongloe, kamp pengasingan bagi orang-orang yang terlibat Partai Komunis Indonesia. Dibuka pada 1969, tempat penahanan ini resmi dibubarkan sepuluh tahun berselang.
Soemiran dulu polisi yang bertugas di Pelabuhan Makassar. Ia dijebloskan ke rumah tahanan militer karena dianggap membantu pelarian seorang tokoh PKI dengan kapal ke Jawa. "Saya hanya ingin membantu guru saya. Saya lihat surat-suratnya lengkap, saya persilakan naik ke kapal," kata lulusan Sekolah Kepolisian di Mojokerto, Jawa Timur, yang melanjutkan belajar di SMA Sawerigading, Makassar, untuk mendapatkan kenaikan pangkat itu.
Ia baru masuk kamp tersebut pada 1978, ketika semua tahanan politik telah dibebaskan. Moncongloe berubah menjadi tempat penahanan bagi militer. Mereka masing-masing diberi lahan satu hektare dan sepetak rumah. Setahun kemudian, mereka dibebaskan. Saat ini tinggal Soemiran yang bertahan, sedangkan rekan-rekan seangkatannya sudah pindah dan menjual lahannya.
Menurut buku Kamp Pengasingan Moncongloe, yang ditulis Taufik, tempat penahanan ini dibuka pada Maret 1969. Sebelas tahanan politik, yang terdiri atas tujuh laki-laki dan empat perempuan, dibawa ke Moncongloe untuk mendirikan barak darurat. Dua bulan kemudian, masuklah 44 tahanan, yang diberi tugas menyiapkan kamp pengasingan.
Anwar Abbas, salah seorang dari 44 tahanan politik itu, masih menyimpan semua kenangan di tempat tersebut. Dia menunjukkan kepada Tempo setumpuk dokumen terbungkus plastik berisi catatan dengan tulisan dari mesin ketik, peta lokasi Moncongloe, beberapa helai foto, dan dua lembar kliping koran. "Ini catatan singkat saya," kata pria 66 tahun itu ketika ditemui di rumahnya di Gowa, dua pekan lalu.
Dengan peralatan seadanya, tahanan yang kemudian disebut Kelompok 44 membuka hutan dan membangun kamp. Di bawah pengawasan ketat anggota polisi militer, kelompok ini membangun kompleks pengasingan lengkap dengan lima barak berukuran 120 meter persegi, masjid, gereja, poliklinik, dan aula.
Pada Desember 1969, Moncongloe menampung tahanan politik yang sebelumnya menghuni rumah tahanan militer di berbagai kota di Sulawesi Selatan, mulai Majene, Tana Toraja, Palopo, Makassar, Bulukumba, sampai Selayar. Pemindahan ini bertahap hingga 1971.
Anwar, Ketua Pemuda Rakyat Pangkajene Kepulauan (Pangkep), sebelumnya ditahan di kantor polisi di kotanya pada 1965. Namun ia minta dipindahkan ke rumah tahanan militer di Makassar karena seorang temannya yang ditahan di sini telah dibebaskan. Dia baru bebas pada 1977.
Di tahanan militer ini, mereka diinterogasi. Menurut Anwar, di sinilah mereka disiksa. Keluar dari ruang pemeriksaan, para tahanan politik ini mendapat kategori B atau C. "Kriterianya apa, tidak tahu. Suka-suka petugasnya," kata Anwar sambil mengisap rokok kreteknya.
Ia mengakui kondisi di kamp lebih baik daripada saat di penjara Makassar. Untuk makan, setiap tahanan mendapat jatah setengah liter beras per hari. Lauknya, mereka mengupayakan sendiri dari kebun dan hutan. Tempat tinggal mereka pun lebih baik daripada sel sempit untuk 20 orang.
Tapi di sini mereka diperlakukan seperti budak oleh para penjaga kamp. M. Jufri Buape, 71 tahun, mengatakan para tahanan harus menggarap lahan tentara tanpa dibayar minimal enam jam sehari. "Jangankan upah, bisa-bisa kami kena pukul jika dianggap kerja tidak benar," kata laki-laki yang belum lama ini terkena stroke ringan itu.
Sekretaris Lekra Sidrap ini enggan memerinci bentuk hukuman yang diterima jika pekerjaan tidak sesuai dengan kemauan penjaga. "Ya, macam-macamlah," katanya. Sering pula para tentara memerintahkan tahanan mengambil kayu di hutan atau bambu untuk dijual. Tentu saja mereka tidak mendapat bagian.
Jufri masih ingat nama para penjaga kamp. "Banyak yang sudah meninggal," ujarnya. Saat jabatan komandan kamp dipegang Kapten Siregar dan Kapten Lubis, kekerasan fisik terhadap para tahanan sering terjadi. Menurut Anwar, tidak ada tahanan yang sampai meninggal karena penyiksaan. Ada beberapa dari mereka yang sakit dan meninggal. Kebanyakan tahanan menderita hepatitis akibat beratnya pekerjaan dan kurangnya asupan gizi.
Sebagai bentuk perlawanan, tahanan sering kali bekerja sekadarnya asalkan tidak mendapat hukuman. Mereka lalu mencuri kesempatan menggarap ladang penduduk atau lahan milik tentara yang ada di luar kamp. Dari kerja sampingan ini, mereka memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan, mulai peralatan mandi, pakaian, sampai rokok. Apalagi beberapa tahanan suami-istri ada yang membawa anak.
Tahanan perempuan, menurut Anwar, juga sering menjadi korban pelecehan para penjaga. Dalam buku Taufik disebutkan tentang tahanan perempuan berprofesi perawat yang hamil dan dikeluarkan dari kamp, tapi kemudian nasibnya tidak jelas.
Selama di kamp, para tapol juga merasakan kerja rodi: membangun jalan sepanjang 20 kilometer dari Moncongloe ke Daya, Makassar. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok, yang bertugas mulai mencari batu di gunung sampai mengeraskan jalan.
Taufik, peneliti di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, ketika meneliti tentang Moncongloe berhasil mewawancarai tiga tentara yang bertugas menginterogasi tapol. Mereka membenarkan adanya penyiksaan di kamp pengasingan. Sayangnya, para penjaga kamp tidak bercerita lebih gamblang.
Menurut Taufik, sebelum ia menulis buku, tak ada informasi tertulis tentang kamp yang hanya berjarak 28 kilometer dari Makassar itu. "Tidak ada referensi saat itu. Saya harus mewawancarai puluhan tapol dan mencari pelaku," ujarnya.
Taufik mengatakan awalnya banyak tahanan politik yang menolak bicara. Dia harus beberapa kali bertemu untuk meyakinkan mereka. Kesulitan terberat: saat hendak mewawancarai eks petugas. Para pensiunan tentara itu menolak dengan alasan beragam. "Mereka khawatir dituntut balik dan paham komunis bangkit kembali," kata Taufik, yang menjadikan penelitian tentang kamp itu sebagai bahan tesis pascasarjana di Universitas Hasanuddin, Makassar.
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nurkholis, dua tahun lalu meninjau Moncongloe bersama sejumlah bekas penghuninya. Moehamad Arman dari Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, yang mendampingi korban gerakan antikomunis itu, berharap negara segera memulihkan nama baik mereka, melakukan rekonsiliasi , dan menyelesaikan kasus 1965.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo