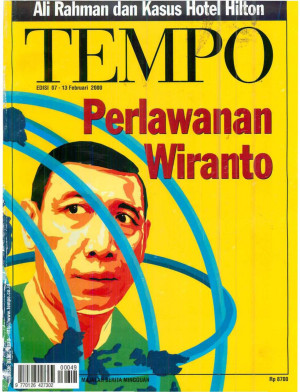MAYAT-mayat boleh hilang di liang lahad, tapi peris-tiwa tak mungkin selamanya dipendam di dalam kubur sejarah. Dan penggali kubur itu bernama Ab-durrahman Wahid. Setelah menyantap aneka pasta, di sela seruputan cappuccino dalam jamuan makan malam di Kedutaan Besar RI di Vatikan, Abdurrahman bercerita bahwa nyawanya dan nyawa Mega pernah diselamatkan Wiranto.
Cerita Abdurrahman ini, selain mengingatkan akan apa yang disebut Operasi Naga Hijau, juga mengingatkan akan Operasi Naga Merah. Sasaran Naga Merah ini adalah Megawati, terutama pada "Peristiwa 27 Juli", yang selalu dikaitkan dengan isu konspirasi menjegal Mega dari tampuk DPP PDI.
Adakah Operasi Naga Merah itu? Banyak yang mengatakan, seperti halnya Operasi Naga Hijau, itu hanya "guyonan" Abdurrahman. Tapi tak kurang juga yang percaya bahwa sejatinya memang operasi tersebut pernah digelar aparat keamanan. Bahkan, seorang purnawirawan jenderal yang memegang posisi elite militer saat itu dengan tegas membenarkannya.
Awalnya, menurut sang jenderal, Soeharto gerah menyusul terpilihnya Megawati sebagai ketua umum lewat Musyawarah Nasional PDI di Jakarta. Soeharto, yang tak bosan-bosannya berkuasa itu, merasa bahwa pengaruh Megawati yang makin menjulang akan menyulitkan ambisinya mempertahankan kedudukan sebagai presiden. Ketakutan ini seolah mendapatkan pembenaran saat aktivis PDI Aberson Sihaloho menyebarkan formulir dukungan kepada Mega untuk menjadi presiden. Maka, kata sebuah sumber, keluarlah instruksi Soeharto untuk menggulingkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Titah ini diterima Feisal Tanjung dan Yogie S.M. Disusunlah sebuah operasi, lengkap dengan nama mentereng: Operasi Naga Merah. Operasi ini mencakup pelaksanaan Kongres Medan, 20 Juni 1996, yang memilih kembali Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.
Tentu saja kongres itu ditolak massa PDI. Di Jakarta, bersamaan dengan berjalannya kongres di Medan, massa pendukung Megawati bergerak ke arah Gambir, menuju Istana. Akibat hadangan barikade aparat, di tempat ini pecah insiden cukup besar. Sejak insiden ini, massa kemudian terkonsentrasi di Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Mereka memilih mimbar bebas sebagai ajang unjuk rasa.
Lewat mimbar yang tergelar sekitar satu bulan ini, nama Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Budiman Sudjatmiko mulai dilirik aparat intelijen. Apalagi setelah Soeharto mewanti-wanti Soerjadi dan kawan-kawan akan adanya "setan gundul" yang mendompleng mimbar bebas PDI tersebut. Target sudah mulai dibidik. Oleh Soerjadi dan aparat, hal ini dianggap sebagai "restu" untuk segera melakukan penyerangan.
Sebelum kejadian itu meletus, Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) Syamsir Siregar sudah menolak proposal makar ini. Tapi ia tak mampu berkutik ketika Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Hartono dan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) Syarwan Hamid bermain sendiri. Mereka inilah, menurut sumber, yang memutuskan operasi penyerbuan ke kantor PDI itu. Pimpinan BIA kemudian tak pernah lagi disertakan dalam rapat-rapat perencanaan yang berlangsung di Kodam Jaya, tempat panglimanya, Sutiyoso, ditetapkan sebagai pangkolaops—panglima komando lapangan dan operasi—operasi ini.
Untuk mendanai operasi ini, Sutiyoso pernah meminta kepada Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI, yang saat itu dijabat Soeyono. Jumlahnya Rp 1,5 miliar. Karena kocek ABRI memang terbatas, Kasum hanya bisa menutup sepertiganya. Sutiyoso kemudian berinisiatif menutup kekurangan ini. Safarinya ke beberapa konglomerat, termasuk kerabat Soeharto, Sudwikatmono, akhirnya mampu menomboki kekurangan tersebut.
Pukul 06.00 pagi, Sabtu, 27 Juli 1996 itu, para pendukung Mega yang kelelahan setelah begadang semalam suntuk dikejutkan tujuh truk tronton yang menderu-deru dari arah Jalan Surabaya. Tak banyak yang sempat mengucek-ucek mata ketika sejumlah orang berbadan tegap berkaus merah menyala turun dan berteriak-teriak, "Hidup PDI, hidup PDI." Setelah terdengar teriakan, "Serbu," kawanan ini segera merangsek masuk. Batu-batu, corn-block yang dicopot dari trotoar, serentak melayang ke arah para pendukung Mega yang bertahan di dalam gedung. Tak kurang dari dua jam tawuran itu berlangsung. Lalu, bagai disulut minyak, kerusuhan pun berkobar di sebagian Jakarta.
Akibat tawuran, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat, 5 orang tewas, 149 luka, dan 23 orang hilang dalam kejadian itu. Ada juga korban lain di jajaran militer. Sebulan setelah kejadian itu, Syamsir Siregar dan wakilnya di BIA, Achdari, dicopot bersamaan—hal yang tak pernah terjadi dalam sejarah intelijen militer kita. Begitu juga Kasum ABRI Letjen Soeyono, yang bahkan hanya lima hari setelah kejadian. Mereka dianggap tak cukup loyal untuk membantu operasi.
Para pejabat militer yang disebut-sebut terkait dengan peristiwa ini kini memilih aksi bisu. Feisal Tanjung menolak memberikan jawaban. Lewat seorang karibnya, jenderal berkumis tebal itu hanya menyampaikan bahwa dirinya tak punya kaitan apa pun. Selain membisu, jurus lempar batu sesama kolega juga mereka lakukan. Syamsir Siregar, misalnya, saat dihubungi TEMPO, hanya berujar, "Tanya saja Syarwan. Itu bidangnya. Dulu kan dia Kassospol."
Syarwan Hamid juga memilih diam dan berkesan mengajak melupakan hal itu. "Lupakan saja masa lalu. Apa kita akan mempersoalkan masa lalu yang masih perlu perdebatan?" katanya. Hartono sama saja. Kepada TEMPO yang menghubunginya sekitar setahun lalu, ia menafikan hal itu. "Saya saat itu KSAD. Tugas saya pembinaan personel, tak ada urusan dengan itu."
Kini, Abdurrahman Wahid sedang menggali sejarah yang kelam.
Darmawan Sepriyossa, Edy Budiyarso, dan Setiyardi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini