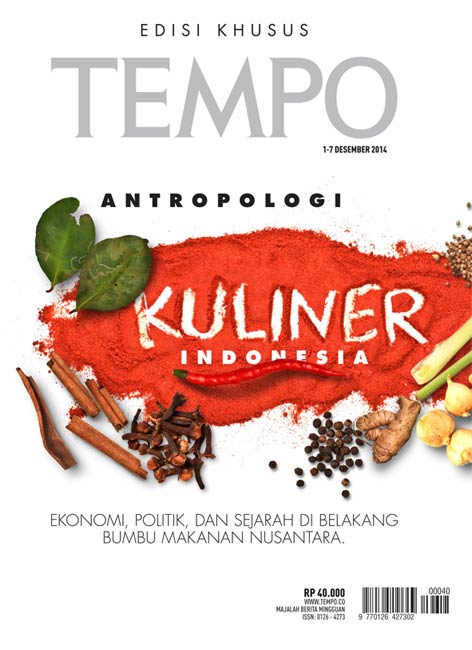Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SETELAH setengah jam menembus hutan pekat yang didominasi pohon aren, langit kembali terbuka. Kami sampai di kebun milik Jemi Pandei dan istrinya, Thris Pontoan, di Kokoken, Kelurahan Tara-Tara III, Tomohon. Lebih dari dua ribu perdu cabai rawit setinggi paha menghampar di lereng curam kaki Gunung Tatawiran, anak Gunung Lokon, berbatasan dengan hutan kelapa yang pucuknya menggaruk langit. Di samping kanan dan kiri, tertanam jagung, ubi, pisang, cengkeh, dan pala. Ini gudang makanan khas Minahasa, etnis mayoritas di Sulawesi Utara.
Sore itu, akhir bulan lalu, sang empunya kebun memanen cabai rawit, pekerjaan yang dilakoni setiap pekan. Cabai—di sana disebut rica—mudah tumbuh di wilayah setinggi 600 meter di atas permukaan laut itu. Hanya dengan satu liter bibit, Jemi bisa membentang rica di lahan seluas setengah hektare tanpa pupuk atau karbit. Menghirup aromanya saja air mata saya menetes.
Hasil panen dijual ke Pasar Beriman Tomohon, pasar terbesar di Kota Tomohon, 45 menit dari Manado. Rata-rata, setiap pekan, mereka bisa memetik 25 kilogram. "Dan pasti ludes," ujar Thris. Jangankan 25 kilogram. Pedagang di pasar Tomohon, Manado, dan Tondano bisa menjual 40-90 kilogram cabai setiap hari. "Bagi kami, rica itu sama pentingnya dengan garam," kata Jenny Karouw, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara.
Ada dua sumber makanan Minahasa. Dari hutan pedalaman, mereka mendapatkan sayuran, satwa liar, dan ikan air tawar. Dari pesisir, ada ikan laut, kerang, dan udang. Meski berbeda bahan, rasa keduanya sama-sama menyengat karena lumuran rica. Bahkan pisang goreng pun dimakan dengan sambal. "Kalau tak makan rica tak kenyang," ujar Johanis Wajong, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sulawesi Utara.
Makanya cabai selalu diburu, walaupun harganya melampaui Rp 100 ribu per kilogram. Setiap bulan, penduduk Sulawesi Utara menghabiskan 200-800 ton cabai, atau 15 gram per hari untuk satu orang, yang dipasok sekitar 30 ribu petani. Karena stok lokal sering kurang, cabai harus dikirim dari Gorontalo, bahkan Jawa Timur.
Rica sebenarnya asalnya bukan tumbuhan asli Sulawesi Utara. Kedatangan cabai tidak bisa dilepaskan dari perebutan pengaruh di jalur perdagangan rempah-rempah kala itu, antara Portugis dan kesultanan di Ternate. Pada 1563, Sultan Khairun dari Ternate bermaksud menguasai Sulawesi Utara dan mengislamkan penduduknya. Rencana Sultan dengan mengirim anaknya, Babullah, ini diketahui Portugis dan membuat mereka berusaha sampai lebih dulu ke Sulawesi Utara.
Sebagaimana ditulis oleh Dr Th. van den End dalam buku Ragi Carita: Sejarah Gereja di Indonesia, Portugis mengirimkan pasukan dengan dua kapal kora-kora ke Manado. Di kapal itu terdapat Pater Magel Haes. Dialah yang kemudian membaptis Raja Manado dan rakyatnya. Menurut sejarawan dan budayawan Minahasa, Fendy E.W. Parengkuan, saat datang ke Sulawesi Utara itulah Portugis mengenalkan tomat.
Pada 1570, Spanyol, yang menguasai Filipina, masuk ke Sulawesi Utara. Spanyol membaptis orang-orang di wilayah-wilayah yang berbeda dengan Portugis. "Misalnya Portugis membaptis orang di Siau, Spanyol mungkin di Tahuna. Jaraknya bisa hingga 300 kilometer," kata Fendy. Spanyol lebih intensif. Portugis tak pernah masuk sampai ke Minahasa di pedalaman. Ketika itulah Spanyol mengenalkan cabai yang mereka bawa dari jajahan mereka di Amerika Latin.
Satu abad sebelumnya, setelah Christopher Columbus datang dari pengembaraannya ke Amerika, cabai ditanam di biara-biara di Spanyol dan Portugis. Menurut artikel "Chile Pepper History & Chile Pepper Glossary" di majalah kuliner The Nibble, percobaan kuliner yang dilakukan para biarawan menunjukkan bahwa kepedasan cabai bisa menggantikan lada hitam, yang saat itu sangat mahal dan digunakan sebagai alat tukar resmi di sejumlah negara. Karena itu, cabai hanya dikembangkan oleh gereja. Mereka mencari tempat yang subur untuk cabai, berharap suatu saat cabai dapat menggantikan lada dan mereka tak bergantung lagi pada para penguasa Maluku Utara.
Spanyol sempat mengisi posisi Portugis di Maluku dan Sulawesi Utara pada awal abad ke-17. Namun, pada 1644, VOC Belanda dan Ternate bergabung menggempur Spanyol, mendesak mereka keluar dari Maluku dan Sulawesi Utara, kembali ke pos mereka di Filipina. Orang Minahasa pun berpindah dari Katolik menjadi Kristen, yang dibawa Belanda. Salah satu warisan Spanyol yang masih tersisa adalah cabai.
Orang Minahasa yang saat itu hidup sebagai petani di gunung yang sejuk tertarik pada cabai yang panas. Semua bahan makanan "impor" ini bercampur dengan rempah yang "panas" dari pedalaman, seperti cengkeh, pala, dan jahe, serta bawang merah, serai, balakama (kemangi), daun kunyit, dan daun lemon (daun jeruk).
Makanan pedalaman ini akhirnya menyebar ke pesisir, seperti Manado, Amurang, dan Belang, karena hubungan dagang. Begitu juga makanan pesisir akhirnya dikenal di pedalaman. Pertukaran budaya diperkirakan intens terjadi pada abad ke-19. Indikasinya, baru pada awal abad ke-20-an ikan laut diberikan saat pesta kematian. "Itulah asal-usul ikan bakar rica. Orang pedalaman tak terlalu suka ikan, kecuali jika rasanya pedas," ujar Fendy.
SEPULANG dari kebun, rombongan kami kembali berjalan menembus hutan, membawa sekeranjang rica dari Jemi dan Thris. Kami hendak bermalam di pondok di tengah Hutan Ranoriri, setengah jam dari Kokoken. Sebagian papan pondok itu terlepas hingga angin bebas masuk. Untung suhu udara malam itu sangat bersahabat, 28 derajat Celsius.
Malam itu kami—saya, fotografer Wisnu Agung, dan kameramen Mochammad Irzal—bermalam bersama penduduk setempat: Johanis Imbar, Mewan Tumurang, dan Novri Wenas. Ada juga Indra Franky Kaawoan dan Felix Sangkilang, yang menemani tim Tempo dari Manado. Kami akan berburu kawok (tikus hutan), salah satu lauk favorit Minahasa. "Ini penganan yang paling dicari saat pesta karena susah ditangkap," ujar Johanis. Dagingnya dianggap lebih manis daripada daging ayam.
Satwa liar seperti tikus, kelelawar, dan ular awalnya diburu untuk membasmi hama jagung dan padi. Sedikitnya ada 12 jenis tikus hutan yang mereka ketahui. Yang paling disukai adalah saluan—tikus pohon yang memiliki ekor dan perut putih—karena dagingnya banyak dan enak. Menurut Bernadeth Ratulangi, pakar kuliner Minahasa, semua hewan itu harus dimasak dengan cabai yang banyak. "Untuk menghilangkan aroma tanah dan hutan," ucapnya.
Sekitar pukul 8 malam, kami mulai jalan. Novri, yang berburu sejak usia 10 tahun, menjadi pemandu. Ia menenteng senapan angin, dengan senter sorot terikat di kepala. "Tikus akan terpaku jika melihat cahaya," ujarnya. Saat itulah mereka menjadi sasaran empuk pelurunya.
Kami mengendap-endap di belakang Novri, menerobos pohon, bambu, kebun, ranting kasar, dan rumput yang gatal. Selama hampir sejam, kami melakukan "ritual" yang sama. Novri berhenti di depan pohon yang buahnya digemari tikus. Ia menengadahkan kepala sembari bercicit memancing mereka. Demikian mirip suaranya, sempat saya berpikir itu tikus asli. Mewan membantu menyorongkan senter ke pohon. Sedangkan kami mematikan semua alat penerang.
Sudah jauh menembus hutan, tak ada kawok lewat. Mungkin saja bulan sepenggal terlalu terang dan tikus keburu melihat kami. Atau kami terlalu berisik. Apa pun alasannya, kami memutuskan berubah haluan dan pergi ke tempat Novri menaruh palompit—perangkap bambu—yang ia sebar pada sore hari.
Kali ini sukses besar. Dari empat jebakan yang kami periksa, tiga berhasil menjerat. Tapi kami belum mendapat saluan. Mewan berganti menjadi pemandu. Dia membawa kami lebih jauh lagi ke perangkap yang ia pasang, blusukan ke dalam hutan yang semakin rapat pohonnya.
Medannya jauh lebih berat. Tak terhitung berapa kali kami mendaki bukit terjal dan lereng curam. Bahkan Novri pun mengeluh. Tapi Mewan, yang paling senior, justru tak kenal letih. Petani 60 tahun itu lincah menerabas gelap, meninggalkan kami semua.
Baru setelah sejam, di antara bambu yang menjulang semakin tinggi dan bulan yang mulai lenyap, kami sampai tujuan. Saluan terjerat di wetes, perangkap khusus di atas pohon. Mewan pun tersenyum lebar.
SELEPAS subuh, saya terbangun oleh ketukan parang yang menebas bambu. Batangnya akan menjadi wadah memasak hidangan pesta kebun hari ini. "Kami menggunakan bambu saat acara khusus, seperti perkawinan atau kematian," ucap Johanis.
Entah kapan tradisi memasak memakai lulut (bambu) dimulai. Yang jelas, kebiasaan ini sudah ada jauh sebelum dunia luar mengenal Minahasa. "Ketika itu, lulut digantung di loteng rumah, pangkalnya dipanaskan tungku," kata Fendy. Bambu semakin banyak dipakai setelah gempa bumi 1832, agar masakan tak mudah tumpah.
Kami lalu menuruni hutan menuju Kelurahan Tara-Tara I. Di sana, Henny Ranti dan Renny Imbar, juru masak hari ini, menyambut kami. Sebentar membersihkan diri, kami berangkat ke Pasar Beriman Tomohon bersama mereka.
Ini Sabtu, hari pasar besar. Dagangan yang dijual lebih lengkap, menyongsong pembeli yang ingin menggelar hajatan pada hari Minggu. Suasana pasar ramai, walau tak sampai berdesakan.
Masuk dari arah terminal, kami menyusuri toko kelontong serta kios cakalang fufu dan ikan roa asap yang diikat bambu. Penjaja ikan segar berseling dengan lapak sayur dengan tumpukan cabai dan bawang yang menggunung. Kami juga mampir ke kios penjual pangi (Pangium edule)—daun pohon kluwek—sayur pedalaman yang menjadi menu wajib pesta.
Tapi magnet utama pasar adalah area grosir daging, karena jualannya yang tak lazim. Begitu masuk, aroma bulu terbakar dengan bau daging mentah menyerang hidung. Pedagang merontokkan bulu celeng dan anjing menggunakan slang gas.
Setiap penjual di area sekitar 1.200 meter persegi itu memiliki dagangan andalan. Ada ular piton yang melingkar dengan kepala terpotong. "Beratnya 100 kilogram seekor. Hari Sabtu bisa laku semua," ujar si penjual, Evander Keloay. Kelelawar tanpa sayap telentang dengan mulut menyeringai. Badan kawok dibakar untuk merontokkan bulunya.
Daging anjing—biasa disebut RW—dijual hidup atau sudah terpotong. Cara membunuhnya mengerikan. Kepala mereka dipukul dengan balok hingga mati. Beberapa orang Minahasa tak setuju praktek ini. "Seharusnya ditertibkan," kata Bernadeth. Terkadang ada penjual kucing dan yaki (Macaca nigra)—primata endemis yang dilindungi. Tapi kami tak menemukannya pagi itu. "Itu biasanya pesanan," ujar Henny.
Makan yaki adalah fenomena yang relatif baru. Yaki, yang terdesak karena hutan dirambah, diburu karena menghabiskan tanaman jagung pada 1950-an. Penduduk minta bantuan gerilyawan PRRI-Permesta—yang kala itu masuk ke desa—untuk membasmi yaki.
Orang Minahasa sudah maklum melihat turis ternganga. Tapi mereka menanggapi dengan ringan. Mereka punya pepatah: semua yang merayap dimakan, kecuali kereta api. Semua yang terbang dimakan, kecuali pesawat terbang. "Bahkan ular pun kabur ketemu orang Minahasa," kata Indra Franky Kaawon, salah seorang warga lokal, berseloroh. Daging "ekstrem" ini adalah makanan yang dicari, terutama saat hajatan. "Menu ini bagian dari kemeriahan pesta," ujar Fendy.
SEKITAR pukul 11 pagi, kami berangkat ke kebun Mewan, yang terletak di kaki Gunung Lokon, 700 meter di atas permukaan laut. Kebun seluas satu hektare itu ditanami pohon duren, pisang goroho, pisang susu, dan kelapa. Di tengah lahan yang dibiarkan kosong, tercagak pondok kayu mungil.
Begitu sampai, Henny dan Renny membongkar belanjaan. Mereka harus memberi makan sebelas orang yang lapar. Meja panjang ditaruh di tengah kebun untuk wadah meracik rempah dan lauk. Kedua juru masak bergantian menumbuk bumbu di lesung kayu. Daun pepaya disebar di atas meja untuk mengusir lalat. Cabai dari Kokoken ludes terpakai.
Menunya spesial. Ada tinoransak, babi yang dimasak dengan buluh. Aslinya masakan ini dicampur darah agar warnanya cerah. Tapi Renny tak suka karena tak bisa disimpan lama. Cakalang, ayam, pangi, dan jantung pisang juga dimasak di buluh. Hanya kawok yang digoreng garo rica. Garo berarti "garuk", seperti sodet yang "menggaruk" wajan.
Bumbu masakan buluh dan garo rica serupa: cabai, goraka (jahe), bawang, batang bawang (daun bawang), balakama (kemangi), serai, daun lemon (daun jeruk), daun kunyit, dan garam. Pangi dan jantung pisang dicampur lemak babi agar lebih gurih, sedangkan cakalang diolesi perasan lemon cui agar tak amis.
Novri dan kakaknya, Basti Wenas, menyiapkan pembakaran dari serabut kelapa dan ranting pohon. Buluh bambu dipotong hingga kira-kira semeter. Mewan menyiapkan nasi bungkus, semacam lontong khas Minahasa. Ia membungkus beras segenggam dengan daun laikit, daun tanaman hias.
Tradisi nasi bungkus awalnya untuk menjatah nasi di keluarga besar. Dalam perkembangannya, daun laikit digunakan dalam acara adat sebagai pengganti piring untuk tanda kebersamaan. "Dari yang berpangkat hingga orang biasa makan dengan alas yang sama," kata Alex Ulaen, antropolog Universitas Sam Ratulangi.
Satu per satu buluh dijejalkan dengan racikan masakan hingga hampir penuh. Ujung bambu disumbat dengan daun singkong agar cepat matang. "Air buluh yang manis membuat rasa makanan sedap. Tak perlu vetsin," ujar Renny. Air dituang ke buluh nasi bungkus hingga terendam. Bambu lalu disenderkan ke perapian, ditopang penyangga dari ranting kayu. Ketika satu sisi buluh menguning, Basti dan Novri memutarnya ke sisi lain.
Setelah hampir sejam, semua masakan matang. Kulit daun nasi bungkus berubah kekuningan. Dasar bambu dilubangi agar air di dalamnya keluar. Masakan lain sudah menyusut hingga ke tengah buluh.
Meja dirapikan dan dialasi daun pisang, yang berfungsi sebagai taplak. Semua hidangan disajikan di atasnya. Aroma bumbu yang terbawa angin membuat perut semakin bergemuruh. Kami meriung di meja, mengambil makanan dengan tangan dan menaruhnya di atas daun laikit. Sisa tulang dibuang ke atas tanah, untuk makanan ayam dan anjing. "Ini tradisi tetua kami," ucap Mewan.
Setelah makan, Johanis membuat dua gelas bambu khusus bagi kami. Ini untuk meneguk saguer, air nira dari mayang enau. Tuak ini menjadi minuman wajib pesta makan, bagaikan anggur saat fine dining. Rasanya yang mirip tape memadamkan rica yang membakar lidah. Inilah pencuci mulut yang sempurna.
Glosarium
Bumbu campur:
Istilah untuk menyebut kuartet bumbu serai, kemangi, daun kunyit, dan daun jeruk. Biasa dijual sepaket di pasar-pasar Sulawesi Utara.
Balakama:
Kemangi
Batang bawang:
Daun bawang
Goraka:
Jahe
Kawok:
Tikus hutan
Lemon cui:
Jeruk mungil yang banyak ditemui di Sulawesi Utara dengan nama ilmiah Citrus microcarpa. Rasanya asam segar dan aromanya lebih harum daripada jeruk nipis. Biasa dipakai untuk meredam bau amis ikan dan menambah rasa.
Lulut:
Bambu
Paniki:
Kelelawar
RW:
Singkatan dari rintek wuuk, yang berarti bulu halus. Istilah ini umum dipakai untuk menyebut anjing.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo