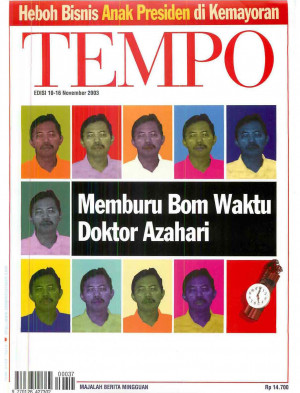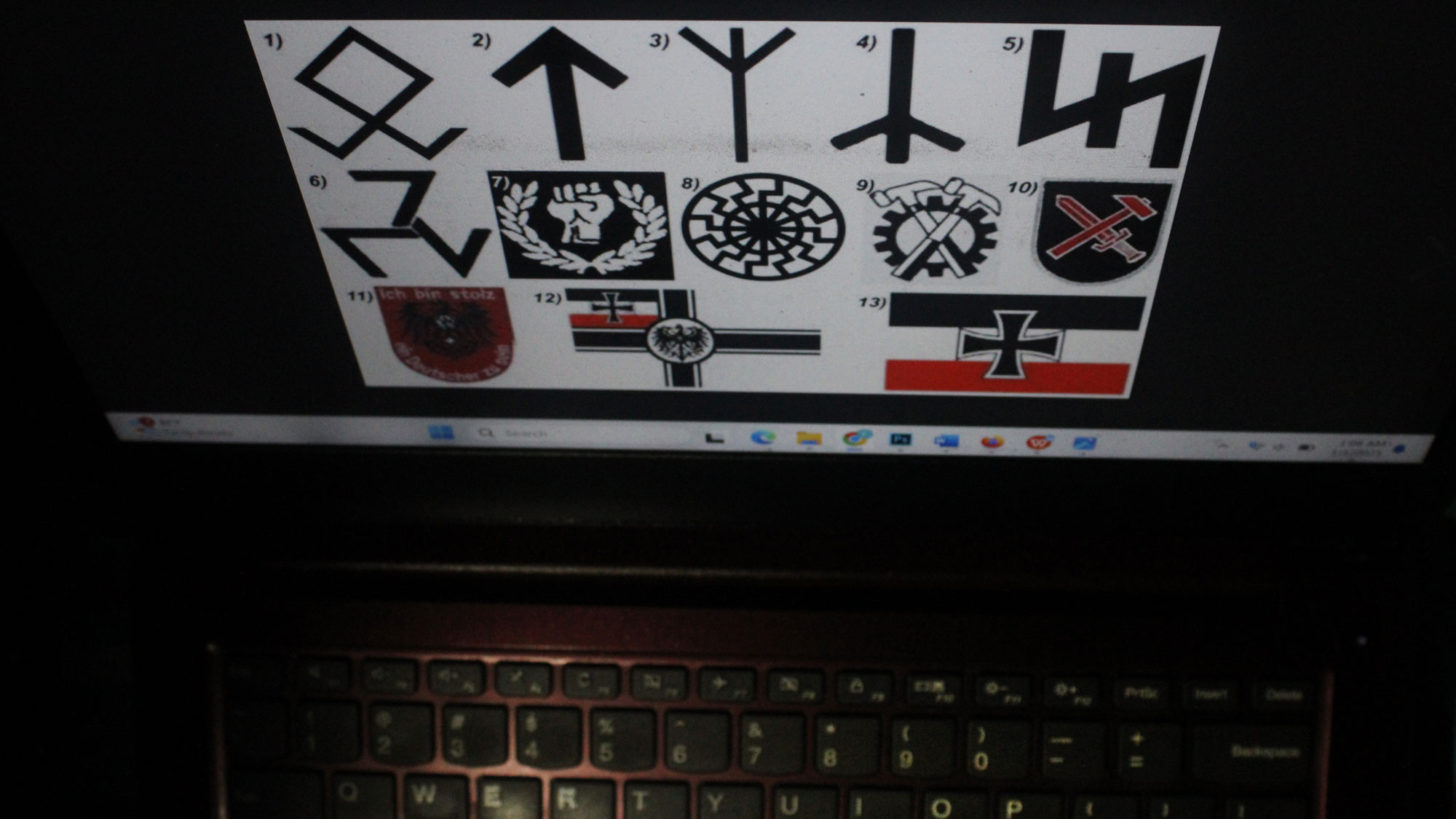Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang wartawan foto mampir ke Ambon pada pertengahan Agustus lalu. Beberapa pekan tinggal di kota itu, ia merekam aneka peristiwa rekonsiliasi—menjelang hari jadi ke-428 Kota Ambon, yang jatuh pada 7 September 2003. Tantyo Bangun, sang fotografer, terperangah menyaksikan suasana bahagia yang meruap. Di jalanan, di lapangan bola, di kampus, di lorong-lorong kota, warga Islam dan Kristen berbaur. Anak-anak muda—tanpa menanyakan soal suku dan agama—baku tolong dalam rangkaian perayaan 17 Agustus ataupun hari jadi Kota Ambon. Dan kaum tua-tua berbincang di tepi jalan menyaksikan orang berdansa karteji dalam iringan irama gendang dan seruling, sembari menikmati hawa petang yang hangat.
Di tengah suasana perayaan itu, Khalid Turuy, satu anak muda Ambon yang aktif dalam gerakan rekonsiliasi, berbisik kepada Tantyo: "Orang bilang perlu 10 tahun, bahkan satu generasi, untuk memulihkan pertikaian di Ambon." Dia melanjutkan: "Tapi kami pulih jauh lebih cepat, karena akar masalahnya tidak di sini." Melihat suasana Ambon pada hari-hari ini, siapa kira kota itu pernah terbakar dalam amarah dan perseteruan pada lebih dari tiga tahun silam, sampai-sampai meminta lebih dari 3.000 nyawa manusia?
Petang hari, 19 Januari 1999. Tanggal ini banyak dicatat sebagai pembuka babak konflik besar pertama di Maluku. Warga muslim tengah bergembira merayakan hari raya pertama Idul Fitri. Tapi sial bagi Jopie Saiya, seorang sopir angkutan umum warga Desa Batumerah Atas di Kota Ambon. Dia dicegat sekelompok pemuda dari Desa Batumerah Bawah untuk dimintai sejumlah uang. Jopie, yang merasa telah menyetor ongkos palak, menolak tagihan ekstra dari para pemuda yang diduga preman itu. Akibatnya, Jopie diunjuki senjata tajam. Dia lari pulang, mengadu pada kerabatnya di Batumerah Atas.
Mendengar cerita Jopie, hati kaum kerabatnya mendidih. Mereka bersepakat mendatangi kampung tetangganya. Semula, mereka bermaksud menanyakan kenapa Jopie diperlakukan buruk. Tapi, karena tamu datang dengan parang di tangan, niatan itu tentu saja sulit diterima warga Batumerah Bawah—yang tengah merayakan Lebaran. Apalagi para pemuda yang semula memalak Jopie berteriak gaduh memanaskan suasana. Alih-alih menyelesaikan masalah, Jopie dan kawan-kawan justru dikejar-kejar warga Batumerah Bawah.
Pengejaran berlanjut hingga Desa Batumerah Atas, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Karena buruan tak ditemukan, sasaran kegusaran warga Batumerah Bawah beralih ke rumah-rumah di kawasan itu. Tentu saja warga setempat tidak terima. Dan bentrokan pecah.
Berita perkelahian menjalar dengan cepat ke telinga warga Desa Mardika, yang berjarak sekitar tiga kilometer dari lokasi. Warga Mardika, yang kebanyakan pendatang dari Bugis dan Buton, dengan cepat bergerak karena terbetik kabar ada masjid yang dibakar. Sebaliknya, warga kampung-kampung yang mayoritas Kristen tak mau kalah karena mendengar ada gereja yang dibakar. Entah dari mana, isu-isu jahat semacam ini deras melanda Ambon pada saat itu.
Suasana berhantam menjalar secepat kilat ke setiap penjuru kota dan pulau. Dua kelompok massa—mula-mula Islam dan Kristen, lalu diperluas dengan bentrok antarsuku—berhadapan. Perkelahiannya mirip adegan film perang kuno. Anak panah, tombak, batu-batu besar beterbangan mencari mangsa. Bahkan adu nyali lewat duel-duel parang pun berlangsung dengan seru, lengkap dengan bumbu "kisah-kisah heroik" dari pihak masing-masing.
Ajal datang dalam bentuk yang amat kasar: kepala menggelinding, usus terburai, tangan dan kaki putus, bencah-bencah darah bertebaran di tanah dan jalanan kota. Pihak aparat dianggap lamban bertindak. Kerusuhan berlanjut hingga pekan berganti bulan. Api terus berkobar di sejumlah tempat karena banyaknya aksi pembakaran. Ambon memuncratkan warna merah api dan darah—setelah ratusan tahun hidup dengan warna biru laut dan pasir putihnya yang terkenal.
Sehari setelah insiden Batumerah—pada 20 Januari 1999—saat matahari baru setinggi tombak, mendaratlah dua batalion Kostrad dari Kodam Wirabuana, Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menghentikan konflik. Tapi aparat keamanan kewalahan karena konflik cepat sekali meluas. Pengusiran masyarakat muslim pendatang mulai terjadi. Suku Buton, Bugis, dan Makassar dipaksa keluar dari pulau oleh warga Kristen Maluku. Terjadilah eksodus besar-besaran.
Konflik Maluku mulai mereda pada Mei 1999 ketika digelar pemilihan umum. Namun, pada Juni 1999, konflik kembali meletup. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai babak kedua konflik Maluku. Berbeda dengan babak pertama, yang kental dengan isu etnis, pertikaian babak kedua ini sarat oleh isu agama. Maluku porak-poranda dan terbelah. Tiap-tiap kelompok membela imannya, tanpa peduli jika harus menyerang saudara sendiri.
Pada babak kedua ini sistem perekonomian lumpuh total. Peralatan yang digunakan untuk berperang telah meningkat dari golok, tombak, dan panah menjadi senjata api rakitan sendiri. Sedangkan suplai amunisinya berasal dari sejumlah sumber. Siapa saja? Menurut Koordinator Gerakan Bakubae Maluku, Ichsan Malik, suplainya berasal dari oknum-oknum militer TNI dan Polri.
Celakanya, Ichsan menambahkan, dalam babak kedua ini aparat keamanan—tepatnya pihak kepolisian—ikut terbelah. Ada polisi Islam dan polisi Kristen. Polisi Islam berkumpul di polres dalam wilayah Islam, begitu pula sebaliknya. Bantuan militer yang dikirimkan ke Maluku menjadi 24 batalion—17 batalion berada di Kota Ambon.
Lalu, pecahlah konflik babak ketiga yang dimulai pada Januari 2000. Babak ini ditandai dengan menguatnya isu separatisme. Di awal tahun itu, muncul Front Kedaulatan Maluku. Bermarkas di wilayah Kristen Kota Ambon, forum ini punya sekitar 100 orang anggota. Di kalangan muslim Ambon juga muncul kelompok jihad. Dalam catatan Ichsan Malik, sebagian besar dari mereka berasal dari Pulau Jawa dan relatif terlatih dalam berperang.
Dalam konflik Ambon babak ketiga, perseteruan melebar hingga ke pulau-pulau di luar Ambon. Di masa inilah pihak-pihak yang bertikai telah menggunakan senjata organik. "Senjata yang mereka miliki itu merupakan hasil dari pembobolan gudang senjata militer," Ichsan menjelaskan kepada TEMPO.
Setelah babak demi babak kerusuhan, hasilnya kurang-lebih sebagai berikut: 29.414 unit rumah penduduk, 251 tempat ibadah, 129 unit sekolah, 13 sarana kesehatan, 106 perkantoran, dan 636 unit pertokoan, kios, serta pasar hancur, terbakar, plus dijarah. Korban jiwa? Sebuah penelitian mencatat angka sekitar 3.000 jiwa lebih.
Upaya perdamaian dan rekonsiliasi digulirkan sejak tahun 2001. Dan hasilnya pelan-pelan mulai dituai. Memang, wajah pulau itu masih banyak yang compang-camping. Dalam istilah Ichsan Malik: "Masih banyak soal yang belum disentuh. Umpamanya relokasi penduduk, kasus tanah, dan penegakan hukum." Masyarakat jenuh membicarakan konflik—yang telah mereka pandang sebagai sebuah isu basi.
Warga memang merindukan lagi Ambon yang riang dan hangat. Kini, pada setiap akhir pekan, penduduk kota berpesiar memadati kawasan pantai yang tadinya senyap. Boleh jadi, mereka tengah berupaya merebut kembali mooie Amboina—Amboina yang manis—julukan yang diberikan oleh Majoor Gouverneur der Molukkos, De Kock, kepada pulau itu, jauh di abad ke-19.
Nurdin Kalim (Jakarta), Mochtar Touwe (Ambon)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo