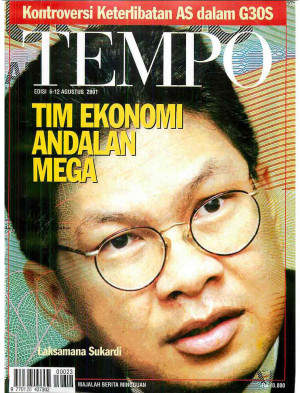BAGAIMANA mengukur keberhasilan seorang presiden Indonesia? Bila kesejahteraan masyarakat menjadi ukuran, Soeharto bisa dianggap berhasil sampai periode tertentu. Pada tahun 1996, menurut data Badan Pusat Statistik, pendapatan per kepala Indonesia mencapai US$ 1.155. Dan angka itu dicapai lewat anak tangga demi anak tangga sejak Soe-harto menjadi presiden. Adakah ia seorang presiden yang kepemimpinannya di masa tertentu patut diteladani?
Seorang penulis bernama Christina Ismail-Mahn, tinggal di Eropa, menulis perihal Soeharto dengan penuh puji-pujian. Buku tipis 67 halaman itu ditulis pada 1981, berjudul President Suharto, A Profile. Soeharto digambarkan bak seorang presiden tanpa cela yang berhasil menyelamatkan dan menyejahterakan bangsa Indonesia. Terlepas dari rasa kagum si penulis (berkali-kali di-katakannya bahwa sebutan ”bapak pem-bangunan” sangatlah tepat dan sesuai dengan yang diperbuat Soeharto), ada beberapa hal yang menjelaskan keberhasilan Soeharto.
Menurut Christina, Soeharto bekerja sangat keras sejak awal ia memerintah guna memenuhi tuntutan rakyatnya (hlm. 13). Sejak awal ia sudah membedakan diri dengan pendahulunya, Sukarno. Soeharto tak pandai pidato membakar semangat rakyat, tapi memilih lebih baik bekerja. Dan ia memang pandai memilih orang yang bisa bekerja untuk diangkat menjadi menterinya.
Buku ini menulis perihal Menteri Luar Negeri Adam Malik yang dengan tangkas menetralkan kritik dari dunia internasional bahwa Soeharto memenjarakan lawan-lawan politiknya di Pulau Buru. Sebagian pengritik menyamakan perilaku ini dengan perilaku Hitler. Tapi kritik segera mereda setelah Adam Malik menjawab dengan sebuah pertanyaan. Adakah mereka mau melihat Soeharto mengorbankan 120 juta (waktu itu) rakyat Indonesia dan membela sekitar setengah juta orang yang ”memaksakan kehendak dan lebih daripada itu keateismeannya kepada mayoritas rakyat”.
Di bidang ekonomi, Soeharto juga sangat terbantu oleh para menterinya. Waktu itu, oleh mereka yang tak begitu suka, tim ekonomi itu disebut ”mafia Berkeley”. Tapi, suka atau tak suka, merekalah yang menjadikan pendapatan per kapita naik, pembangunan terwujud (lihat saja, dengan program perumnas dan kredit pemilikan rumah, banyak orang Indonesia bisa memiliki tempat tinggal). Tim ini pula, dipimpin Widjojo Nitisastro, yang kemudian berani mengurangi subsidi minyak untuk membiayai program pemerintah yang lain: wajib belajar.
Dengan kata lain, keberhasilan Soeharto di awal masa kepresidenannya karena ia berperan sebagai manajer yang pandai memilih orang.
Hal kedua, menurut penulis itu, yang mendukung keberhasilan presiden kedua RI itu, ia sering langsung berdialog dengan rakyat, terutama petani. Dengan lancar dan konon benar, Presiden itu bicara tentang cara-cara yang baik beternak sapi, menanam jagung, dan sebagainya. Ini bukan saja membuahkan dukungan luas, tapi juga menyurutkan bahkan menghilangkan sisi kemiliteran Soeharto. Christina, penulis buku itu, yang bertemu pertama kali dengan Soeharto pada 1971, menyatakan keheranannya. Ia sama sekali tak melihat presiden petani ini seperti yang digambarkan di media cetak di Eropa: dengan sepatu lars, Soeharto berdiri di atas rakyat yang menjerit.
Penulis ini juga membela Soeharto terhadap keluhan sejumlah orang bahwa tak ada jaminan keamanan buat mereka yang berani mengkritik Soeharto. Benar, Soeharto selalu mendorong agar siapa saja berani mengutarakan kritik, tapi yang konstruktif. Kata Soeharto, kritik seperti itu akan dite-rima dengan lapang dada. Masalahnya, mana yang konstruktif dan yang tidak semata bergantung pada selera pihak Soeharto, kata mereka yang mengeluh itu.
Lebih dari itu, buku ini juga menyatakan, sesungguhnya dorongan Soeharto agar orang berani menyatakan kritik bukanlah sekadar ucapan di bibir. Buktinya, kata si penulis, lembaga internasional yang meneliti derajat kebebasan pers di negara-negara berkembang menyatakan bahwa kebebasan pers Indonesia itu unik.
Tak disimpulkan secara jelas, sebenarnya adakah kebebasan pers di Indonesia. Juga tak diuraikan yang dimaksud dengan ”unik”.
Inilah gaya kepemimpinan yang antara kata di bibir dan perbuatan bisa berbeda. Dengan cara-cara ini Soeharto dengan cepat membuat Indonesia stabil, memang. Tak ada debat, tak ada polemik. Kadang muncul tulisan yang mempersoalkan ”keadilan buat semua orang”, yang tentulah ditulis dengan hati-hati, tapi tenggelam oleh deru pembangunan jalan raya antarprovinsi, perumahan sederhana, waduk, dan masih banyak lagi. Kritik itu, yang tentulah ditulis dengan sangat hati-hati, tenggelam karenanya. Buku ini melihat lembaga legislatif, yang ”diam” dan mendukung Presiden karena keber-hasilan program-programnya, bukan karena lembaga tersebut memang sudah diatur agar terdiri dari para pendukung Presiden.
Adakah kepemimpinan seperti ini yang kita kehendaki? Mengorbankan setengah juta orang demi 120 juta yang lain? Memberikan kebebasan pers yang semu agar propaganda tersamarkan karenanya dan dunia internasional melihat demokrasi di Indonesia karenanya?
Ada yang bilang, keberhasilan Soeharto pada awal-awalnya juga karena Perang Dingin waktu itu. Naiknya sang Presiden karena berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia, menjadikan Barat (Amerika terutama) tutup mata untuk hal-hal yang pada masa akhir kepresiden Soeharto di-sebut-sebut sebagai korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya. Bukan cuma pura-pura tidak tahu, Barat pun mengucurkan bantuan.
Adalah Plato, filsuf Yunani yang berbicara tentang demokrasi dan partisipasi oleh seluruh rakyat. Ia mengibaratkan sebuah negara dengan perahu yang sedang ditimpa badai. Nakhoda harus menentukan arah menurut pengalaman dan instingnya. Kalau ia harus meminta pendapat terlebih dahulu kepada seluruh awak kapal dan kemudian menentukan arah menurut suara terbanyak, dipastikan kapal keburu tenggelam sebelum suara dihitung. Berdasarkan ”ajaran” Plato yang diceritakan kembali dalam buku ini, agaknya Christina menilai Soeharto.
Barangkali, awal kepemimpinan Soeharto memang layak diteladani dengan beberapa catatan yang sudah disebutkan (soal kebebasan pers yang semu, tentang anggota lembaga legislatif yang diatur, dan lain-lain), karena perahu Indonesia sedang ditimpa badai. Tapi, sesudah badai mereda, Soeharto tetap menjalankan kebijakan di masa angin topan. Misalnya, setelah badai mereda, ia mengundurkan diri, tak bersedia dipilih menjadi presiden lagi, siapa tahu ia bakal dikenang sebagai presiden yang membangun. Kritik mungkin masih tersisa, yakni yang berkaitan dengan peristiwa G30S.
Sesudah badai mereda, betapa mudah orang mencatat segala yang negatif dari Soeharto. Misalnya, soal menyingkirkan tokoh-tokoh yang berpotensi menyainginya. Dan sebenarnya ini sudah dilakukannya pada pertengahan 1970-an: menyingkirkan Jenderal Sumitro pasca-Peristiwa Malari 1974. Lalu, pembatasan aktivitas Ali Sadikin setelah tersebut terakhir ini tak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Popularitas Ali Sadikin, terutama di kalangan masyarakat Jakarta dan Jawa Barat, sangatlah nyata. Gubernur yang membangun Jakarta itu suatu ketika membuka Jakarta Fair, acara yang juga di-hadiri Presiden Soeharto. Konon, tepuk tangan massa yang menyambut lebih gemuruh terhadap Ali Sadikin ketimbang kepada Soeharto.
Ninik L. Karim, psikolog yang juga aktris, menyebut perilaku Soeharto tersebut dekat dengan ciri-ciri seorang machiavellian. Mengelabui rakyat, mengeksploitasi rakyat, mengontrol dengan ketat seluruh gerak-gerik rakyat, memberlakukan sistem kontrol dan hukuman yang ketat bagi yang menentang kekuasaan. Yang paling buruk, ia menikmati semua praktek manipulasi ini karena tak ada patokan moral. Kata Niniek, ”Kita tidak pernah melihat wajahnya yang benar-benar marah, tapi keputusan-keputusannya sangat menakutkan.”
Mungkin, Soeharto adalah pilihan yang benar, tapi ia boleh dikata dibiarkan saja tanpa teguran. Ketika sang pemimpin mulai menyimpang, sebagian besar masyarakat tak mau tahu atau memang tidak tahu. Sebaik-baik pemimpin diperlukan kontrol, agar bisa diluruskan kembali atau bila memang perlu: diganti.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini