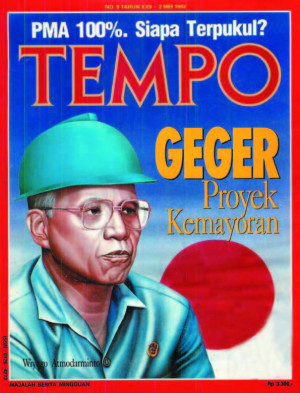SEPENTING jalan raya tempat melajunya kendaraan adalah tempat parkir untuk menyimpan kendaraan untuk sementara. Sulit membayangkan, sebuah kota hanya terdiri dari jalan tanpa tempat parkir. Apa lalu mobil-mobil, terutama mobil pribadi, mesti disuruh berputar-putar terus sementara pemiliknya sedang belanja di sebuah toko serba ada, misalnya? Dalam soal perparkiran, aktor utamanya tentu saja para petugas parkir, resmi maupun tak resmi. Tokoh kita itulah yang sering membuat para pengemudi kendaraan bernapas lega, karena dipandu ketika mau parkir, atau ketika mau meninggalkan tempat parkir di saat-saat padat lalu lintas. Dari satu sudut, pekerjaan petugas parkir hampir mirip seorang parajurit berani mati. Tiba-tiba saja ia memasang tubuhnya di tengah melajunya mobil-mobil, hanya untuk menyetop arus lalu lintas guna memberi kesempatan sebuah mobil meninggalkan tempat parkirnya. Parkir tentu saja merupakan satu bagian penting dari perlalulintasan seluruhnya. Cara pengaturan parkir yang sembrono bisa memecetkan araus lalu lintas. Guna menangani perparkiran yang tak cuma membantu pemilik kendaraan tapi juga melancarkan lalu lintas itulah, tampaknya, bila gubernur DKI Jakarta menyerahkan urusan ini pada Badan Pengelola Perparkiran (BPP) sejak tahun 1979. Selain urusan parkir pinggir jalan, BPP juga mengelola beberapa gedung parkir milik Pemda DKI Jakarta. Tak semua gedung parkir di Jakarta di tangan BPP. Sejumlah gedung parkir di perkantoran dan pertokoan dikelola oleh swasta dengan SIPP (Surat Izin Pengelolaan Parkir) dari Pemda. Pemegang SIPP ini diwajibkan menyetorkan 25% dari hasil bruto langsung ke kas daerah. Di Jakarta, kini sekitar 160 gedung parkir ditangani mereka yang memegang SIPP. Di DKI Jakarta, yang luas wilayahnya sekitar 670 km2, BPP mengoperasikan lebih dari 4.000 juru parkir. Sekitar 1.000 di antaranya punya status sebagai karyawan Badan Pengelola Perparkiran DKI Jakarta yang membawa pulang gaji setiap bulannya. Sisanya, karyawan berseragam yang penghasilannya ditentukan 20% dari pendapatannya dari uang parkir di tepi jalan. Perhitungan 20% itu tentu saja lewat karcis yang habis. Suwilo, 38 tahun, koordinator parkir kawasan lalu lintas sekitar SMAN II di Jakarta Pusat, berhak mengenakan seragam parkir sejak 1978. Sebagai koordinator, ia tiap bulan dapat membawa pulang gaji Rp 165.000 per bulan ditambah uang transpor sehari Rp 1.000. Di luar penghasilan tetapnya itu ia tiap hari mengantongi sisa uang setoran Rp 4.000 sampai Rp 6.000 w tak jelas apakah ini memang hak dia atau ini dimungkinkan karena keteledoran manajemen BPP. Tugasnya mengurus lokasi parkir yang berkapasitas 60 mobil yang ditangani oleh enam anak buahnya di situ. Lalu ada Soleh, 41 tahun, yang berpendidikan kelas III SD. Prakteknya di sekitar Hayam Wuruk Plaza. Dari tujuh jam kerja malam dan 14 ruang parkir, ia mempunyai kewajiban menyetor Rp 9.000. Rata-rata ia masih bisa mendapat Rp 5.000 sisa setoran untuk diberikan pada istri dan ketiga anaknya. Di seberang tempat kerja Suwilo ada juru parkir Tuher, 31 tahun, lulusan SMP, dan Suhendri, 25 tahun yang mengaku pernah menjadi mahasiswa fakultas teknik sipil. Keduanya bisa mendapat "gaji" bersih Rp 15.000 per malam karena menjaga sekitar 26 mobil para om yang masuk klub malam. "Wah, kita sering dapet seribu perak sekali parkir. Lima ribu juga pernah kalau yang punya mobil lagi mabuk," katanya pada TEMPO. Jumlah petugas parkir di lapangan diperkirakan lebih dari yang dipantau BPP. Karena tak jarang bermunculan tukang parkir "tembak" alias mereka yang mendapat konsesi dari petugas parkir yang resmi. Dengan menyetor sekitar Rp 7.000 untuk giliran parkir malam pada petugas resmi, mereka bisa meminjam baju seragam juru parkir. Di antaranya Agus, 23 tahun, bekas pedagang kaki lima, yang dapat memperoleh Rp 3.000 hingga Rp 4.000 dengan "menembak". Kata Agus, tamatan SD, bukan cuma ia sendiri yang bisa "menyewa" baju seragam. Agus malah bercita-cita bisa "membeli" kaveling di kawasan hiburan malam di Jakarta Pusat kalau ada yang mau menjualnya. "Keluar Rp 500.000 juga berani. Nggak bakal rugi, deh," katanya. Ilustrasi sekilas itu menggambarkan bahwa parkir -- bagian penting dari dunia lalu lintas -- merupakan tambang emas di tengah kota. Pengumpulan uang receh dari ratusan ribu mobil yang parkir di seantero Jakarta diperkirakan setiap tahunnya bisa menghasilkan gunung uang milyaran rupiah. Menurut Ketua DPRD Suparno dalam ceramah di forum Lembaga Pengkajian Sumber Daya Manusia, Juli silam, sudah 20 perusahaan swasta yang melamar ke Pemda DKI Jakarta untuk ikut mengelola parkir. Perusahaan itu rata-rata menyatakan kesanggupan memberi masukan per tahun Rp 10 milyar sampai 20 milyar ke kas Pemda, atau Rp 25 juta sampai Rp 50 juta per hari. Jika perhitungan perusahaan swasta yang menawarkan diri mengelola perparkiran DKI Jakarta itu benar, itu berarti uang parkir yang masuk lewat BPP ke APBD DKI Jakarta selama ini di bawah realitanya. Coba hitung, tahun anggaran lalu, 1990-1991, BPP hanya memasukkan Rp 2,8 milyar ke kas daerah. Jumlah ini konon 50% dari pendapatan kotor parkir, karena separuhnya dikembalikan lagi oleh BPP untuk biaya operasional, antara lain gaji tukang parkir, biaya pendidikannya, dan pembuatan rambu-rambu lalu lintas. Tahun anggaran 1991-1992, Badan Pengelola Parkir DKI Jakarta hanya ditargetkan menyetorkan uang parkir Rp 3 milyar. Tapi memang diakui, mengklopkan perhitunag di kertas dengan kenyataan, dalam pemungutan uang parkir, sulit. Di DKI Jakarta pengelolaan parkir sudah berpindah tangan beberapa kali. Seingat Naimuddin Aziz, kepala bidang perizinan BPP, era 1950-an, sebelum Pemerintah mengurusi parkir, areal parkir umum ini dikuasai oleh yang disebut "pemborong" alias para penguasa lahan parkir. Mereka terorganisasi dalam kelompok yang menjual jasa sebagai "tukang jaga oto". Dari sini lahir "gang-gang" penguasa parkir, dengan jawara dan sejumlah anak buah w nama kerennya, sih, mafia parkir, begitu. Jalan Sabang, pusat pertokoan di kawasan Jakarta Pusat, umpamanya, pernah dikuasai anak-anak Medan. Lalu arek-arek Suroboyo menguasai bilangan Senen. Masing-masing punya bos yang ditakuti. Untuk daerah Pasar Baru dan sekitarnya tersebutlah jawara parkir legendaris Samin Kitjot. Kata Samin Kitjot, yang kini sudah renta, "Saya sudah jadi bos parkir sejak Ratu Yuliana kawin," katanya. Yang membuatnya tak lupa karena waktu itu recehan parkir yang diterimanya berbentuk uang sen bolong yang dikeluarkan untuk memperingati perkawinan ratu Belanda itu, sekitar 1936. Saat itulah Samin dikenal sebagai tibang, sebutan untuk kepala parkir di suatu kawasan. Untuk Samin, kerajaan bisnis parkirnya berada di pusat pertokoan Pasar Baru dan sekitarnya. Yang bisa bergabung dengan kelompok-kelompok ini adalah kawan terseleksi dan keluarga. "Sejak itulah, sampai sekarang, mereka merasa areal itu merupakan milik nenek moyang mereka sendiri," kata Naimuddin Aziz, kepala bidang perizinan BPP itu. Konon, pekerjaan -- tepatnya penguasaan kawasan parkir itu w -- turun-temurun. Baru pada tahun 1955 Pemerintah mengeluarkan peraturan daerah tentang parkir. Gubernur menunjuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengelola parkir. Tapi karena tidak ada ketentuan pelaksanaan, kata Azis, sistem perparkiran berjalan tanpa kendali. Tampaknya fungsi Dinas PU baru sebatas mengumpulkan uang parkir, dan pelaksana lapangannya masih yang itu-itu juga, termasuk tentu saja Samin Kitjot. Bisa ditebak, dengan cara begini Dinas PU bisa dibohongi, atau pejabatnya disuap. Pokoknya, uang yang masuk ke kas Pemda cuma sekian persen dari jumlah uang parkir sebenarnya. Samin mengenang, pada tahun 1950-an sampai 1970-an adalah zaman keemasan baginya. Ia waktu itu mendirikan organisasi bernama Penjaga Keamanan Auto (PKA) dan punya wilayah kekuasaan Pasar Baru dan sekitarnya. "Anak buah saya sekitar seribu orang," kata Samin. Pasukan parkir ini disebar dalam pakaian seragam hitam dengan badge PKA di lengan. Kekuasaan anak buahnya dibatasi oleh tiang listrik. Satu tiang listrik dikuasi oleh dua anggota PKA. Anak-anak PKA itu membawa bonggolan karcis yang dicetak oleh bosnya. Yang hebat, menurut Samin, ia menugasi anak buahnya untuk menjaga titipan kendaraan dalam arti sebenarnya. Bukan sekadar menarik "pajak" lahan. "Waktu itu kalau sampai ada oto yang kehilangan lampu, kami ganti dengan lampu yang sama. Kalau ada motor ilang, kami pun siap mengantinya," katanya. Dengan menguasai lahan parkir itu, Samin, yang delapan jarinya berhiaskan cincin dengan batu seukuran jempol, hidup makmur. Samin tak ingat persis jumlah kocek hariannya, tapi ia sanggup membeli sedan. Jadi, ke mana-mana bos parkir itu naik roda empat, dikawal 2-3 anak buahnya. Kunci suksesnya? Samin mengaku menerapkan sistem kepemimpinan tangan besi. "Kalau anak buah nggak patuh, saya gaplokin," tutur Samin, yang kini tinggal bersama istri keempatnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia memang punya kaki tangan yang bertugas mematai-matai operasi anak buahnya. Syahdan, pada awal Orde Baru, pihak Pemda DKI Jakarta mulai berniat menarik masuk uang parkir dengan lebih baik. Pada 1968, "Walaupun para oknum atau pribadi tertentu masih berkuasa di lokasi parkir," kata Azis, urusan aprkir diserahkan pada wali kota. Maksudnya, dengan wilayah yang lebih terbatas, lima wali kota Jakarta diharapkan lebih bisa memantau masalah parkir, termasuk pemasukan uang parkir ke Pemda, dengan labih ketat. Tapi sistem itu hanya bertahan empat tahun. Dengan kata lain, sistem desentralisasi itu pun tak menambah uang masuk. Gubernur DKI Jakarta, waktu itu masih Ali Sadikin, lalu mengesahkan sebuah perusahaan swasta, PT Parkir Jaya, untuk mengurus lahan parkir di DKI Jakarta, 1972. Waktu itu, kata Azis, pemegang saham perusahaan itu adalah unsur ABRI. "Mungkin pengalaman kemiliteran sangat diperlukan untuk mengelola parkir saat itu," kata Azis. Maksudnya tentulah untuk melawan mafi-mafia di masa lalu, yang tampaknya tak rela rezekinya hilang atau berkurang karena peraturan baru. Direktur utamanya, Kolonel Marinir Bambang Wijanarko, bekas ajudan Presiden Soekarno. Dengan mandat dari Pemda, pihak Parkir Jaya minta pada para "mafia" parkir, termasuk Samin, untuk menyerahkan lahannya. "Mula-mula saya menolak," kata Samin. Akhirnya, Samin setuju asal diberi ganti rugi. "Dulu saya kan pakai modal untuk membesarkannya, misalnya modal seragam dan kesejahteraan anggota," katanya. Konon, Samin dijanjikan mendapat 10% dari penghasilan kotor. Tapi, katanya, prakteknya ia cuma mendapat "honor" Rp 10.000 per hari selama sembilan bulan. Sesudah itu, nol. Syukurlah ia bisa hidup dari yang disebutnya sebagai "gaji buta" Rp 135.000 tiap bulan dari BPP Parkir, sembari iseng-iseng menjual batu cincin. Kini, 5 dari 18 anak Samin mewarisi kerja sebagai Samin muda. Pada 1977 terjadi lagi kebijaksanaan perparkiran. Pemda DKI Jakarta kembali mengambil alih urusan ini lewat yang disebut Badan Pelaksana Otorita Pengelola Parkir (BPOPP) dan dua tahun kemudian badan itu berganti nama menjadi Badan Pengelola Parkir Pemda DKI. "Instansinya sama, hanya karena ada peraturan istilah otorita hanya untuk Batam, maka pengelolaan parkir tak lagi menjadi otorita parkir," kata Sudigdo, kepala BPP. Keputusan ini diperkuat lagi dengan SK gubernur tahun 1986 yang berlaku hingga kini. "Pertama kali saya masuk ke BPP saya kira perparkiran itu cuma masalah mengumpulkan uang receh, eh ternyata masalahnya rumit sekali," kata Sudigdo, yang menjadi Kepala Badan Pengelola Perparkiran sejak 1988. Berbagai masalah itu antara lain menertibkan areal parkir agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Dan tak kalah repotnya "mengambil alih" daerah kekuasaan para jawara itu. Ternyata, akibat "permafiaan" parkir di tahun 1950-an masih terasa sampai sekarang. Coba saja dengar kata Samin Kitjot, kendati pengelola parkir sudah berpindah tangan beberapa kali, ia tetap merasa wilayah Pasar Baru dan sekitarnya adalah miliknya. "Ibarat mobil, itu mobil saya. Biar sopirnya diganti 100 kali, ya tetap sopirnya harus nyetor ke saya," kata Samin. Inilah rupanya salah satu kebocoran yang sulit disumbat. Suatu kali Sudigdo mengumpulkan para jawara ini. "Saya tak mau menggunakan cara kekerasan," katanya. Padahal, sebelum menjabat kepala BPP ia dibisiki banyak orang agar menindak tukang parkir liar dengan tangan besi. Tapi ia juga mendengar ada seorang pensiunan ABRI mati dikeroyok ketika mencoba menertibkan "preman" di lingkungan parkir ini. Hasilnya? "Para pelopor parkir itu sekarang sudah menjadi pegawai kita," kata Prawoto S., kepala kepegawaian BPP. Dan setiap tahun BPP merekrut para juru parkir liar. Sebagian dari petugas parkir itu diwajibkan lebih dulu mengikuti pendidikan satpam. Yang merepotkan lagi, kata Aziz, adalah memantau ancar-ancar pemasukan, karena karakteristik tempat parkir yang bervariasi sekali. Misalnya, perbedaan antara tempat parkir di muka kantor dan rumah makan, dan juga pemasukan di hari Sabtu dan hari Senin. Seperti sudah disebut, BPP menghadapi tudingan bahwa perolehan instansi itu jauh di bawah pendapatan yang seharusnya. Salah satu ketua komisi DPRD, H. Muhammmad Rodja, menghitung seharusnya BPP bisa mengumpulkan sekitar Rp 43 milyar per tahun dari lahan parkir. Pemimpin komisi yang membawahkan bidang anggaran, keuangan, dan kekayaan daerah itu memberikan taksiran kasar begini. Katakan dalam sehari hanya 400 ribu mobil yang keluar dari garasi dan hanya parkir satu kali. Maka, sehari bisa terkumpul Rp 120 juta. Jadi setahun, tinggal dikalikan dengan 360 hari. Menurut Rodja, yang mungkin terjadi sekarang adalah "kebocoran" di lahan parkir liar dengan tukang parkir yang liar pula. Artinya, sejumlah badan jalan yang sebenarnya tidak diizinkan sebagai tempat parkir, tapi karena kebutuhan, akhirnya menjadi ruang parkir juga, misalnya di muka tempat kursus atau di depan warung kaki lima tempat anak-anak tanggung berkumpul. Dan itu bisa terjadi, tentu saja karena "petugas di situ main mata dengan petugas parkir resmi," katanya. Pendek kata, tempat itu "menghasilkan uang" tapi bocor di tengah jalan. Secara umum, kata Rodja, penyebab kebocoran adalah kontrol yang tidak efektif. "Sistem tiket tunggal seperti pajak tontonan tidak berlaku pada parkir," katanya. Karena manajemen karcis ini tidak jalan, pilihannya adalah sistem setoran yang sulit diawasi pemasukan riilnya. Ada kekecualian, di beberapa lingkungan parkir pertokoan tetap diberlakukan sistem karcis, tapi itu pun, kata Rodja, perhitungan jumlah kendaraan yang parkir sering di bawah angka sebenarnya. Rodja tampaknya benar. Ambil contoh satu kawasan pertokoan Blok M, Jakarta Selatan. Menurut sumber TEMPO, tiap hari satu pintu masuk parkir Blok M menyetorkan Rp 300 ribu pada BPP. Sedangkan di kawasan pertokoan itu ada empat pintu masuk. Kalau ini benar, BPP bisa menerima Rp 1,2 juta sehari hanya dari lingkungan parkir Blok M. Jadi, pukul rata dari hanya satu tempat parkir ini setahun bisa masuk Rp 360 juta. Belum lagi pemasukan kelebihan dari dua jam pertama parkir. Kepala parkir wilayah Blok M, Eric Timbul, tak bersedia menyebutkan jumlah setorannya ke BPP. Ia hanya menyebutkan Blok M bisa menampung 450 kendaraan dengan frekuensi mobil parkir sebanyak 2.500 mobil setiap hari. Jadi, kalaupun ada kebocoran, di mana? Wartawan TEMPO yang mewawancarai seorang tukang parkir di wilayah pertokoan yang padat di wilayah Jakarta Pusat mendapat gambaran soal bocor ini. Si tukang parkir ini, kita sebut saja Ujang, bertugas delapan jam sehari. Ia diwajibkan menyetor pada kater -- inilah bos tak resmi di wilayahnya yang mesti dituruti, agar keamanan di situ terjamin -- sebanyak Rp 23.000. Ia sendiri bisa mengantongi Rp 15.000 sehari. "Tapi saya disuruh kater mengaku hanya menyetor Rp 12.500 saja kalau ada survei," kata Ujang. Survei ini adalah evaluasi mingguan BPP ke lahan-lahan parkir. Memang, menurut Sudigdo, BPP-lah yang paling tahu keadaan di lapangan. "Orang kalau melihat dari kulitnya saja bisa berpikir macam-macam," katanya. Misalnya mengenai jumlah kendaraan yang parkir. "Mobil pribadi yang keluar saja saya perkirakan hanya separuhnya yang parkir, sisanya terus bergerak," kata Sudigdo. Di samping itu, beberapa jalan sudah dibebaskan dari parkir. Dan menurut perhitungan BPP, mereka sebenarnya baru bisa mengkover 46% dari keseluruhan tempat parkir yang ada di Jakarta. "Sisanya adalah lahan-lahan yang tak terpantau," kata Sudigdo. Yang paling penting, kata Sudigdo, BPP adalah salah satu subsistem tata laksana Pemda DKI yang bertugas memberi pelayanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir. "Sedangkan pendapatan jelas bukan fungsi utama," katanya. Rupanya, soal pendapatan parkir belum menjadi keputusan politik, apa pun sebabnya. Bila benar demikian, gagasan uang parkir Rp 1.000, yang salah satu tujuannya untuk membatasi pemakaian kendaraan pribadi, mungkin masih sulit diputuskan. Di sini tampaknya diperlukan suatu keputusan politik, untuk mengubah "filosofi" tugas BPP itu. Yakni dengan cara tak terlalu memanjakan pengguna jasa parkir yang hampir seluruhnya adalah pemilik kendaraan pribadi itu. Dua hal bisa diperoleh bila soal perparkiran ini dapat diatasi: masuknya dana untuk menaikkan pelayanan jasa angkutan umum, dan mungkin pemakaian kendaraan pribadi jadi berkurang. Bunga S., Indrawan, Andi Reza Rohadian, Ivan Harris, dan Bambang Sujatmoko
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini