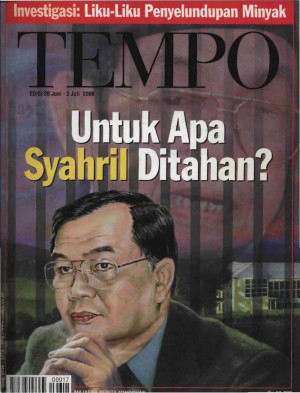Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SJAMSUL Nursalim dikejar, Bob Hasan diuber-uber. Tapi bagaimana dengan Sofjan Wanandi, Fadel Mohammad, Tutut, Gus Dur, dan yang lain-lain?
Mereka sama-sama pemilik bank yang menikmati bantuan khusus berjulukan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mereka juga bernasib sama: bank miliknya ditutup pemerintah. Bedanya, Sjamsul dan Bob masuk dalam ”kelompok terbredel” pertama: Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul dan Bank Umum Nasional (BUN) milik Bob ditutup pada Agustus 1998. Sedangkan nama-nama yang disebut belakangan menyusul dalam ”kloter” berikutnya: bank mereka ditutup pada Maret 1999.
Sialnya Sjamsul, celakanya Bob, mereka masuk dalam kloter para raksasa. Mereka masuk dalam kelompok bank besar yang rakus melahap dana talangan dari Bank Indonesia itu. Dari 12 bank besar yang ditutup dan diambil alih pemerintah saat itu, kewajibannya mencapai Rp 111 triliun lebih. Mungkin karena jumlahnya yang begitu besar, pemerintah bertindak sigap. Tak sampai tiga bulan setelah bank-bank itu ditutup, hitung-hitungannya sudah jelas: siapa menanggung berapa.
Sjamsul, misalnya, menanggung beban kewajiban Rp 28,4 triliun, Bob Rp 6,2 triliun, dan Liem Sioe Liong (pemilik BCA) Rp 47,8 triliun. Bukan cuma jumlahnya, pola pelunasannya juga jelas: mereka harus melunasi kewajiban dalam tempo empat tahun, dengan bunga 30 persen setahun. Pada tahun pertama, mereka harus membayar cicilan 27 persen dari pokok, sedangkan selebihnya dibagi rata tiga tahun. Dan karena mengaku tak punya duit kontan, para raksasa itu menyerahkan harta dan aset sebagai jaminan—untuk dijualkan pemerintah. Kelak, kalau hasil penjualan ini kurang, begitu janjinya waktu itu, mereka masih harus nombok.
Dengan pola dan jadwal yang sudah jelas seperti itu pun, pelunasan ”rezeki nomplok” BLBI itu tetap saja amburadul. Hingga hari ini, satu setengah tahun setelah settlement digelar, tak sampai Rp 5 triliun dana kasbon Bank Indonesia yang bisa ditarik kembali dari para raksasa ini. Penjualan harta mereka berjalan sangat-sangat lamban. Ketentuan bahwa pada tahun pertama (jatuh tempo 10 November tahun lalu) harus disetor cicilan pokok Rp 30 triliun lebih berlalu begitu saja—tanpa ada sanksi apa-apa.
Nah, jika utang para raksasa yang diikat perjanjian saja tak kembali sesuai dengan jadwal, bagaimana pula nasib BLBI yang nyangkut ke Sofjan (pemilik Bank Danahutama), Fadel (pemilik Bank Intan), Tutut (pemilik Bank Yakin Makmur), Gus Dur dan Hashim Djojohadikusumo (pemilik Bank Papan Sejahtera)? Ah, untungnya Tutut, mujurnya Gus Dur. Hingga hari ini, lebih dari setahun setelah bank-bank itu ditutup, hitung-hitungan siapa menanggung berapa belum pernah ada.
Upaya untuk menggelar hitung-hitungan itu memang pernah terdengar—dulu. Tapi para bankir pemilik 38 bank ini memprotes keras. Alasannya, berbeda dengan bank para raksasa yang kolaps gara-gara dibobol rush nasabah, mereka jatuh semata-mata karena krisis. Dan krisis, begitu mereka punya argumen, tidaklah bersumber pada kesalahan mereka dalam mengelola bank, tapi pada kelalaian pemerintah mengendalikan fundamen perekonomian.
Argumen ini, tentu saja, bisa diperdebatkan. Sedikitnya, tak bisa dibantah, kesembronoan para bankir dalam menyalurkan kredit menjadi salah satu biang keladi terjadinya krisis. Selain itu, tak ubahnya seperti bank-bank milik konglomerat besar yang semaput lantaran dirongrong rush, mereka juga ikut menarik dana BLBI untuk mempertahankan likuiditas bank. Kendati ukurannya bukan raksasa, bankir 38 bank kloter kedua ini bukan pula para liliput: mereka pun tak kalah rakus melahap dana kasbon Bank Indonesia (yang juga sering disebut sebagai uang rakyat itu).
Menurut catatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), kewajiban 38 bank yang dibredel ini mencapai Rp 55 triliun. Angka ini terdiri atas Rp 34 triliun kewajiban kepada Bank Indonesia (alias BLBI), Rp 20 triliun kewajiban terhadap BPPN (untuk menalangi dana masyarakat dan utang kepada pasar uang antarbank), dan Rp 1 triliun kewajiban kepada pihak lain (misalnya pesangon karyawan). Dan dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terlihat jelas bahwa sebagian besar dana kasbon Bank Indonesia itu tak digunakan menurut ketentuan.
Rinciannya, dari Rp 75 triliun dana BLBI yang diterima oleh 42 bank yang akhirnya ditutup (termasuk bank-bank kloter kedua tadi), cuma Rp 63,6 triliun yang bisa dilacak pemakaiannya. Dari jumlah itu pun, 98 persen di antaranya (sekitar Rp 62,6 triliun), ketahuan dengan jelas, telah diselewengkan. Sisanya, sebesar Rp 11,4 triliun lagi, kata Kepala BPKP Arie Soelendro di depan DPR belum lama ini, ”Belum ketahuan pemakaiannya sama sekali.”
Bagaimana bisa begitu? Menurut seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada sekitar 10 jurus tipu-tipu yang dilakukan para bankir untuk menggasak kasbon empuk ini, misalnya ”berkongsi” dengan oknum Bank Indonesia untuk membuka keran kasbon sebelum ada permintaan resmi dari bank. Ada juga bankir yang menggangsir banknya sendiri agar dana talangan dari rakyat itu ngocor ke kantong pribadi. Kok, segampang itu? ”Karena mereka selalu berkomplot dengan pejabat bank sentral,” kata sumber ini.
Toh, hingga saat ini, polisi baru menyidik pengelola dua bank yang dibredel, yaitu mantan direksi Bank Putra Surya Perkasa dan Bank Jaya. Selebihnya, bankir-bankir tadi cuma dikenai cekal. Malah, ada yang bebas berkeliaran lantaran punya koneksi politik yang kuat.
Berdasarkan data-data yang sulit disanggah itu, gampang dipahami jika pemilik 38 bank ini mestinya bernasib sama seperti Sjamsul, Bob, dan Om Liem: diuber-uber agar segera melunasi duit rakyat yang sudah telanjur disikat. Mereka juga harus segera menyerahkan aset dan hartanya sebagai jaminan jika tak mampu membayar kontan. Menurut Wakil Kepala BPPN Arwin Rasjid, untuk memikul Rp 55 triliun kewajiban tadi, ke-38 bank itu cuma memiliki harta sebesar Rp 46 triliun. Itu pun berdasarkan data yang tercatat dalam buku. Nilai sesungguhnya pasti jauh lebih kecil. Dengan memperhitungkan tingkat kredit macet yang bisa mencapai 60 sampai 70 persen, dari jumlah yang kecil itu pasti akan lebih mungil lagi yang bisa diuangkan kelak.
Sejauh ini, menurut data dari BPPN, memang ada 54 orang yang sudah meneken komitmen awal alias janji atau kesediaan untuk menyerahkan aset. Itu pun masih belum jelas berapa yang harus mereka bayar. Bagaimana dengan sisa 17 bankir yang lain? Sedikitnya sembilan bekas pemegang saham pengendali bank-bank ini dinilai tidak kooperatif lantaran tak mau meneken. Mereka adalah pemilik Bank Sahid Gajah Perkasa, Bank Central Dagang, Bank Bira, Bank Uppindo, Bank Asia Pacific, dan Bank Dewa Rutji.
Pemerintah memang telah menetapkan batas akhir penyelesaian aset ke-38 bank ini, yakni September mendatang. Tapi ini sudah sangat terlambat—sekitar satu setengah tahun setelah bank-bank ini ditutup. Apalagi, berdasarkan pengalaman selama ini, settlement aset itu baru langkah awal. Setelah para bankir ini mau mengakui utang-utangnya dan berjanji melunasinya, BPPN masih harus melakukan audit untuk menghitung nilai aset yang diserahkan. Dalam tahap ini, mungkin saja BPPN akan menemui sandungan: aset-aset yang digelembungkan nilainya. Setelah itu, masuk satu tahap lagi yang jauh lebih sulit: bagaimana menguangkan aset-aset yang biasanya keropos itu.
Tampaknya, tak ada pilihan lain bagi BPPN untuk bekerja ekstrakeras dan cepat. Jika tidak, mereka akan bernasib lebih buruk dari keledai: terperosok dua kali di lubang yang sama.
Dwi Setyo, Nugroho Dewanto, Leanika Tanjung
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo