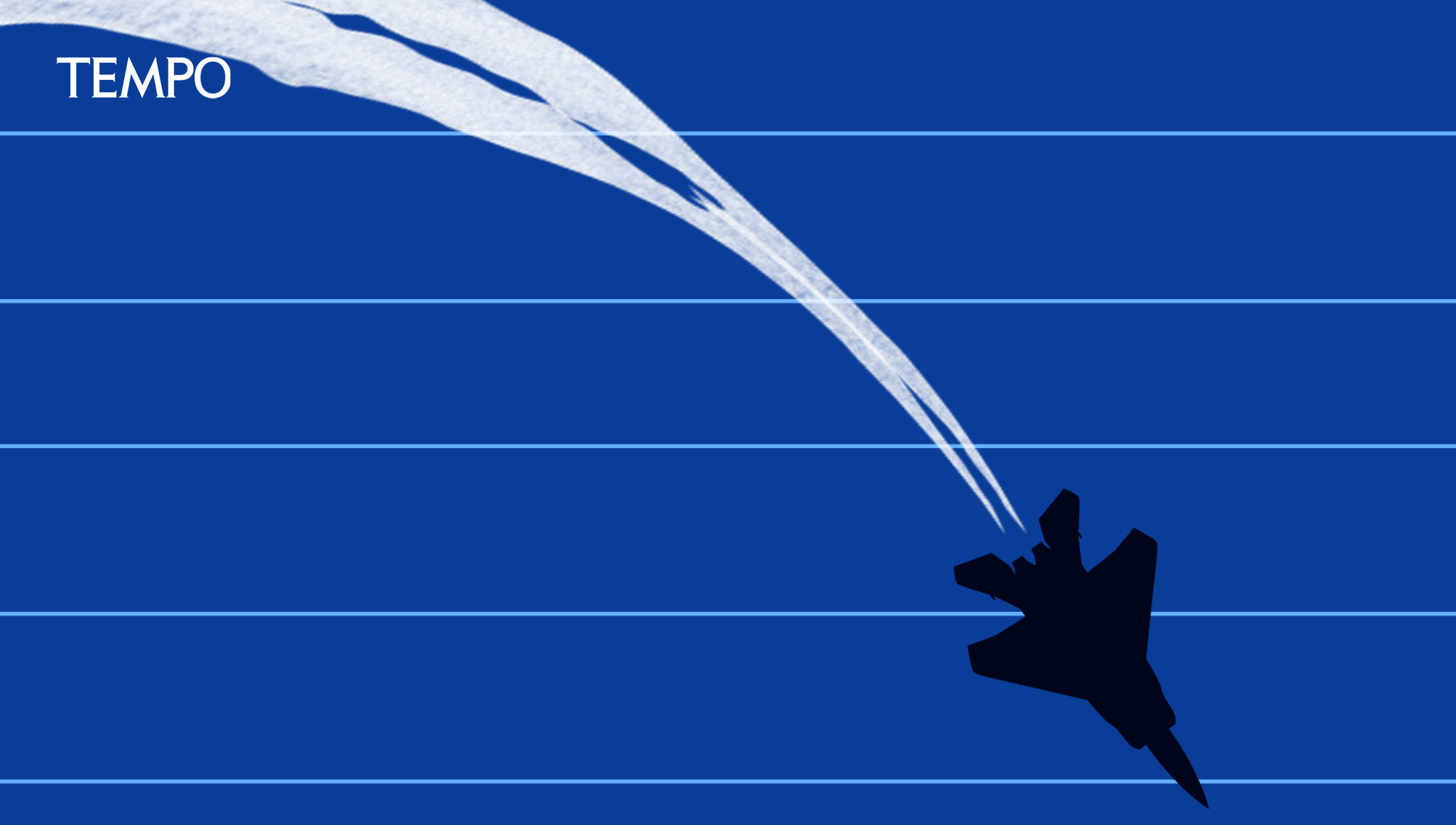Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

HARI ini hampir pasti kita tidak bisa hidup tanpa jasa pengantaran (kurir) barang, makanan, dan keperluan sehari-hari lain. Mobilitas kita juga makin bergantung pada layanan kendaraan online. Para kurir dan pengemudi jasa pengantaran ini pun berperan vital menopang hidup banyak orang selama masa pandemi ketika pemerintah membatasi pergerakan masyarakat.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo