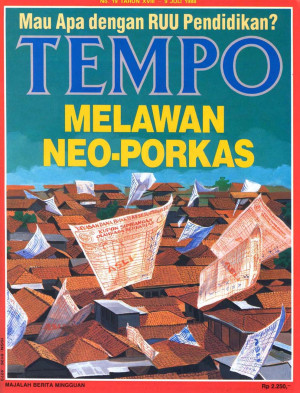KACAUKAN uang, kata Lenin, dan kapitalisme bakal ambruk. Teori bapak revolusi Rusia itu, ternyata, diperhatikan benar-benar oleh pakar ekonomi kapitalis. Contoh kongkret bisa dilihat sejak awal dasawarsa ini. Ketika inflasi berkobar-kobar mencapai belasan persen di awal tahun 1980-an, mereka ramai-ramai mengatur peredaran uang. Inflasi lalu bisa ditekan sampai sekitar 4%. Demikian pula ketika kurs valuta asing menggila. Lima negara industri terkemuka pada September 1985 sama-sama mengatur penurunan kurs dolar. Kini tujuh negara industri maju (AS, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Kanada, Prancis, dan Italia) berusaha mengekang perkembangan uang di dunia. Dari pertemuan G-7 tiga pekan silam di Toronto, (Kanada), tercapai kesepakatan. Intinya: "bila dolar dibiarkan jatuh terus atau dibiarkan naik terus, hal itu akan merugikan (counter productive)". Usai pertemuan Toronto, pasar uang internasional bergetar. Orang berlomba-lomba membeli dolar. Di pasar valuta asing Tokyo saja, jumlah dolar yang dibeli Rabu pekan lalu mencapai rekor US$ 14,35 milyar -- atau hampir tiga kali jumlah cadangan devisa di Bank Indonesia. Kurs dolar pun terdorong naik. Di Jepang, misalnya, pekan lalu, orang telah berani membeli satu dolar dengan 134,50 yen. Ada yang meramalkan selama pekan ini -- kalau saja Bank of Japan tidak turun tangan -- maka nilai dolar bisa mencapai 137 yen. Sementara itu, di Jerman Barat, harga satu dolar sudah mencapai 1,83 Deutsche Mark (DM). Padahal, pertengahan bulan lalu, harga dolar masih sekitar 125 yen dan, 74 mark. Namun, kerja sama tujuh negara maju belum tampak nyata. Bank-bank sentral di Eropa berusaha menahan membubungnya nilai dolar, dengan melemparkan cadangan dolarnya ke pasar. Tak kurang dari tujuh bank sentral Jerman Barat, Swiss, Prancis, Inggris, Italia, Belgia, dan Austria diduga secara terkoordinasi pekan lalu melemparkan US$ 1 milyar -- US$ 1,5 milyar ke pasaran. Bahkan bank sentral Inggris dan Jerman Barat terpaksa menaikkan suku bunga deposito, untuk menarik simpanan dalam poundsterling dan DM. Di pihak lain, Jepang dan AS tenang-tenang saja. Menteri Keuangan Jepang Kiichi Miyazawa mengatakan bahwa Jepang belum perlu mengikuti jejak bank-bank sentral terkemuka Eropa itu. Melemahnya nilai yen -- yenyasu kata orang Jepang -- hanya akan berlangsung sementara, begitu keyakinan Miyazawa. Namun, gubernur bank sentral Jepang, Satoshi Sumita, tampaknya khawatir juga. Rabu pekan lalu, ia mengatakan bahwa Bank of Japan akan bertindak jika kurs sudah cukup berbahaya. Maksudnya, jika yenyasu ini berlangsung lama dan rush penjualan yen kian membesar. Sumita menduga yenyasu terjadi, karena pihak Jerman Barat telah menaikkan suku bunga perbankan. Sejauh ini Bank of Japan memang tak berbuat apa-apa -- disinyalir karena Jepang menyesuaikan sikapnya dengan Washington -- tapi lewat sebuah bank Jepang di Singapura telah dijual US$ 30-50 juta. Tapi jumlah ini tak ada artinya, sementara yenyasu, bagaimanapun, bakal menolong banyak perusahaan Jepang yang sudah lama tercekik yendaka (menguatnya nilai yen). Sementara itu, dari AS pun belum ada tanda-tanda bahwa Federal Reserve Bank (bank sentral AS) mau mengendalikan nilai tukar uang dolarnya yang hijau itu. Ada dugaan, pihak AS memang menghendaki nilai tukar dolar menguat. Keinginan ini terutama datang dari kalangan partai politik, yang gencar berkampanye menjelang pemilu presiden AS, November mendatang. Dan Fed tidak menentangnya, mungkin karena apresiasi dolar diperhitungkan akan bisa mencegah inflasi yang tampaknya mulai berkobar di sana. Tahun ini laju inflasi di AS diperkirakan mencapai 5,7%, naik dari 4,4% tahun 1987. Inflasi terjadi, sebagian karena Fed telah melonggarkan peredaran uangnya sejak musibah bursa saham di Wall Street, Oktober 1987. Meningkatnya arus pembelian dolar sebenarnya wajar saja. Orang mulai pulih kepercayaannya untuk investasi dalam dolar, apakah dalam bentuk deposito dolar ataupun saham-saham di bursa AS. Dan kepercayaan itu tidak timbul begitu saja. Satu hal pasti, indikator ekonomi AS mulai membaik. Tahun silam -- sebelum musibah Senin Hitam di Wall Street -- orang melihat ekonomi Amerika terancam bangkrut. Utang AS sudah mencapai US$ 400 milyar, sementara neraca perdagangannya terus mencatat defisit yang membengkak. Tapi sejak triwulan akhir 1987, ekonomi AS, yang semula diperkirakan bakal terkena resesi, justru malah tumbuh. Bisnis dan investasi AS yang bertebaran di mancanegara telah meningkatkan daya tahan perusahaanperusahaan Amerika, hingga tidak begitu terpukul oleh kelesuan pasar d negerinya sendiri. Dewasa ini, neraca perdagangan AS memang masih defisit. Nilai total ekspornya April lalu tercatat masih lebih rendah sekitar US$ 9,8 milyar dari total nilai impornya. Neraca perdagangannya per Mei 1988, yang akan diumumkan pertengahan bulan ini, diperkirakan masih akan defisit sekitar 11 milyar dolar -- lebih jelek dari neraca April 1988. Tapi jika defisitnya di bawah US$ 10 milyar, itu pertanda neraca perdagangan AS harapkan akan tercapai pada 1992. Hanya saja keseimbangan neraca perdagangan AS itu baru tercapai jika nilai tukar dolar berada pada titik yang sepadan. Karena itu, apreasiasi dolar tersebut hanya bersifat sementara. Ada yang menduga hanya sampai usai pemilihan presiden AS, November mendatang. Sementara ini malah ada yang menduga, nilai tukar dolar AS belum meluncur ke titik terendah. Satu tim pakar ekonomi dari Goldman Sachs di London memperkirakan bahwa nilai tukar dolar terhadap yen dan poundsterling bakal terbanting lebih rendah. Ramalan mereka, sebagaimana dimuat majalah The Economist, akan terwujud dalam 12 bulan mendatang. Sementara itu, gejolak di pasar uang internasional, ternyata, belum memicu pemborongan dolar di bursa Jakarta. Transaksi jual beli mata uang asing di BI pada 27-29 Juni lalu memang melampaui pembelian. Bursa mengalami defisit sekitar US$ 20,1 juta, suatu jumlah yang relatif kecil dibandingkan cadangan devisa di BI yang berjumlah sekitar US$ 6,3 milyar pekan silam. Sementara ini, kurs rupiah yang dikendalikan BI, tampaknya, masih sangat terpaut pada dolar. Kurs tengah dolar, yang ditetapkan BI sejak 18 Juni lalu sampai akhir pekan silam, hanya naik 11 angka atau sekitar 0,9%, yakni dari Rp 1.677 menjadi Rp 1.688 per dolar. Sebaliknya, nilai tukar rupiah terhadap valuta asing lainnya tampak menguat. Pertengahan bulan lalu, untuk mendapatkan satu DM, orang perlu menyediakan Rp 960, tapi pekan silam cukup Rp 800 (turun 16%). Harga poundsterling di BI pun telah turun (4,16%) dari sekitar Rp 3.000 menjadi Rp 2.875. Sementara itu, harga satu yen Jepang telah turun hampir 6%, yakni dari Rp 13,37 menjadi sekitar Rp 12,58 per yen. Depresiasi atau melemahnya nilai rupiah terhadap dolar, menurut Menkeu Sumarlin, tak perlu dikhawatirkan. "Di satu sisi, hal itu memang akan menambah beban utang yang harus dibayar dalam dolar. Tetapi di sisi lain, ekspor kita akan lebih terdorong, dan akan menghasilkan dolar lebih banyak," kata Sumarlin. Max Wangkar, Budiono Darsono (Jakarta), Seiichi Okawa (Tokyo)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini