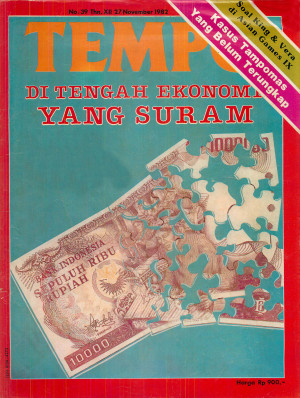CUKUP luar biasa. Setelah 9 tahun tak pernah berkumpul, para
menteri perdagangan negara-negara kaya kini tengah bertemu di
Jenewa. Mereka yang selama 35 tahun bertindak sebagai polisi
yang mengatur lalu-lintas perdagangan dunia kini merasa cemas:
persaingan ternyata kian bertambah sengit di antara mereka
sendiri. Mereka pun tengah mencari jalan keluar untuk
menenangkan tekanan darah para industrialis yang diguncang oleh
resesi.
Itulah sidang GATT, yang dikenal sebagai 'klub negeri-negeri
kaya' (baca Kolom Moh. Sadli). Seberapa jauh para menteri itu
berhasil, masih harus ditunggu. Tapi resesi dunia, di luar
dugaan banyak pengamat, ternyata telah menggigit lebih dalam,
menggerogoti lebih luka. "Ada tanda-tanda yang akan merusak
sistem perdagangan dunia," kata Albert Bressand, ahli
perdagangan yang bekerja pada Institute for International
Relations di Paris. Dia khawatir kalau persaingan yang semakin
sengit itu akan menjelma menjadi suatu "perang dagang", yang
akan saling mematikan.
Beberapa korbannya sudah kelihatan. International Harvester,
perusahaan alat-alat besar No. 2 di Amerika, sudah melepaskan
ribuan buruhnya. Dan negeri besar itu kini menderita tingkat
pengangguran setinggi 10%.
Kanada, negeri di Utara yang nampak aman itu, lebih susah lagi
tingkat pertumbuhannya sudah di bawah nol persen, dan jumlah
buruhnya yang menganggur mencapai 11-12% kurang lebih sama
dengan Inggris.
Di Jerman Barat, perusahaan-perusahaan besar, seperti
AEG-Telefunken yang terkenal itu, mengalami kesulitan
likuiditas. Sedang yang menengah dan kecil kelas Eropa "sudah
lama mengalami default (kesulitan mencicil utang-utangnya pada
bank)," kata Menteri Keuangan Indonesia Ali Wardhana yang,
mengingat eratnya kaitan ekonomi Indonesia dengan ekonomi negeri
industri, memperhatikan itu dengan cemas.
Angin resesi yang bertiup kencang dari belahan Utara itu memang
sudah lebih dulu menyambar banyak negara berkembang. Dan
akhirnya menjangkiti ekonomi Indonesia pada awal 1982.
Pengaruhnya jelas terlihat dalam bentuk menurunnya ekspor,
akibat pasaran yang lemah di negeri-negeri industri.
Dari Bank Indonesia keluar laporan yang tak menggembirakan:
Antara Januari sampai dengan Juli tahun ini ekspor, termasuk
minyak dan LNG, berjumlah US$ 10,7 milyar. Pada periode yang
sama tahun lalu ekspor tersebut masih mencapai US$ 12,6 milyar.
Sedang ekspor di luar minyak, sampai Juni tahun ini, berjumlah
US$ 1,8 milyar -- turun sebanyak 21% dibandingkan periode yang
sama tahun lalu.
Akibat pasaran internasional yang melemah, hampir seluruh harga
komoditi ekspor utama Indonesia mengalami penurunan. Harga karet
RSS I misalnya, pekan lalu mencapai US$ 0,43 setiap pound
(1 pound = 453,6 gram), dibanding US$ 0,70 pada November 1980.
Kopi yang pada Maret 1980 masih US$ 680 tiap pikul, sekarang
merosot lebih separuh, menjadl US$ 302 tiap pikul. Harga minyak
sawit turun dari US$ 650 per ton pada Januari 1981, menjadi
hanya US$ 350 per ton sekarang ini. Sedang harga timah di bursa
London, yang bulan Januari lalu masih bertahan pada œ 8.700 per
ton, sekarang menjadi œ 7.240.
Daftar penurunan harga itu masih bisa diperpanjang lagi dengan
tembaga, nikel, tembakau, teh, lada, sampai kayu lapis
(plywood). Tapi bagi Chairun Sarumpaet, 31 tahun, yang memiliki
warisan kebun karet di Desa Aek Tolang, dekat Sibolga, itu
berarti kehidupan yang makin runyam. Menyadap 200 batang pohon
karet dalam seminggu, ayah dari lima anak itu paling banter
mendapat 20 kg. "Apa boleh buat, penghasilan seminggu hanya Rp
3.000," katanya.
Di Tapanuli, para petani kopi juga sudah banyak yang
meninggalkan kebunnya. "Merawat pohon kopi itu jauh, lebih sulit
dari karet," kata R. Sitompul, dari Desa Saitnihuta, Tapanuli
Selatan. Ia mengenang masa sesudah Kenop 15, tahun 1978-1979.
Ketika itu untuk sekilo kopi, para petani masih bisa mengantungi
sekitar Rp 2.500. "Tapi sekarang, paling banter cuma Rp 500,"
katanya.
Buruh di perkebunan kelapa sawit agaknya masih beruntun
ketimbang para petani kecil seperti Chairun Sarumpaet dan
Sitompul. Sekalipun ekspornya menurun, dan kilang-kilang minyak
sawit di dalam negeri, menurut pihak Gabungan Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia di Medan, tak mampu menyerap lebih banyak dari
650.000 ton per tahun (produksi tahun ini diperkirakan 815. 000
ton), belum terdengar buruh-buruh perkebunan ada yang
diberhentikan. "Saya masih tetap memperoleh gaji seperti biasa,
Rp 16.000 sebulan," kata Tukiran, buruh di perkebunan Socfindo,
Sum-Ut. Cuma, katanya, "kini tak ada lagi kerja lembur."
Perkebunan itu masih memberikan beras sebanyak 67 kg buat ayah
dari lima anak itu.
Perusahaan PMA mulai banyak yang kempas-kempis, mengikuti
induknya di luar negeri. Seperti perusahaan Inco Indonesia di
Soroako, Sul-Sel. Selain terus merugi, bulan Oktober lalu
perusahaan nikel itu kembali memberhentikan 426 dari 3.600
karyawannya. Mudah diduga tahun depan akan banyak lagi yang
terpaksa mendapat uang pesangon, mengmgat Inco Ltd, induknya di
Toronto, sudah lama mcngetatkan ikat pinggang (TEMPO, 30
Oktober).
Di Bandung, PT National Semiconductor (PMA Australia) yang
berdiri sejak 1970, baru-baru ini telah memberhentikan 700 dari
2.500 karyawannya, umumnya wanita muda tamatan SD dan SMP.
Perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik integrated
circuit untuk ekspor itu, lalu mengimpor puluhan mesin otomatis
mengganti manusia (TEMPO 13 November) mengingat pasaran mereka
di Eropa dan Amerika, bukan mustahil akan lebih banyak buruh
wanita PT NS, yang menjadi penganggur tahun depan.
Termasuk dalam barisan yang merasa paling terpukul adalah Dwima
Grup, yang punya sembilan PT, bergerak dalam ekspor kayu, kayu
lapis sampai jasa perkapalan. "Kami sudah membuat proyeksi
kerugian milyaran rupiah sampai tahun 1984," kata Dir-Ut Dwima
Slamet Sarojo. Berkantor di Wisma Antara, Jakarta, perusahaan
itu mulai merasakan pengaruh resesi pada 1980, berbarengan
dengan keluarnya SKB Tiga Menteri, yang melarang ekspor kayu
gelondongan.
Pendapatan grup Dwima yang pada 1979 mencapai Rp 10 milyar,
kontan anjlok menjadi Rp 2 milyar setahun kemudian. Tahun ini,
Dir-Ut Slamet merlghitung penghasilannya "hanya bisa mencapai
sekitar Rp 1 milyar," katanya.
Tapi ada juga yang masih bisa tertawa, seperti perusahaan sepatu
Bata. Perusahaan di Kalibata, Jakarta, itu masih tetap
memproduksi sesuai dengan rencana. "Pasar kami cukup besar 150
juta rakyat Indonesia, dan produksi kami baru 6 juta," kata
Dir-Ut PT Sepatu Bata, P.Z. Baldik kepada TEMPO Tapi menurut
pria Jerman yang gemuk itu, pasaran bisa mulai mengurus tahun
depan, kalau tak cepat diambil ancang-ancang. 'Kami sudah
bersiap-siap menghadapi tahun sulit itu, antara lain dengan
meningkatkan dan menyempurnakan kualitas, mode sepatu,
memeratakan distribusi dan mengekspor," kata Baldik.
Untuk itu, tahun depan juga, Bata akan membangun pabrik baru di
Surabaya dengan investasi sekitar US$ 6 juta. aksudnya, agar
lebih mudah menjangkau pasaran di Indonesia baian timur.
Perusahaan Unilever, yang lebih dulu ke khalayak (go pubic)
dari Bata, nampaknya juga masih bisa tertawa. "Selama lima bulan
terakhir ini belum ada satu produk kami pun yang dinaikkan
harganya kata Dir-Ut Unilever, Yamani Hasan pekan lalu. Kepada
Eddy Herwato dari TEMPO, orang No. 1 Unilever Indonesia itu
menerangkan ada juga keuntungan dari resesi itu buat
perusahaannya.
Kebutuhan bahan kimia untuk mengolah 30 produk Unilever umumnya
masih didatangkan dari Eropa dan Jepang. Dan resesi, yang
membuat mereka sulit mendapatkan pasar, memungkinkan Unilever
untuk menekan harga impornya. Apalagi perbandingan nilai rupiah
terhadap nilai mata uang Eropa dan Jepang belakangan ini
mengalami apresiasi. Artinya, turunnya kurs mata uang seperti
DM, Franc (Prancis), Gulden, œ dan Yen terhadap US$ bergerak
lebih cepat dibanding turunnya nilai rupiah terhadap US$.
NAMUN demikian perusahaan ini, yang produknya merasuk sampai ke
kampung dan desa, tak terlepas dari libatan efek resesi di
dalam negeni Hasan, pertumbuhan pasaran Unilever kini berkurang
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya --dengan catatan, penjualan
barang Unilever di Jawa dan Sumatera berbeda.
"Gejala ini sudah kelihatan sejak tahun lalu," katanya. Ia
mencatat, pertumbuhan di pasaran Palembang dan Lampung sangat
lamban, sementara secara keseluruhan, di Jawa pertumbuhan pasar
masih lebih besar. "Jika tahun 1980 pertumbuhan di Jawa,
Kalimantan, dan Sumatera rata-rata masih 10% setahun, sejak
tahun lalu sudah flat (datar) untuk Kalimantan dan Sumatera,"
katanya.
Data yang dikemukakan Yamani Hasan menunjukkan terjadinya
pertumbuhan yang datar di daerah-daerah penghasil komoditi
nonminyak, seperti karet, lada dan kopi. Itu pula yang dirasakan
Tanri Abeng. Kata Dir-Ut PT Multi Bintang itu, "Berdasarkan
penelitian sendiri, dan intormasi sesama produsen makanan dan
minuman lain, penurunan permintaan amat terasa di luar Jawa."
Di Sumatera dan Sulawesi Utara, pasaran dari perusahaan yang
terutama memproduksi minuman bir itu, mengalami penurunan
permintaan sekitar 16%.
Namun Tanri Abeng tak melihat penghasilan bersih perusahaannya,
yang tahun ini diperkirakan di atas Rp 5 milyar, akan berkurang.
Bahan baku untuk membuat bir, seperti yeats (semacam gandum) dan
ragi dari Belanda, menurun akibat kelebihan suplai. "Itu amat
menolong kami," katanya.
PT National Gobel, produsen barang-barang elektronika dan
alat-alat rumah tangga dari listrik, juga merasakan penurunan
permintaan di dalam negeri. Tahun lalu perusahaan yang
mempekerjakan sekitar 2.500 buruh di pabrik Cawang, Jakarta
Selatan ini masih menikmati kenaikan permintaan 20-30%. Tahun
ini, menurut Direktur Pelaksana amien. A. Tahir, hanya 5-10%.
Tapi dia tak khawatir, karena prospek pasaran masih bagus buat
mereka tahun-tahun mendaung. Sebabnya? "Sekarang baru 159, dan
penduduk yang kebagian aliran listrik. Kelak itu pasti akan
naik," kata Jamien.
Dari situ dapat dilihat, bahwa berbeda dengan perusahaan yang
punya pasaran di luar negeri-- seperti plywood --pabrik yang
berpijak di konsumen Indonesia masih bisa bicara optimistis.
Singkat kata, ekonomi dunia Barat payah, ekspor pun susah.
Mengendurnya ekspor, terutama ekspor minyak, mengakibatkan
defisit pada neraca pembayaran tak bisa dielakkan. Cadangan
devisa Indonesia pun terus merosot sejak bulan Maret 1981.
Cadangan devisa pada akhir September tercatat USS 4,2 milyar,
turun dari US$ 6,4 milyar pada akhir Maret 1982. Pcnurunan
cadangan devisa yang paling hesar terjadi pada kuartal kedua
tahun ini hanya dalam tiga bulan, devisa merosot dengan US$ 1,8
milyar (lihat graiik. Tak pelak lagi, penurunan itu akibat uang
yang masuk dari minyak mulai berkurang.
Ekspor minyak Indonesia memang tak bisa lepas dari pengaruh
resesi. Permintaan minyak oleh negara-negara industri terus saja
berkurang sejak tahun lalu. Maka jumlah minyak yang bisa dijual
oleh OPEC juga menjadi lebih rendah. Tadinya timbul harapan,
menjelang musim dingin tahun ini permintaan akan minyak mulai
pulih. Nyatanya, harga-harga minyak malah semakin mengendur,
sekalipun musim dingin di belahan bumi Utara sudah dekat. Tak
ada tanda-tanda permintaan minyak akan meningkat sampai OPEC
bersidang lagi di Jenewa atau di markas besar mereka di Wina,
ibukota Austria, 9-11 Desember.
Sampai akhir minggu pertama November, Pfrtamina masih berusaha
untuk mempertahankan harga minyak ekspornya. Kepada pembeli di
Jepang yang terus mendesak sejak pertengahan tahun ini, pihak
Pertamina telah mencoba membujuknya dengan memberi kelonggaran
masa pembayaran, dari 30 hari menjadi 60 hari.
Siasat itu ternyata tak juga berhasi!. Maka akhirnya Pertamina
pun mengalah, dan mulai 11 November harga ekspor minyak
Indonesia secara resmi diturunkan semua. Mulai jenis Minas
(Light Sumatran Crude) dari US$ 35 menjadi US$ 34,53, jenis
Cinta turun dengan US$ 70 sen, Attaka turun pula dengan US $
1,30. Danl jenis Duri yang seret pasarannya, turun US$ 1,90 per
barrel.
Penurunan hara minyak, seperti kau Menteri Pertambangan dan
Energi Subroto, adalah "pertanda bahwa kita juga turut
memikirkan kepentingan mereka". Itu ada betulnya kalau penjual
tak memikirkan sama sekali kepentingan pembeli, mana bisa laku
barangnya? Apalagi nampak: para pembeli di Jepang sudah banyak
juga yang beralih ke Iran. Nippon Oil Coy. misalnya, pengilangan
minyak terbesar di Jepang, beberapa waktu lalu sudah
menandatangani kontrak dengan Iran. Dan Iran, yang masih sibuk
perang melawan Irak, bersedia saja menjual harga kontrak
minyaknya (jenis Iraniar Light Crude), hanya dengan harga US$
31,50 termasuk biaya pengangkutan sampai di tempat tujuan.
Melihat hal semacam itu, akan berhasilkah Indonesia memperbesar
ekspor minyaknya? Masih harus dilihat. Tapi yang pasti,
penurunan harga minyak kita akan membawa akibat terhadap
penerimaan devisa dari ekspor LNG. Dalam kontrak dengan pembeli
LNG di luar negeri -- Jepang yang paling besar --harga LNG
ternyata dikaitkan dengan harga minyak ekspor. Dalam APBN
sekarang, devisa yang masuk dari ekspor LNG diperkirakan US$ 1,4
milyar lebih. Realisasinya bisa dipastikan akan lebih kecil.
Walhasil, tanda suram lagi. Kalau ada yang menggembirakan
pemerintah dalam resesi ini, adalah turunnya konsumsi BBM di
dalam negeri, seperti diungkapkan Menteri Subroto. Pemakaian BBM
antara Januari - Oktober tahun ini tercatat 19 juta kilo liter.
Itu berarti konsumsi BBM 20% lebih rendah dari konsumsi tahun
lalu.
Dari segi konservasi energi yang lagi didengung-dengungkan, itu
merupakan sesuatu yang positif. Tapi ada yang ironis: subsidi
BBM dalam tahun anggaran ini, sebagaimana diakui Menteri
Keuangan Ali Wardhana, akan jauh lebih besar dari Rp 924 milyar
(baca box wawancara).
Ali Wardhana belum bersedia mengungkapkan berapa besar kenaikan
itu sekarang. Faktor kenaikan itu, selain harga minyak yang kita
impor dari Arab Saudi jadi lebih mahal, juga karena prorata
crude yang biasanya diterima Pertamina dari para kontraktor
minyak asing berkurang. Sesuai kontrak, Pertamina memperoleh 10%
dan produksi setiap kontraktor asing, dengan harga cuma US$ 10
per barrel.
Hasil prorata itu biasanya dijual ke luar negeri, karena
termasuk minyak yang berkualitas baik. Hasilnya, antara lain
untuk membeli minyak dari Arab Saudi yang lebih murah, untuk
diolah menjadi kerosin (minyak tanah) dan hasil minyak lainnya.
Tapi dengan produksi antara 1,2-1,3 juta barrel sehari, minyak
prorata itu tak sebesar dulu. Dan subsidi BBM pun membubung.
Seorang pejabat minyak mcmperkirakan subsidi BBM itu akan naik
dua kali, menjadi sekitar Rp 1,9 triliyun pada akhir Maret 1983.
Maka yang akan dilakukan pemerintah sudah jelas subsidi BBM itu
sekali lagi akan dipotong. Harga bahan bakar yang tak banyak
disubsidi itu dengan sendirinya akan melonjak. Yang nampaknya
akan naik sekali harganya adalah minyak tanah dan solar.
Keduanya disubsidi sekitar seratus persen selama ini --dan itu
dianggap terlalu besar. Pemerintah perlu mengerem pengeluaran
rutinnya, seraya mengerahkan dana yang bisa diraih.
Itu berarti mengejar pajak secara hebat-hebatan. Dalam APBN yang
berjalan, pajak perseroan minyak -- tulang punggung penerimaan
pemerintah (60%) -- diharapkan mencapai Rp 9,1 triliyun.
Pemerintah menghitungnya atas dasar produksi minyak 1,46 juta
barrel, dengan harga ekspor rata-rata US$ 35 per barrel. Tapi
akibat resesi dunia, untuk pertama kalinya dalam waktu 10 tahun,
anggaran penerimaan dari pajak perseroan minyak tak akan
tercapai dalam APBN 1982/1983.
Berkurangnya penerimaan dari minyak memaksa pemerintah untuk
meng gali lebih dalam sumber-sumber di luar sektor minyak.
Dalam APBN 82/83, pemerintah menggantungkan harapannya pada
tercapainya penerimaan dari pajak pendapatan dan pajak
perseroan: masing-masing diusahakan agar naik dengan 24% dan
47%.
Mungkin tak begitu sulit untuk mencapai sasaran penerimaan dari
pajak pendapatan dari Rp 207 milyar jadi Rp 256 milyar. Sebab
penerimaan itu sebagian besar berasal dari pajak golongan
berpenghasilan tetap. Dan cara mengumpulannya relatif mudah.
Tapi menurut Dir-Ut PT Unilever Indonesia, Yamani Hasan, sasaran
pemerintah dari pajak pendapatan itu masih bisa ditingkatkan
lagi. Caranya? "Jika kelak intensifikasi sudah terasa jenuh,
boleh saja pemerintah menggarap lewat ekstensiikasi," katanya
Orang Unilever itu menilai tarif pajak pendapatan di Indonesia
masih rendah, hanya 50% dari pendapatan. "Di Belanda bisa
mencapai 74% dari pendapatan," katanya.
Pajak pendapatan memang lebih mudah ditembak dibandingkan pajak
perseroan. Apalagi pemerintah--dengan aparat pemungut pajaknya
yang tak begitu bersih--sering dihadapkan pada perseroan yang
menggunakan dua pembukuan: satu untuk bank dan satu untuk kantor
pajak. Di masa lalu, ketika penerimaan dari minyak sering
membanjir, pemerintah tak begitu ambil pusing dengan praktek
begitu. Tapi kini apa boleh buat: pendekatan sedang dilakukan
antarabank-bank dan kantor pajak, agar mereka hanya menerima
satu laporan keuangan yang sama dari setiap wajib pajak
perseroan.
Pemerintah juga mengancam akan menyita perusahaan yang belum
membayar pajaknya, 65 hari sesudah penilaian rampungnya
dikeluarkan kantor pajak. Dan perusahaan akan mendapat surat
peringatan kalau pajaknya belum dibayar 30 hari sesudah adanya
keputusan rampung. Kalau dalam 35 hari sesudah peringatan itu
pajaknya masih juga belum dibayar maka perusahaan akan disita,
dan kekayaannya akan dilelang. Penerimaan dari lelang akan masuk
ke kas pemerintah sebagai pengganti pajak yang tidak dibayar.
Selama ini pembayaran pajak sering diulur berbulan-bulan, bahkan
bertahuntahun. Seorang pejabat Departemen Keuangan khawatir,
bila penerimaan pajak perseroan, pajak pendapatan dan MPO
dibiarkan terus tertunda, penerimaan dari sektor ini bisa 15-20%
lebih kecil dari yang dianggarkan. Juga, seperti kata pejabat
itu, pengumpulannya harus benar.
Dir-Ut PT Bank Niaga, Idham, menyambut keinginan pemerintah
untuk menggarap lebih banyak pajak perseroan. Telah memimpin
bank devisa itu selama 37 tahun, ia bangga tahun lalu bisa
menyetor Rp 2 milyar lebih. Sedang kelompok perusahaan Gobel
Grup, menyatakan bisa menyetor pajak perseroan sebesar Rp 16
milyar. Total penjualannya tahun ini, menurut Wakil Dir-Ut
Lukman Hakim, berkisar sekitar Rp 1,3 triliyun.
Melihat sudah demikian banyaknya perusahaan yang tumbuh di
Indonesia, baik asing maupun nasional, Idham yang pernah menjadi
ketua Perbanas, beranggapan sasaran pajak perseroan yang
sekarang Rp 822,5 milyar itu, masih bisa diperbesar lagi. "Kalau
bank seperti ini bisa menyetor dua milyar boleh dihitung berapa
banyak perusahaan besar di Indonesia pasti lebih dari lima
ratus," kata Idham.
Idham mungkin betul. Masih banyak perusahaan di Indonesia yang
punya kebiasaan ingin menghindari membayar pajak yang
sebenarnya. Itu sudah pula diakui oleh Menteri Ali Wardhana.
Tapi sedalam-dalamnya pajak dalam negeri itu digarap, defisit
dari neraca barang dan jasa (current account) untuk tahun
anggaran 82/83 ini sudah bisa diterka: lebih besar dari US$ 4,5
milyar seperti semula diperkirakan oleh pemerintah. Dalam APBN
tahun lalu, defisit itu masih US$ 2,8 milyar. Sekarang, akibat
berkurangnya penerimaan dari minyak, defisit barang dan jasa itu
diperkirakan mencapai US$ 6,5 milyar.
Beberapa sumber pemerintah yang mengetahui, malah memperkirakan
angkanya bisa lebih besar dari 6,5 milyar dollar. Tapi, seperti
dikatakan Gubernur BI Rachmat Saleh, kita tak perlu menjadi
panik. Sang Gubernur baru saja kembali dari perjalanan jauh,
antara lain menandatangani perjanjian utang komersial sebanyak
US$ 300 juta di London.
Bisa dipastikan Rachmat Saleh dan anak buahnya tidak panik.
Mencari utang tambahan di pasar uang internasional memang bukan
unda kekalutan. "Itu biasa, dan berlaku di mana pun juga," kata
seorang pejabat Bank Dunia.
Sebagai orang yang pernah berpengalaman di beberapa negara
berkembang, pejabat Bank Dunia itu beranggapan, utang-utang
komersial yang dibuat BI "masih dalam baus-batas yang normal".
Dia bahkan kagum akan kepandaian orang Indonesia mengelola
utang. "Mereka sungguh berhati-hati melakukan debt management,"
katanya.
Menurut orang Bank Dunia itu utang-utang yang dibuat Indonesia
setiap tahun akan terisi lagi, baik dari utang-utang resmi yang
sifatnya setengah lunak, maupun dari utang-utang komersial yang
berjangka sekitar 10 tahun dengan bunga di bawah 10%. Ia
mengingatkan akan adanya kredit-kredit yang sudah disetujui,
tapi belum dilaksanakan (undsbursed), berupa pinjaman resmi dan
yang datang dari bank-bank swasta internasional.
Pada akhir Maret 1982, seluruh utang yang sudah direalisasi akan
mencapai sekitar US$ 14,5 milyar. Sedang utang-utang yang belum
direalisasi diperkirakan masih sebanyak US$ 10,6 milyar pada
tanggal yang sama. Artinya, tahun depan pemakaian utang-utang
itu tak usah datang dari yang akan dibuat, tapi dari jumlah yang
belum direalisasikan tadi.
Berapa besar persentase utang yang jangka panjang dibanding yang
berjangka menengah (komersial di akhir Maret tahun depan masih
belum diketahui. Pada tahun 1980, menurut Direktur BI J.E.
Ismael, utang dari bank-bank swasta itu mencapai 37%. Dia
menyadari bahwa utang dari pihak swasta itu lebih tidak terikat
oleh prosedur resmi dan cocok untuk kegiatan jangka pendek. Maka
melihat persentase utang komersial masih kecil, dan Indonesia
perlu segera, BI pun ditugasi untuk mencari utang-utang
komersial baru.
Mungkin yang perlu dijaga adalah keseimbangan perbandingan utang
itu. Salah satu yang agaknya turut menambah beban, adalah
utang-uung komersial yang disalurkan untuk perusahaan milik
pemerintah. Sumber-sumber di BI mencatat utang komersial yang
sudah direalisasi, dan masih berlaku (still outstanding)
berjumlah sebanyak US$ 1,8 milyar lebih pada akhir Maret tahun
depan. Itu terdiri dari utang Pertamina dan PT Garuda Indonesia
Airways. Sedang utang yang belum direalisasi untuk
perusahaan-perusahaan milik negara, masih sebanyak US$ 373 juta
pada tanggal yang sama.
Adakah uung yang belum dilaksanakan itu akan dialihkan sasaran
penggunaannya? Itulah yang antara lain dipersoalkan oleh Prof.
Dr. Sumitro Djojohadikusumo belum lama ini. Sang profesor, yang
berpengalaman sebagai menteri keuangan dan perdagangan --dan di
tahun 1950-an adalah dekan FE-UI-menghimbau rekan-rekannya
se-Almamater yang kini mengelola ekonomi Indonesia: "Perlu ada
pergeseran prioritas." Dengan kata lain, ia menganjurkan agar
proyek-proyek besar yang amat memakan biaya, kalau belum mulai
dilaksanakan, hendaknya ditunda dulu.
PROF. Sumitro barangkali khawatir melihat kasus Meksiko. Negeri
penghasil minyak yang beberapa tahun lalu masih
dibangga-banggakan oleh para ekonom dan bankir internasional
sebagai "contoh negara berkembang", kini telah dililit segunung
utang. Uungnya pada Agustus 1982, tercatat sebanyak US$ 80
milyar US$ 60 milyar utang yang dibuat oleh pemerintah dan
perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan US$ 20 milyar utang
pihak swasta Sekitar US$ 42 milyar dari jumlah itu telah jatuh
waktu dalam tahun 1982.
Peristiwa yang menimpa Meksiko memang bisa membuat siapa saja
bergidik Untung Indonesia agaknya pernah pula mengalami
peristiwa serupa, dalam porsi yang lebih kecil: bencana
Pertamina. Dengan gaya pembangunan yang jumawa, tapi lengah,
Indonesia waktu itu tiba-tiba terperosok ke jurang uung sebesar
US$ 10,5 milyar. Sebagian berjangka pendek, misalnya utang
dagang yang US$ 2,5 milyar dan utang sewa-beli armada tanker
yang US$ 3,3 milyar.
Pengalaman pahit itu tentu tak akan dilupakan orang. Terutama
oleh para pengelola ekonomi dan keuangan Indonesia. Dan
baru-baru ini, adalah Men-Ko Ekuin Prof. Dr. Widjojo Nitisastro
yang menyatakan bahwa, "kita harus lebih banyak menggali
sumber-sumber keuangan dari dalam negeri," serta "lebih banyak
membuka kesempatan kerja yang bisa menampung banyak orang".
Artinya, ia boleh ditafsirkan sependapat dengan Sumitro--jangan
ingin cepat-cepat menoleh ke industri-industri hulu, yang padat
modal.
Resep Widjojo--sesuai pula dengan gaya dan pandangan Presiden
Soeharto -- ialah pembangunan, dengan hati-hati. Agaknya itulah
yang akan lebih terasa di tahun depan, sebentar lagi, di depan
lampu merah sekarang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini