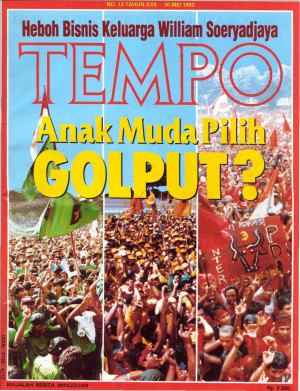TANRI Abeng, yang sering disebut manajer satu milyar, terperosok di kampungnya sendiri. Sulit untuk percaya, tapi itulah yang terjadi. Empat tahun lalu, di Ujungpandang, Tanri bersama Arnie Arifin -- putri Kabulog Bustanil Arifin merintis industri sari markisa. Beroperasi sejak tahun 1990, perusahaannya PT Markisa Segar kini ternyata menderita rugi. Kerugian itu kabarnya hampir Rp 1 milyar. "Saya tidak tahu persis, karena tidak turun langsung," kata Tanri di Ujungpandang pekan silam. Sebagai direktur utama, Tanri memang tidak langsung menangani usaha sari buah itu. Dan laporan untuknya terlambat disampaikan. "Saya baru tahu masalahnya belakangan. Itu kebiasaan orang Indonesia, tak mau melaporkan kenyataan," ujar Tanri kepada koresponden TEMPO Waspada Santing. Kini Tanri sudah tahu masalahnya. Pertama, mesin produksi yang tak mampu menghasilkan kualitas ekspor. Sari buah markisa yang diolah dengan mesin Ricerman ternyata masih tercemar serbuk-serbuk halus biji markisa. "Padahal, di pasar ekspor, orang teliti sekali," ujar Yisca Lody, Manajer PT Markisa Segar. Selain itu, suplai buah markisa juga di bawah kapasitas terpasang. Dengan investasi Rp 3 milyar, pabrik tersebut siap mengolah 2.000 kg markisa setiap hari, sementara perkebunan markisa milik Tanri hanya mampu memasok 20 sampai 30 persen dari kebutuhan itu. Padahal, menurut Tanri, agroindustri baru mencapai break even point jika produksi sampai 50% dari kapasitas terpasang. "Jadi, sudah pasti rugi," Tanri menyimpulkan. Tapi manajer top ini belum mau mundur. Untuk mengatasi masalah mesin, pihak Ricerman didesaknya agar memperbaiki mesin. Supaya suplai markisa terjamin, PT Markisa Segar menjalin kerja sama dengan PT Aurora Sabang Setia, yang akan membuka areal perkebunan markisa seluas 100 ha. Tanri juga sudah meminta technical assistance dari United States Aid (USAID). Ia optimistis, sari markisa menjanjikan prospek cerah. Hanya dua daerah yang menghasilkan markisa: Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Ekspor PT Markisa Segar -- yang sebagian di bawah standar mutu itu -- bahkan meningkat drastis, dari 14 ton (tahun 1990) menjadi 80 ton (tahun 1991). "Jadi, bukan bisnisnya yang salah, tapi aspek teknis dan bahan bakunya," kata Tanri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini