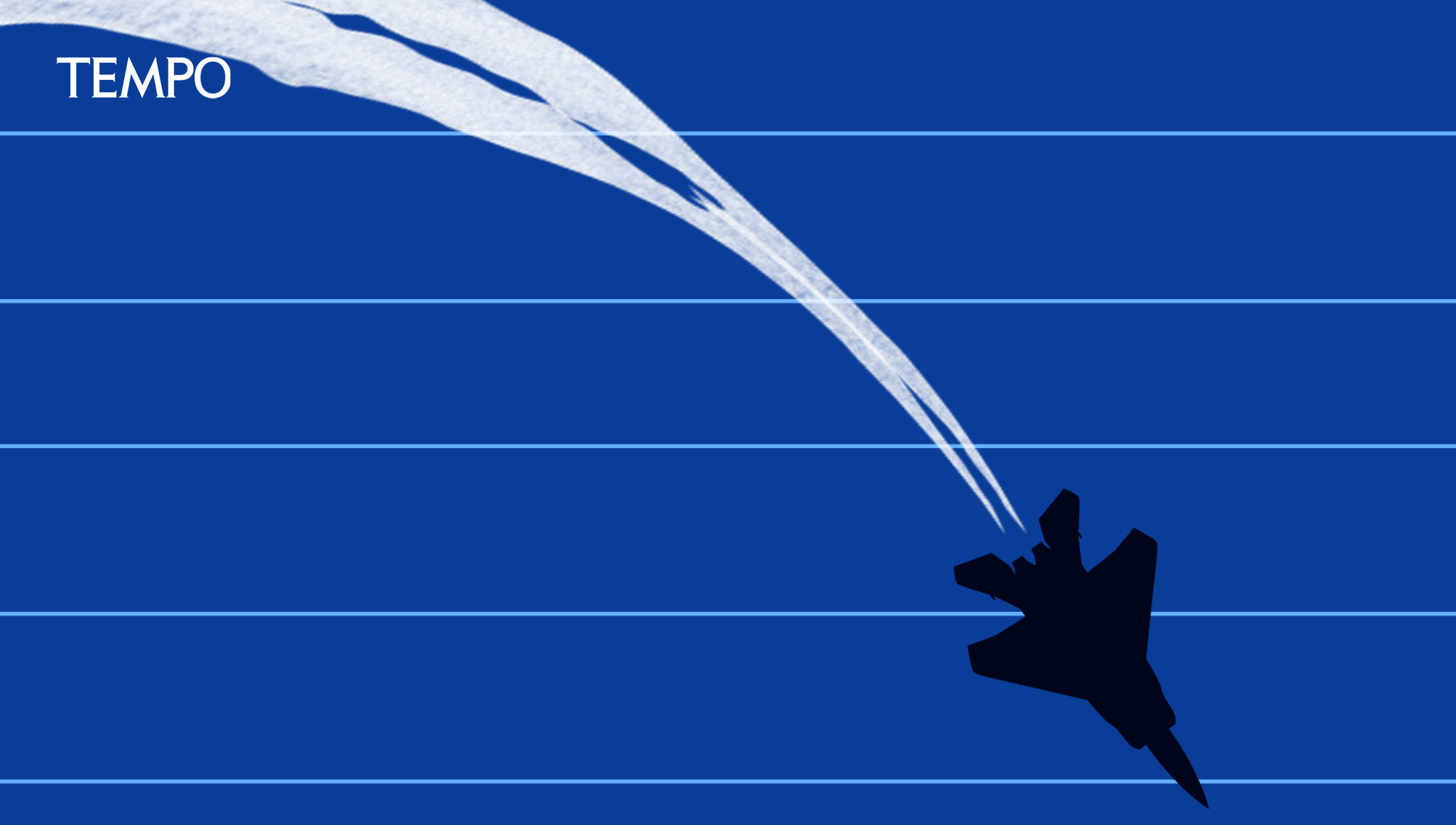Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Pemerintahan baru selalu menjanjikan swasembada pangan.
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan serangkaian kebijakan di sektor pangan untuk mencapai swasembada.
Masalah logistik memperburuk pembenahan sektor pangan.
HAMPIR dalam setiap pergantian pemerintahan calon presiden menjanjikan swasembada pangan. Jargonnya berubah-ubah, dari “Feed the World” hingga “Menjadi Lumbung Pangan Dunia”. Namun realitasnya selalu berbanding terbalik. Alih-alih swasembada tercapai, ketergantungan terhadap impor pangan justru kian membengkak.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo