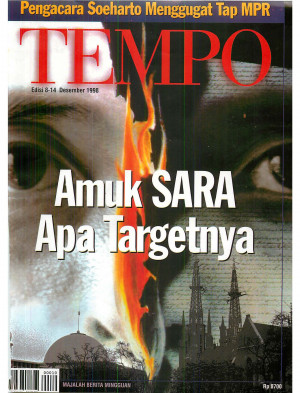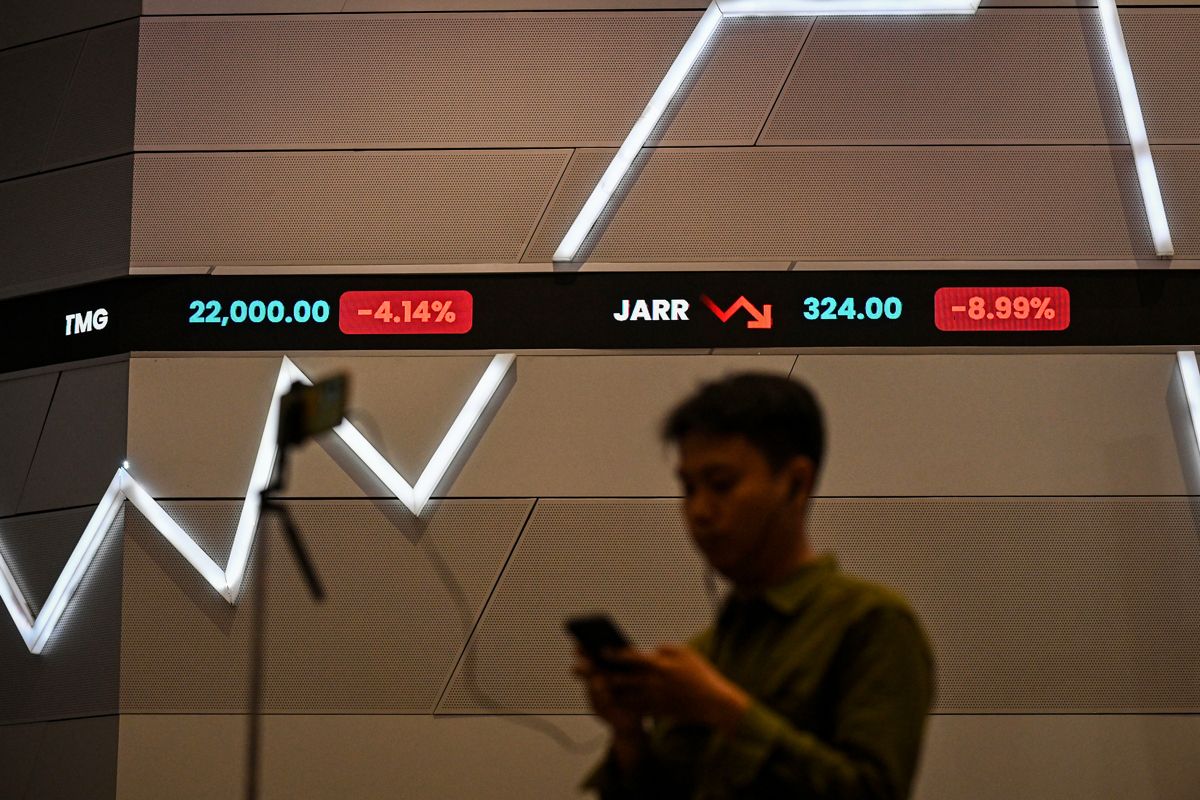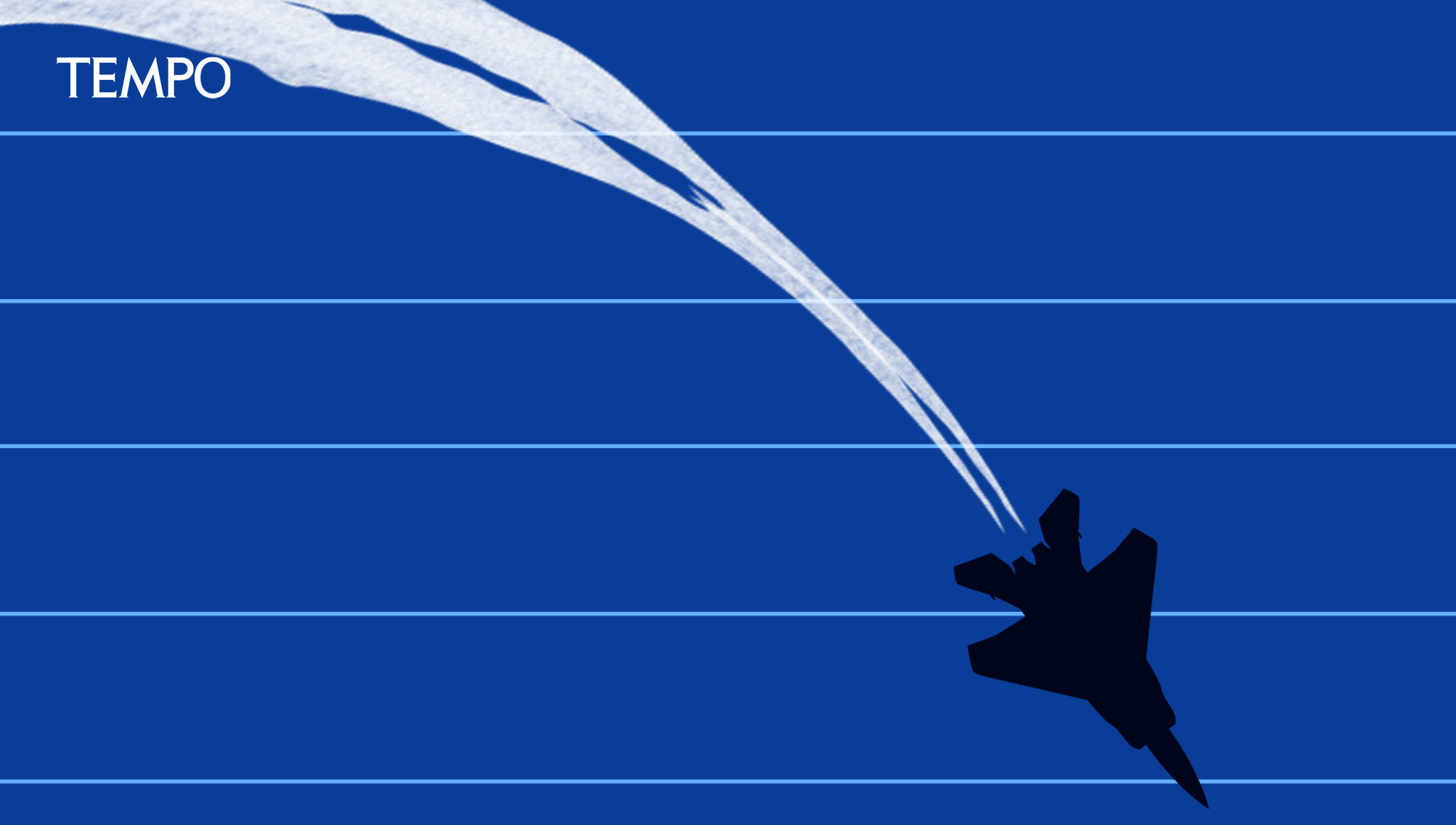Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Selain Timor, sasaran tembak kedua adalah dugaan penyelewengan dana di yayasan milik Soeharto. Yayasan ini umumnya dibentuk dan dibiayai dengan memobilisasi dana publik. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM), misalnya, mendapatkan duit dengan mengutip perusahaan dan orang-orang kaya. Setiap perusahaan diminta menyisihkan 2 persen labanya untuk disumbangkan ke YDSM. Jika ini dilakukan, jumlah sumbangan itu diperhitungkan dalam pengurangan pajak.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo