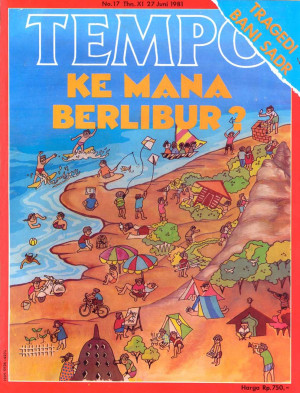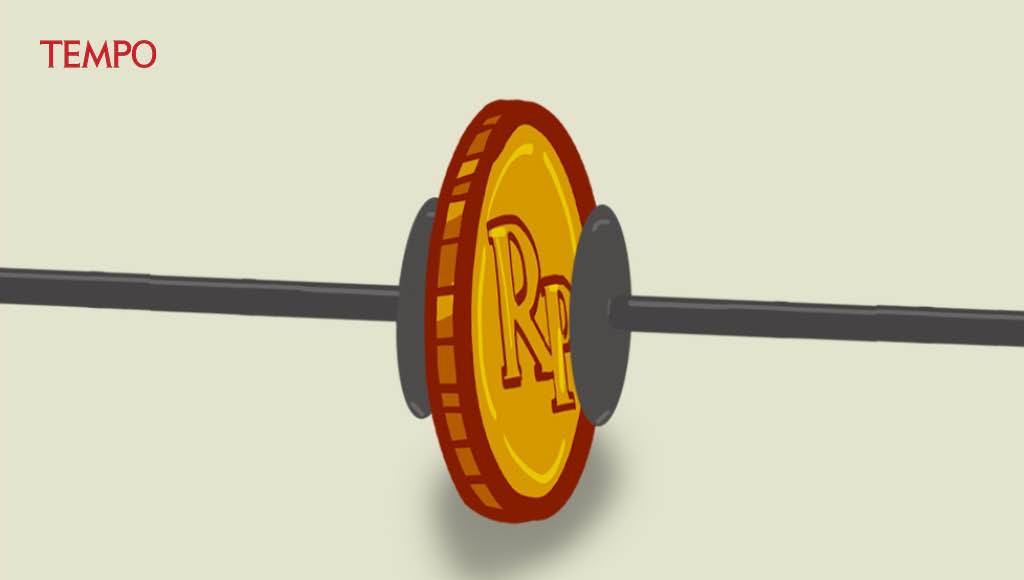HAJI Mohamad Sulchan, bekas pengusaha trawl dari Semarang itu,
masih penasaran. Ia beranggapan dicabutnya nyali kapal-kapal
trawl (yang juga dikenal dengan pukat harimau) ternyata tidak
saja merugikan sejumlah pengusaha ikan dan udang yang
menghasilkan devisa, tapi juga tak mampu mengangkat derajat
kehidupan kaum nelayan kecil. Dalam sebuah surat terbuka 2 Juni
lalu -- 20 hari sebelum pengusaha beken itu mendapat piala utama
dari Menteri Agama karena terpilih sebagai keluarga teladan
(lihat Pokok & Tokoh) -- dia menulis "Yang besar sudah telanjur
hancur, tetapi yang kecil bahkan mati. . . "
Dir-Ut PT Cejamp (Central Jawa Marine Products), pabrik
pendingin udang di Semarang itu tak menentang ucapan Mensesneg
Sudharmono betapa para nelayan akan memperoleh lebih banyak ikan
setelah itu trawl dilarang beroperasi. Di lain pihak, Sulchan
tak melihat penghasilan ikan yang bertambah itu akan menambah
rezeki para nelayan. Soalnya, menurut Sulchan, pemasaran
ikan-ikan yang kecil itu tidaklah semudah menjual udang. Perlu
tempat penjemuran yang luas, tempat penyimpanan dan jaringan
penjualan, yang semuanya membutuhkan modal dan ketrampilan.
Sulchan berpendapat para nelayan sudah merasa senang, kalau saja
mereka mendapatkan tiga kilogram udang sekali melaut.
"Bayangkan, di pabrik pendingin sekilo udang bisa laku antara Rp
7.000 sampai Rp 8.000," katanya.
Sejak Oktober tahun lalu, beberapa saat setelah keluarnya
Keppres No. 39 tanggal 1 Oktober 1980 yang melarang tawl itu,
pabriknya yang patungan dengan Jepang kontan menurun
produksinya. "Udang yang masuk dari pasaran umum waktu itu hanya
25%, sedang dari kapal sendiri sifatnya cuma tambahan," kata
Sulchan yang kini banting stir ingin membuka pabrik semen.
Dinding Bambu
Keterangan Sulchan itu dibenarkan oleh Eddy Soehodo, 29 tahun,
mahasiswa Undip, calon sarjana hukum yang memiliki dua kapal
pukat harimau. Kini kapalnya diubah berjaring gilnet, tapi baru
jalan satu. Kapal Eddy itu diongkosi lewat kredit Rp 8 juta dari
Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk diubah menjadi gilnet. "Tapi
untuk mengangsur tiap bulan Rp 240 ribu, setengah mati," katanya
kepada wartawan TEMPO Hamid S. Darminto di Semarang.
Pada 18 Juni lalu hasil tangkapan nelayan pribumi itu sampai
sekitar dua ton, berupa ikan cucut dan jenis lainnya. "Tapi
uangnya cuma Rp 900 ribu," katanya. Musim begini memang sepi,
belum panen. Tapi andaikata panen, penghasilan dari gilnet itu
menurut Eddy toh tetap kecil dibandingkan trawl. "Paling tidak
satu berbanding sepuluh," katanya.
Tapi benarkah sinyalemen Sulchan itu -- yang disetujui oleh Eddy
-- tentang kehidupan nelayan kecil yang masih payah setelah
pukat harimau disingkirkan? Matran, 55 tahun, nelayan di
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mengakui penghasilannya kini
rata-rata Rp 900 sehari. Semasih ada trawl Rp 800. Nelayan dari
Desa Jobokuto, Jepara, yang menghidupi delapan mulut itu
memiliki perahu sendiri yang sampai sekarang belum juga
bermesin.
Lain lagi Fadlan, 45 tahun, dari desa itu juga. Bersama enam
rekannya, nelayan yang beranak lima dari satu istri itu sudah
sebulan melaut, mencari ikan untuk dijadikan ikan asin. Bekal
yang dibawa Fadlan menelan Rp 100 ribu, yang ia pinjam dari
seorang tengkulak, dengan perjanjian: hasil tangkapannya harus
dijual kepada si pedagang itu dengan harga di bawah pasaran.
Untuk teri hitam misalnya Rp 500 per kilo, sedang di pasar laku
Rp 800. Setelah dihitung-hitung, nelayan itu merasa rugi. "Saya
harus menombok Rp 10 ribu kepada majikan saya," katanya.
Pembantu TEMPO B. Amarudin yang merekam kehidupan nelayan di
perairan Jepara itu juga menceritakan nasib jelek yang diderita
Sutadji, 45 tahun, asal Jobokuto juga. Nelayan ini tadinya
memiliki sebuah perahu. Sekarang sudah dijual untuk menombok
utang. "Sekarang saya ikut orang," kata ayah dari lima anak itu.
Sebagaimana banyak nelayan lain di sana, Sutaji sudah seminggu
lebih menganggur, karena terang bulan.
Kehidupan para nelayan di Jepara itu nampak tidak berubah.
Perumahan umumnya terbuat dari dinding bambu, lantai dari tanah
liat dan atap daun rumbia. Mereka rata-rata punya lima anak,
yang paling banter bersekolah di SD. Tapi adalah anak-anak itu
pula yang sepulang dari sekolah bekerja keras sebagai pengrajin
ukiran. Kegiatan para pengrajin cilik itu antara lain terdapat
di Desa Bulak, Kecamatan Kedung, Jepara. "Kalau tak ada
anak-anak ini, kehidupan para nelayan di sini pasti lebih
susah," kata Sutoyo, Kepala Desa Bulak.
Untung saja di samping cerita dari Jepara yang memprihatinkan
itu, masih ada kabar baik. Mastam, 35 tahun, pemilik kapal "Keno
Lowo Putih" di daerah nelayan Tambakrejo Semarang merasa
bersyukur dengan hilangnya pukat harimau. Hasil tangkapannya
melonjak. Dalam musim sepi seperti sekarang ini, nelayan itu
mengaku paling sedikit masih bisa mengantungi seribu perak
sehari. "Dulu waktu ada trawl, laut seperti diaduk-aduk,"
katanya. Dia mendoa agar "setan aduk-aduk" itu untuk selamanya
dilarang beroperasi.
Toh kabarnya masih ada "setan" yang berkeliaran. Itu diakui baik
oleh Eddy Soehodo maupun Sulchan. Sehari menjelang dilarangnya
travl, Eddy merasa yakin kapalnya telah berpapasan dengan dua
kapal asing yang masingmasing memasang dua jaring pukat harimau.
"Jelas itu mencuri. Apalagi sekarang," katanya.
Pencurian udang oleh kapal asing itu ternyata memang menjadi
omongan banyak nelayan bekas trawl di Semarang. Sulchan pun
menambahkan: "Apa sih sulitnya. Mereka tangkap itu udang,
langsung didinginkan di kapal, dibungkus lalu lari ke luar.
Beres." Apa iya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini