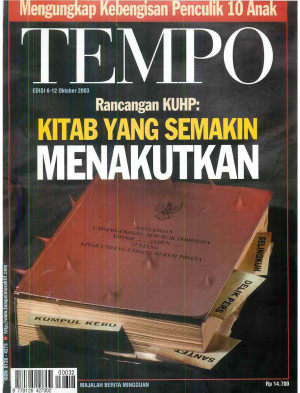Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketika buluh bambu diraut, ditimbang kiri-kanan, lalu kertas warna-warni mencolok ditempel, datanglah kesenangan tak terkira. Itulah saat layang-layang dicipta. Prosesnya bikin deg-degan. "Saya selalu ingin coba-coba bentuk baru," kata Agus Setiawan, perancang di Bengkel Layangan LeGong, Jakarta. Pernah, bersama kawan-kawannya, dia membuat layangan berbentuk kuda laut berperut gendut, perahu layar setinggi 6 meter, juga layang-layang superpanjang yang tersusun dari 1.003 layangan kecil.
Mata Agus kian berbinar. Pemuda 25 tahun ini mengenang momen-momen mendebarkan saat uji coba menerbangkan layangan. Bangga, senang, haru tak terkatakan bila layangan sukses menari berlenggang di langit biru. "Terutama bila karakter si layangan itu muncul kuat," kata Agus. Umpamanya, layangan kuda laut tadi, yang perut gendutnya maju-mundur lucu di udara.
Layang-layang, lajengan dalam bahasa Madura, memang bukan sekadar mainan kanak-kanak. Dia jauh lebih dalam dari itu. Datuk Bagindo, wiraswasta dari Kelapa Gading, Jakarta, misalnya, mendasarkan filosofi hidupnya pada layang-layang: bahwa segala sesuatu harus seimbang, tak boleh berlebihan. Atau, "Seperti benang layangan, gulungan benang yang ada di tangan tak boleh habis," katanya, "agar jika ada angin kencang mendadak, kita bisa segera mengulur si layangan." Datuk menafsirkan, kita tidak boleh bersikap mutlak atau habis-habisan. Segala sesuatu mesti ada ruang toleransinya.
Sementara itu, Sari Madjid, pemilik Bengkel Layangan LeGong, memuja keindahan layangan yang sedang terbang. Gradasi warna, bentuk, dan karakter bergerak indah ditiup angin. "Mirip pertunjukan teater di alam terbuka," kata artis senior Teater Koma ini. Dan memang betul. Kemegahan teater tampak nyata ketika, Minggu dua pekan lalu, puluhan layang-layang beraksi di lapangan Monas dalam Festival Layang-layang se-Jakarta Pusat.
Sari sendiri kepincut ketika menyaksikan festival layang-layang internasional di Bali pada 1992. Sejak saat itulah dia serius mengembangkan hobi, termasuk dengan berbisnis mendirikan Bengkel LeGong di rumahnya, di Jalan Setiabudi, Jakarta. Pasar yang dibidik LeGong cukup lumayan berhubung makin meningkatnya minat masyarakat bermain layang-layang. Setiap bulan, 1.000 layangan terjual dengan omzet sekitar Rp 50 juta. Jenis yang laris adalah layangan delta, berbentuk segitiga dengan kibaran warna pelangi, yang berharga Rp 30 ribu-50 ribu per buah.
Sari, bersama kawan-kawan di Yayasan Masyarakat Layang-layang Indonesia (YMLI), juga giat menjelajah dari Sabang sampai Merauke demi berburu layangan tradisional yang khas. Kagati, layangan tradisional Sulawesi Tenggara, misalnya, adalah maskot yang mengundang decak kagum setiap kali ditampilkan di ajang internasional. Betapa tidak. Kagati jauh berbeda dibandingkan dengan layang-layang luar negeri, yang hanya mengandalkan akurasi teknologi canggih. Rangka layangan ini terbikin dari bambu halus. Lalu, sebagai pengganti kertas, digunakan anyaman daun sela, sejenis daun waru, yang dikeringkan. Penempelan lembar demi lembar daun pun bukan dengan lem, melainkan dijelujur rapi dengan benang yang terbuat dari serat daun nanas hutan. Dibutuhkan ketelatenan ekstratinggi untuk mewujudkan kagati yang biasa diterbangkan petani Sulawesi di masa panen ini.
Kagati memang istimewa. Menurut Sari, seorang arkeolog dari Jerman berminat meneliti asal mula kagati. Soalnya, baru-baru ini ditemukan gua purba di Sulawesi yang dindingnya bergambar layangan. "Siapa tahu penelusuran di gua purba ini akan meruntuhkan teori yang dipercaya selama ini bahwa layangan tertua berasal dari Cina, 200 tahun sebelum Masehi," kata Sari.
Maskot yang lain adalah canggan, layangan tradisional dari Bali. Kepalanya berbentuk naga, bersayap lebar, dan berekor panjang. Pembuatan layangan yang disucikan ini disertai ritual upacara sesajen dari warga puluhan banjar yang ada di Bali. Ongkos pembuatan yang berjuta-juta pun ditanggung renteng semua banjar. Bagian yang dianggap suci terutama adalah kepala sang naga. Kertas untuk sayap dan ekornya boleh diganti dan diperbarui, tapi kepala naga harus tetap dipertahankan sama. "Kepala naga yang terbang tinggi ini diharapkan menyampaikan pesan syukur kepada Hyang Widhi yang ada di atas sana," Sari menjelaskan.
Saat canggan diterbangkan ke langit, Sari melanjutkan, tak boleh ada kecelakaan yang membuat kepala naga jatuh ke bumi. Puluhan orang harus sudah bersiap di lapangan, bertugas menyelamatkan andai tiba-tiba kepala naga terjun terempas angin. Tidak jarang air mata dan keringat tumpah lantaran upaya penyelamatan yang dramatis. Wajarlah bila canggan menjelma menjadi tontonan yang atraktif di setiap festival internasional. Beberapa tahun lalu, LeGong mendapat pesanan canggan dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Layangan bernilai Rp 7,5 juta ini berukuran raksasa: rentangan sayapnya 5 meter dan ekornya menjuntai sampai 100 meter.
Kegandrungan pada layang-layang bukan hanya milik Sari Madjid. Endang Ernawati Puspoyo, istri Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, juga tergila-gila pada layangan sejak 15 tahun silam. Saking gandrungnya, Endang memutuskan mempelajari layang-layang dengan serius. Dia membeli segala buku, literatur, tentang pembuatan dan sejarah layang-layang dari seluruh dunia. Endang juga belajar membuat layangan hingga akhirnya ibu tiga anak ini pun menjadi ahli. Kini jadwal Endang penuh dengan undangan mengajar layang-layang di berbagai sekolah asing di Jakarta. Bayarannya lumayan, US$ 25 per jam pelajaran.
Sepanjang waktu Endang juga giat berbelanja. "Bukannya belanja tas, baju, sepatu, atau permata," katanya sambil tersenyum, "saya malah ngeborong jenis layangan, tradisional atau kreasi." Untuk produk luar negeri, Endang biasanya membeli layang-layang bekas. "Yang baru mahal banget, Rp 100 juta sebuah," katanya. Koleksi layangan Endang yang terbaru adalah Octopus, layangan cumi 30 x 8 meter yang dibeli dari "pelayang" di Inggris seharga Rp 30 juta.
Perburuan belasan tahun tentu mendatangkan koleksi yang melimpah, sedikitnya 500 layangan. Koleksi Endang yang paling unik adalah tiga layangan sutra tipis dengan lebar tak lebih dari jempol jari tangan. Layangan dari Cina ini berbentuk lebah, kupu-kupu, dengan rangka bambu yang diraut sampai sehalus satu helai rambut. Soal keseimbangan, dijamin, layangan ekstramini ini sudah teruji sanggup terbang dengan stabil.
Kemudian, sejak Maret 2003, seluruh koleksi Endang dipajang di Museum Layang-layang, Jalan Haji Kamang, Jakarta. Inilah museum layang-layang pertama di Indonesia. Dan hanya sedikit negara yang punya museum semacam ini. Museum ini juga dilengkapi workshop yang tiap bulan menghasilkan 1.000 layang-layang yang dijual untuk umum, dengan harga di atas Rp 30 ribu per buah.
Begitu memasuki area seluas 3.000 meter persegi ini, pengunjung dijamin terpesona menyaksikan keasrian bangunan bergaya joglo Jawa serta koleksi layangan yang ada di dalamnya. Ratusan layangan beragam ukuran, dari yang terkecil, 2 x 2 sentimenter (dari Cina), sampai yang terbesar, 30 x 12 meter (dari Selandia Baru), terpajang rapi dengan tata letak atraktif. Koleksi layangan tradisional dari 20 provinsi pun komplet tersedia. Misalnya layangan kagati, kelung dari Aceh, bunga raflesia dari Bengkulu, dan lembu Suana dari Kalimantan Timur.
Endang enggan mengungkapkan nilai total museum plus isinya. "Nilainya tak terhingga karena semuanya kesayangan saya yang ingin saya bagi dengan orang lain," katanya bangga. Tarif masuk Rp 5.000 per pengunjung—museum ini dikunjungi 400 orang per bulan—tidak sanggup menutup pengeluaran Endang selama ini. Memang, tak bakal ada harga yang pantas untuk sebuah kelangenan dan kecintaan.
Mardiyah Chamim, Adek, Ecep S. Yasa, Faisal (Tempo News Room)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo