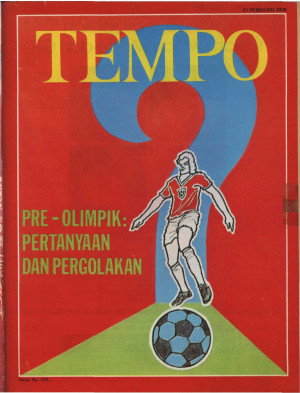REPOT juga untuk menyebut bahwa air bah itu tidak
berbahaya. Tapi Eni, seorang ibu di Bogor toh sempat berkata
(dalam bahasa Sunda) hikmah banjir itu ada juga. Paling tidak,
bagi mata pencahariannya sehari-hari. Berusia lebih setengah
abad, ibu dari 7 anak dan nenek dari selusin cucu ini adalah
pengumpul pasir dan batu kali -- yang amat dibutuhkan sebagai
bahan bangunan di kota-kota. Dari balik pelupuk matanya yang
mengendor, Eni memandang banjir dengan harapan lain. Sebab
dengan bantuan bah itulah pasir dan batu-batuan di Kali Ciapus
niscaya bertambah. Ini sering terbukti: serentak air susut,
maka ia bisa dengan lancar mencari nafkah, sementara suaminya,
Ata, memecah batu.
Pada hari biasa, kali itu nyaris kering. Kalaupun ada bagian
yang dalam, itu di balik batu besar atau tempat-tempat yang
barusan dikuras koralnya. Pukul 06 pagi ia sudah di sana, tanpa
kenal hari libur. Peralatannya hanya pengki yang biasa dibikin
suaminya, plus tempurung kelapa sebagai alat penguras. Bekerja
sampai sore, hingga tak heran bila kulitnya keriput dimakan
hari. Namun pasir dan koral yang dikumpulkannya paling banter
mencapai 1/4 kubik. Sering juga kurang. Bisa dibayangkan cuma
berapa penghasilannya bekerja sehari suntuk itu, bila harga
per-kubik pasir Rp 500 atau batu Rp 400 sekubik. Sedangkan
sekitar lima tahun silam, ia masih kuat mengumpul sampai jumlah
sekubik, masing-masing pasir dan batu. Halangannya memang lebih
terpulang pada tenaganya yang tambah tua.
Pat Gulipat
Kini tak kurang dari 40 truk menceburkan diri ke Kali Ciapus di
bilangan desa Pasireurih, kecamatan ciomas, Bogor. Truk-truk ini
memang tak ada urusan langsung dengan bu Eni, lantaran yang
punya izin penambangan hasil alam itu adalah pemborong atau
pengusaha pangkalan, yang kelak menjual bahan-bahan itu sekitar
dua atau tiga kali lipat. Untuk batu dan pasir ke truk itu
dilakukan oleh sejumlah kuli, yang umumnya terdiri dari anak
muda. Per kubik mereka beroleh upah Rp 50. Namun hasil itu
dipandang kurang memadai, lalu mereka bikin akal. Bila ada
muatan 5 kubik misalnya, kepada Eni dan kawan-kawan mereka
sebutkan 4 kubik, sementara sekubik mereka kantongi. Boleh jadi
karena bodoh atau memang tak ada waktu, Eni dan kawan-kawannya
tak pernah protes. Yang jelas mereka belum pernah mengukur luas
bak truk.
Itu baru satu korban. Perkara main akal-akalan dalam muatan truk
itu pun konon suka berkepanjangan sampai di kota-kota. Misalnya,
muatan 5 kubik itu bisa saja disulap menjadi 7 kubik. Caranya,
dengan modal Rp 200 si supir dikabarkan bisa menciptakan 1 M3
angka bayangan. Tentu saja ini kerjasama dengan kuli, yang sudah
diatur begiu ada batu yang turun, begitu cepat ia mesti
melempar lagi ke atas bak truk. Hanya pasir yang tak mudah
disulap, sebab bentuknya macam bubuk. Para pengusaha bahan
bangunan tentu maklum pat-gulipat semacam ini.
Akan halnya Eni, tak urung memang memandang model hidupnya kini
bagaikan peuyeum jatuh. Lebih sepuluh tahun lalu (harap maklum,
lantaran buta huruf, ia tak sanggup menghasta bilangan waktu)
hidupnya, katanya, "lumayan" punya lebih sehektar sawah, juga
punya sebuah warung yang menjual rupa-rupa keperluan dapur. Lalu
hasil- menyeretnya lain, serentak suaminya kawin lagi. "Dasar
lelaki, waktu si Itang dihamilkan dua bulan, suami saya main
perempuan lagi sampai punya anak", Eni buka riwayat di tengah
kali sembari mengoleskan kapur ke daun sirih. Hari-hari itu
dikenangnya sebagai awal berantakannya dari hidupnya. Warung tak
keruan, sebagian sawah terpaksa dilego. Memang ia tak sampai
cerai, namun rumah-tangganya toh keburu kucar-kacir jadinya.
Meski ada tersisa sawah, hasilnya paling banter 300 Kg gabah.
Terang tidak cukup. Sejak itulah ia dan suaminya berpaling ke
Kali Ciapus, merogoh pasir dan batu-batuan itu.
Tapi kerja di luar rumah bukan pertama kali itu dilakukannya.
Ketika masih perawan dulu Eni sudah bekerja di pabrik teh. Malah
pernah menjadi pemetik teh -- bermula dengan gaji 15 sen sampai
25 sen, sementara harga beras 12 sen seliter. Sebagai anak yang
masih ditanggung orang tua, penghasilannya itu dirasakannya
menyenangkan juga. Lebih menyenangkan pula adalah kenyataan
bahwa di pabrik teh ini pula kisah kasihnya dengan pemuda Ata
dimulai. Bila perawan Eni memilih daun teh, Ata yang punya tugas
merawat bangunan waktu itu, suka-cita membantu Eni. Jam 12 siang
mereka sama-sama istirahat. Pada saat semacam itu asmara
keduanya saling berpadu. Bukan hanya sekedar kongko di belakang
pabriK, mereka juga sering turun berdua ke Ciapus yang letaknya
20 meter dari pabrik. Mandi. "Badannya tegap. dan . . . " bu Eni
tak sanggup menuturkan lebih jauh kesannya tatkala pertama kali
meIihat pemuda yang kelak menjadi suaminya itu. Ketawanya
terburai sampai ludah sirihnya ikut berhamburan di batu kali,
sementara mang Ata cronggok jongkok di batu yang agak besar
sambil menyedot kretek.
Kini hidup mereka nampak rukun. Mendiami sebuah rumah sederhana
berukuran 3 x 5 meter. Terletak tak jauh dari Ciapus. Empat
anaknya meninggal. Tiga yang ada sudah berumah-tangga. Dengan
bekal sekolah tak leuwt dari kelas 3 SD, anak-anaknya itu kini
menjadi pedagang sayur. Dan seminggu dua kali mereka menggotong
hasil bumi buat perut orang Jakarta, berupa sayur-mayur.
Jagung, timbul dan sebagainya. Dua dari anaknya itu sudah punya
rumah sendiri-sendiri. Tinggal satu yang masih nebeng dengan
mertua. Ini diniatkan bu Eni untuk dibuatkannya rumah. Persiapan
sudah dimulai, tapi selanjutnya bergantung pada nasib.
Sebab berapa sih kemampuan tenaga seorang perempuan? Untunglah,
dibanding dengan suaminya, bu Eni memang terbilang lebih ulet.
Ia hanya mampu menghasilkan l/2 kubik pasir dan batu sehari,
sang suami malah sering tak lehih dari itu. Juga syukur ia tak
sampai sering sakit. Paling banter serangan kuman gatal di kaki.
Itupun mudah diobati. "Dengan minyak klantik", katanya. Minyak
dari minyak kelapa murni.
Hujan mengguyur Jakarta. Jalanan rusak. Jalan diperbaiki.
Jalanan macet. Tapi di celah-celah itu, ada seorang yang
menggantungkan hidupnya. Misalnya Harun, sehari-hari pekerja
perbaikan jalan raya. Bulan-bulan belakangan ini ia dan
kawan-kawannya sedang terlibat membenahi jalan Senen Raya. Para
pengemudi mobil sering menggerutu. Tapi kadang-kadang tidak.
Boleh jadi karena hoki lagi bagus, maka dari balik jendela
mobil terkadang terlempar sebungkus kretek buat para pekerja
jalanan itu. Mereka memecah aspal lama buat penggalian parit,
untuk selanjutnya memasang polongan air. Ini dikerjakan Harun
bersama 25 kawannya.
Harun kini mendekati umur 20 tahun. Usia itu boleh jadi masih
muda, namun di antara pekerja jalanan itu nyelip pula
wajah-wajah yang nampak masuk bilangan bocah. Berasal dari
Cirebon, delapan tahun silam, serentak jeblok di kelas 4 SD, ia
hijrah ke ibukota. Diakuinya sendiri bahwa ia memang malas
sekolah. "Kawan saya sekampung banyak yang buta huruf" tuturnya.
ukan sekedar tak mau kalah berduyun ke kota. Keadaan
menggiringnya mau tak mau bergeser ke Jakarta. Sebab, boleh
dibayangkan bila misalnya ia toh bertani. Hasil per-hari Rp 125.
Itu sudah menguras tenaga, sementara buat mendapatkan mata
pencaharian lain, tidak cukup ada lapangannya. Tambahan pula
Harun merasa ekonomi orang tuanya senin-kemis. Merasa ia tak
bisa mengajak perutnya berdamai, ia nyelonong ke Jakarta.
Mulanya hanya sekedar membantu ayahnya yang telah lebih dulu
boyong ke Pasar Ikan dan berniaga sebagai tukang air.
Kini mereka berdiam di sebuah kamar sewaan. Bangunan papan yang
sederhana. Cuma jangan salah faham. Mereka di sini bukan cuma
berdua. Bersama dengan ayah dan anak ini, ada 15 lelaki lagi
yang terdiri dari berbagai tingkatan umur yang bcrasal dari
daerah yang sama. Semua pekerja kasar. Ada kuli jalanan,
bangunan, dagang air, pengemudi becak. Semua menggeletak di
tikar. Ongkos sewa Rp 45 ribu setahun, mereka tanggung bersama.
Dan mereka masing-masing turun rumah di pagi hari tanpa sibuk
memasak sarapan lagi. Harun, misalnya, pukul 06 pagi sudah
berangkat ke pekerjaan. Baru sekitar jam 10 ia menyerbu warung.
Menunya: dua piring nasi plus sepotong tempe. Ini berarti ia
kena Rp 125. Tapi acara tangsel perut ini perlu tiga kali
sehari, sementara hasilnya per-hari adalah Rp 750 Atau
kadang-kadang Rp 1000. "Itu tergantung prestasi kerja
masing-masing", ujar Billy -- sehari-hari petugas PT Pembangunan
Jaya -- perusahaan yang melaksanakan pelebaran jalan itu.
Ditambahkannya: "Tapi Rp 750 itu memang minimal". Pembayaran
dilakukan seminggu sekali. Dengan Harun dkk PT Pembangunan Jaya
tak punya ikatan langsung. Para pekerja itu berstatus pekerja
harian lepas. Mereka adalah orang-orang dari pemborong yang
dipercayakan mendapatkan tenaga kerja.
Apakah Harun berniat terus bermain dengan martil yang
beratnya 5 Kg itu? Sementara asap kreteknya menggebu-gebu Harun
memang sering menerawang. Kadang-kadang hatinya cemburu juga
menyaksikan lalu-lalangnya orany bermobil di jalan raya. Tapi
segera disadarinya bahwa itu merupakan lamunan yang keliwatan.
Sebab tekadnya adalah semasa kondisi tubuhnya masih kuat ini
jangan sampai nasib getir di kampung dulu, sampai terulang lagi.
Selama ini ia di Jakarta, ada juga keinginannya untuk sekali
waktu mudik. Dan selama itu pula ia memang bukan melulu memeras
tenaga sebagai kuli jalanan. "Saya suka aplusan juga dengan
bapak dagang air", ujarnya. Dan hasil yang didapatnya hampir tak
berbeda Tapi yang jelas, dagang air itu tak sampai melelahkan.
Demikianlah, pemuda berkulit hitam yang berperawakan pendek ini,
bisa ditemui di jalan Bandengan, dekat pabrik bir. Cuma jangan
keliru, katanya, "jangan tanya Harun pegawai PT Jaya, tapi Harun
tukang air", katanya tersenyum. Ia suka senyum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini